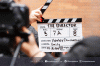Meskipun sejalan dengan narasi Tionghoa dari kedua film tersebut di mana Tionghoa masih dianggap sebagai yang "lain", terlihat bahwa Joko mengambil pendekatan yang lebih kelam, struktural, dan pesimistis melalui permainan ruang.
Tapi di balik itu semua, sejalan dengan dampak Wijkenstelsel dalam sejarah, ruang-ruang ini terkadang dapat dibaca sebagai perwujudan solidaritas antar-Tionghoa, seperti yang tampak pada Bar Wijaya. Vera, meskipun perannya kecil, menjadi satu dari sedikit karakter perempuan Tionghoa yang berbicara. Dalam momen singkat, ia memberi semangat pada Edwin: "Di sini gak boleh ada yang sedih. Lihat sekitar, gak ada yang sedih, kan." Kalimat ini, disertai sorakan semangat dari pengunjung lain, live music, atraksi bartender, sampai desakan pengunjung untuk melanjutkan musik di tengah jeda berita kerusuhan, telah menciptakan ilusi ruang aman -- sebuah dunia kecil yang bebas dari kekerasan dan rasa takut, meskipun sifatnya sementara.
Pergumulan Tionghoa dengan ruang terbatas dalam film Joko pun sebenarnya coba dibayar (pay-off) dengan simbol harapan saat Edwin mengalahkan Jefri dalam adegan duel, lalu diselamatkan oleh Panca dengan mobilnya.
Hanya saja, mempertahankan gaya chamber-nya, kemenangan itu dikesankan tidak merdeka, tidak mengubah status quo. Ujung-ujungnya Edwin dan para Tionghoa yang diselamatkan itu berakhir di ruang sempit (lagi), di sebuah mobil yang sesak bersama 'korban' lainnya. Mereka (etnis Tionghoa) tetap berada dalam bingkai 'korban' dan tetap terkungkung dalam Republik Preman yang semakin subur. Dunia seolah tetap berjalan seperti biasa, padahal kekerasan dan luka kolektif belum usai. Edwin bahkan masih mengenakan topi untuk menyamarkan identitasnya. Sebuah siklus yang berulang, yang membingkai narasi ini dalam melankolia yang tak selesai.
Jika merujuk tradisi estetika sinema, Pengepungan di Bukit Duri tampak bersinggungan dengan konsep chamber films yang dikembangkan sutradara eksperimental, Maya Deren. Selain karena bujet, 'chamber' dalam film-film Deren menjadi ruang refleksi eksistensial -- Deren biasa berlakon di filmnya sendiri. Refleksi ini, dalam bentuk yang lebih massal, salah satunya, pernah dipraktikkan secara ambisius oleh Lars Von Trier dalam Dogville (2003) yang mengangkat ruang minimalis sebagai cermin moralitas komunitas.
Baik karya Von Trier yang eksentrik, maupun karya Deren yang filosofis, chamber films dalam tradisi estetika sinema seringnya mengusung gagasan soal "rumah". Barangkali permainan ruang terbatas dalam film Joko pun menjurus pada gagasan serupa: 'Rumah' sebagai ruang emosional dan simbolik. Jika demikian, gagasan ini menyeret kita pada sebuah pertanyaan: apakah 'rumah' itu masih mengingat dan menerima Tionghoa sebagai bagian dari sejarah, atau justru, sebagai tamu tak diundang?
Mentalitas Korban Kelompok Mayoritas
Sebagaimana rhetoric of victimhood yang identik dengan perebutan status korban, peran 'korban' dalam film ini juga melekat pada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai "orang Indonesia asli".
Sejak masa kolonial, tak sedikit masyarakat bumiputra mewarisi mindset 'korban' kekuasaan asing. Di film ini, warisan itu mewujud sebagai perasaan menjadi korban dari kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap mengistimewakan etnis Tionghoa. Perasaan sebagai korban itu perlahan menjadi identitas, bahkan senjata ideologis untuk menjustifikasi kekerasan terhadap yang dianggap sebagai 'pelaku' (etnis Tionghoa).
Jika etnis Tionghoa adalah korban secara literal, maka kelompok mayoritas di film ini adalah korban secara pikiran.
Michael Ovey dalam artikelnya "Victim Chic? The Rhetoric of Victimhood (2006)" memperingatkan bahaya ketika victim-thinking atau mentalitas korban menjadi identitas permanen. Ketika seseorang atau sekelompok orang melihat diri sendiri sebagai korban secara kontinu, mereka rentan menempatkan diri sebagai pihak yang paling benar -- menjadikan pihak lain sebagai pelaku atau pihak yang salah. Ini adalah "ilusi kekorbanan mayoritas" yang justru memperkuat dominasi. Sementara minoritas, tetap dalam posisi yang lebih rentan secara struktural.
Penyandingan etnis Tionghoa sebagai 'korban' bersama kelompok mayoritas menjadikan ketimpangan itu semakin kentara. Ketegangan inilah yang memunculkan efek dramatis bagi penonton, sekaligus membuka kemungkinan pembacaan atas mayoritas sebagai 'pelaku' retorika kekorbanan. Dengan menyandingkan keduanya, penonton punya ruang untuk menentukan siapa 'korban sejati' -- atau dalam istilah Peter Utgaard: real victimhood -- di antara keduanya.