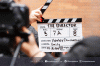Maka pada bagian ini, saya akan membagi analisis korban dalam tiga kategori, yakni etnis Tionghoa, mayoritas, dan perempuan. Ketiga korban ini -- dengan dunia cerita dan aturan bertahan yang telah dibahas sebelumnya -- memiliki akar ketertindasan dan penggambaran yang berbeda-beda. Selanjutanya, akan dibahas juga bagaimana unsur kekerasan tampil dalam film.

Ruang dan Citra Korban Kelompok Tionghoa
Bagi Edwin dan kelompok etnis Tionghoa lainnya, hidup dalam Republik Preman berarti harus terus bersembunyi dan mencari ruang aman. Otoritas yang ia tampilkan di sekolah tak berlaku di luar. Begitulah cara rhetoric of victimhood bekerja. Sebesar apa pun usaha bersembunyi dan mencari ruang aman, sosok dan penderitaan 'korban' selalu dibutuhkan untuk mempertahankan tatanan yang rusak dalam narasi yang dibangun.
Dengan meminjam kerangka "Segitiga Korban" yang dipopulerkan Stephan Karpman, yang mengklasifikasikan seseorang atau sekelompok orang dalam salah satu dari tiga peran (lihat gambar 3), maka Edwin (etnis Tionghoa) adalah 'korban' dalam kisah ini. Apabila kerangka Karpman diuraikan dalam premis naratif, maka: Edwin (korban) menjadi target kekerasan dari Jefri (pelaku) dan gengnya, yang kemudian diselamatkan oleh Panca (penyelamat).
Posisi Edwin sebagai 'korban sejati' ini sudah ditegaskan sedari babak prolog. Afirmasi visual terhadap narasi ini hadir dalam rentetan adegan: Edwin menyaksikan kakaknya diperkosa massal di depan matanya; Edwin dipukuli dan menjadi sasaran kekerasan masyarakat; Edwin menyamarkan identitasnya lewat jelaga di wajahnya; Edwin menatap rumahnya yang hangus terbakar (asumsi orangtuanya turut menjadi korban kebakaran).
Tapi, kendati struktur naratif awal itu tampak mengafirmasi skema ini secara ketat, narasi Edwin justru bergerak ke arah yang lebih kompleks. Semisal tetap berpegang pada kerangka Karpman, maka peran korban -- yang menurut Karpman dapat menjerumuskan seseorang pada ketidakberdayaan dan ketergantungan serta membuat mereka merasa 'tak lebih dari sekadar korban' -- tak berlaku secara total pada Edwin.
Sebagai korban, Edwin dalam narasi ini adalah karakter berdaya. Luka dan trauma yang dipikulnya -- yang mewakili memori kolektif diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia -- tidak digambarkan sebagai beban yang melumpuhkan. Trauma itu justru menjelma sebagai sumber kekuatan yang membentuk kepribadiannya yang kukuh dan tegar. Perhatikan bagaimana Edwin berjalan tegap (dibingkai dengan teknik kamera tracking low angle), cara dia menatap lawan bicara (Jefri) tanpa gentar, serta bagaimana ia mempertahankan prinsipnya sebagai guru yang tak mau tunduk pada teror muridnya sendiri.

Dengan begitu, meskipun film ini mengusung retorika korban yang berporos pada Edwin, ia menghindari jebakan dramatisasi sentimental yang mengemis air mata penonton. Inilah bentuk politik identitas dalam Pengepungan di Bukit Duri, wujud rhetoric of victimhood yang tak jatuh pada representasi korban sebagai subjek yang hadir hanya untuk dikasihani. Dengan cara ini, Joko berupaya mendobrak dominasi representasi minoritas arus utama lewat karakter Edwin.
Hanya saja, kompleksitas Edwin sebagai korban tak serta-merta mencerminkan keragaman representasi etnis Tionghoa secara menyeluruh. Rasanya terlalu dini dan tak adil untuk menyimpulkan penggambaran korban (representasi etnis Tionghoa) hanya lewat Edwin.
Walaupun memang, apabila boleh mengidentifikasi etnis Tionghoa lewat tampang oriental dan/atau aktor yang berperan, maka bisa dikatakan komunitas Tionghoa dalam film ini hanya diwakilkan lewat dua karakter saja (mengecualikan Edwin dan Silvi remaja di babak prolog), yakni Edwin (versi dewasa) dan bartender di Bar Wijaya, Vera (Shindy Huang).