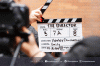Adegan yang saya maksud ialah adegan menjelang akhir dari dokumenter ini. Dalam adegan itu, Adi Rukun -- adik dari Ramli, salah satu korban pembantaian 1965 -- bertemu keluarga Amir Hasan, seorang pelaku eksekusi. Ketika Adi bersama Joshua menyampaikan kisah tentang tragedi yang menimpa keluarga Adi, salah satu anggota keluarga Amir Hasan memotong, "Tak usah dibuka-buka. Tak usah dipanjang-panjangkan masalah, Joshua!" Adegan rekonsiliasi penuh canggung itupun ditutup dengan potret wajah Adi dalam tatapan yang menggantung -- bisu tapi sarat makna.
Adegan ini, menariknya, justru menjadi cerminan bagaimana sebagian publik memandang film Senyap. Di antara banjir dukungan dan gemerlap apresiasi puluhan ajang perfilman internasional atas upaya pengungkapan sejarah yang penuh distorsi itu, sebagian kalangan justru mengkritik film Joshua sebagai karya provokatif, ditafsirkan sebagai upaya mengorek luka lama yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat (Laporan Komnas HAM).
Dan agaknya, Pengepungan di Bukit Duri menempuh jalur serupa -- meski berbeda isu dan bentuk (film). Jika Joshua menelusuri luka 1965 melalui dokumenter yang kontemplatif, Joko menyiasati sejarah lewat distopia fiksi near future yang menyimpan gema 1998. Keduanya menggunakan bingkai serupa: negara sebagai sponsor kekerasan, masyarakat yang dicekam rasa takut dan benci, serta impunitas yang membekas di tubuh sosial.
Film Joko maupun Joshua menghadapi dilema yang sama: apakah mengingat artinya menyembuhkan, atau justru mengoyak kembali?
Film semacam ini -- yang menggali ingatan kolektif -- tak bisa dielakkan dari tuduhan "mengorek luka lama". Akan tetapi, itu jugalah paradoksnya. Sebab, tidak akan ada pemulihan tanpa keberanian mengingat. Tak mungkin menyembuhkan luka sosial tanpa menatap bekasnya, meski dengan risiko menimbulkan rasa sakit. Dalam konteks ini, pengalaman menonton sudah bukan sekadar peristiwa konsumsi visual, melainkan bentuk partisipasi dalam ingatan kolektif -- sebuah "ritus trauma" dalam kemasan sinema.
Maka, yang penting bukanlah "seberapa akurat" film ini terhadap catatan sejarah 1998, melainkan: bagaimana ia memilih untuk mengingat, dan ingatan macam apa yang coba dibangkitkan dalam diri penontonnya. Seperti yang ditulis Lauren Ball dalam artikelnya "The Historical Value of Film", keakuratan bukan satu-satunya ukuran dalam film berdasar sejarah. Yang lebih esensial adalah bagaimana film mengaktifkan narasi-narasi yang ingin dikenang. Film bukan pengganti arsip, tapi jembatan emosi yang membuat sejarah itu terasa dekat, hidup, dan personal.
Dari sini, Pengepungan di Bukit Duri bisa dilihat sebagai kerja ingatan. Sebuah ajakan untuk menyaksikan ulang betapa kekerasan rasial bukan sekadar episode masa lalu, tapi bayang-bayang yang selalu mungkin datang kembali. Lewat ketegangan, kekerasan, dan konflik etnis yang digarap Joko dengan gaya dan estetika sinematiknya yang gamblang, film ini menyuguhkan semacam "spektakel trauma". Kita sebagai penonton diajak menatap penderitaan untuk memahaminya. Dan, beginilah cara film berbicara.
Maka, pertanyaannya bukan lagi: "Apakah film ini akan diterima semua orang?" Jawaban siapa pun tak akan cukup. Namun barangkali, trauma yang muncul dari tindakan menonton ini justru adalah harga yang sepadan demi kembali membuka ruang dialog, memperdebatkan sejarah, dan merawat ingatan akan sejarah bangsa yang, ada kalanya, diwarnai distorsi ini.[]
Daftar Referensi
Buku
- Aristoteles. 2018. Retorika (Seni Berbicara). Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- Bazin, Andr. 1967. What Is Cinema? Vol. 1. Berkeley: University of California Press. (Vol. 2, 1971).
- Bordwell, David & Kristin Thompson. 2013. Film Art: An Introduction (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hanich, Julian. 2018. The Audience Effect: On the Collective Cinema Experience. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Heryanto, Ariel. 2015. Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Imanjaya, Ekky & Hikmat Darmawan (eds.). 2019. Tilas Kritik: Kumpulan Tulisan Rumah Film (2007--2012). Jakarta: Komite Film Dewan Kesenian Jakarta.
- Kristanto, J. B. 2004. Nonton Film, Nonton Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pratista, Himawan. 2017. Memahami Film: Edisi 2. Yogyakarta: Montase Press.
- Sontag, Susan. 2003. Regarding the Pain of Others. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. "Can the Subaltern Speak?" Dalam Cary Nelson & Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, hlm. 271--313. Urbana: University of Illinois Press.
Artikel Jurnal / Prosiding
- Bleakley, Amy; Romer, Daniel; Jamieson, Patrick E. 2014. "Violent Film Characters' Portrayal of Alcohol, Sex, and Tobacco-Related Behaviors." Pediatrics 133(1): 71--77. https://doi.org/10.1542/peds.2013-1922
- Brand, Roy. 2008. "Identification with Victimhood in Recent Cinema." Culture, Theory and Critique 49(2): 165--181.
- Mulvey, Laura. 1975. "Visual Pleasure and Narrative Cinema." Screen 16(3): 6--18.
- Todorov, Tzvetan. 2001. "In Search of Lost Crime: Tribunals, Apologies, Reparations, and the Search for Justice." The New Republic, 29 Januari, hal. 29--36.
- Weaver, A. J., & Wilson, B. J. 2009. "The Role of Graphic and Sanitized Violence in the Enjoyment of Television Dramas." Human Communication Research 35(3): 442--463.
Laporan / Organisasi
- Komnas HAM. 2014. Senyap (The Look of Silence): Katalog Film Dokumenter. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sumber Daring
- Ball, Lauren. "The Historical Value of Film." Metahistory -- An Introductory Guide to Historiography. Diakses 23 Juni 2025 dari https://unm-historiography.github.io/metahistory/essays/thematic/film.html
- Bedard, Mike. 2025. "What Is Postmodernism? Definition and Examples for Filmmakers." StudioBinder, 2 Februari. Diakses 5 Juli 2025 dari https://www.studiobinder.com/blog/what-is-postmodernism-definition/
- Dunham, Brent. 2020. "What is Poetic Justice? Definition and Examples for Screenwriters." StudioBinder. Diakses 5 Juli 2025 dari https://www.studiobinder.com/blog/what-is-poetic-justice-definition-and-examples/
- Firdausi, Fadrik Aziz. 2020. "Wijkenstelsel & Passenstelsel: Mula Stigma Eksklusif Orang Tionghoa." Tirto.id, 29 Januari. Diakses 19 Juli 2025 dari https://tirto.id/wijkenstelsel-passenstelsel-mula-stigma-eksklusif-orang-tionghoa-euU6
- Heryanto, Ariel. 1999. "Republik Preman Indonesia: Analisis Sekumpulan Pengamat Asing tentang Situasi di Indonesia." Tempo, edisi 28 November, hlm. (PDF 1--2). Diunduh dari https://arielheryanto.wordpress.com (akses: 11 Juli 2025).
- Novita, Maychaella. 2020. "Menyingkap Distorsi Realitas di Media Sosial Bersama Guy Debord." Kumparan, 9 Desember. Diakses 6 Agustus 2025 dari https://kumparan.com/maychaella-novita/menyingkap-distorsi-realitas-di-media-sosial-bersama-guy-debord-1ukOMHEKwUA
- Prabangkara, Hugo Sistha. 2022. "Asyiknya Menjadi Masyarakat Penonton: Refleksi Konsep Spectacle ala Guy Debord." Nalarasa, 3 Maret. Diakses 6 Agustus 2025 dari https://nalarasa.com/2022/03/03/asyiknya-menjadi-masyarakat-penonton-refleksi-konsep-spectacle-ala-guy-debord/
- Pengepungan di Bukit Duri. 2025. IMDb. Diakses dari https://www.imdb.com/title/tt33479839/
- StudioBinder. "Postmodern Cinema." StudioBinder. Diakses 5 Juli 2025 dari https://www.studiobinder.com/blog/what-is-postmodernism-definition/
- Tranouli, Eleni. 2021. "Entering Maya Deren's 'Chamber Films'." Medium, 17 Maret. Diakses 28 Juli 2025 dari https://elenitranouli.medium.com/entering-maya-deren-chamber-films-bd14b6fdd092
- What Is Up, Indonesia? (WIUI). 2025. "Indonesia & the Horror That Hits Too Close to Home -- Joko Anwar." What Is Up, Indonesia? YouTube, 19 April. https://www.youtube.com/watch?v=K7QpXiTclO4 (diakses 23 Agustus 2025).
- Muzakki, Ahmad Zidan. 2023. "Tradisi-Tradisi Pinggiran: Perspektif Subaltern." Komplek-eL, 11 Mei. Diakses 2 Agustus 2025 dari https://komplek-el.com/tradisi-tradisi-pinggiran-perspektif-subaltern/
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI