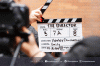Dari sana, Pengepungan di Bukit Duri dapat diterjemahkan bukan hanya sebagai kisah tentang korban kekerasan rasial, tetapi sebagai refleksi tentang bagaimana 'korban' itu dihadirkan -- baik sebagai tokoh maupun sebagai representasi. Tapi, Sebelum menyelami lebih jauh bagaimana film ini membangun narasi tentang 'korban' dan 'kekerasan', penting untuk terlebih dahulu memahami intensi ideologis sang sutradara atas film terbarunya ini.
Peringatan dari Joko Anwar
Sastrawan Rosihan Anwar pernah mengkritik banyak dari film Indonesia hanya menyuguhkan tontonan basic yang simplistik -- atau, sebut saja menyederhankan realitas -- dengan mengeskploitasi sensasi-sensasi dasar manusia (horor, seks, juga kekerasan). Jejak-jejak eksploitasi sensasi itu bahkan bisa kita rasakan sampai sekarang. Banyak di antaranya mewujud dalam genre horor.
Dalam Pengepungan di Bukit Duri, meski dipenuhi adegan kekerasan, Joko menolak menggunakan sensasi tersebut sebagai alat eksploitasi. Unsur-unsur kekerasan itu disandingkan dengan narasi "bercelah" yang relevan yang menuntut partisipasi aktif dari penontonnya.
Lewat adegan-adegan eksplisit penuh kekerasan verbal dan fisik, Joko tak hanya membingkai kekejaman sebagai tontonan artistik, tapi juga sebagai pengalaman emosional yang mengharuskan penonton turut merasa, terusik, dan berpikir. Joko berupaya menempatkan bioskop bukan sekadar ruang tonton, tapi juga tempat perenungan dan perlawanan atas "lupa kolektif".
Hal ini sejalan dengan pandangan Julian Hanich dalam "The Audience Effect on the Collective Cinema Experience (2018)", bahwa bioskop berpotensi mengubah cara kita memandang, merasakan, dan bereaksi terhadap realitas sehari-hari. Dan, itu yang coba dilakukan Joko lewat Pengepungan di Bukit Duri.
Pendekatan ini punya akar lebih dalam jika ditelusuri lewat sejarah pertemanan dan diskusi kreatif Joko. Sekitar tahun 2007, Joko sempat berdiskusi dengan Edwin -- sutradara Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021). Kala itu, Edwin bercerita kalau film debutnya, Babi Buta yang Ingin Terbang (2008), adalah manifestasi dari serangkaian pertanyaan menyangkut keresahan soal identitasnya sebagai, kata Edwin "keturunan Cina", yang tumbuh dalam bayang-bayang diskriminasi.
Ketika Joko bertanya apakah film itu bisa menjawab kegelisahan identitas tersebut, Edwin tak memberi jawaban pasti. Tapi paling tidak, kata Edwin, proses kolektif pembuatan film telah memberinya semacam ruang terapi, terutama saat ia berbagi pengalaman serupa dengan rekan setimnya, Sidi Saleh. Filmnya sendiri tak sampai menemukan jawaban atas pertanyaan identitas tadi.
Kesadaran akan "ketiadaan jawaban" itu terasa berkelanjutan dalam Pengepungan di Bukit Duri. Seperti Edwin, Joko tidak memberi penjelasan lugas atas musabab kebencian rasial yang menjadi latar cerita filmnya. Ia memilih membiarkan narasi itu menggantung, agar penonton bisa menyusun sendiri rantai kausalitasnya.
Kerusuhan yang tiba-tiba pecah (tanpa eksposisi) itu menyiratkan film ini tidak sedang bicara soal "sebab" dengan gaya didaktis-preachy. Pengepungan di Bukit Duri hadir sebagai proyeksi "akibat", sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah sentilan. Joko menyodorkan distopia sosial, di mana intoleransi, kekerasan, dan pengucilan etnis menjadi bagian dari lanskap hidup yang sudah "jadi".
Dan, seperti Edwin yang menggunakan film sebagai ruang penyembuhan personal, Joko pun, baik secara sadar maupun tidak, memosisikan film ini sebagai ruang trauma bagi penontonnya -- tempat di mana luka sejarah etnis Tionghoa bisa dikenang, dibicarakan, dan "dirasakan" ulang, khususnya bagi generasi yang tak mengalaminya.
Fungsi sosial ini terasa semakin penting ketika Joko menyadari banyak penonton muda -- khususnya Generasi Z -- tidak mengerti isu apa yang coba direpresentasi oleh film ini. Banyak dari mereka, lanjut Joko, tidak tahu tentang kerusuhan 1998. Beberapa bahkan tidak pernah mendengarnya. Maka, film ini tak hanya jadi produk ekspresi artistik, tetapi juga sarana edukasi sejarah, sebab "Kita tidak akan pernah bisa tumbuh sebagai bangsa jika tak mau dan tak berani membicarakan hal-hal sulit seperti ini," kata Joko dalam podcast di kanal YouTube What Is Up, Indonesia? (WIUI).