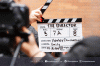Alih-alih berpaling dari semangat realisme, konsep near future Pengepungan di Bukti Duri justru jadi sarana untuk menyoroti realitas sosial-politik kontemporer secara alegoris. Kekerasan komunal, diskriminasi terhadap minoritas, serta absennya negara jadi kritik terhadap kondisi sosial masa kini yang dikemas dalam bingkai waktu spekulatif.
Oleh karena itu, rasanya tepat membaca film ini sebagai bentuk realisme distopik -- pendekatan yang menggunakan fiksi masa depan untuk mengungkap kondisi sosial yang sedang berlangsung. Contoh lain penggunaannya dapat dilihat dalam film lain, seperti Children of Men (2006), atau bahkan series anime Neon Genesis Evangelion (1995) yang menggunakan narasi masa depan untuk menggambarkan dampak perkembangan sains yang mencaplok kemanusiaan.
Dengan demikian, Pengepungan di Bukti Duri memadukan realisme fotografis (Bazin), dokumenter sosial (Kracauer), dan realisme batin (Tarkovsky). Kerja editingnya tidak memutus keterhubungan dengan realitas, melainkan memperluas pengertian realisme dari sekadar visual ke ranah psikologis dan afektif.
Realitas dalam film ini dikemas sebagai bentuk peyoratif dari konsep republik: Republik Preman. Bentuk negara distopik ini adalah istilah (atau, mungkin sindiran) yang saya pinjam dari sosiolog Ariel Haryanto saat ia menguraikan sekaligus mempertanyakan bagaimana permisifnya Indonesia, berikut pejabat pemerintah, terhadap premanisme dalam dokumenter The Act of Killing (2012) arahan Joshua Oppenheimer (Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia, 2015).
Dalam tulisannya, Ariel menguraikan beberapa adegan di film Joshua yang memperlihatkan mesranya hubungan antara kelompok preman dengan pejabat tinggi pemerintahan. Kata Ariel, dalam tulisan lain yang dimuat di Tempo, preman yang menguasai suatu wilayah tertentu menganggap wilayahnya bak 'negara' -- dalam negara -- dan mereka (preman) rajanya.
"Dalam keadaan stabil, preman adalah mitra terbaik bagi pejabat maupun pengusaha," tulis Ariel, dikutip dari Tempo.
Sejalan dengan Ariel, sebagai sebuah film 'peringatan', agaknya realitas yang mengadopsi Republik Preman ini sengaja dipilih untuk -- seperti kata Roy Armes saat memaparkan tujuan dari karya realisme -- mempertanyakan (sekaligus menguraikan) realitas yang tak kondusif di Indonesia. Film ini terasa dibangun dengan fondasi berbahan baku pembentukan sebuah negara preman. Indikasinya hadir dalam; aksi premanisme, kuasa yang gratis, pemerintah yang absen, sampai interaksi sosial disosiatif yang, selain tampak dari kerusuhan massal, juga ada pada pecakapan-percakapan off/on screen dan visual bangunan termasuk coretan vandalisme (grafiti) bernada pengenyahan.
Republik Preman itu terbentuk sejak babak prolog (dalam struktur skenario, jelang akhir babak pertama film, merupakan tahap terbentuknya dunia cerita yang baru bagi karakter: Republik Preman). Adegan pokoknya ada saat kamera menampilkan telapak tangan karakter Panca digores oleh perusuh yang dilanjutkan dengan perobekan baju Silvi, kakak Edwin, dalam adegan rudapaksa yang enggan disorot kamera (panning).
Pembacaan atas adegan ini bisa saja metaforis meski terkesan wagu: Panca dan Silvi sebagai wujud Pancasila yang "terluka". Tapi yang pasti, aksi nista terhadap Panca dan Silvi, pada gilirannya, memicu kemunculan seorang "anak haram" (meski merujuk pada Jefri, sebutan ini, secara luas, saya gunakan untuk mendefinisikan Jefri sebagai simbol dari generasi yang lahir dari trauma sosial dan kebencian rasial) di masa depan, yang terpaksa hidup dalam lingkaran kekerasan dan kebencian.
Tragedi itu berlangsung cepat. Narasi loncat ke tahun 2027 di mana Edwin (Morgan Oey) sudah dewasa. Trauma masa lalu itu telah membentuknya menjadi pribadi. Sebagai guru seni, Edwin berpindah dari sekolah ke sekolah untuk menemukan si "anak haram" demi -- seperti janjinya kepada Silvi -- menyampaikan permintaan maaf kakaknya karena telah menelantarkannya.
"Anak haram" itu menjadi cerminan dominan republik buatan Joko. Representasi kondisi masyarakat yang sibuk pada perdebatan usang mana yang "Indonesia" dan mana yang "tak-Indonesia". Masyarakat yang mempertahankan prinsip "mayoritas di atas minoritas". Ia gandrung akan kuasa, rasa hormat, dan ditakuti; lewat aksi persekusi etnis Tionghoa. Tapi di sisi lain, "anak haram" itu juga menawarkan perlindungan bagi mereka yang mau bergabung dengan kelompoknya dalam memberantas apa yang dikonfirmasi masyarakat sebagai yang "bukan bagian dari kami". Dan, "anak haram" itu adalah Jefri (Omara Esteghlal), anak yang selama ini dicari-cari oleh Edwin.