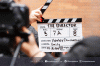Sorotan istimewa pada luka-luka itu mengkonstruksi tubuh Jefri sebagai simbol kekuasaan dan luka sejarah. Dalam satu adegan penyanderaan, Jefri bahkan memamerkan bekas luka di tubuhnya sambil berkata: "Lu kenapa, sih? Cengeng banget, gitu doang. Itu enggak ada apa-apanya dibanding yang ini," kata Jefri sambil menarik bajunya dan membiarkan kamera mengabadikan tubuhnya.
Perlakuan kamera terhadap tubuh Jefri (tubuh laki-laki) mirip dengan pandangan Laura Mulvey dalam "Visual Pleasure and Narrative Cinema" (1975) di mana kamera dalam sinema konvensional sering kali menempatkan perempuan sebagai objek erotis bagi mata laki-laki (male gaze). Hanya saja, dalam film ini, kamera mengalihkan gaze itu ke tubuh laki-laki penuh luka dengan framing yang tidak erotis, melainkan heroik dan traumatik. Tubuh laki-laki menjadi situs pembuktian maskulinitas melalui penderitaan. Adegan Jefri memperlihatkan luka di tubuhnya kepada kamera (dan penonton), merupakan bukti bahwa ia pantas ditakuti dan dihormati.
Seiring dominasi visual terhadap karakter laki-laki, Pengepungan di Bukit Duri membuka ruang analisis tentang relasi kuasa yang bekerja melalui tubuh. Sebab tubuh bukan sekadar entitas biologis, melainkan lokasi strategis di mana kuasa bekerja dan ditanamkan.
Dalam film ini, tubuh Jefri bukan hanya tempat luka tertanam, tapi juga simbol prestise sosial. Kamera menyorotnya secara intens (termasuk saat adegan Jefri menurunkan celananya di hadapan Edwin dan Darmo), memperlakukan bekas luka sebagai tanda legitimasi dalam hierarki kekerasan. Luka, dalam Pengepungan di Bukit Duri, menjadi bahasa kekuasaan: semakin dalam bekasnya, semakin tinggi posisinya di piramida premanisme.
Menariknya, perlakuan film ini terhadap Jefri dan Edwin juga dapat dibaca melalui lensa hegemonic masculinity. Maskulinitas dominan -- yang diasosiasikan dengan kekuatan, dominasi, dan penguasaan ruang publik -- menjelma secara ekstrem dalam karakter Jefri. Sedangkan, karakter seperti Edwin justru mewakili bentuk maskulinitas subordinat: terpelajar, minoritas, dan sering kali berada di ruang domestik atau aman. Dengan begitu, pergulatan Edwin dan Jefri -- yang menjadi suguhan utama film ini -- bukan hanya soal kekuasaan etnis, tapi juga tentang dua model maskulinitas yang saling menegaskan satu sama lain.
Namun, seperti juga Edwin dan Pak Darmo, "rasa takut", yang menjadi hantu dilema dalam Republik Preman, juga berlaku pada maskulinitas dominan Jefri.
Menjelang akhir film, identitas Jefri terungkap (sebagai keturunan Tionghoa). Tubuh Jefri (yang diasosiasikan dengan maskulinitas dominan) yang di-framing sebagai laki-laki perkasa, nyatanya menyimpan kerapuhan. Di titik ini, tabiat Jefri dengan berlagak membenci, memburu, dan memukuli siswa keturunan Tionghoa, bahkan memanggil mereka dengan sebutan "babi", menjadi kompleks dalam ranah tafsir.
Selain dapat dibaca sebagai manifestasi atas otoritas serampangan khas preman, perilaku tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai cara dia menyembunyikan identitasnya. Ini adalah mekanisme pertahanan, penyangkalan, bahkan bentuk ekstrem dari internalized racism Jefri. Pengungkapan identitas Jefri sebagai keturunan Tionghoa pun disuguhkan dalam adegan yang penuh ledakan emosi: Jefri merekam sendiri adegan pembunuhannya lantas memaki (penonton) sambil menatap kamera ponsel yang ia gunakan; "Emang iya gue Cina. Nyokap gue Cina, diperkosa ramai-ramai. Senang elo? Bokap gue banyak. Gue kayak kolam p*ju, kayak tempat sampah. Senang elo anjing. Ngento* elo semua!" teriak Jefri.
Jika disatukan, aspek-aspek ini -- Republik Preman, relasi gender dan maskulinitas, serta tubuh sebagai medan kuasa -- memperlihatkan bahwa Pengepungan di Bukit Duri bukan sekadar film aksi distopik. Ia adalah refleksi multidimensi atas kondisi sosial Indonesia di mana kuasa tidak diperoleh lewat legitimasi moral atau institusional, tetapi lewat tubuh yang terluka dan sistem yang merawat kekerasan sebagai norma.
Tapi, dengan dunia cerita yang sarat aksi dan politik tubuh laki-laki itu, apakah film ini, dalam lingkup rhetoric of victimhood, membuka ruang empati bagi penontonnya atas 'korban' yang ditampilkan atau justru menawarkan visual yang menyulap penderitaan itu menjadi tontonan yang menghibur?
Bagian II: Para Korban dan Kekerasan
Catatan penting dalam esai Brand mengenai paradigma narasi kekorbanan ini, ia mengeksplorasi keterkaitan erat antara trauma, kekerasan, dan proses identifikasi diri sebagai korban dengan mengklaim bahwa dalam era modern, figur korban dan pelaku terus berputar (perebutan status korban) menciptakan konflik baru.