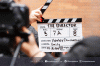Sebagai proyeksi 'akibat', Joko menyajikan film ini dengan pendekatan ala sinema postmodern. Seperti para sutradara pasca 1970-an yang gemar mendobrak ekspektasi publik akan gaya dan struktur naratif, Joko dengan sadar menggunakan ironi dan kekerasan eksplisit untuk menggambarkan trauma secara immersive.
Dengan keluwesan postmodern, unsur kekerasan dalam rhetoric of victimhood Pengepungan di Bukit Duri jadi ironi yang perlu untuk diumbar dan dipertontonkan. Kamera tidak berpaling dari adegan sadis seperti pembacokan, pembakaran, dan pengeroyokan. Gaya sinematografi Jaisal Tanjung (Dop) -- kamera handheld, zoom, pan, dan tilt yang spontan -- mempertegas estetika kekerasan yang realis dan mentah. Kekerasan ini tidak ditampilkan ala Quentin Tarantino, misalnya, yang penuh koreografi, melainkan sebagai pengalaman visual yang menyuntikkan rasa takut ke tubuh penonton. Atau, dengan kata lain, gambar yang sadis ini menjelma perasaan tidak nyaman yang entertaining.

Perasaan "terhibur" ini sejalan dengan studi "Violent Film Characters' Portrayal of Alcohol, Sex, and Tobacco-Related Behaviors" (2014), yang menemukan sekitar 90% film yang berpendapatan tinggi menampilkan adegan karakter utama yang terlibat dalam kekerasan. Unsur kekerasan dalam film kerap jadi jaminan keseruan cerita.
Efek ini senada dengan gagasan Susan Sontag, bahwa gambar-gambar kekerasan dapat sekaligus mengguncang dan menghibur. Ada paradoks dalam menyaksikan penderitaan sebagai tontonan. Kekerasan dalam film Joko ditampilkan bukan hanya untuk menggambarkan realitas, tapi juga untuk memancing efek emosional: keterkejutan, keterpukauan, atau bahkan kenikmatan estetis.
Pada tingkat sinematik, Pengepungan di Bukit Duri memperkuat paradoks ini. Kita menyadari bahwa kekerasan dan penderitaan dalam film ini dipoles menjadi bagian dari estetika visual. Ia indah, dramatis, tapi juga tak jarang menumpulkan empati.
Ketegangan situasi melalui penggambaran ruang-ruang yang penuh grafiti bernada pengenyahan, umpatan rasis, konflik sektarian, serta adegan kekerasan yang, tak jarang, tampil beriringan dengan musik atau dialog humor, dapat menjelma bentuk estetisasi kekerasan. Adegan pemukulan remaja Tionghoa yang diiringi musik up beat adalah contoh paling mencolok bagaimana kekerasan disulap menjadi tontonan yang nyaris menghibur (adegan yang saya maksud adalah adegan saat dialog "Iiih darah babi" terlontar).
Dalam lanskap budaya visual yang sarat spectacle seperti Indonesia kontemporer, kekerasan menjadi komoditas visual yang menjual. Guy Debord, dalam esai yang telah disebut di muka, mengingatkan bahwa masyarakat modern hidup dalam representasi yang telah menggantikan realitas itu sendiri. Selain sebagai fakta sosial, kekerasan dalam film jadi semacam pertunjukan: sesuatu yang ditonton, dikonsumsi, dan dirayakan.
Namun, sedari awal Joko sudah mewanti-wanti penonton bahwa semua bentuk kekerasan yang mereka saksikan adalah semata film atau realitas rekaan yang, dalam satu dan lain hal, adalah bagian dari "hiburan". Itu tampak, misalnya, melalui lagu "Guruku Tersayang" yang non-diegetic, atau manipulasi pergerakan waktu dari 2009 ke 2027, yang hanya bisa dilakukan oleh film (kerja editing). Maka, kekerasan yang disaksikan dapat dipahami penonton sebagai sebuah atraksi filmis semata (yang telah dijahit sedemikian rupa di ruang edit).
Tapi justru di situlah jebakannya. Dalam permainan "hiburan kekerasan" ini, figur korban bisa tergelincir menjadi ornamen. Kekerasan berakhir menjadi spectacle. Condongnya film ini dalam menyajikan alternatif 'hiburan' berupa kekerasan realis yang atraktif penuh tegang terkadang menjadi selimut yang terlampau tebal. Penuhnya wujud 'korban' dalam film ini pun -- baik simbolik maupun literal -- jadi sulit ditampung dan diberi "suara" dan/atau "wajah" oleh Joko.
Salah satu film yang mampu keluar dari jebakan spectacle itu adalah film debutan Rungano Nyoni, I Am Not a Witch (2017). Di Film ini, Nyoni meramu kekerasan struktural dan budaya terhadap perempuan di Zambia dengan latar dan pemain non-profesional dalam bingkai visual yang penuh ironi dan nyaris surealis. Kisah Shula, gadis kecil yang dituduh sebagai penyihir dan diasingkan ke kamp bersama para "penyihir" lainnya, memang disampaikan dengan pendekatan estetika yang mencolok, seperti panorama gersang kering kelontang Zambia, kostum dengan warna-warna kontras, serta penggunaan musik klasik yang memberi nuansa teatrikal.