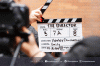Tetapi, alih-alih menjadikan penderitaan Shula sebagai tontonan "indah" yang menjauhkan penonton dari kenyataan brutal yang ia alami, pendekatan estetis ini justru punya peran penting dalam mempertegas absurditas sistem masyarakat yang menindasnya. Kekerasan yang dialami Shula dibingkai sebagai rutinitas banal yang memilukan. Visual yang tampak "indah" itu justru memperbesar ketimpangan antara bentuk dan isi: memaksa penonton merenungkan absurditas sistem patriarki dan kolonial yang masih hidup dalam tubuh negara postkolonial. Shula jarang bicara, namun kehadirannya yang diam -- sering diposisikan secara visual sebagai pusat komposisi gambar -- menjadi bentuk perlawanan. Di tangan Nyoni, estetika itu menjadi alat untuk mendedahkan trauma dengan cara yang menuntut keterlibatan penonton secara emosional maupun etis.
Adegan-adegan kekerasan yang atraktif dan shocking itu memang identik Joko. Menyaksikan film Joko berarti harus siap dengan unsur-unsur eksplisitnya. Mungkin beginilah cara Joko mendudukan kembali film sebagai "media hiburan" -- seperti yang sering ia katakan. Joko ingin penonton terhibur setelah meluangkan waktu menyaksikan karyanya, sembari berharap, social commentary dalam film dapat terbaca dan memantik diskusi di kalangan penonton.
Dengan mendudukan kembali film sebagai "media (hiburan)", tentu penggambaran korban akan selalu dibarengi etika. Mungkin sisi etika ini menjadi rem bagi film Joko ketika kehadiran korban -- yang beberapa hadir tanpa "suara" dan berkali-kali menjadi sasaran kekerasan -- rentan dan nyaris terjerumus menjadi "keindahan sinematis" semata yang menumpulkan empati.
Korban dalam lingkup "media" mendapat perlakukan khusus guna menyelamatkan mereka dalam bingkai eksploitasi. Dan sebagai generasi 'anak nakal' perfilman Indonesia, Joko bermain di batas bingkai itu.
Dalam penelitian lain (The Role of Graphic and Sanitized Violence in the Enjoyment of Television Drama, 2009), ditemukan bahwa, baik film yang memuat adegan kekerasan maupun ketika adegan kekerasan itu dihilangkan (sampel film yang sama), tidak mereduksi kepuasan penonton dalam menonton filmnya. Maka rasanya cukup sahih untuk mengatakan, barangkali, yang dinikmati oleh penonton adalah menyaksikan karakter jahat mendapat ganjaran setimpal, bukan kekerasan itu sendiri. Atau, dengan kata lain, penonton menantikan semacam poetic justice (keadilan puitik). Di sinilah bingkai etika itu terlihat.
Joko tampak berupaya menyeimbangkan daya hibur dengan tanggung jawab etis. Ia hadirkan semacam poetic justice yang menyamankan hati penonton: Jefri yang penuh kekerasan akhirnya mati. Tapi bentuk poetic justice yang lebih retoris muncul ketika tokoh-tokoh yang sebelumnya tunduk pada kekerasan (Dotty, dan dua anggota geng Jefri lainnya) memilih pergi dan mengejar "masa depan" (meninggalkan Jefri) dengan diiringi teriakan Edwin: "Dia ini pembunuh. Kalian bukan pembunuh. Kalian masih punya masa depan. Pergi!"
"Masa depan" menjadi kata kunci dari kemungkinan membebaskan diri dari warisan kekerasan dan trauma. Tetapi jalan menuju ke sana tidak pernah mudah. Dialog Khristo menunjukkan bahwa rasa takut dan keengganan berempati telah menjadi penghalang kolektif, "Harusnya kita gak ikut lari, kita gak ada masalah apa-apa sama mereka," kata Khristo saat adegan awal pengepungan.
Pendirian Khristo ini pun tak mengalami perubahan. Saat ia dan Bu Dinda berhasil melarikan diri, lalu Bu Dinda hendak kembali untuk membantu Edwin, Khristo kembali berujar, "Kalau saya sendiri, nanti saya ditangkap sama mereka, Bu," Kalimat ini menandai bahwa dalam masyarakat yang kehilangan solidaritas, masa depan selalu dibayangi rasa takut dan ketidakpedulian.
Sampai akhir film, Pengepungan di Bukit Duri tidak menawarkan solusi apa pun (dan memang tak perlu). Tetapi film ini berhasil menginterogasi struktur yang melanggengkan budaya kekerasan: sistem, simbol, dan spectacle. Ia juga menyibak ironi kekorbanan -- yang merasa diri korban, tetapi justru menjadi pelaku. Ia menyentil budaya populer yang menikmati kekerasan, sembari menampilkan bagaimana perempuan dan minoritas tetap menjadi yang paling bisu di antara kerumunan.
Bagian III: Epilog
Sepulang menyaksikan film ini di bioskop bersama teman saya, seperti biasa, kami mampir ke warung kopi terdekat -- ritual wajib yang kami lakukan untuk membicarakan film yang baru kami tonton, mumpung ingatan masih segar. Setelah berlarut-larut membicarakan yang asyik dan yang tidak asyik dari film ini, obrolan kami makin lama mengerucut ke soal respons penonton, faktor yang kerap luput dari perhatian kami, dua orang penggemar film Jokan; "Gimana ya perasaan orang Tionghoa kalau nonton film ini? Kesel gak ya?" Pertanyaan ini bukan cuma soal materi filmnya, tapi juga soal menatap kembali luka sejarah itu.
Sebagai orang yang juga minoritas (Arab), cukup lama saya memikirkan pertanyaan itu. Bahkan konyolnya, saya sempat mengandaikan Pengepungan di Bukit Duri mengambil sudut pandang karakter keturunan Arab di Indonesia yang mengalami kekerasan rasial di filmnya. Sampai akhirnya, terlintas salah satu adegan paling powerfull di jagat perfilman (atau, tentang) Indonesia, terutama yang membahas luka sejarah; The Look of Silence (Senyap, 2014) karya Joshua Oppenheimer.