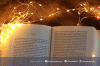Apa jadinya jika Batman jadi ojek online atau Ratu Elizabeth kerja di warteg? Itulah dunia parodi, dunia alternatif yang dibangun dari tiruan, tapi penuh tawa dan kritik tersembunyi.
Komedi parodi adalah cabang humor yang mengolok-olok atau meniru gaya karya lain secara berlebihan, biasanya dengan tujuan lucu, sindiran, atau keduanya.
Parodi bisa hadir dalam bentuk sketsa, lagu, film, video pendek, hingga meme. Tapi untuk jadi parodi, ia harus punya satu syarat: penonton harus tahu bahwa ini tiruan dari sesuatu yang sudah ada.
Asal-usul dan Sejarah Parodi
Kata parody berasal dari bahasa Yunani kuno paridia, gabungan dari kata para- (bersebelahan atau melawan) dan id (lagu atau puisi). Artinya kira-kira: "lagu tandingan."
Dalam era klasik, penyair seperti Aristophanes sudah menggunakan parodi untuk menyindir tokoh politik dan karya sastra populer pada zamannya.
Di abad pertengahan hingga era Renaisans, parodi berkembang dalam pentas-pentas rakyat sebagai bentuk hiburan dan kritik terhadap Gereja atau kerajaan.
Contoh paling terkenal adalah Don Quixote karya Miguel de Cervantes (1605), yang memarodikan roman ksatria kuno secara cerdas dan lucu.
Masuk ke abad modern, parodi menjadi bagian penting dari dunia hiburan: dari teater, film, hingga media sosial.
Ia bukan hanya untuk membuat orang tertawa, tapi juga untuk menggugat norma, menggoda yang mapan, dan membuka mata lewat cara yang ringan.
Ciri Khas Parodi
Untuk mengenali atau menulis parodi, kamu harus paham unsur dasarnya:
Mengenali sumber asli.
Parodi selalu berangkat dari sesuatu yang sudah dikenal luas: film, lagu, tokoh, gaya bicara, atau ide populer.Melebih-lebihkan atau membelokkan.
Teknik utamanya adalah exaggeration atau twist. Bayangkan film "Titanic" diparodikan dengan kapal bebek, atau drama Korea yang tokohnya kepleset saat adegan romantis.Ada unsur kritik atau pembacaan ulang.
Parodi bukan sekadar lucu. Ia bisa menyentil klise, ketimpangan, bahkan ideologi tersembunyi dalam karya aslinya.Butuh konteks.
Jika penonton tak tahu yang diparodikan, mereka tak akan menangkap kelucuannya. Karena itu, parodi sering ditujukan untuk penonton yang "melek budaya."
Parodi vs Satire: Mirip Tapi Beda Arah Tertawanya
Banyak orang mengira parodi dan satire itu sama, padahal keduanya punya pendekatan berbeda meski sama-sama mengundang tawa dan kritik.
Parodi biasanya fokus pada gaya atau bentuk suatu karya. Ia meniru, lalu membelokkannya menjadi lucu. Objek yang diparodikan bisa berupa film, lagu, gaya bicara, iklan, bahkan gaya berpakaian tokoh terkenal.
Misalnya, ketika sinetron Indonesia diparodikan dengan adegan lebay, efek suara dramatis, atau logika cerita yang sengaja dibikin tidak masuk akal, itu parodi. Yang ditertawakan adalah bentuk dan gayanya.
Sementara itu, satire lebih menyorot pada isi atau substansi. Ia tidak selalu meniru, tapi lebih kepada menyindir fenomena sosial, perilaku tokoh publik, atau kebijakan tertentu dengan gaya tajam dan kritis.
Nada satire seringkali terasa lebih pahit, sinis, bahkan getir, meskipun dikemas dalam bentuk humor.
Contohnya, acara seperti Last Week Tonight oleh John Oliver atau konten editorial ala New York Times bisa menyisipkan satire terhadap politik atau kebijakan negara. Mereka tidak meniru gaya siapa pun, tapi menyampaikan sindiran tajam lewat analisis lucu.
Jadi, sederhananya: parodi menertawakan bentuk, satire menertawakan isi.
Parodi bisa terasa ringan dan lucu, sementara satire cenderung menggigit dan membuat kita berpikir lebih dalam setelah tertawa.
Meski begitu, keduanya sering tumpang tindih. Sebuah parodi bisa mengandung satire jika plesetan itu menyentil ideologi, kebijakan, atau perilaku sosial tertentu.
Maka, banyak karya humor modern yang memainkan keduanya sekaligus---tertawa karena lucu, lalu diam karena merasa "tersindir."
Parodi di Dunia Modern
Di era digital, parodi berkembang pesat dalam berbagai bentuk:
Film & TV: Austin Powers, Spaceballs, dan Scary Movie adalah film-film yang memarodikan genre atau film terkenal.
YouTube & TikTok: Banyak konten kreator membuat parodi iklan, sinetron, film pendek, bahkan berita. Misalnya parodi sinetron "Azab" yang melebih-lebihkan adegan pamali jadi lelucon visual.
Media sosial: Meme yang memarodikan tokoh publik, gaya caption selebriti, atau pidato politikus viral adalah bagian dari humor parodik.
Di Indonesia, kita punya Warkop DKI, Project Pop, Majelis Lucu Indonesia, hingga akun seperti @ngakakkocak dan @awreceh.id yang rutin memproduksi konten parodi berbasis budaya pop lokal.
Tips Menulis Parodi yang Baik
Pilih objek yang populer dan relevan.
Parodi harus bisa dikenali dengan cepat. Pilih karya atau tokoh yang sedang tren.Amati gaya aslinya secara mendalam.
Kalau ingin memarodikan sinetron, pahami gaya bicara, latar musik, logika cerita, dan kostumnya.Cari celah kelucuan.
Bisa berupa klise yang diulang, logika yang aneh, gaya bicara yang terlalu dramatis, atau kostum yang norak.Jaga etika dan hindari penghinaan personal.
Parodi yang baik menertawakan ide, bukan menyakiti orang.Berikan twist tak terduga.
Kombinasikan dua hal yang bertabrakan. Misalnya, tokoh Naruto kerja di kantor kelurahan. Lucu karena tak cocok, tapi tetap nyambung.
Tawa yang Datang dari Tiruan
Parodi mengajarkan kita untuk menertawakan budaya yang kita konsumsi. Ia bukan sekadar pengulangan, tapi reinterpretasi. Dan justru dari situ muncul ketawa---karena kita menyadari betapa lucunya dunia yang selama ini kita anggap serius.
Dalam dunia yang penuh absurditas, kadang parodi justru jadi bentuk kejujuran paling jenaka.***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI