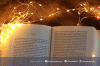Kata Menkeu Purbaya, "saya punya uang Rp425 triliun di BI. Dari jumlah itu, Rp200 triliun mau saya pindahkan ke sistem perbankan." Begitu kata Purbaya. Kalimat itu sederhana. Tapi implikasinya rumit.
Di balik angka itu, ada persoalan klasik: apakah dana Rp200 triliun yang dipindahkan itu murni kas operasional APBN, atau ada porsi yang menggerus SAL (Saldo Anggaran Lebih), bantalan fiskal yang mestinya jadi cadangan darurat?
Pertanyaan ini bukan soal semantik. Ini soal disiplin fiskal. Dalam kerangka UU No. 17 Tahun 2003, SAL ditetapkan sebagai instrumen budget financing.
Secara teori fiskal, SAL sebaiknya jadi rainy day fund, bukan rekening giro. Undang-undang Keuangan Negara pun mensyaratkan penggunaannya dengan otorisasi DPR lewat APBN atau APBN-P.
Artinya, SAL hanya boleh dibuka kalau sudah ada persetujuan politik-anggaran. Menkeu memang berhak mengelola kas, tetapi tidak bisa begitu saja memperlakukan SAL sebagai likuiditas jangka pendek.
Fungsinya jelas: shock absorber, cadangan risiko fiskal, mekanisme countercyclical policy. Ia adalah fiscal buffer. Artinya, ia hanya boleh digunakan bila sudah diotorisasi DPR melalui UU APBN atau APBN-P.
Praktiknya, kas pemerintah di BI total Rp425 triliun itu adalah campuran. Ada penerimaan pajak, hasil penerbitan SBN, penarikan pinjaman, dan sebagian bisa saja dari penarikan SAL.
Pemerintah lalu memindahkan Rp200 triliun ke bank umum. Alasan resminya: cash management. Dana yang idle bisa diubah jadi likuiditas perbankan.
Bank lebih siap menyalurkan kredit. Ekonomi pun diharapkan berdenyut. Masalahnya: bagaimana kalau sebagian Rp200 triliun itu sesungguhnya mengambil napas dari SAL?
Lebih jauh lagi, uang pemerintah yang parkir di BI itu sebenarnya tidak sepenuhnya menganggur. Selama ini, dana tersebut juga menjadi underlying asset bagi SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia).