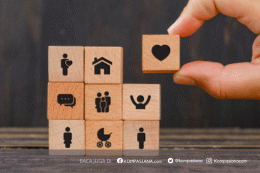Didesa kecil pinggiran kabupaten, seorang bocah berjalan tanpa alas kaki menuju sekolah yang hampir roboh. Ia membawa buku tipis yang sampulnya sudah lusuh, sementara di kejauhan terdengar suara bising sepeda motor anak-anak sekolah internasional yang melaju kencang ke arah gedung mewah berpendingin udara. Pemandangan itu seperti panggung dunia yang timpang. Ada anak yang belajar dengan perut kosong, ada pula yang sejak kecil sudah dipenuhi vitamin otak, les bahasa asing, hingga gawai canggih untuk menunjang belajarnya. Dua dunia itu sama-sama ada di negeri ini, berdampingan, namun seperti hidup di planet yang berbeda. Di titik inilah kita memahami, bahwa sejak seorang anak masih dalam kandungan, jalan hidupnya sudah ditentukan oleh privilese.
Jejak Privilege dalam Dunia Pendidikan
Ketika masyarakat ramai membicarakan artis besar yang mendapatkan beasiswa bergengsi, sebagian publik bertanya dalam hati. Mengapa seseorang yang sudah jelas-jelas punya akses finansial, koneksi luas, dan reputasi mentereng masih perlu mengambil jatah yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Pertanyaan itu bukan soal iri hati, melainkan refleksi atas kenyataan yang kita hadapi bersama.
Sejak awal, individu yang lahir dari keluarga berpunya sudah ditempa dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Nutrisi berkualitas, fasilitas kesehatan terbaik, dan stimulasi intelektual diberikan tanpa kompromi. Mereka masuk ke sekolah berstandar internasional dengan biaya yang fantastis, dibimbing guru asing, bahkan punya kesempatan belajar musik klasik atau seni rupa sejak dini. Sementara itu, di pelosok negeri, banyak anak yang bahkan harus bergantian memakai satu buku tulis untuk tiga mata pelajaran berbeda.
Ketika proses seleksi beasiswa berbasis meritokrasi dibuka, siapa yang paling siap? Tentu mereka yang sejak kecil ditempa dengan berbagai privilege. Mereka datang dengan portofolio cemerlang, skor tes bahasa yang tinggi, pengalaman organisasi di luar negeri, dan surat rekomendasi dari tokoh terkemuka. Sementara anak-anak dari keluarga sederhana sering kali bahkan tidak tahu bagaimana cara mendaftar, apalagi membayar biaya ujian bahasa internasional yang bisa menelan jutaan rupiah. Maka wajar jika muncul anggapan bahwa meritokrasi tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial hanyalah perpanjangan dari diskriminasi sejak dalam kandungan.
Fenomena artis atau figur publik mendapatkan beasiswa adalah cermin yang memperlihatkan wajah paradoks sistem kita. Di satu sisi, beasiswa memang berbasis prestasi akademik, terbuka bagi siapa saja yang lolos seleksi. Namun di sisi lain, sulit untuk menutup mata dari kenyataan bahwa peluang untuk “lolos” itu jauh lebih besar bagi mereka yang punya modal sosial, ekonomi, dan kultural sejak dini.
Pertarungan Antara Prestasi dan Keadilan Sosial
Pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa negara menyediakan beasiswa. Apakah semata untuk merayakan kecemerlangan individu, ataukah sebagai instrumen pemerataan kesempatan? Jika tujuan utamanya adalah mobilitas sosial, maka seharusnya beasiswa diprioritaskan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga yang tidak mampu. Jika tujuan utamanya adalah menjaga daya saing global, maka meritokrasi bisa dijadikan tolok ukur utama. Namun yang terjadi sekarang adalah pencampuran tanpa batas yang sering menimbulkan kebingungan publik.
Ambil contoh beasiswa LPDP yang didanai dari uang rakyat. Ketika publik melihat seorang selebriti sukses mendapatkan beasiswa tersebut, muncul pertanyaan etis. Apakah tepat dana publik digunakan untuk membiayai orang yang sebenarnya mampu membayar sendiri? Apakah tidak sebaiknya beasiswa itu diberikan kepada anak kampung yang jenius, tetapi gagal melanjutkan sekolah karena tidak punya uang untuk ongkos bus ke kota?
Masalah ini bukan sekadar persoalan siapa yang lebih pintar atau lebih layak. Ini adalah persoalan keadilan sosial. Banyak anak dari desa atau keluarga miskin yang sebenarnya memiliki kapasitas intelektual luar biasa, namun terhambat oleh gizi buruk, sekolah yang kekurangan guru, atau ketiadaan akses internet. Mereka kalah bukan karena bodoh, melainkan karena arena pertandingan tidak pernah setara. Di sinilah muncul istilah diskriminasi sejak dalam kandungan, karena sejak lahir hingga dewasa, sebagian anak selalu berada di posisi yang kalah dalam struktur sosial.
Namun tidak berarti beasiswa berbasis prestasi harus dihapuskan. Justru yang perlu dilakukan adalah diferensiasi yang jelas antara beasiswa untuk prestasi murni dan beasiswa untuk afirmasi kebutuhan. Beasiswa prestasi tetap diberikan untuk menjaga standar akademik, namun porsinya jangan mendominasi. Beasiswa afirmasi harus diperluas, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, daerah tertinggal, atau kelompok minoritas yang sering terpinggirkan. Transparansi distribusi juga sangat penting agar publik tahu berapa banyak dana dialokasikan untuk prestasi dan berapa banyak untuk pemerataan.
Jika reformasi ini dilakukan, beasiswa bisa berfungsi ganda. Ia tetap menjadi panggung meritokrasi bagi yang berprestasi, sekaligus menjadi tangga mobilitas vertikal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, beasiswa tidak lagi dipersepsikan sebagai hadiah untuk orang yang sudah berada di atas, melainkan sebagai instrumen sosial untuk membongkar lingkaran ketidakadilan.
Membongkar Mitos Meritokrasi
Dalam perdebatan ini, sering muncul argumen bahwa prestasi adalah hasil kerja keras pribadi. Namun jika kita menelusuri lebih dalam, kerja keras itu hampir selalu didukung oleh struktur sosial yang berpihak. Seorang anak yang tumbuh di rumah dengan rak penuh buku, orang tua berpendidikan tinggi, dan guru privat tentu memiliki modal yang berbeda dengan anak yang membantu orang tuanya di sawah sejak kecil dan belajar hanya dengan cahaya lampu minyak.
Meritokrasi murni sering kali hanyalah mitos yang menutupi kenyataan tentang ketidaksetaraan kesempatan. Prestasi akademik bukan semata hasil usaha individu, tetapi juga hasil akumulasi modal sejak lahir. Ketika seseorang yang sudah punya privilese kemudian mendapatkan beasiswa bergengsi, maka sesungguhnya negara sedang mengakui keunggulan yang sudah terjamin sejak awal, bukan memberi kesempatan baru.
Dalam kerangka ini, wajar jika publik mempertanyakan keadilan distribusi beasiswa. Tidak ada yang salah dengan individu kaya atau artis besar yang mengajukan beasiswa, tetapi ada masalah struktural ketika sistem membiarkan ketimpangan kesempatan terus direproduksi. Jika negara sungguh-sungguh ingin mencetak generasi emas, maka yang harus diperjuangkan bukan sekadar siapa yang paling cerdas di atas kertas, melainkan bagaimana membuka ruang bagi anak-anak yang selama ini tertutup aksesnya.
Pada suatu senja di kampung, anak-anak berlari pulang dari sekolah, kaki mereka berdebu, wajahnya bercahaya. Mereka tertawa meski seragamnya lusuh. Di kota besar, anak-anak lain sibuk mengulang hafalan bahasa asing, bersiap masuk universitas ternama di luar negeri. Dua pemandangan ini adalah dua ujung yang saling bertolak belakang, namun terikat dalam satu negeri. Jika beasiswa hanya jatuh ke tangan yang sudah kuat, maka jurang itu akan semakin lebar. Tetapi jika beasiswa diarahkan untuk mereka yang berjuang dari bawah, maka mungkin suatu hari anak yang berjalan tanpa alas kaki itu bisa berdiri sejajar dengan siapa pun di dunia.
Kita tidak boleh terus-menerus menutup mata pada diskriminasi sejak dalam kandungan. Negeri ini akan benar-benar adil hanya jika setiap anak, tanpa peduli lahir dari rahim siapa dan di desa mana, memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi setinggi langit. Seperti kata seorang penyair, pendidikan adalah jembatan emas, dan tugas kita adalah memastikan jembatan itu bisa dilintasi oleh semua orang, bukan hanya mereka yang sudah lahir di seberang sana.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI