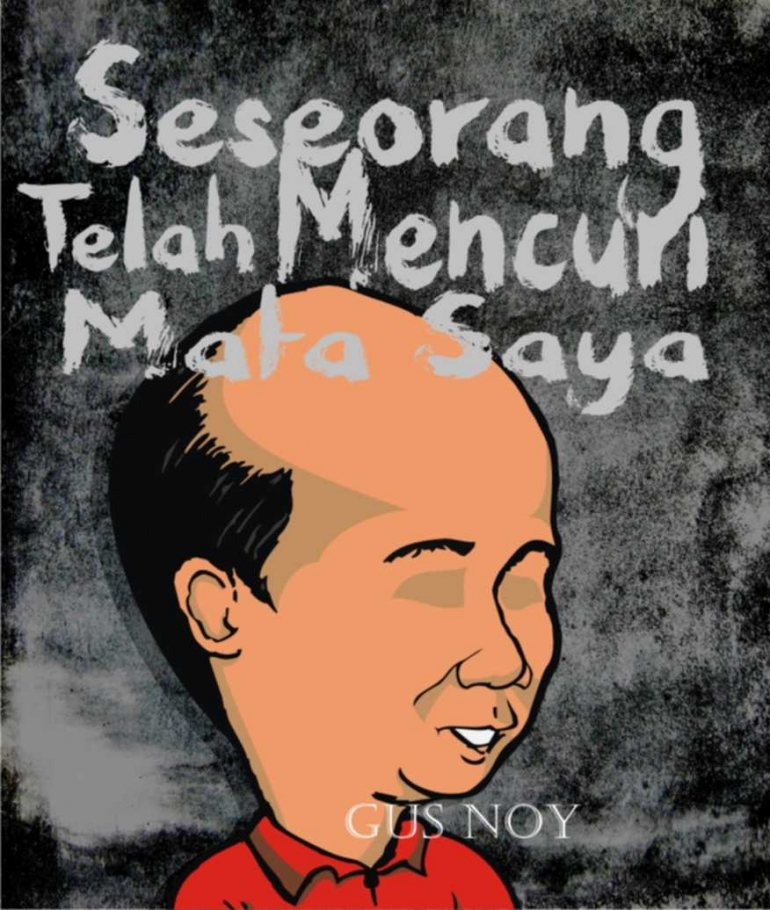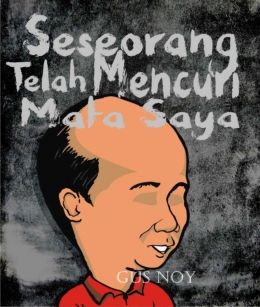Masih gelap ketika saya terjaga. Saya duduk di ranjang dengan kedua kaki selonjor. Sesekali mengulet untuk sedikit menyegarkan badan. Sesekali menggaruk-garuk bagian bokong.
Hari masih gelap, untuk apa bangun, pikir saya.
Memang masih gelap. Gelap ini mungkin karena saya belum benar-benar sadar. Masih gelap tapi udara sudah gerah. Mungkin mendung telah membendung angin, dan menekan suhu panas hingga merangsek ke kamar.
Ah, mending tidur lagi, pikir saya sambil merebah kembali.
Bagi saya, tidur lelap merupakan satu-satunya kemerdekaan sejati yang saya miliki. Sebab, ketika saya melihat--apa, siapa, segala situasi, mendadak saya kehilangan kemerdekaan sejati. Serta-merta pikiran saya bertempur dengan segala dugaan dan kemungkinan. Panas kepala saya. Tak pelak, rambut di jidat saya berguguran, dan jidat akhirnya tandus.
Makanya saya memilih situasi gelap sebagai dukungan untuk keputusan saya melelapkan diri. Saya mengambil posisi tidur meyamping kanan. Bantal agak saya tinggikan agar pundak kanan tidak terlalu memikul beban.
Saya ingin tidur lagi. Saya ingin lelap lagi. Saya ingin mimpi lagi. Saya berhitung dari satu sampai seratus untuk melelahkan pikiran, dan mengundang kantuk. Bila belum juga datang kantuk, saya akan meneruskan dari seratus sampai seribu.
Sayup-sayup kicauan burung dekat kamar. Sayup-sayup kendaraan melintas. Sayup-sayup bising anak-anak--entah sedang bermain apa. Gelap masih memenuhi setiap bidang pandang.
Kicauan burung?
Pikiran saya terhenti dalam hitungan ke-62. Rencana melelahkan pikiran mulai kacau gara-gara kicauan itu, ditambah bisingnya anak-anak sedang bermain.
Sialan, maki saya. Hari masih gelap, burung sudah berkicau, anak-anak sudah bermain.
Ya, saya ingin melanjutkan lelap selagi hari masih gelap. Tetapi, selain kondisi gerah kamar dan kuyup di punggung begini, malah kicauan dan kebisingan itu mengacaukan undangan untuk kantuk.
Keringat terus mengucur, bahkan dari dahi. Pikiran telah terbang ke kicauan dan kebisingan dalam gelap pandang saya. Situasi yang cukup menyiksa.
"Jangan lari-lari, Sarwan!" teriak seorang ibu. "Nanti jatuh, bikin repot lagi!"
"Hei, Sarwan! Bisa dibilangin, nggak?" bentak seorang bapak.
"Aku mau main ke Om Oji..."
"Pagar masih terkunci. Tuh, gemboknya masih terpasang."
"Eh, jangan manjat! Nggak baik begitu!" timpal seorang bapak.
Oh, itu keluarganya Demun, pikir saya.
Suara mobil mendekati mereka. Sayup-sayup saya dengar sebuah sapaan, dan percakapan singkat.
"Siang-siang mau tamasya ke mana nih, Pak?"
"Biasalah, Pak Demun."
Siang?
Saya terkejut. Saya menggerakkan kepala untuk mencari letak jendela.
***
Seseorang telah mencuri mata saya!
Kalimat itu yang pertama saya gumamkan ketika berusaha untuk melihat, meraba kedua mata, dan menghentak pikiran. Saya bangkit dengan pikiran berantakan. Jantung berdetak kencang.
Buk! Aduh! Saya terjatuh dari ranjang.
Duk!
"Bangsat!" Kepala membentur pinggiran daun pintu. Alangkah sakitnya.
Saya tidak peduli. Berdarah, benjol... Saya merangkak sambil meraba ke sana-sini.Saya mau keluar kamar.
Oh, gelap sungguh gelap. Bangsat! Keparat! Laknat! Oh!
Semua makian paling keji saya umbar secepat debaran dada saya sambil merangkak, dan meraba-raba. Apalagi ketika kepala berkali-kali membentur benda keras, entah kursi, meja, dinding, atau apa lagi. Makian, kesakitan, dan kepanikan tidak terhingga langsung memenuhi pikiran, perasaan, dan gerakan tubuh saya.
Suara beberapa benda jatuh, pecah, berisik juga mengiringi suara makian dan gerakan saya.
***
Saya terduduk di lantai sambil menyandar di dinding. Kaki menyelonjor. Pakaian saya basah kuyup--entah karena keringat, air kencing, air kamar mandi, atau air apa lagi. Aneka bebauan mengitari penciuman. Perih pun terasa di sekujur tubuh.
Saya sedang mengalami kelelahan jiwa dan raga tertinggi dalam perjalanan hidup saya. Gelap gulita sedang menguasai saya secara mendadak. Bukan karena katarak, terkena cairan atau benda apa pun, kedua bola mata entah ke mana.
Saya tidak bisa menangis. Alangkah sesak dada saya menahan desakan perasaan dan pikiran. Alangkah sesaknya karena kehilangan indera andalan yang sejak kecil menjadi bagian utama dalam hidup saya. Indera paling andalan, malah.
Sekarang saya telah kehilangan mata saya. Sungguh-sungguh mengerikan kelak apa yang bakal saya hadapi.
***
Tidak henti-hentinya saya meraba muka, dan bagian kedua mata saya. Cekung adalah pemukaan yang saya temukan berkali-kali. Tidak ada perih sama sekali.
Oh, apa yang sebenarnya telah terjadi?
Dalam kelelahan lengkap, dan debaran dada berangsur reda, saya mencoba menguras ingatan, terutama apa yang terjadi sebelum saya tidur. Dengan perlahan saya merunutnya lagi.
Saya telah mengunci pintu pagar, pintu rumah, dan tidak pernah lalai memeriksa jendela sebelum saya tidur. Ya, itu paling akhir.
Sebelum saya mengunci dan memeriksa ini-itu, tadi malam Demun dan anaknya--Sarwan--berkunjung. Demun--seorang tetangga berjarak sepuluh rumah dari rumah saya--jarang berkunjung tetapi anaknya cukup sering karena anaknya suka membaca buku komik yang saya koleksi sejak seusianya. Ya, Demun dan anaknya.
Tadi malam saya berbincang-bincang dengan Demun tentang banyak hal, dan peristiwa, baik terkini maupun keterpautannya pada masa lampau. Suatu perbincangan yang panjang karena, memang, Demun dan anaknya berkunjung selepas magrib, kami jarang memiliki kesempatan untuk berbincang semacam tadi malam karena kesibukan masing-masing apalagi Demun sedang disibukkan oleh suatu kegiatan sebagai seorang tokoh penting di daerah kami, dan Demun-anaknya pulang pada pukul 21.00 karena anaknya merengek-rengek mengajak pulang.
Demun memang seorang tokoh penting, yang selalu andil dalam segala kebijakan yang terkait dengan rencana dan situasi di daerah kami. Karena terlalu pentingnya Demun, tidak ada keputusan di daerah kami yang tanpa melalui persetujuan Demun. Apa pun keputusan itu.
Sedangkan saya bukanlah siapa-siapa. Saya sama sekali tidak suka melibatkan diri dalam hal-hal yang dilakukan seperti Demun.
Kedatangan Demun tadi malam, katanya, sekadar menemani anaknya, yang tadi malam, mendadak merengek untuk membaca koleksi saya. Anaknya sedang gemar membaca, khususnya komik. Sebagian besar koleksi saya memang komik, baik komik anak-anak maupun komik dewasa--dewasa dalam arti komik sosial-politik sesuai dengan usia saya sekarang sekaligus bahan gagasan saya menulis hal-hal sosial-politik, selain melalui pemberitaan terbaru.
Perbincangan tadi malam, seingat saya, cukup menguras pengetahuan dan wawasan saya. Mitra bincang saya jelas bukan orang biasa-biasa seperti saya, walaupun saya pernah ditawari untuk bergabung dengan suatu kelompok yang siap menokohkan saya karena mereka selalu menganalisis tulisan saya, juga kalimat-kalimat saya dalam suatu wawancara dengan media daerah kami.
Sementara ketokohan Demun sudah dikenal oleh tetangga serta orang-orang di daerah kami selama lebih dari dua dekade. Sudah barang tentu, ketokohan Demun tidak sekadar suara angin yang tertulis dalam berita-berita media massa apalagi angin dari mulut para tetangga.
Inti perbincangan kami adalah politisasi segala bidang, termasuk formal dan non-formal, berikut kriminalisasi yang sedemikian rupa. Saya tidak tedeng-aling dalam perbincangan tadi malam karena saya tidak memiliki kepentingan apa pun, kecuali memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan semua isi pemikiran saya selagi bermitra bincang dengan Demun.
Saya tidak peduli, apakah ada yang menyinggung atau biasa saja bagi Demun. Bahkan ketika ada tetangga saya lainnya berkomentar "jangan terlali idealis dalam hidup di negeri ini, Oji", saya keukeuh pada prinsip hidup saya. Kebenaran adalah kebenaran. Sangat tidak benar jika kebenaran dibelokkan ke selokan.
Sejengkal pemahaman dan sekepal penglihatan saya terhadap realitas akhirnya terjungkal dalam pembincangan tadi malam. Ya, saya lebih sering membaca daripada benar-benar berada dalam segala situasi seperti yang dialami langsung oleh Demun. Tidak jarang saya hanya melongo ketika Demun menyampaikan apa saja, atau menanggapi saya.
"Mujurlah saya tidak menghidupi diri dengan semua itu, Pak. Saya hanya melihat sedikit yang langsung, banyak yang diolah media. Juga hanya memikirkan dan menuliskannya sebagian. Anggap sajalah omong kosong."
"Ya, Pak Oji. Soalnya, dalam situasi kapan pun, tetaplah berlaku hukum mutlak bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tidak ada yang gratis dalam hidup bersama ini."
***
Saya belum berencana keluar rumah hari ini. Saya belum bisa berpikir untuk tindakan selanjutnya. Saya masih berkubang dalam kekhawatiran, kalau keluar rumah justru ada orang masuk, sembunyi dalam rumah.
Saya pun tidak bisa melapor ke polisi karena terlihat seperti tidak ada bukti yang patut dijadikan bahan hukum. Saya tidak merasa apa-apa ketika kedua mata saya diambil, dan sampai sekarang sama sekali tidak ada perih.
Saya merasa aneh sendiri ketika meraba muka saya. Kedua bagian itu terasa kulit dengan permukaan cekung, yang berbunyi duk-duk ketika saya ketuk perlahan dengan ujung telunjuk. Kalau saya melapor ke polisi, jangan-jangan justru membingungkan.
Saya benar-benar belum bisa memutuskan untuk berbuat apa. Saya sedang dibekuk kebingungan paling membingungkan. Bahkan, saat ini, saya tidak memahami, apakah sudah sore atau malah malam telah datang. Gelap gulita telah menaklukkan saya.
Saya tidak tahu sampai berapa lama mata saya akan kembali, dan bagaimana caranya berfungsi lagi seperti sedia kala. Saya sangat berharap mata saya kembali dan berfungsi seperti sedia kala. Biarlah rekaman di dalamnya diambil tapi mata saya harus kembali.
Ya, biarlah semua rekaman dalam mata saya diambil asalkan mata saya kembali, dan berfungsi. Tanpa mata, apalah guna hidup saya ini. Mata adalah satu-satunya andalan saya selama saya bisa melihat sejak kecil.
Saya kehilangan daya. Tidak mampu berpikir untuk berbuat apa selanjutnya. Gelap gulita berkuasa penuh atas diri saya. Tubuh saya seakan kehilangan tulang-belulang.
Saya di ambang keputusan tamat riwayat dalam berpikir, apalagi kemudian bukan itu saja yang saya pikirkan dan cemaskan. Kekhawatiran saya perlahan-lahan menular ke bagian indera saya lainnya.
Telinga yang merekam segala suara. Lidah yang sering menyampaikan banyak pendapat secara lisan. Jemari yang juga sering menyampaikan pendapat secara tertulis. Yang paling mengaduk kekhawatiran saya adalah otak.
Bagaimana seandainya nanti semua itu pun dicuri dalam kelelapan saya nanti?
Debar dada semakin kencang. Saya berupaya untuk terjaga, meskipun tubuh terasa lemas sekali seakan lumpuh total. Saya khawatir, kalau terlena sebentar saja, terkabullah kekhawatiran saya. Bisa benar-benar tamat riwayat saya.
*******
Panggung Renung Balikpapan, 2017