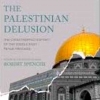Sebuah deklarasi pun digelar di Tasikmalaya. Para guru berikrar: Sekolah Ramah Anak! Spanduk dicetak. Foto diunggah. Tapi adakah spanduk yang bisa menghalau bisikan kejam di ruang kelas? Adakah deklarasi yang bisa melindungi anak-anak dari rasa takut yang mereka bawa pulang?
Barangkali kita perlu lebih jujur.
Bahwa sistem pendidikan kita sedang tidak sehat. Ia tidak memberi ruang bagi anak untuk menangis. Ia tidak memberi ruang bagi guru untuk lelah. Ia tak memberi ruang bagi sekolah untuk gagal tanpa dimarahi Dinas. Maka semua orang berpura-pura.
Guru berpura-pura mengajar. Murid berpura-pura belajar. Dan kepala sekolah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara di sudut kelas, seorang anak diam-diam mencari tali.
Kini jasad itu sudah dikubur. Tapi soalnya belum selesai. Kita masih belum tahu, apakah setelah ini kita akan berubah. Atau kita hanya akan menyusun kurikulum baru tentang empati yang tidak pernah diajarkan. Atau malah membentuk tim satgas anti-gantung diri---lengkap dengan anggaran dan seragam.
Sebab negeri ini punya kebiasaan unik: setiap tragedi disambut dengan seminar. Setiap kematian jadi peluang proyek. Dan setiap nyawa hilang, diabadikan dalam press release yang terlambat.
Kita berharap ada keadilan. Tapi keadilan macam apa yang bisa menebus hidup seorang bocah yang sudah tak bisa pulang? Kita minta kepala sekolah dicopot. Baik. Tapi adakah kepala sistem yang akan ikut bertanggung jawab?
Sementara itu, sekolah-sekolah terus berdiri. Dengan pagar tinggi dan CCTV di setiap sudut. Tapi tidak ada kamera yang bisa menangkap perasaan. Tidak ada sensor yang bisa membaca kesepian.
Anak-anak tetap berangkat pagi, pulang sore. Mereka membawa tas penuh buku. Tapi juga penuh beban yang tak terlihat. Dan kita---orang tua, guru, negara---masih percaya bahwa selama mereka tidak mengeluh, berarti mereka kuat.
Kita lupa bahwa diam juga bisa menjadi jeritan.
Dan Garut?