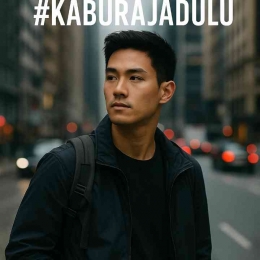Surat itu membuatnya menangis untuk pertama kali sejak datang ke Amerika. Bukan karena sedih, tapi karena rasa malu yang mendalam. Ia sudah terlalu lama hidup sebagai versi orang lain. Kini, yang tersisa hanya dirinya sendiri---dan harapan bahwa mungkin, pulang bukan kekalahan, tapi keberanian.
Ia mulai menulis surat balasan. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat permohonan maaf. Untuk kebohongan yang terus-menerus. Untuk ambisi yang menyesatkan. Untuk semua malam yang ia lalui dengan berpura-pura baik-baik saja. Surat itu tak punya alamat. Tapi isinya menyelamatkan.
Lalu datang hari ketika ia harus memutuskan: mengajukan banding dan memperpanjang ketidakpastian, atau menyerah dan pulang ke negeri yang dulu menolaknya. Ia menatap cermin di ruang interogasi. Melihat wajah yang tidak ia kenal. Tapi kali ini, ia tidak takut.
Ia memilih pulang.
***
Ia turun dari pesawat dengan langkah gontai. Jaket tebal yang dulu menyelamatkannya dari musim dingin Amerika kini terasa tak berguna di udara panas tropis. Wajahnya lelah. Bukan karena jet lag, tapi karena semua beban yang akhirnya ia izinkan jatuh ke tanah. Tak ada koper mewah. Hanya satu tas kecil, berisi sisa hidup yang tak sempat dibanggakan.
Tidak ada sambutan. Tidak ada karpet merah. Hanya terminal bandara yang terlalu terang, dan petugas imigrasi yang menatapnya tanpa ekspresi. Tapi di luar, seseorang menunggu: ibunya. Tak membawa bunga, tak membawa poster nama, hanya senyum yang sedikit gemetar dan mata yang langsung basah saat melihat anaknya berdiri kembali di tanah air.
Pelukan itu adalah rumah.
Kabar kepulangan Reihan cepat menyebar di desa. Tapi bukan kabar yang ia takutkan---bukan hinaan, bukan sindiran. Justru keheningan. Orang-orang tahu, kadang hidup terlalu rumit untuk dihakimi. Mereka hanya menyapa singkat, dan kembali ke kesibukan masing-masing. Seolah memberi ruang bagi Reihan untuk bernapas lagi, perlahan-lahan.
Ia tidak langsung kembali ke dunia kerja. Tidak buru-buru mencari "kesempatan baru". Ia duduk di rumah, menemani ibunya memasak, memandangi sawah di kejauhan, dan mulai memperbaiki pagar yang rusak. Hari-hari sederhana, tapi penuh makna yang dulu ia anggap remeh. Dunia tak lagi berputar cepat seperti Manhattan, tapi di situlah justru ia merasa selamat.
Tak lama, tetangga menawarkan pekerjaan paruh waktu: membantu warung kopi di dusun. Reihan menerimanya tanpa banyak tanya. Ia membersihkan meja, mengantar pesanan, kadang membantu meracik kopi. Tak ada dollar, hanya receh rupiah. Tapi setiap senyuman pelanggan terasa lebih hangat dari tip besar di restoran Amerika.