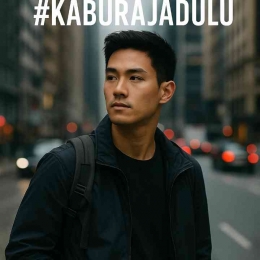Sinopsis Novel
Reihan tidak pernah membayangkan bahwa secarik ijazah yang dulu disambut sorak sorai keluarga kini hanya menjadi benda mati yang tak punya daya di meja ruang tamu. Ia lulus dengan predikat baik, nilai memuaskan, dan CV penuh pengalaman organisasi. Tapi setiap pagi yang ia buka dengan semangat selalu ditutup dengan bunyi notifikasi email yang menolak pelan-pelan, seperti sindiran halus dari sistem yang tak peduli berapa besar usaha yang sudah ia lakukan.
Awalnya ia sabar. Katanya, rejeki butuh waktu. Tapi waktu berjalan lambat, sementara kekecewaan datang cepat. Ayahnya tak lagi bicara banyak. Tak ada marah, hanya diam---dan di situlah Reihan merasa paling gagal. Sebab tak ada yang lebih menusuk daripada ayah yang tak lagi punya kata-kata untuk anak lelakinya. Ia mulai menimbang: mungkin ini bukan soal usaha, mungkin memang tidak ada tempat untuk orang sepertinya di negeri ini.
Di hari-hari ketika semangat sudah seperti api kecil yang kehabisan udara, Reihan mencari jalan lain. Ia mengirim lamaran ke mana saja: magang, freelance, bahkan lowongan yang tulisannya penuh janji palsu. Ia pernah datang ke wawancara kerja yang ternyata hanya seminar motivasi berbayar. Pernah juga "magang" di startup yang tak jelas, disuruh datang tiap hari tapi tidak dibayar. Dunia kerja tampak seperti pasar yang hanya menjual harapan, bukan kesempatan.
Lalu datang reuni. Momen di mana teman-temannya terlihat begitu berhasil, begitu mapan, begitu bahagia dengan pekerjaan dan pasangan. Reihan berdiri di tengah mereka dengan senyum plastik, cerita palsu, dan jaket murah yang terlihat mewah hanya karena pencahayaan kafe yang temaram. Malam itu, ia sadar: semua orang sedang berlari, dan ia masih berdiri di garis start, sambil pura-pura tak kelelahan.
Ketika segalanya makin sempit, datang tawaran dari seniornya dulu. Seorang yang pernah aktif di himpunan, tapi kini kerja di luar negeri dengan jalur tak resmi. "Kalau di sini mandek, ya ke sana. Banyak kok yang sukses," katanya. Reihan ragu, tapi benih hasrat sudah ditanam. Ia mulai membaca thread panjang di Twitter tentang kisah para TKI ilegal yang hidup nyaman, punya mobil, bahkan rumah di kampung. Semua dibungkus tagar: #KaburAjaDulu.
Itu bukan rencana matang. Itu pelarian yang dirancang tergesa. Ia gadaikan motornya, pinjam sedikit dari teman, beli tiket pesawat sekali jalan, dan mencari jalur visa turis dengan cara-cara yang tak sepenuhnya legal tapi bukan juga sepenuhnya kriminal. Ia tidak kabur dari hukum. Ia hanya kabur dari keputusasaan yang terlalu sunyi untuk didengar negara.
Malam sebelum keberangkatan, ibunya memeluknya erat. Tak ada tangis di mata, tapi suara yang bergetar tak bisa disembunyikan. "Hati-hati, ya, Nak," katanya. Reihan tahu, pelukan itu bisa jadi yang terakhir. Tapi tak mungkin ia bilang akan pergi jadi gelandangan di negeri asing. Jadi ia hanya mengangguk dan tersenyum seperti pahlawan, meski dalam hatinya, ia hanya bocah yang tak tahu arah.
Bandara adalah ruang liminal antara harapan dan ketakutan. Di sana, Reihan duduk memandangi layar keberangkatan, mencoba menyakinkan diri bahwa ini bukan keputusan nekat, melainkan perjuangan. Tapi siapa yang bisa yakin seratus persen saat masa depan diserahkan pada negara asing yang bahkan tidak mengenalnya?
Penerbangan panjang menjadi perenungan tak henti. Wajah-wajah asing, aroma makanan yang tak dikenalnya, dan tatapan sinis saat ia terlihat terlalu gugup di imigrasi. Tapi akhirnya ia lolos. Pesawat mendarat di JFK, dan Reihan berdiri untuk pertama kalinya di tanah Amerika. Udara dingin New York menyentuh kulitnya, seperti menyambut dan menghardik sekaligus. Ia bukan siapa-siapa di sini. Hanya seorang manusia dengan visa turis dan niat bertahan hidup.
Langkah pertama dimulai di sebuah apartemen sempit yang disewa bersama kenalan dari komunitas Indonesia. Ia tidur di sofa, berbagi dapur dengan enam orang lain, dan bekerja cuci piring di restoran yang menuntut kerja cepat dan sunyi. Tak ada basa-basi, tak ada cuti, hanya waktu yang dipotong jadi lembur tanpa bayaran. Tapi Reihan bersyukur---ini lebih baik daripada diam di rumah menatap dinding.
Hari-harinya jadi rutinitas yang menyusutkan jiwa. Pagi bangun, kerja, malam tidur, dan ulangi lagi. Tak ada nama untuk waktu-waktu yang ia lalui. Dunia di luar jendela tampak sibuk dan maju, tapi hidupnya mandek di titik bertahan. Ia bertemu Fahri dan Lina, sesama TKI ilegal yang hidup dari sisa-sisa keberanian. Mereka saling bantu, saling jaga, membentuk keluarga dari luka yang sama.
Kadang ada pesta kecil yang digelar diam-diam. Pengajian atau perayaan hari kemerdekaan dengan nasi kotak dan lagu nasional. Di sanalah air mata bisa jatuh tanpa malu, di antara tawa yang dipaksakan dan lagu yang dinyanyikan dengan kerongkongan kering. Karena siapa pun yang datang ke pesta itu tahu: mereka tidak punya tempat di sini, tapi juga tak bisa pulang.
Gaji pertama membuatnya senang, tapi potongan "biaya perlindungan" dari penyalur menyadarkannya bahwa sistem eksploitatif tetap mengejarnya, bahkan di negeri yang katanya bebas. Lalu datang kabar buruk: Lina hamil, Fahri menghilang. Reihan ikut terjebak. Membantu Lina bukan hanya soal tanggung jawab moral, tapi juga rasa bersalah karena merasa tak berdaya melawan nasib.
Suatu malam, ibunya menelepon. Reihan berkata bahwa ia kerja kantoran di Manhattan, pakai kemeja, duduk di meja, minum kopi dari Starbucks. Padahal tangannya masih basah deterjen, dan napasnya bau makanan basi. Bohong kecil, katanya. Tapi bohong itulah yang membuat ibunya bisa tidur malam itu tanpa terlalu cemas.
Hari-hari berikutnya diisi ketakutan. ICE---badan imigrasi---menggerebek restoran tempat Reihan bekerja. Ia melarikan diri lewat pintu belakang, bersembunyi di gang becek, memeluk dirinya sendiri sambil mendengar suara sirene menjauh. Sejak itu, Reihan tak lagi punya tempat tetap. Ia berpindah-pindah kerja: jadi buruh bangunan, kurir makanan, penjaga toko. Apa pun asal bisa makan.
Tapi tubuhnya mulai kalah. Kaki pegal tak kunjung sembuh. Tidur jadi mewah, mimpi jadi ancaman. Ketika Lina akhirnya melahirkan, anak itu datang ke dunia tanpa status, tanpa akta, tanpa negara. Tapi dengan mata yang jernih, seolah berkata: "Aku pun ingin hidup."
Dan di situ, Reihan mulai mempertanyakan segalanya: untuk apa semua ini?
***
Hari-hari di negeri impian berubah menjadi musim-musim gelap yang tak lagi bisa dibedakan. Ketika salju mulai turun di luar jendela, Reihan mendapati dirinya semakin menjauh dari siapa dirinya dulu. Ia pernah bermimpi bekerja di bank, mengenakan jas, pulang dengan membawa martabat. Kini, ia mengenakan jaket bekas, sepatu murahan, dan berjalan kaki lima belas blok dalam suhu minus demi mengantar paket ke alamat yang tak ia kenal.
Ia mengalami serangan panik pertama kali di subway. Di antara suara logam kereta yang melaju dan hiruk-pikuk penumpang, napasnya tercekat, pandangannya kabur. Ia terduduk di pojok gerbong seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tak ada yang berhenti untuk menolong. Tak ada yang peduli. Semua orang di New York terburu-buru---bahkan untuk merasa.
Sementara tubuhnya kian lelah, pikirannya kian teriris. Video call dari rumah hanya memperparah luka yang tak terlihat. Ayahnya sakit. Dirawat di rumah sakit kecil, dan ibunya hanya bilang, "Gak usah pulang, yang penting kamu sehat di sana." Tapi Reihan tahu, itu bukan permintaan. Itu keputusasaan. Sebab mereka tahu: untuk pulang pun Reihan tak punya jalan yang legal.
Ia mencoba mengalihkan rasa bersalah dengan melihat-lihat Instagram teman-temannya. Ada yang baru beli motor, ada yang menikah, ada yang buka bisnis kecil. Mereka hidup sederhana, tapi tetap bisa tertawa. Sementara Reihan, yang dulunya merasa lebih pintar, lebih aktif, lebih "berpotensi", kini tidur di kasur tipis dengan suara tikus dari plafon yang bolong.
Di tengah semua keputusasaan itu, ia menemukan sebuah kebun tersembunyi di Queens. Bukan tempat mewah, hanya lahan kecil dengan tanaman liar dan bangku reyot. Tapi di sanalah, untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa bernapas dengan utuh. Kebun itu jadi tempatnya menulis. Catatan harian. Doa-doa yang tak pernah sampai. Janji-janji pada dirinya sendiri yang mulai terasa seperti omong kosong.
Untuk bertahan hidup, Reihan menerima pekerjaan di rumah duka. Ia bantu mengurus kremasi jenazah, membersihkan sisa dupa, menyapu abu orang asing yang tak pernah dikenal semasa hidup. Pekerjaan itu sunyi, tapi jujur. Di sana, ia belajar bahwa semua manusia akhirnya pulang ke tanah, entah punya paspor atau tidak.
Suatu hari, seseorang menawarkan jalan pintas: dokumen palsu untuk bisa kerja lebih leluasa. "KTP California, bisa buat buka rekening, daftar kerja, asal tahu tempatnya," katanya. Reihan menimbang. Jika tertangkap, ia bisa dideportasi. Tapi jika tidak, ia bisa menghidupkan lagi sisa-sisa mimpinya. Dan terkadang, yang membuat orang melangkah bukan karena yakin, tapi karena terlalu lelah untuk terus diam.
Dokumen itu membuatnya bisa bekerja di tempat yang lebih layak. Gajinya besar. Ia mulai mengirim uang ke rumah, menyimpan sedikit demi sedikit untuk "hari pulang". Tapi rasa itu tak serta-merta membaik. Ia duduk di restoran mahal, makan sandwich tujuh dolar, tapi jiwanya terasa lapar. Duit banyak, tapi dingin.
Lalu, sebuah kabar buruk datang. Fahri, sahabatnya dulu, tertangkap imigrasi. Dideportasi dalam waktu singkat. Tidak sempat pamit. Tidak sempat menyelamatkan apa pun. Reihan terpukul. Ia jadi paranoid. Menghindari tempat ramai, mengganti rute pulang, bahkan menyimpan uangnya dalam bentuk tunai di bawah kasur. Seolah setiap pagi bisa jadi hari terakhirnya di negeri ini.
Musim dingin datang lebih cepat tahun itu. Salju pertama turun saat Reihan duduk sendirian di kebun Queens, mengenang bagaimana dulu ia pernah percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Ia menulis di jurnal kecil: "Barangkali, yang membuat manusia tetap hidup bukan harapan, tapi keengganan untuk menyerah mentah-mentah."
Di salah satu malam sunyi, ia bertemu Tuan Miguel, pria tua dari Meksiko yang sudah dua puluh tahun hidup tanpa status. Mereka duduk bersama sambil makan roti dan berbagi cerita. "Yang menang bukan yang punya banyak. Yang menang itu yang masih bisa senyum, walau semua hal udah hilang," kata Miguel. Kata-kata itu tinggal lama di kepala Reihan.
Tapi kehidupan tak memberi jeda. Dokumen palsunya terbongkar saat ada pemeriksaan acak di tempat kerja. Polisi menahannya. Ia tak melawan. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya merasa lelah karena akhirnya yang ditakutkan datang juga. Di ruang detensi, ia kembali jadi angka. Dicatat, difoto, ditanya: apakah akan dideportasi atau mengajukan banding?
Malam-malam di sana lebih sunyi daripada gelap. Tak ada ponsel, tak ada jam. Hanya cahaya putih yang selalu menyala, dan bunyi batin yang terus berdetak tak tentu. Tapi dari kejauhan, datang sesuatu yang membuatnya goyah: surat fisik dari ibunya. Diketik rapi, dikirim lewat kenalan. "Mas, pulanglah. Kami gak butuh uangmu. Kami butuh kamu."
Surat itu membuatnya menangis untuk pertama kali sejak datang ke Amerika. Bukan karena sedih, tapi karena rasa malu yang mendalam. Ia sudah terlalu lama hidup sebagai versi orang lain. Kini, yang tersisa hanya dirinya sendiri---dan harapan bahwa mungkin, pulang bukan kekalahan, tapi keberanian.
Ia mulai menulis surat balasan. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat permohonan maaf. Untuk kebohongan yang terus-menerus. Untuk ambisi yang menyesatkan. Untuk semua malam yang ia lalui dengan berpura-pura baik-baik saja. Surat itu tak punya alamat. Tapi isinya menyelamatkan.
Lalu datang hari ketika ia harus memutuskan: mengajukan banding dan memperpanjang ketidakpastian, atau menyerah dan pulang ke negeri yang dulu menolaknya. Ia menatap cermin di ruang interogasi. Melihat wajah yang tidak ia kenal. Tapi kali ini, ia tidak takut.
Ia memilih pulang.
***
Ia turun dari pesawat dengan langkah gontai. Jaket tebal yang dulu menyelamatkannya dari musim dingin Amerika kini terasa tak berguna di udara panas tropis. Wajahnya lelah. Bukan karena jet lag, tapi karena semua beban yang akhirnya ia izinkan jatuh ke tanah. Tak ada koper mewah. Hanya satu tas kecil, berisi sisa hidup yang tak sempat dibanggakan.
Tidak ada sambutan. Tidak ada karpet merah. Hanya terminal bandara yang terlalu terang, dan petugas imigrasi yang menatapnya tanpa ekspresi. Tapi di luar, seseorang menunggu: ibunya. Tak membawa bunga, tak membawa poster nama, hanya senyum yang sedikit gemetar dan mata yang langsung basah saat melihat anaknya berdiri kembali di tanah air.
Pelukan itu adalah rumah.
Kabar kepulangan Reihan cepat menyebar di desa. Tapi bukan kabar yang ia takutkan---bukan hinaan, bukan sindiran. Justru keheningan. Orang-orang tahu, kadang hidup terlalu rumit untuk dihakimi. Mereka hanya menyapa singkat, dan kembali ke kesibukan masing-masing. Seolah memberi ruang bagi Reihan untuk bernapas lagi, perlahan-lahan.
Ia tidak langsung kembali ke dunia kerja. Tidak buru-buru mencari "kesempatan baru". Ia duduk di rumah, menemani ibunya memasak, memandangi sawah di kejauhan, dan mulai memperbaiki pagar yang rusak. Hari-hari sederhana, tapi penuh makna yang dulu ia anggap remeh. Dunia tak lagi berputar cepat seperti Manhattan, tapi di situlah justru ia merasa selamat.
Tak lama, tetangga menawarkan pekerjaan paruh waktu: membantu warung kopi di dusun. Reihan menerimanya tanpa banyak tanya. Ia membersihkan meja, mengantar pesanan, kadang membantu meracik kopi. Tak ada dollar, hanya receh rupiah. Tapi setiap senyuman pelanggan terasa lebih hangat dari tip besar di restoran Amerika.
Suatu sore, ia kembali mengunjungi kebun kecil yang dulu ditinggalkannya. Tapi kali ini bukan di Queens, melainkan di tanah belakang rumahnya sendiri. Ia mulai menanam cabai, lalu tomat, lalu mencoba hidroponik setelah menonton tutorial dari YouTube. Apa yang dulu dianggap "jalan buntu" kini terasa seperti jalur baru menuju kedamaian.
Tulisan-tulisannya yang sempat disimpan dalam jurnal kini dibaca ulang. Ada rasa malu. Ada juga rasa bangga. Lalu ia putuskan untuk menyalinnya, mengedit sedikit, dan membagikannya ke grup Facebook komunitas pemuda desa. Tak disangka, kisah itu viral. Bukan karena gaya bahasanya, tapi karena kejujuran yang terasa mentah dan nyata.
Undangan datang dari mana-mana. Dari RT, dari komunitas pemuda, bahkan dari kampusnya dulu. Semua ingin mendengar cerita "anak muda yang pergi, gagal, tapi pulang tanpa malu". Reihan berbicara bukan sebagai motivator, bukan sebagai korban, tapi sebagai cermin. Ia hanya berkata jujur. Tentang ketakutan, kesalahan, dan keberanian mengaku salah.
Radio lokal mengundangnya sebagai narasumber tetap. Ia berbicara tiap minggu tentang harapan, realitas, dan keputusan-keputusan yang dulu terasa seperti akhir, tapi ternyata adalah awal. Suaranya tak lantang, tapi tulus. Dan mungkin, justru itu yang dibutuhkan generasi yang sudah lelah dengan kata-kata besar.
Satu hari, ia menerima pesan dari Lina. Sebuah foto dikirimkan lewat email. Lina berdiri di tengah taman, mengenakan jaket musim semi. Di sampingnya, anaknya---yang kini berusia dua tahun. "Kami berhasil ke Kanada, legal," tulisnya. "Terima kasih karena dulu kamu tetap tinggal waktu aku nyaris putus asa."
Reihan tersenyum. Dunia memang tidak adil, tapi bukan berarti tidak bisa dilalui.
Akhirnya, ia menulis surat terbuka. Bukan untuk pemerintah. Bukan untuk media. Tapi untuk generasi setelahnya. Ia beri judul: "Jangan Berhenti di Pintu Pertama." Surat itu dibagikan di balai desa, disalin oleh remaja karang taruna, bahkan dibacakan di acara 17-an. Isinya sederhana: hidup memang tak selalu sesuai rencana, tapi menyerah bukan satu-satunya pilihan.
Kini, Reihan tak lagi mengejar dolar. Ia mengejar makna. Ia tak punya mobil, tapi bisa naik motor pinjaman dan tertawa di perjalanan. Ia tak punya kartu kredit, tapi bisa menabung untuk beli bibit tanaman. Ia tak viral lagi, tapi setiap pagi ada anak-anak muda yang datang ke rumahnya, bertanya: "Mas, bisa ajari kami bikin sistem tanam air itu?"
Dan ia akan mengangguk.
Karena Berburu Dollar #KaburAjaDulu bukan sekadar kisah tentang pergi dan pulang. Ini adalah cerita tentang luka yang disembuhkan dengan waktu, tentang mimpi yang berubah bentuk, dan tentang keberanian untuk berkata: "Aku gagal, tapi aku tumbuh."
Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.
Baca novel gratisnya di KBM APP atau kbm id
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI