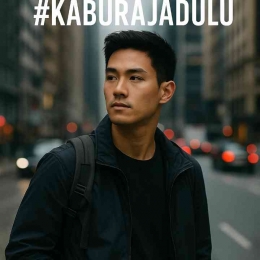Sementara tubuhnya kian lelah, pikirannya kian teriris. Video call dari rumah hanya memperparah luka yang tak terlihat. Ayahnya sakit. Dirawat di rumah sakit kecil, dan ibunya hanya bilang, "Gak usah pulang, yang penting kamu sehat di sana." Tapi Reihan tahu, itu bukan permintaan. Itu keputusasaan. Sebab mereka tahu: untuk pulang pun Reihan tak punya jalan yang legal.
Ia mencoba mengalihkan rasa bersalah dengan melihat-lihat Instagram teman-temannya. Ada yang baru beli motor, ada yang menikah, ada yang buka bisnis kecil. Mereka hidup sederhana, tapi tetap bisa tertawa. Sementara Reihan, yang dulunya merasa lebih pintar, lebih aktif, lebih "berpotensi", kini tidur di kasur tipis dengan suara tikus dari plafon yang bolong.
Di tengah semua keputusasaan itu, ia menemukan sebuah kebun tersembunyi di Queens. Bukan tempat mewah, hanya lahan kecil dengan tanaman liar dan bangku reyot. Tapi di sanalah, untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa bernapas dengan utuh. Kebun itu jadi tempatnya menulis. Catatan harian. Doa-doa yang tak pernah sampai. Janji-janji pada dirinya sendiri yang mulai terasa seperti omong kosong.
Untuk bertahan hidup, Reihan menerima pekerjaan di rumah duka. Ia bantu mengurus kremasi jenazah, membersihkan sisa dupa, menyapu abu orang asing yang tak pernah dikenal semasa hidup. Pekerjaan itu sunyi, tapi jujur. Di sana, ia belajar bahwa semua manusia akhirnya pulang ke tanah, entah punya paspor atau tidak.
Suatu hari, seseorang menawarkan jalan pintas: dokumen palsu untuk bisa kerja lebih leluasa. "KTP California, bisa buat buka rekening, daftar kerja, asal tahu tempatnya," katanya. Reihan menimbang. Jika tertangkap, ia bisa dideportasi. Tapi jika tidak, ia bisa menghidupkan lagi sisa-sisa mimpinya. Dan terkadang, yang membuat orang melangkah bukan karena yakin, tapi karena terlalu lelah untuk terus diam.
Dokumen itu membuatnya bisa bekerja di tempat yang lebih layak. Gajinya besar. Ia mulai mengirim uang ke rumah, menyimpan sedikit demi sedikit untuk "hari pulang". Tapi rasa itu tak serta-merta membaik. Ia duduk di restoran mahal, makan sandwich tujuh dolar, tapi jiwanya terasa lapar. Duit banyak, tapi dingin.
Lalu, sebuah kabar buruk datang. Fahri, sahabatnya dulu, tertangkap imigrasi. Dideportasi dalam waktu singkat. Tidak sempat pamit. Tidak sempat menyelamatkan apa pun. Reihan terpukul. Ia jadi paranoid. Menghindari tempat ramai, mengganti rute pulang, bahkan menyimpan uangnya dalam bentuk tunai di bawah kasur. Seolah setiap pagi bisa jadi hari terakhirnya di negeri ini.
Musim dingin datang lebih cepat tahun itu. Salju pertama turun saat Reihan duduk sendirian di kebun Queens, mengenang bagaimana dulu ia pernah percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Ia menulis di jurnal kecil: "Barangkali, yang membuat manusia tetap hidup bukan harapan, tapi keengganan untuk menyerah mentah-mentah."
Di salah satu malam sunyi, ia bertemu Tuan Miguel, pria tua dari Meksiko yang sudah dua puluh tahun hidup tanpa status. Mereka duduk bersama sambil makan roti dan berbagi cerita. "Yang menang bukan yang punya banyak. Yang menang itu yang masih bisa senyum, walau semua hal udah hilang," kata Miguel. Kata-kata itu tinggal lama di kepala Reihan.
Tapi kehidupan tak memberi jeda. Dokumen palsunya terbongkar saat ada pemeriksaan acak di tempat kerja. Polisi menahannya. Ia tak melawan. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya merasa lelah karena akhirnya yang ditakutkan datang juga. Di ruang detensi, ia kembali jadi angka. Dicatat, difoto, ditanya: apakah akan dideportasi atau mengajukan banding?
Malam-malam di sana lebih sunyi daripada gelap. Tak ada ponsel, tak ada jam. Hanya cahaya putih yang selalu menyala, dan bunyi batin yang terus berdetak tak tentu. Tapi dari kejauhan, datang sesuatu yang membuatnya goyah: surat fisik dari ibunya. Diketik rapi, dikirim lewat kenalan. "Mas, pulanglah. Kami gak butuh uangmu. Kami butuh kamu."