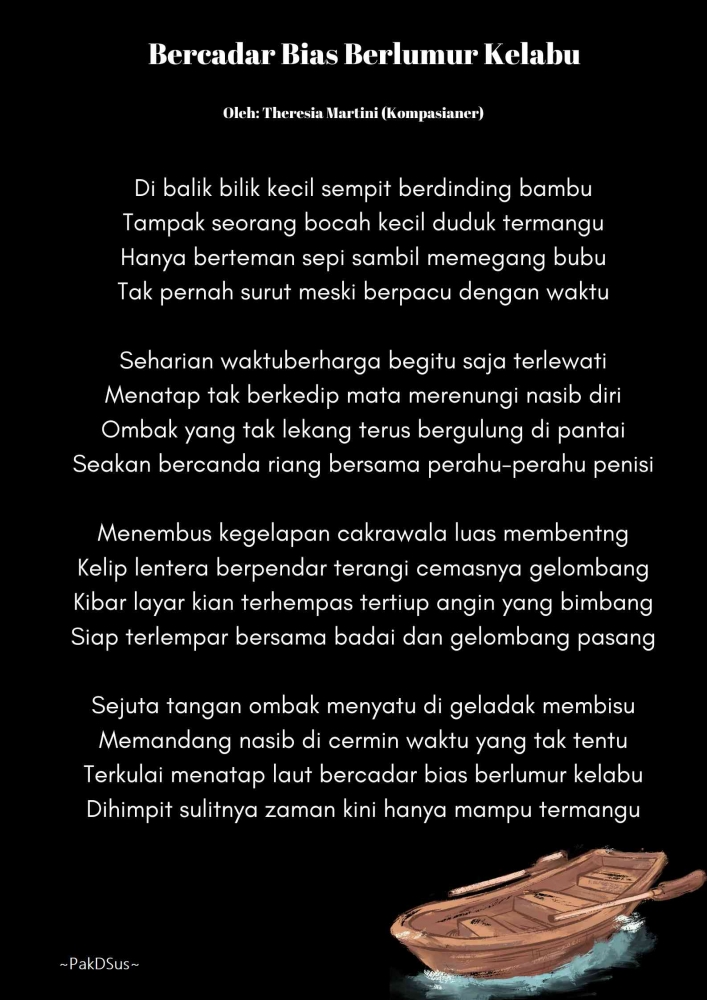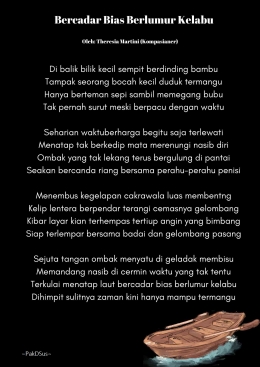"Assalaamu'alaikum, Selamat Pagi ...!"
Terdengar suara di luar pintu. Hari Minggu ini Pak Eko tidak berkegiatan. Badannya kurang mengizinkan. Bersepeda santai yang biasa ia lakukan bersama teman-teman sebayanya tidak bisa dilakukan. Jika dipaksakan dan jatuh sakit, siapa yang akan mengurusi? Si Uti, begitu ia memanggil istrinya, sudah tiada. Lima bulan lalu ia meninggalkan lelaki yang sebulan lagi pensiun itu, seorang diri.
"Wa'alaikum salam, selamat pagi juga. Siapa, ya?"
Lelaki berumur hampir enam puluh tahun itu bergegas ke ruang tamu. Sampai di belakang pintu, ia buka pintu rumahnya. Tampak di depannya seorang gadis. Beberapa tahun lebih muda dari anaknya nomor dua. Yang jelas, Diana sekarang adalah siswa kelas sebelas SMA. Ia tetangga Pak Eko.
"Ada apa, Nana? Apa kau disuruh ibumu ke rumah, Pak?" tanya Pak Eko kepada gadis yang sejak kecil sering main ke rumahnya. Ia menonton televisi bersama Rahma, anak pak guru itu yang nomor dua. Bermain boneka dan masak-masak. Diana, atau Nana sudah seperti anak sendiri bagi lelaki yang biasa dipanggil Pak Eko itu.
"Tidak, Pak. Nana ada tugas," jawab Diana.
"Tugas apa?" Pak Eko balik bertanya.
"Tugas bahasa. Diminta bu guru mencari puisi. Lalu diminta menceritakan isi puisi. Nah, yang sulit ada nih. Dari puisi yang dipilih disuruh mengkritisi dan menulis kembali versi sendiri. Aduh, pusing aku," jelas Diana. Ia tampak manja. Bukan karena Pak Eko sudah seperti ayah sendiri, melainkan ia juga tipikal anak yang suka mengeluh sebelum berusaha.
"O, kebetulan Pak Eko sedang istirahat di rumah. Badan kurang sehat. Tapi, untuk membantu tugas Diana masih sangat bisa. Sudah dapat puisinya?" balas Pak Eko.
Lelaki tua itu membetulkan kacamatanya dan mengajak Diana duduk di kursi tamu. Pintu rumahnya ia buka lebar-lebar. Demikian pula korden ruang tamu ia sibak agar ruangan lebih terang.
Diana dahulu gadis kecil mungil. Sekarang ia gadis remaja beranjak dewasa. Sementara Uti sudah tiada. Guru yang hampir pensiun itu sekarang sendirian. Kedua anaknya merantau di luar kota. Ia lakukan itu agar tidak menimbulkan fitnah.
"Diana dapat dari mana, puisinya?" tanya Pak Eko.
"Dari Kompasiana, Pak. Mamah sekarang rajin nulis Kompasiana sejak ada tantangan menulis, katanya," jawab Diana menceritakan perihal ibunya.
"O, bukannya mamahmu menulis di blog. Saya sering baca tulisannya. Tentang parenting, motivasi, dan dunia perempuan," timpal Pak Eko.
"Masih, kok. Ini mau ngomongin mamah apa bantu Nana, sih?" protes Diana.
"Ha ha ha ..., kamu masih seperti dulu Nana. Kalau Mbak Rahma ada di rumah pasti senang ngobrol denganmu," jawab Pak Eko.
"Pak Eko nggak tahu saja. Nana sering lo, telfonan sama mbak Rahma. Eh, jadi tidak, nih?"
"Ha ha ha ... iy ... zaaa ..., jadi!" Sambil membetulkan kacamata plusnya, pak Eko kembali menjawab.
"Nana ambil dari sini: https://www.kompasiana.com/theresiabonytha9185/631fd46e08a8b570bc76e3c3/bercadar-bias-berlumur-kelabu. Judulnya, Bercadar Bias Berlumur Kelabu," jawab Nana.
Pak Eko pun mengambil kertas bertuliskan puisi karya Theresia Martini yang Diana print ulang. "Sebentar, saya baca." Pak guru berkaca mata itu pun membaca puisi dengan suara keras.
"Wah, bagus banget Pak Eko baca puisi." puji Diana sambil bertepuk tangan.
"Mau mengkritik pembacaan puisi atau mengkritik puisi?" tanya Pak Eko sambil pura-pura mendelik.
"Ha ha ha .... Iya, deh."
Mereka pun terlibat diskusi.
"Kamu tahu cadar itu apa?" tanya Pak Eko.
"Penutup muka," jawab Diana cepat.
"Selain penutup muka, cadar dalam istilah Geografi berarti hamparan awan tipis tembus cahaya, yang menutupi matahari atau bulan. Nah, untuk memahami puisi ini, coba kamu baca setidaknya tiga kali mengulang. Lalu, resapi. Silakan!" perintah Pak Eko.
Nana pun menurut. Tanpa malu, ia baca puisi itu seperti Pak Eko membacakan untuknya. Selesai sekali, berhenti sebentar lalu mengulang. Setelah tiga kali Diana pun berkomentar.
"Pak, baris keempat bait pertama kok lain, ya? Sebelumnya menceritakan bahwa ada anak kecil di balik bilik berdinding bambu. Sendirian tidak ada siapa-siapa kecuali bubu sebagai temannya. Nah, kalimat keempat "Tak pernah surut meski berpacu dengan waktu" merujuk ke mana, ya?"
Pak Eko diam saja.
"Kalau diikutkan ke bait bawahnya, hmm ... terasa tidak 'nyambung'. Bait kedua bertutur tentang kegiatan si bocah yang merenungi nasibnya yang tak kunjung berubah.
"O, ya? Seperti apa pengarang menggambarkan nasib si bocah yang tak kunjung berubah?" tanya Pak Eko.
"Ya, seperti ombak yang terus bergulung, tidak pernah berhenti."
"Bagus," kata Pak Eko memuji Diana, "Bait pertama dengan kedua erat hubungannya, ya?"
"Coba baca bait ketiga!" perintah Pak Eko.
"Maksdunya apa ya, Pak? Nana belum paham," keluh Diana.
"Sama. Pak Eko juga. Ha ha ha ...," jawab Pak Eko sambil terbahak.
"Ih, Pak Eko ini. Serius, Nana tidak tahu," kata Nana.
"Kalau menurut Pak perenungan si bocah akan nasibnya begitu mendalam. Digambarkan seperti cahaya lentera. Tahu lentera? Cari di internet! Ketika mbak Rahma kecil dan Pak Eko masih tinggal jauh di pedalaman, kami menggunakan lentera untuk menerangi depan rumah. Lentera yang cahayanya tidak seberapa terang itu mencoba menembus gelapnya malam. Mungkin tidak? Si bocah bertanya, kapan nasibku berubah. Mampukan aku melewati kesulitan hidup? Begitu kira-kira," jelas Pak Eko.
"Terus apa makna: kibar layar kian terhempas tertiup angin yang bimbang, siap terlempar bersama badai dan gelombang pasang?" tanya Diana dengan mimik bingung.
"Si bocah tadi dalam hatinya ingin mencoba mengubah nasibnya siap menghadapi rintangan seperti layar yang berkibar tertiup angin yang siap terlempas bersama badai. Kamu tahu 'kan. Meskipun terhempas angin, layar terkembang membuat perahu melaju? Artinya hidup itu harus optimis. Jangan kayak kamu. Dikit-dikit, mumet aku, pusing aku. He he he ...," kata Pak Eko menjelaskan.
"Kena, deh," tukas Diana sambil mengangkat bahu.
"Coba jelaskan apa maksud bait keempat?" tantang Pak Eko.
"Hmm ... kalau nggak salah, nih. Usaha si bocah mengubah nasih masih banyak menemui rintangan. Ombak yang seharusnya disibak karena layar sudah terkembang, bahkan menahan laju perahu. Nasibnya tidak jelas, bagaikan memandang nasib di cermin waktu. Si Bocah semakin putus asa. Nasib baik yang ia gambarkan semakin sulit terwujud." terang Diana dengan semangat.
"Wow Diana seperti mahasiswa jurusan bahasa, lo. Bukan main," puji Pak Eko.
"Ah, Nana jadi malu." Muka Diana memerah dipuji Pak Eko.
"Pak Eko penasaran. Apa maksud dua larik terakhir puisi itu?" tanya Pak Eko selanjutnya.
"Kalau menurut Nana, si bocah hilang semangat akibat sulitnya hidup," jawab Nana
"Kalau Pak Eko menafsirkannya begini. Laut bagi nelayan adalah ladang mencari rezeki. Namun laut pun bercadar bias, artinya seakan tidak ada kepastian apakah si nelayan masih bisa melaut mencari ikan. Kemudian, berlumur kelabu. Kelabu identik dengan samar-samar, penuh ketidakpastian. Akibatnya ia ragu melaut, ia hanya mampu termangu," terang Pak Eko.
"Diana ...," kata Pak Eko, "Si bocah yang digambarkan dalam puisi itu patut dicontoh atau tidak?" tanya Pak Eko.
"Gimana ya, Pak?" jawab Diana ragu.
"Hidup yang keras, zaman yang sulit yang digambarkan penulis sebagai sinar lentera yang mencoba menembus cakrawala. Juga digambarkan sebagai kibar layar terempas angin dan siap terlempar jika badai datang. Sejuta tangan ombak atau ombak yang begitu besar meghadang, lalu langit yang gelap akibat bercadar bias berlumur kelabu. Oleh si bocah nelayan dianggap sebagai hal yang sulit, sehingga ia meminta pembenaran dengan mengatakan hanya mampu termangu."
"Seharusnya rintangan itu ditaklukkan 'kan, Pak?" timpal Diana.
"Seperti siapa?" tanya Pak Eko.
"Siapa, Pak?" tanya Diana bingung.
"Seperti kamu. Tugas gurumu berat lo, tapi kamu taklukkan dengan berdiskusi dengan Pak Eko. Nah, sebelum Nana bangun kembali larik-larik puisi itu, apa mungkin penggambaran kesulitan hidup itu dilakukan oleh seorang bocah kecil?" tanya Pak Eko.
"Rasanya, tidak mungkin," jawab Diana. Ia semakin paham alur puisi yang dipilihnya. Diksinya indah namun bernada pesimis.
"Mestinya, diganti. Misalnya seorang lelaki atau seorang nelayan tua, atau lainnya?" jawab Diana.
"Cerdas!" Pak Eko mengacungkan kedua jempolnya ke arah Diana.
Dua hari kemudian, Pak Eko mendapat pesan WA berisi puisi yang sudah diubah oleh Diana sesuai dengan pemahamannya.
Bercadar Bias Berlumur Kelabu
(Ditulis ulang dari puisi karya Theresia Martini oleh: Nana Diana)
Di balik bilik kecil sempit berdinding bambu
Tampak seorang nelayan tua duduk termangu
Hanya berteman sepi sambil memegang bubu
Jaring terajut, tak surut berpacu dengan waktu
Nelayan tua duduk termangu
waktu berharga begitu saja berlalu
Menatap tak berkedip mata merenungi nasib
Ombak tak lekang terus bergulung berkejaran
Bercengkerama bersama perahu-perahu nelayan
Gelapan cakrawala luas membentang
Kelip lentera berpendar terangi cemasnya gelombang
Kibar layar terhempas tertiup angin, bimbang
Siap terlempar bersama badai dan gelombang pasang
Sejuta tangan ombak menyatu, geladak membisu
Memandang nasib pada cermin waktu tak tentu
Terkulai menatap laut bercadar bias berlumur kelabu
Dihimpit sulitnya zaman nelayan tua hanya termangu
Musi Rawas, 14 September 2022
Salam dan bahagia untuk Ibu Theresia,
PakDSus