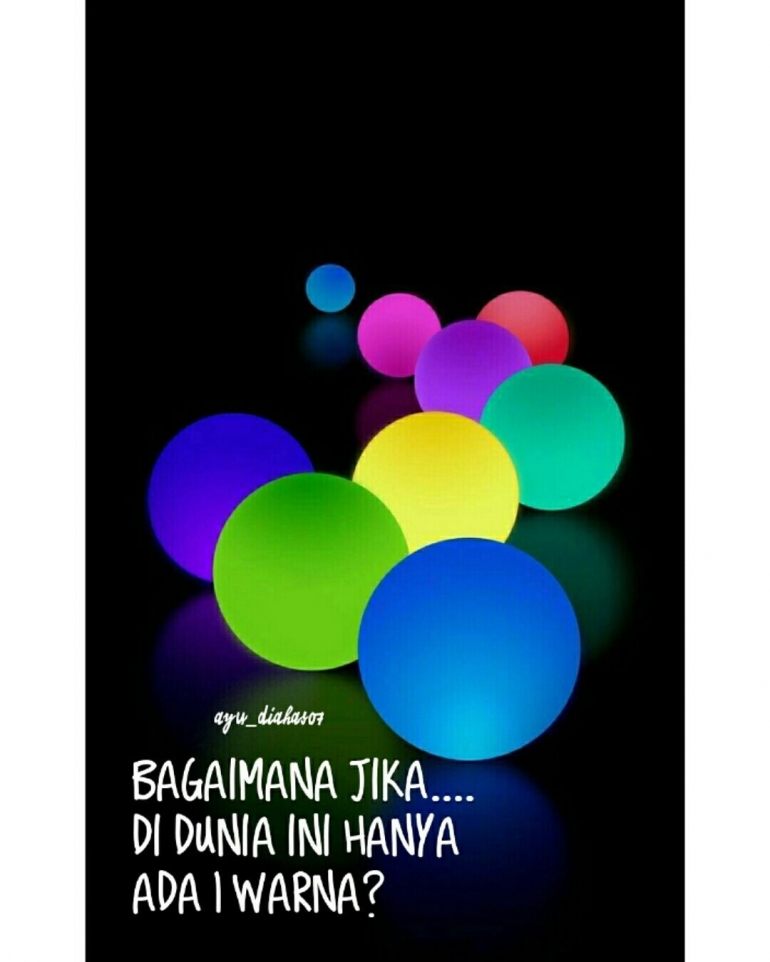Kadang ia hanya bermain "River Flows In You" kala benak penuh cuitan masa lampau bersama Bapak. Trauma pasca perceraiannya dengan Bapak yang kini memilih hidup bersama wanita lain dan keluarganya, belum habis dari ingatan ibu.
Seorang Bapak yang memilih pergi meninggalkan ibu dan aku untuk secuil rasa yang dipujanya sebagai cinta pada wanita yang ingin kusebut sebagai kuntilanak. Membencinya? Entahlah. Kurasa aku hanya harus menjalani hidup seadanya saja.
Ibu, wanita paruh bayaku, seolah mampu berdiri sendiri, menepis stigma janda dalam konstruksi norma masyarakat patriarki, yang terpatri menjadi susunan aturan hakiki, yang sedikit banyak kubenci.
Bapak tak pernah mendengar keluhku, kala botol minumku pernah mampir di rahang Panji, gegara umapatan kejinya pada rambut keritingku. Apa salah Tuhan menciptakan rambut keriting ? Ini indah. Apa salahnya dengan kulit gelapku? Ini pun sempurna. Ya, Tuhan sempurna dalam segala keadilanNya, begitulah kata ibu saat mendamaikan amarahku kala itu.
Asap wangi mengepul memenuhi meja jamuan makan malam yang hanya kami hadiri berdua, ibu dan aku. Yang terhidang di hadapanku bukan tengkleng atau sepiring empal gepuk kesukaanku. Malam ini aku memilih semangkuk bubur hangat lengkap dengan segala uraian aroma bawang, sereh, daun salam, serta kaldu ayam yang melekat di lidah, menerbangkanku ke cielo.
Komposisi sayuran dalam bubur hangat kini menggurui otakku, membanjiri lidah dengan segala keindahan cita rasa sayur nusantara yang beraneka warna. Bubur yang bercampur rempah dari bumbu yang berbaur, tanpa kilatan benci maupun anarki dari tiap sayur yang melebur.
"Kamu ndak usah ikutan komen macem-macem di medsos lho, Ri...,"
Wejangan ibu mulai menelanjangi alur pikirku. Yang kutahu, ibu hanya ingin aku bertumbuh jadi remaja yang berpikir sewajarnya remaja. Namun swargaloka literasi Bapak sejak aku SMP membuat pemahaman "duniaku" agak berbeda dengan mereka yang seusiaku.
Logikaku berputar searah peta jaman bagi kaum milenial seusiaku. Sebenarnya ibu juga tahu, segala bentuk ujar dan konten sensasi anak medsos di berbagai media sosial bukanlah "duniaku". Rasa ingin tahuku yang besar pada kasus sospol seringkali membuat ibu harus turun mata mengawasi rutinitas daringku.
Aku hanya mampu menyuguhkan senyum untuk mengurangi kecemasannya. Tak perlu banyak akrobat kata untuk memenuhi inginnya.
Meskipun aku tak pernah tahu sampai kapan aku menyelesaikan diriku dan ras australomelanesid-ku. Ataukah cukup bagiku menjemur seutas harap di bawah matahari, bahwa label superior pada kulit putih ini segera berlalu. Punah. Terkubur di bawah tanah menjadi batu bertajuk fosil.