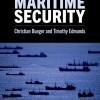Dalam satu pertemuan di ruang kelas. Seorang guru mengajarkan tentang sopan santun. Ketika Guru meminta seorang siswa membersihkan papan tulis tanpa mengucapkan "jika tak keberatan" atau kata "tolong" serta "terima kasih". Maka pertemuan itu, buang-buang waktu saja.
Paragraf di atas, tulisan seorang praktisi parenting, Arlene Silberman. Kukutip dari buku Mendidik Anak (Anton Adiwiyoto, 1993). Buku lama, ya?
Pun, butuh waktu lama aku mengunyah paragraf itu. Aku kembali mengingat dan menghitung ulang, berapa banyak pertemuan yang dianggap buang-buang waktu, gegara berapa kali aku melakukan seperti yang diungkapkan di atas. Sebagai orangtua, teman atau rekan kerja.
Teori-teori yang Terdampar di Ruang Sepi
Sebagai orangtua, tak terhitung kali aku mengajarkan tentang etika dan tata susila kepada anakku. Mesti menghargai dan menghormati orang lain, kalau bicara jangan teriak-teriak, dan selalu menerapkan "tiga kata ajaib" di keluarga. Maaf, Tolong dan Terima kasih.
Namun aku sendiri, sering tak menghargai dan menghormati anakku sendiri, masih suka teriak-teriak, bahkan acapkali lupa mengucapkan maaf, jika telambat mengantar atau menjemput anakku ke sekolah. Hiks...
Sebagai teman, karena kadung merasa dekat dan akrab. Terkadang aku yang sering becanda, terlanjur melampaui "garis batas" etika pertemanan. Yang mungkin tak kulakukan pada orang lain. Dengan alasan, "kan, teman?"
Terkadang, jabatan teman, membuatku "merasa bebas" melakukan apa saja sesuai inginku, karena merasa yakin, temanku pasti akan memaklumi itu. Aih, aku bahkan tak bertanya, apatah dia keberatan dengan hal itu? Hiks lagi...

Aku menjadi ragu! Jejangan aku malah tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan rekan kerjaku. Gawatnya lagi, aku malah mengabaikan apa yang kuucapkan. Aih, paragraph itu mengajakku membuat daftar rasa bersalah. Hiks lagi, dan lagi...
Aku merasa bersalah. Merasakan diri, seperti komandan upacara bendera hari senin, dengan teriakkan "Kepada Bendera Merah Putih, Hormaaaaaat, graak!" Tetapi aku sendiri tidak melakukan penghormatan, dan tidak peduli peserta upacara hormat atau tidak. karena tugasku begitu!
Akupun merasa bersalah lagi. Mungkin saja aku seperti panglima yang menyusun taktik dan strategi perang, kemudian memberikan sambutan yang membakar semangat pada semua pasukan, bahwa itu adalah pertempuran penting menentukan hidup atau mati. Saat pasukanku berjuang, aku duduk minum kopi sambil menunggu laporan.
Aku masih saja merasa bersalah. Terlambat sadar, seharusnya tak perlu banyak membuat aturan yang memuat kata "harus" dan "tidak boleh". Ketika tahu, semakin banyak aturan itu kubuat, maka akan semakin banyak pelanggaran yang terjadi. Dan aku jadi bertambah emosi! Padahal aturan itu terkadang kutambahkan sendiri.
Terkadang, aku menyesali dengan jejalan teori-teori yang yang kudapati. Kenapa mesti ada banyak teori, jika tidak dilakukan? Kenapa dulu, aku tidak diajari contoh-contoh saja, agar aku bisa melakukan hal yang diinginkan, tanpa tersendat gerbong teoritis dengan kalimat "seharusnya".

Aku jadi ingat, Ibuku saat aku meminta izin merantau ke Padang Panjang untuk melanjutkan sekolah. Petuah Beliau yang tak tamat Sekolah Rakyat (sekarang SD) padaku yang baru tamat SMP. "Tiga Petuah Ibu" itu, Tahu diri, Ringan tangan dan Jujur.
Beliau tidak memberikan ceramah yang panjang tentang integritas diri. Namun, tiga hal itu, kulihat melekat dalam keseharian ibuku.
Saat mengantarku ke terminal, tak lagi ada pesan atau ucapan. Ketika kuraih tangan ibu untuk bertukar salam, sesaat sebelum menaiki bus. Beliau tersenyum. Walau aku tahu, ibuku menyimpan airmata juga keresahan seorang ibu.
Hal yang sama kualami, saat anak sulungku, mengikuti jejakku. Di usia yang nyaris sama, Baru tamat SMP, merantau ke kota yang sama, tapi tempat pendidikan yang berbeda.
Sebagai seorang ayah. Aku merasa bersalah juga khawatir, jangan-jangan, tak cukup membekali anakku seperti ibuku dulu. Apatah lagi, di Minang, ada ujaran yang berlaku umum, "Laki-laki tu, nan kadipacik keceknyo!". Lelaki itu, yang dipegang adalah kata-katanya.
Terakhir...
Saat pandemi ini, sulungku masih "dirumahkan". Akupun masih memiliki waktu untuk menyigi pikiran dan perasaanku. Apatah hubungan ayah-anak yang kulakukan selama ini, adalah kegiatan buang-buang waktu?
Analogi perkataan tak seiring dengan perbuatan yang tersirat pada paragraf pembuka tadi, membuatku terjebak pada pertanyaan, "memilih bersalah atau merasa bersalah?"
Curup, 03.07.2020
Zaldychan
[ditulis untuk Kompasiana]