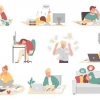Sebagai negara pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger", yang juga diusung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral negara, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Program pemulihan ekonomi nasional sendiri juga mencanangkan kebijakan ekonomi Inklusif, yang menyasar kelompok rentan seperti kaum penyandang disabilitas, pemuda dan perempuan.
Secara khusus, ekonomi Inklusif untuk penyandang disabilitas cukup relevan dengan saya secara pribadi. Kebetulan, saya sendiri adalah seorang penyandang disabilitas, karena kelainan syaraf motorik bawaan yang saya punya sejak lahir.
Ketika ekonomi Inklusif dicanangkan dengan mengusung orientasi jangka panjang, saya mengapresiasi, karena isu ini memang sudah lama jadi satu PR besar di Indonesia. Maklum, penyandang disabilitas kadang jadi kaum terlupakan; ada, meski kadang kurang dianggap.
Tapi, kalau boleh jujur, sebelum digarap, "ekonomi Inklusif" ini seharusnya diawali dulu dengan membangun "budaya inklusif" sebagai fondasinya.
Mengapa?
Karena, posisi penyandang disabilitas secara budaya (di Indonesia) kurang menguntungkan. Ada pembedaan yang hadir secara sistematis, dan membuat situasi terasa kurang mengenakkan.
Di sekolah misalnya, penyandang disabilitas yang sekolah di sekolah umum kadang rawan jadi sasaran "bully" karena tidak bisa melawan. Jumlah pem-"bully" nya memang tak banyak, tapi sulit kalau dilawan sendiri dengan kondisi fisik terbatas.
Sudah harus belajar dan mengerjakan banyak tugas, masih diganggu pula. Menyebalkan sekali.
Selama masa sekolah, saya sempat mengalami, terutama di masa remaja, karena jadi satu-satunya anak "tidak normal" di sekolah. Pada saat tertentu ini menakutkan, tapi tetap bisa dihadapi, karena teman dan guru yang baik jauh lebih banyak.
Di luar itu, saya juga melihat, "inklusif" masih jadi barang langka. Di ruang publik misalnya, fasilitas umum yang ada belum semuanya bisa diakses secara universal, karena didesain berdasarkan standar kondisi fisik "normal".
Itu belum termasuk kalau fasilitas tersebut dipakai untuk parkir motor berdagang, atau kegiatan lain diluar fungsi utama. Apa boleh buat, fasilitas yang pada dasarnya sudah sulit diakses jadi benar-benar tidak bisa diakses.
Situasi jadi makin menjengkelkan, karena saat menapak dunia kerja, kata "inklusif" lagi-lagi jadi barang langka, karena penyandang disabilitas sering terbentur syarat "sehat jasmani rohani" saat mencari kerja.
Syarat ini seperti tanda verboden yang melarang penyandang disabilitas untuk masuk, bahkan sebelum mendekati. Sekalipun sebenarnya mampu, kondisi fisik sering mendatangkan cap kalau mereka "tidak mampu". Sehebat apapun kemampuannya, setinggi apapun pendidikannya, percuma saja kalau sejak awal sudah dilarang masuk.
Apa boleh buat, kerja serabutan pun jadi pilihan tersisa, sekalipun nilainya kadang masih cukup timpang, jika dibandingkan dengan mereka yang normal secara fisik.
Alhasil, saat ada kesempatan merantau ke ibukota pun, saya tidak ragu, karena itulah kesempatan yang ada. Sebuah pengalaman bagus, sebelum pandemi menghancurkan semuanya.
Soal tenaga kerja berkebutuhan khusus, pemerintah memang mengatur kuota persentase khusus untuk penyandang disabilitas di suatu perusahaan. Masalahnya, di lapangan aturan yang ada kadang masih bisa diakali dengan seribu satu macam cara.
Belakangan, memang mulai ada pelatihan-pelatihan keterampilan, kewirausahaan dan rekrutmen kerja untuk penyandang disabilitas.
Masalahnya, ini masih belum efektif, meski sebenarnya ikut mengkampanyekan kata kunci "inklusif". Ironisnya, pendekatan "eksklusif"-lah yang justru terlihat, karena mereka umumnya dikumpulkan menjadi satu kelompok khusus.
Saat pertama kali melihatnya, ini sempat jadi "culture shock" buat saya, yang selama ini cukup terbiasa menjadi satu-satunya manusia "tidak normal" di sekolah (lalu berlanjut di kampus maupun tempat kerja). Ternyata, gap yang ada memang sangat timpang.
Padahal, kalau benar-benar ingin mendorong hadirnya budaya inklusif, seharusnya mereka diberi kesempatan lebih untuk membaur sebagai diri mereka sendiri. Dengan demikian, ada kesempatan untuk lebih berdaya karena tidak dibiarkan terlalu menutup diri.
Daripada menanamkan hal-hal muluk, akan lebih berguna jika mereka diajak belajar realistis, supaya adaptif terhadap situasi serba tidak pasti. Bagaimanapun, budaya perlakuan terhadap difabel di Indonesia masih cukup "keras", jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih terbuka pada difabel.
Di sisi lain, rekrutmen kerja yang ada umumnya masih memberikan kesempatan terbatas dalam bentuk kerja magang, dan semakin terbatas saat naik ke level kerja kontrak apalagi tetap.
Berwirausaha? Tetap perlu keterampilan dan modal cukup untuk membiayai proses "trial and error". Di sini, punya mimpi saja tidak cukup, karena mimpi itu harus tetap dieksekusi.
Apa boleh buat, ketimpangan pun tetap terjaga. Di saat pekerja dengan kondisi fisik normal bisa menetap di satu tempat sampai pensiun, para penyandang disabilitas terpaksa jadi kutu loncat; dari satu magang ke magang lain, dari satu kontrak ke kontrak lain, bahkan bekerja serabutan.
Tidak ada yang berkelanjutan di sini, selain ketidakpastian, ketimpangan ekonomi, dan kalimat motivasi tanpa solusi nyata. Sebelum pandemi saja ini sudah jadi masalah, apalagi setelah pandemi dan beragam efek dominonya datang susul menyusul.
Padahal, penyandang disabilitas juga manusia yang berhak hidup layak. Mereka jauh lebih membutuhkan kesempatan nyata yang bermanfaat jangka panjang, ketimbang terus dicekoki kata-kata manis tapi memabukkan.
Maka, ketika ekonomi Inklusif dengan orientasi jangka panjang dicanangkan pemerintah, memang sudah seharusnya itu dilakukan, karena negara seharusnya hadir untuk semua warganya, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
Di sini, saya menyebut ekonomi Inklusif sebagai satu PR besar, karena ada hambatan budaya yang harus lebih dulu diberantas. Suka atau tidak, kita perlu mengakui, perlakuan diskriminatif terhadap difabel masih jadi satu budaya negatif, karena sudah lama ada, bahkan sejak dalam pikiran.
Padahal, menjadi penyandang disabilitas seharusnya bukan sebuah dosa. Mereka adalah manusia berkebutuhan khusus yang juga berhak dimanusiakan.
Jika budaya inklusif ini dapat dibangun dengan baik, disinilah kita baru boleh bicara lebih lanjut soal ekonomi Inklusif. Seperti halnya diskriminatif, sikap inklusif pun seharusnya dapat dibudayakan.
Budaya inklusif yang kuat akan membuat kesetaraan lebih mudah tercapai, karena semua sudah bisa berpemikiran terbuka, tidak diskriminatif.
Sederhananya, ekonomi Inklusif yang didasari oleh budaya inklusif itu seperti bangunan kokoh yang tahan bencana karena fondasinya sangat kuat. Tapi, perlu perjuangan panjang untuk sampai ke sana.
Di sini, semua pihak terkait perlu berkolaborasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan terpadu, berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, sekalipun nanti periode Presidensi G20 Indonesia sudah selesai, upaya membangun ekonomi Inklusif tidak ikut selesai begitu saja.
Selama syarat "sehat jasmani rohani" di dunia kerja, dan budaya diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih ada, disitulah ekonomi Inklusif masih jadi perjuangan panjang untuk dicapai.