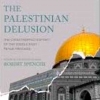Kegaduhan yang dipicu oleh penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang nampaknya masih akan terus berlanjut mengingat perhatian yang semakin meluas dan konsolidasi perlawanan masyarakat sipil yang kian menguat di berbagai daerah.
Sejumlah elit politik, baik di lingkaran istana maupun parlemen, bahkan juga elit-elit partai politik telah mencoba meredamnya dengan melontarkan garansi bahwa UU TNI yang baru saja disahkan tidak akan mengarah pada kebangkitan Dwi Fungsi tentara seperti di era orde baru sebagaimana dikhawatirkan berbagai elemen masyarakat.
Namun dari perkembangan yang dapat dicermati, garansi politik para elit ini terlihat tidak cukup efektif. Penolakan terus meluas dan semakin intens terutama di kampus-kampus di berbagai daerah.
Terkait isu ini ada satu situasi paradoks yang melanskapi perjalanan sejarah tentara kita dalam konteks Indonesia modern yang perlu difahami. Di satu sisi, perspektif demokrasi menghendaki tentara tunduk dibawah prinsip supremasi sipil atas dasar legitimasi politik yang diraih melalui mandat rakyat (Pemilu).
Sementara di sisi lain, sejarah kelahiran tentara Indonesia tidak terlepas dari pergumulan yang intens bersama rakyat ketika melawan dan mengusir penjajah dahulu serta mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Itulah sebabnya, cikal bakal organisasi tentara kita dinamai Badan Keamanan Rakyat (BKR, 1945), lalu bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR, 1945), Tentara Republik Indonesia (TRI, 1946), Tentara Nasional Indonesia (TNI fase pertama, 1947), diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, 1962) di era orde lama, dan terakhir kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI fase kedua, 1999) sejak di era transisi menuju reformasi.
Demokrasi dan Supremasi Sipil
Kembali ke isu penolakan masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI. Ada dua alasan kunci yang melatar belakangi sikap penolakan ini.
Pertama menyangkut tradisi dan cara kerja militer yang dibangun diatas sistem hierarki komando yang secara diametral berlawanan dengan tradisi demokrasi dan masyarakat sipil.
Kedua alasan historis keterlibatan tentara dalam ranah kepolitikan Indonesia modern yang telah meninggalkan jejak pelanggaran hak-hak sipil dan memberangus kebebasan rakyat sebagai warga negara demokrasi.
Secara teoritik fenomena keterlibatan militer dalam politik itu sendiri telah banyak dikaji dan diperbincangkan dalam kerangka hubungan sipil-militer. Pada umumnya para ahli memetakan isu hubungan sipil-militer ini ke dalam dua perspektif. Yakni perspektif negara-negara barat dan perspektif negara berkembang atau negara otoriter.
Di negara-negara barat dimana demokrasi pada umumnya telah mengalami konsolidasi dan establish berlaku model civilian supremacy upon the military (supremasi sipil atas militer).
Dalam model ini, militer berada pada posisi sebagai sub-ordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Dan ini adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Fungsi tunggalnya adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.
Cara pandang yang demikian tentu bukan tanpa alasan. Sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, selain harus fokus dengan fungsi utamanya ini, militer dituntut untuk hanya memiliki loyalitas tunggal yakni terhadap negara.
Dalam rentang waktu tertentu (sesuai dengan masa jabatan pemerintahan sipil hasil Pemilu berkuasa), militer wajib patuh dan loyal pada rezim elektoral.
Kepatuhan dan loyalitas itu merupakan konsekuensi demokrasi karena pemerintahan sipil yang berkuasa dibangun diatas kedaulatan rakyat.
Dengan demikian, kepatuhan dan loyalitas tentara kepada pemerintah hasil Pemilu pada hakekatnya merupakan kepatuhan dan loyalitas tentara kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.
Alasan lainnya karakter militer dianggap berlawanan secara diametral dengan tradisi demokrasi dan masyarakat sipil. Militer dioperasikan dengan cara-cara komando dan bersifat hierarkis. Sementara masyarakat sipil dibangun diatas prinsip dan tradisi demokrasi yang mengedepankan kebebasan, partisipasi dan kesetaraan sebagai warga negara. Memberi ruang pada militer untuk terlibat jauh dalam kehidupan politik potensial dapat menghalangi perkembangan demokrasi.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahwa sebagai institusi, militer merupakan organisasi yang memiliki kekuatan fisik yang melampaui kekuatan elemen-elemen masyarakat sipil. Mereka memiliki anggota (yakni para prajurit) yang terlatih, solid dibawah sistem komando yang bersifat hierarkis, dan dipersenjatai.
Dalam postur yang demikain, memberikan keleluasaan kepada militer untuk terlibat jauh dalam kehidupan politik (termasuk misalnya dalam kontestasi elektoral) adalah tindakan yang mengandung bahaya.
Itulah sebabnya, dalam perhelatan demokrasi elektoral kita, bahkan hak pilih (hak politik) anggota TNI dalam Pemilu ditangguhkan hingga mereka memasuki usia pensiun sebagai tentara.
Esprit de Corpus Tentara
Bertolak belakang dengan perspektif demokrasi yang berlaku di negara-negara barat, di negara-negara berkembang pada umumnya atau di negara-negara otoriter, militer kerap dianggap sebagai kekuatan politik yang memiliki hak untuk ikut mengatur dan mengambil keputusan-keputusan politik strategis bersama kekuatan politik lainnya, terutama partai politik dan parlemen.
Berbasis cara pandang itulah kemudian militer di negara-negara berkembang atau otoriter seringkali --jika tidak selalu-- terlibat jauh dalam kehidupan politik.
Merujuk pada pemodelan yang dibuat oleh Marcus Mietzner (Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation, 2009), diantara faktor yang mendorong tentara terlibat jauh dalam kehidupan politik adalah adanya esprit de corpus, semangat korp di kalangan tentara.
Yakni spirit sebagai institusi utama penjaga ideologi bangsa dan keutuhan negara. Spirit ini biasanya lahir dari akar historis kelahiran dan perkembangan institusi militer itu sendiri dalam lanskap sejarah perjalanan negara yang bersangkutan.
Esprit de Corpus tentara itu tumbuh dalam model Guardian sebagai salah satu dari empat model keterlibatan tentara dalam politik. Di dalam model ini militer tidak terlibat secara langsung dalam pemerintahan sipil.
Artinya militer tetap berada di luar pemerintahan dan bertugas menjalankan fungsinya sebagai alat utama pertahanan-keamanan negara. Akan tetapi, biasanya berdasarkan legitimasi historis, militer menjadi kekuatan yang sangat menentukan (determinative) dalam kehidupan politik.
Meski tidak persis betul, model The Guardian itulah yang (sedikit banyak) pernah terjadi di sepanjang era orde baru melalui doktrin politik Dwi Fungsi, dimana selain berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga diberi fungsi sosial-politik.
Doktrin ini berakar pada pemikiran Jendral AH. Nasution tentang konsep "Jalan Tengah" tentara dalam konstelasi kehidupan politik nasional, yang diterjemahkan secara keliru dan kebablasan oleh Presiden Soeharto.
Distorsi Dwi Fungsi
Dampak buruk praktik Dwi Fungsi ABRI telah banyak dikaji para ahli dan peneliti. Diantaranya Daniel S. Lev ("ABRI dan Politik: Politik dan ABRI" dalam Jurnal HAM dan Demokrasi, 1999), yang menyimpulkan bahwa dwi-fungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi juga menyumbang secara luar biasa bagi kerusakan kelembagaan kenegaraan, karena seluruh lembaga negara diposisikan berada dibawah kekuasaan institusi militer.
Simpulan studi lainnya dikemukakan oleh Peter Britton (Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, 1996), yang mengungkapkan, bahwa "...bagian teritorial dari Angkatan Darat memastikan kehadirannya di setiap kota dan di sementara daerah, di setiap daerah, di setiap desa dengan tugas memelihara keamanan, mengawasi kegiatan-kegiatan aparat pemerintahan sipil dan bertindak sebagai pengawas-pengawas politik. Para perwira militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, semakin banyak yang beralih kepada kedudukan-kedudukan penting sebagai pejabat-pejabat pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan industri, semuanya menjadi berada dibawah pengendalian".
Dominasi dan cengkraman tentara dalam kehidupan politik itu bukan saja telah mengakibatkan tersendatnya pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Melainkan juga telah melahirkan rentetan peristiwa dan berbagai bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) oleh aparatur ABRI di berbagai daerah.
Sebut saja misalnya peristiwa Tanjung Priok (1984), Talangsari Lampung (1989), kerusuhan 27 Juli 1996 dan Timtim pasca referendum penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur (1999) dll.
Ringkasnya, pelbagai distorsi dan ekses negatif penerapan doktrin Dwi Fungsi yang dikombinasikan dengan model struktur kekuasaan teritorial telah "menjerumuskan" ABRI sebagai tulang punggung pertahanan-keamanan negara yang mestinya fokus pada kesiagaan pengamanan negara dari berbagai ancaman (domestik maupun luar negeri, potensial maupun nyata) ke dalam area permainan politik yang merupakan domain masyarakat sipil.
Akibatnya kerap terjadi tentara "terpaksa" harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri; dengan para mahasiswa, para aktivis LSM, para kyai serta elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.
Itulah yang dicemaskan oleh masyarakat sipil saat ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI