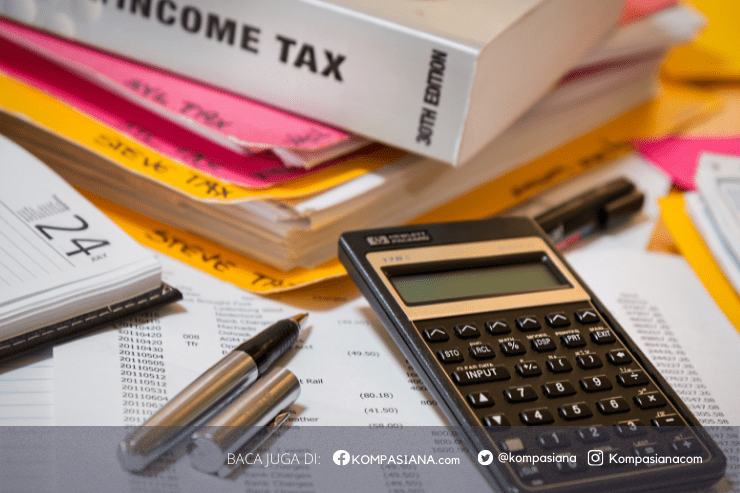Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel kembali memuncak, kali ini melampaui sekadar retorika politik. Dunia dikejutkan ketika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap agresi militer Israel. Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini merupakan jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Lebih dari 20 persen pasokan minyak mentah global melewati kawasan ini setiap harinya.
Langkah ini langsung memicu gejolak di pasar global. Harga minyak mentah melonjak, kekhawatiran terhadap keamanan energi meningkat, dan negara-negara pengimpor utama seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara Uni Eropa mulai mencari alternatif jalur logistik dan pasokan energi.
Namun, di tengah krisis tersebut, Indonesia memiliki peluang besar yang jarang muncul dua kali. Letak geografis Indonesia sangat strategis: berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta dilintasi jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Ketika dunia mencari jalur alternatif, kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia yangberpotensi menjadi simpul logistik dan perdagangan maritim global.
Sayangnya, keunggulan geografis saja tidak cukup. Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika infrastruktur maritim Indonesia siap. Proyek strategis nasional seperti Pelabuhan Patimban, Kuala Tanjung, dan Makassar New Port harus diselesaikan tepat waktu dan terintegrasi dalam sistem logistik nasional. Program Tol Laut juga harus diperkuat dan dijalankan secara konsisten agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi solusi nyata konektivitas antarwilayah.
Selain pelayaran, potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat luas. Perikanan tangkap, budidaya laut, wisata bahari, hingga energi laut terbarukan merupakan sektor yang masih bisa dikembangkan lebih serius. Di tengah ketidakpastian global, kemandirian energi dan pangan berbasis laut menjadi sangat relevan. Energi arus laut dan konversi panas laut (OTEC) berpotensi menjadi solusi energi bersih dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.
Indonesia juga perlu memperkuat industri pendukung seperti galangan kapal dan armada logistik nasional. Jangan sampai negeri kepulauan ini justru bergantung pada kapal asing untuk pergerakan barang dalam negeri. Kemandirian sektor ini akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap berbagai tekanan eksternal.
Krisis Selat Hormuz juga memberi pelajaran penting tentang pentingnya diplomasi maritim. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, dapat memimpin kerja sama kawasan untuk menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik. Kolaborasi dengan ASEAN dan negara-negara mitra seperti Jepang, India, dan Australia sangat diperlukan untuk menjamin jalur pelayaran yang aman dan stabil.
Semua upaya ini idealnya mengarah pada implementasi nyata ekonomi biru atau blue economy. Konsep ini menekankan pemanfaatan laut secara berkelanjutan: menjaga keseimbangan ekologi, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pemerataan sosial. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan kekayaan laut yang luar biasa, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pemimpin ekonomi biru di dunia.
Namun, tantangan tetap ada. Banyak regulasi belum sinkron, birokrasi masih lambat, dan dukungan kebijakan fiskal untuk sektor kelautan masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian politik dan visi jangka panjang untuk meletakkan laut sebagai pusat pertumbuhan nasional, bukan sekadar pelengkap daratan.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukan hanya krisis bagi Timur Tengah, tetapi juga momentum global yang membuka ruang bagi negara-negara lain untuk tampil. Indonesia harus melihat ini sebagai peluang strategis, bukan hanya sebagai penonton di tengah ketidakpastian dunia.
Menjadi negara kepulauan adalah takdir geografis. Namun, menjadi kekuatan maritim dunia adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Pilihan itu kini terbuka. Dunia sedang bergerak. Tinggal bagaimana Indonesia menjawab tantangan zaman dengan langkah yang nyata, bukan hanya wacana.