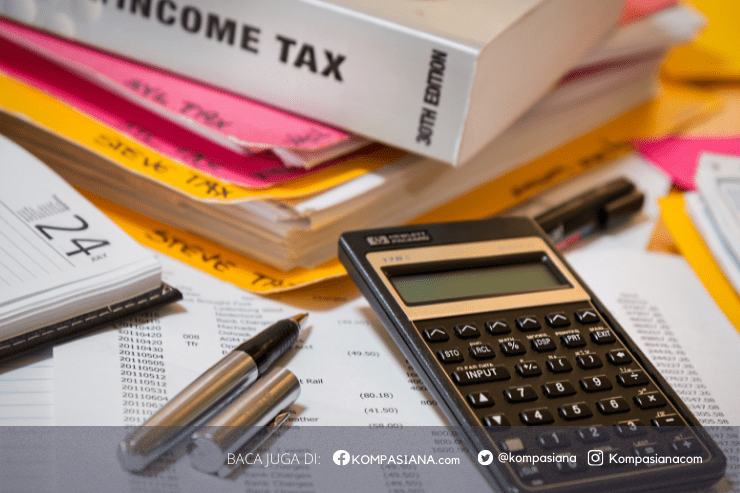Tapi di balik itu, ada asumsi dasar: bahwa semua orang punya daya saing yang sama. Bahwa si ibu penjual gorengan tadi bisa "naik kelas" asal diberi modal dan pelatihan. Padahal mungkin ia tak bisa baca, apalagi mengelola laporan keuangan.
Dan meskipun ada orang yang berhasil, tak sedikit yang gagal, terjerat utang, lalu terpinggirkan lagi. Karena sistem ini memang tidak dirancang untuk menyeimbangkan. Ia hanya memfasilitasi siapa yang bisa lari paling cepat di arena balap.
Yang kuat bertahan. Yang lemah? Silakan minggir.
Sosialisme: "Semua Dikasih Sama Rata Biar Gak Ada yang Iri"
Sosialisme lahir dari kritik terhadap ketimpangan. Bahwa sebagian kecil orang menguasai sebagian besar sumber daya, sementara yang lain cuma jadi buruh. Maka solusinya adalah: negara ambil alih semuanya, lalu dibagi secara adil.
Kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapus. Semua milik negara, atau rakyat secara kolektif. Tak ada lagi bos atau karyawan. Semua sama. Semua dapat bagian.
Masalahnya: teori ini keren di atas kertas, tapi rapuh di dunia nyata. Ketika semua disamaratakan, motivasi individu hilang. Inovasi lambat. Birokrasi jadi raksasa. Dan diam-diam muncul "kelas elite" baru: mereka yang mengatur pembagian.
Akhirnya? Sama-sama susah. Sama-sama antre. Sama-sama mengeluh.
Islam: "Negara Wajib Menjamin Hidupmu"
Islam memandang kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi. Tapi masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan bukan lewat teori pasar atau mimpi kolektif, tapi lewat hukum ilahiah yang praktis.
Solusinya? Sistematis dan berlapis.