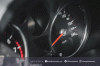Pada 18 September 2025, saya menghadiri sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh AISMOLI, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Kami yang hadir berbicara panjang lebar tentang masa depan kendaraan listrik, tentang ekosistem, tentang percepatan adopsi. Tapi pulang dari sana, saya justru membawa kegelisahan.
Alih-alih memperkuat optimisme, saya pribadi merasa diskusi itu memperlihatkan betapa jauhnya arah kebijakan dan strategi industri dari kebutuhan nyata masyarakat. Yang lebih mengganggu: mindset lama---yang seharusnya sudah ditinggalkan---masih mendominasi cara berpikir banyak pengambil keputusan.
Sepeda Motor Listrik dan Kesederhanaan yang Terlupakan
Sepeda motor listrik lahir dari gagasan yang sederhana dan kuat: menghadirkan moda transportasi yang efisien, murah, praktis, dan ramah lingkungan. Ia tidak membutuhkan SPKLU megah, tidak perlu ekosistem rumit seperti mobil listrik. Justru kesederhanaan itulah kekuatannya.
Namun kini, hampir semua stakeholder sibuk membangun infrastruktur besar yang tidak relevan. SPBKLU dan SPKLU bermunculan di mana-mana, seolah sepeda motor listrik harus tunduk pada logika kendaraan bensin (ICE). Padahal, sepeda motor listrik bisa diisi di rumah dengan colokan biasa. Perawatannya ringan. Konsumsi energinya kecil. Begitu logika ICE diterapkan, keunggulan alaminya hilang. Yang seharusnya jadi solusi sederhana malah dipaksa masuk ke sistem yang kompleks dan mahal.
Mindset ICE yang Masih Menyusup
Inilah akar masalahnya: mindset. Banyak pembuat kebijakan dan pelaku industri masih menggunakan kerangka pikir kendaraan bermesin bensin ketika membicarakan sepeda motor listrik. Karena terbiasa dengan SPBU, bengkel besar, dan sistem sentralistik, mereka pun memaksakan hal yang sama pada EV roda dua.
Muncullah SPKLU dan SPBKLU sebagai prioritas, lengkap dengan regulasi dan investasi besar. Padahal, untuk sepeda motor listrik, logika ini tidak relevan. Kita sedang memaksakan sistem mobil listrik ke kendaraan yang justru dirancang untuk lepas dari ketergantungan infrastruktur besar.
Survei yang Menyesatkan: Antara Keinginan dan Kebutuhan
Salah satu hal yang paling mengganggu, saya sampaikan dalam diskusi AISMOLI adalah cara survei digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Banyak survei yang dilakukan tampaknya lebih menyoroti "apa yang diinginkan" oleh responden, bukan "apa yang dibutuhkan." Ini bukan sekadar perbedaan semantik---ini perbedaan paradigma.
Keinginan sering kali dipengaruhi oleh imajinasi, ekspektasi, atau bahkan gaya hidup yang tidak representatif. Maka lahirlah spesifikasi yang bombastis: kecepatan maksimum 120 km/jam, jarak tempuh 200 km, fast charging hanya 1 jam. Padahal, realitas di jalan jauh berbeda. Rata-rata kecepatan dalam kota hanya 40 km/jam, kebutuhan jarak tempuh harian 20--50 km, dan charging semalaman sudah lebih dari cukup.
Lebih parah lagi, masyarakat kita sering mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan ekstrem yang porsinya sangat kecil. Contoh klasik adalah mudik lebaran: satu kali perjalanan jauh dalam setahun seakan-akan dijadikan standar utama memilih kendaraan. Padahal 360 hari sisanya kendaraan hanya dipakai untuk kebutuhan harian di dalam kota.
Ketika survei hanya menangkap keinginan, maka kebijakan pun ikut terseret ke arah yang tidak relevan. Kita berakhir dengan sepeda motor listrik yang terlalu mahal, terlalu kompleks, dan terlalu jauh dari kebutuhan mayoritas rakyat. Padahal, jika kita mau jujur, kebutuhan masyarakat jauh lebih sederhana: kendaraan yang bisa diisi di rumah, murah, praktis, dan cukup untuk mobilitas harian.
Ojol: Etalase yang Disalahpahami
Salah satu bias terbesar dalam kebijakan EV adalah fokus berlebihan pada ojek online. Karena mereka butuh swap battery dan fast charging, maka seluruh ekosistem nasional diarahkan ke sana. Padahal, jumlah ojol sangat kecil dibanding populasi pengguna sepeda motor secara keseluruhan.
Penggunaan EV oleh ojol seharusnya menjadi etalase---panggung untuk menunjukkan ketangguhan teknologi EV. Bahwa sepeda motor listrik sanggup menempuh jarak panjang, dipakai intensif, dan tetap andal. Tapi menjadikan ojol sebagai tujuan akhir adalah kesalahan. Fokus yang terlalu sempit justru membuat sepeda motor listrik gagal berkembang sebagai kendaraan masyarakat luas. Sepeda motor listrik kemudian identik dengan image sebagai kendaraan kerja bagi ojol dan kurir.
Infrastruktur yang Salah Sasaran
Karena bias ojol ini pula, pembangunan infrastruktur publik menjadi prioritas. SPBKLU dan SPKLU dibangun di mana-mana. Padahal, di negara-negara yang lebih maju dalam adopsi EV, mayoritas pengisian daya dilakukan di rumah. Untuk sepeda motor listrik, pola ini jauh lebih masuk akal. Konsumsi energinya kecil dan bisa dipenuhi dengan daya listrik rumah tangga.
Jika arah pengembangan terlalu menekankan pembangunan infrastruktur publik, justru manfaat sepeda motor listrik sebagai moda sederhana akan hilang.
Pemerintah Belum Memberi Teladan
Di tengah euforia kebijakan, pemerintah sendiri belum memberi contoh nyata. Armada dinas, kendaraan operasional instansi, hingga motor patroli masih didominasi bensin. Padahal, transisi EV seharusnya dimulai dari institusi publik. Tanpa teladan, wacana migrasi hanya berhenti di slogan.
Industri yang Terpecah dan Minim Transparansi
Industri sepeda motor listrik pun belum bersatu. Produsen sibuk membangun ekosistem tertutup masing-masing. Tidak ada interoperabilitas, tidak ada standar bersama. Konsumen dipaksa memilih ekosistem tertutup. Pasar pun terfragmentasi.
Contoh nyata: brand A membangun charging station, tapi hanya bisa digunakan oleh produk brand A. Tidak ada kemauan berbagi infrastruktur. Konsumen bingung, adopsi tersendat.
Kepercayaan publik juga terganjal oleh minimnya transparansi data teknis. Konsumen butuh informasi jelas soal spesifikasi, jarak tempuh riil, durasi charging, harga baterai, dan garansi. Tanpa itu, keputusan pembelian jadi spekulatif. Transparansi bukan hanya soal etika, tapi fondasi kepercayaan.
SDM: Pilar yang Sering Terlupakan
Transisi ke EV juga menuntut kesiapan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan dan pelatihan harus mulai menyiapkan teknisi, insinyur, dan tenaga ahli di bidang kendaraan listrik. Tanpa SDM yang mumpuni, industri EV akan sulit bertahan dan berkembang.
Komunitas: Pedang Bermata Dua
Di tengah semua kebingungan ini, saya sempat menyebut komunitas sebagai ruang yang paling jujur. Tapi saya juga harus mengakui: komunitas bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, komunitas adalah tempat lahirnya semangat. Di sana, orang-orang berbagi pengalaman nyata, saling bantu, saling dorong. Komunitas bisa menjadi katalis perubahan, bahkan lebih cepat dari institusi formal. Tapi di sisi lain, komunitas juga bisa melahirkan bias baru---terutama ketika didominasi oleh anggota yang terlalu "hardcore."
Saya menyaksikan sendiri bagaimana sebagian komunitas EV terjebak dalam glorifikasi teknologi. Ada yang menganggap sepeda motor listrik harus punya torsi tertentu, harus bisa fast charging, harus pakai sistem swap battery, dan sebagainya. Ada pula yang fanatik pada satu merek, menolak interoperabilitas, bahkan menolak diskusi tentang kebutuhan pengguna biasa.
Narasi yang dibangun pun kadang terlalu teknikal, terlalu eksklusif. Seolah-olah hanya mereka yang paham spesifikasi dan algoritma baterai yang layak bicara soal EV. Padahal, transisi ke kendaraan listrik bukan soal membentuk elite baru, melainkan membuka akses seluas-luasnya.
Komunitas yang sehat adalah komunitas yang mampu menampung keragaman pengalaman. Yang tidak hanya bicara soal performa, tapi juga soal aksesibilitas. Yang tidak hanya memuji teknologi, tapi juga berani mengkritik arah kebijakan. Yang tidak hanya mengedukasi, tapi juga mendengarkan.
Komunitas tidak terikat pada siklus politik atau tekanan pasar, mereka punya posisi unik untuk menjaga arah. Pejabat bisa berganti, industri bisa bangkrut, LSM bisa beralih fokus. Tapi komunitas tetap ada—menjadi ruang refleksi, ruang edukasi, memori kolektif dan ruang advokasi yang berkelanjutan.
Saya percaya, jika komunitas EV ingin menjadi kekuatan perubahan, maka ia harus berani merefleksikan dirinya sendiri. Harus berani bertanya: apakah kita sedang membangun gerakan publik, atau hanya membentuk klub eksklusif?
Stakeholder yang Bergerak Sendiri-sendiri
Satu hal yang sangat terasa dalam diskusi AISMOLI adalah minimnya koordinasi lintas stakeholder. Setiap pihak tampak bergerak dengan logikanya sendiri, membangun ekosistemnya sendiri, dan menetapkan prioritasnya sendiri---tanpa kerangka bersama yang menyatukan arah.
Pemerintah sibuk meresmikan proyek infrastruktur dan menetapkan target adopsi, tapi belum memberi teladan penggunaan EV secara konkret. Industri berlomba-lomba memamerkan teknologi dan membangun ekosistem tertutup, tanpa interoperabilitas. Komunitas mendorong edukasi dan adopsi, tapi kadang terjebak dalam glorifikasi teknis. Akademisi dan lembaga riset pun belum sepenuhnya terlibat dalam menyusun standar atau kurikulum teknis yang dibutuhkan.
Akibatnya, ekosistem EV roda dua di Indonesia tumbuh secara parsial dan tidak sinkron. Tidak ada peta jalan bersama, tidak ada standar teknis yang disepakati, dan tidak ada mekanisme kolaboratif yang mengikat. Padahal, transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar urusan teknologi---ia adalah transformasi sistemik yang menuntut sinergi lintas sektor.
Kembali ke Akar
Dari semua hal di atas, saya kembali diingatkan pada fondasi awal kenapa kita perlu bermigrasi ke kendaraan listrik. Bukan untuk mengejar fitur mewah atau infrastruktur megah. Tapi untuk alasan yang membumi: menekan biaya transportasi, mengurangi impor BBM, memperbaiki kualitas udara, dan menyediakan moda transportasi yang bisa diakses semua kalangan.
Sepeda motor listrik seharusnya menjadi kendaraan rakyat. Sederhana, efisien, dan relevan. Ia bukan simbol futuristik yang hanya tampil di konferensi atau pameran teknologi, melainkan alat mobilitas harian yang nyata dan terjangkau.
Jika arah kebijakan terus melenceng dari kebutuhan mayoritas, kita berisiko menjadikan sepeda motor listrik sebagai proyek mahal yang tidak menyentuh kehidupan nyata. Padahal, peluang untuk menjadikannya solusi transportasi massal masih terbuka lebar---asal kita berani kembali ke akar, mendengarkan suara pengguna, dan membangun ekosistem yang inklusif, bukan eksklusif.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI