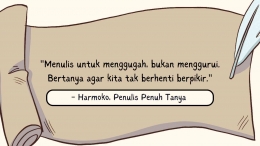"HRD yang baik itu ibarat wasit: tidak berpihak, tapi adil, dan tahu kapan meniup peluit---tanpa membuat pemain trauma."
- Penulis Penuh Tanya
Ekspektasi yang Melangit
Dalam banyak seminar motivasi atau konten di LinkedIn, HRD (Human Resources Development) kerap digambarkan sebagai sosok strategis: jembatan antara kepentingan manajemen dan kesejahteraan karyawan. Ia bukan sekadar penjaga absensi atau pemberi SP, tapi pemikir strategis, pendengar empatik, sekaligus partner bisnis.
Sayangnya, ketika realita mengetuk pintu, ekspektasi itu sering kali hanya jadi narasi cantik di slide PowerPoint.
Banyak pekerja, terutama Gen Z, menganggap HRD seharusnya:
1. Paham kesehatan mental karyawan.
2. Transparan dalam proses rekrutmen.
3. Menyediakan ruang diskusi tanpa intimidasi.
4. Menjadi pembela ketika ada ketidakadilan struktural di tempat kerja.
Namun di sisi lain, beberapa HRD sendiri merasa seperti "tali tambang di tarik ulur dua kapal". Mereka harus mengamankan kepentingan perusahaan, menjaga biaya efisien, namun tetap dipaksa tampil seperti pahlawan berkepala tiga yang bisa menangani konflik kerja, urusan legal, hingga drama pantry.
HRD, Jangan Cuma Jago Excel dan SP
Seorang karyawan pernah berkeluh kesah kepada saya, "Saya kena SP cuma gara-gara telat 15 menit. Tapi ketika saya mengeluh tentang beban kerja berlebihan, HRD bilang itu bagian dari loyalitas. Katanya kalau nggak kuat, ya cari kerja lain aja."
HRD idaman bukanlah yang bersenjata SP, tapi yang bisa membaca situasi. Telat kerja 15 menit bisa jadi pertanda burnout, bukan hanya soal ketidakdisiplinan. Perusahaan modern harus belajar membedakan mana pelanggaran kerja, mana sinyal distress dari pekerja yang terlalu lama menahan beban.
Tentu, HRD juga manusia. Tidak semua dilatih untuk mendalami psikologi kerja atau pendekatan berbasis trauma (trauma-informed approach). Tapi menjadi HRD hari ini menuntut keberanian untuk naik level: dari sekadar pengelola SDM menjadi penjaga kemanusiaan di tempat kerja.
Dunia yang Tak Ideal, Tapi Bisa Dibikin Manusiawi
Tidak semua perusahaan mampu menggaji HRD berpengalaman atau membentuk tim SDM yang ideal. Di banyak perusahaan menengah, bahkan satu orang bisa merangkap: HRD, GA, admin, sekaligus tukang beli galon.
Namun, keterbatasan itu tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk menjadi HRD yang kaku dan tanpa empati.
Menjadi HRD idaman bukan berarti harus punya gelar psikologi klinis atau MBA. Kadang cukup dengan tiga hal ini:
1. Mendengar tanpa menghakimi
Dengarkan karyawan bukan hanya saat exit interview. Jadilah tempat curhat yang aman tanpa merasa sedang menginterogasi.
2. Komunikasi jujur dan transparan
Jangan beri harapan palsu. Jika perusahaan belum bisa memberi kenaikan gaji, jelaskan alasannya dengan terbuka dan logis.
3. Berani memperjuangkan yang benar
Jika ada atasan yang melecehkan karyawan, HRD jangan hanya diam demi menjaga nama baik perusahaan. Sesekali, jadilah pemberontak berdasi.
HRD dan Dunia yang Terus Berubah
Kebutuhan dunia kerja berubah. Dulu, yang penting karyawan datang, kerja, pulang. Kini, karyawan ingin tempat kerja yang punya nilai.
Mereka bertanya:
- Apakah HRD mendukung inklusivitas?
- Apakah ada program kesehatan mental?
- Bagaimana HRD menangani diskriminasi?
Dan jangan salah: HRD juga dituntut untuk terus belajar. Sertifikasi Human Capital Management, pelatihan Diversity & Inclusion, hingga pengetahuan tentang UU Ketenagakerjaan yang selalu direvisi.
Menjadi HRD hari ini bukan hanya soal tahu cara rekrut atau PHK. Tapi soal bagaimana menjadikan tempat kerja sebagai tempat tumbuh bersama.
HRD Bukan Superhero, Tapi Bisa Jadi Sahabat
Jangan dibayangkan HRD sebagai sosok serba bisa. Mereka pun punya tekanan, punya target dari atasan, dan kadang harus bersikap tidak populer demi menyelamatkan bisnis.
Namun, bila kita mampu membangun budaya kerja yang sehat, HRD tidak harus menjadi antagonis di mata karyawan. HRD bisa menjadi pendamping yang adil, jujur, dan terbuka.
Mungkin belum semua HRD bisa seperti itu. Tapi perubahan dimulai dari kesadaran kecil: bahwa di balik angka-angka laporan, ada manusia yang ingin dimengerti.
Penutup: Idealita dan Realita Bisa Bertemu di Tengah
Menjadi HRD idaman adalah proses. Ia bukan gelar yang diberikan, tapi sikap yang dipraktikkan tiap hari.
Dan seperti kata pepatah Jepang: "Shokunin kishitsu" --- semangat menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Dalam dunia kerja yang makin kompleks, HRD punya peluang menjadi tokoh sentral peradaban kantor. Bukan hanya pengelola SDM, tapi penjaga nurani perusahaan.
Palembang, 18 Juli 2025

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI