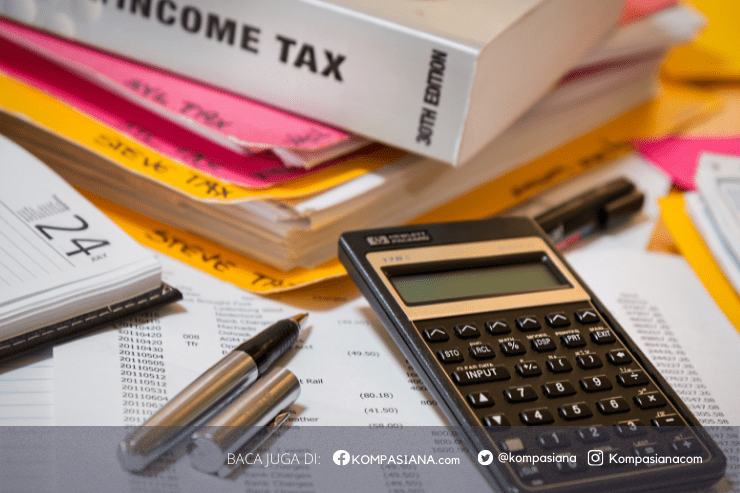Ketika Angka Kemiskinan Menjadi Instrumen Politik...
Pada Juli 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan yang mengklaim bahwa tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,47% atau 23,85 juta jiwa per Maret 2025. Angka ini turun tipis 0,1 poin persentase dari September 2024 yang sebesar 8,57%. Dengan bangga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut ini sebagai "bukti komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan."
Namun, di balik euforia statistik ini, tersembunyi realitas yang jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan. Data BPS yang terkesan "baik-baik saja" ini telah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan peneliti, akademisi, dan lembaga kajian independen. Mereka mempertanyakan validitas metodologi yang digunakan BPS, yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat Indonesia.
Paradoks Mengejutkan: 8,47% vs 68,3%
Ketika BPS mengklaim hanya 8,47% penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2025 mengejutkan dengan temuan yang sangat berbeda: sekitar 68,2 persen penduduk Indonesia, setara dengan 194,4 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan internasional US$6,85 per hari.
Perbedaan yang mencengangkan ini bukan sekadar masalah teknis pengukuran, melainkan menunjukkan ketidakkonsistenan fundamental dalam cara Indonesia memahami kemiskinan. Gap data kemiskinan BPS (8,47%) dan Bank Dunia (68,3%) memantulkan paradoks ini: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan merata.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Bhima Yudhistira, dengan tegas menyatakan bahwa penduduk miskin di lapangan sebenarnya jauh lebih banyak dari data resmi pemerintah. Pernyataan ini bukan tanpa dasar, mengingat CELIOS telah melakukan penelitian lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data statistik dengan realitas di lapangan.
Metodologi Usang: Warisan 1998 yang Tak Kunjung Diperbarui
Salah satu kritik paling mendasar terhadap BPS adalah penggunaan metodologi Cost of Basic Needs (CBN) yang sudah berusia hampir tiga dekade. Peneliti utama SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, mengatakan, standar garis kemiskinan itu sudah tidak relevan karena pemerintah masih mengacu pada metodologi pengukuran garis kemiskinan yang berlaku sejak tahun 1998 dan belum pernah dievaluasi.
Ketidakrelevanan metodologi ini semakin kentara ketika kita melihat perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia selama 27 tahun terakhir. Pada 1998, internet belum menjadi kebutuhan dasar, biaya pendidikan belum semahal sekarang, dan makanan jadi belum mendominasi pola konsumsi masyarakat urban. Namun, BPS masih berpegang teguh pada asumsi bahwa 74,5% pengeluaran rumah tangga miskin adalah untuk makanan, padahal realitas menunjukkan proporsi yang berbeda.
Ironisnya, BPS sendiri mengakui perlunya pembaruan metodologi. Namun, proses yang seharusnya dimulai sejak 2020 ini terus terhambat dengan alasan "kompleksitas pola konsumsi dan keterbatasan data." Keengganan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan politik di balik mempertahankan metodologi usang tersebut.
Garis Kemiskinan yang Tidak Masuk Akal
BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp2,9 juta untuk rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota. Angka ini terdengar wajar di atas kertas, namun ketika dihadapkan dengan realitas biaya hidup, angka tersebut menjadi absurd.
Ambil contoh sederhana: biaya susu formula untuk bayi berkisar Rp500.000-Rp1 juta per bulan. Artinya, hampir sepertiga dari seluruh "anggaran" rumah tangga miskin habis hanya untuk susu formula satu bayi. Belum lagi biaya pendidikan anak (minimal Rp300.000 per anak), listrik, air, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyatakan bahwa metodologi usang dari BPS berdampak langsung terhadap kebijakan anggaran, terutama perlindungan sosial. Menurut Media, dengan jumlah penduduk miskin yang kecil menurut data resmi, maka alokasi untuk bantuan sosial juga menjadi tidak memadai.
Kritik serupa datang dari Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) DIY yang menyinggung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menunjuk BPS sebagai lembaga pengukur capaian pengentasan kemiskinan. "Kalau metodologinya tetap seperti sekarang, hasil akhirnya bisa bias atau dapat dipandang sebagai target politik, bukan kebutuhan rakyat," tambahnya.
Dampak Sistemik: Ketika Data Salah Menentukan Kebijakan
Konsekuensi dari data kemiskinan yang tidak akurat bukan sekadar masalah akademis, melainkan berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan standar kemiskinan BPS sebagai acuan utama.
Hasilnya? Paradoks yang mencengangkan: program bantuan sosial pemerintah menjangkau lebih banyak orang daripada jumlah penduduk miskin versi BPS. Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup 10 juta rumah tangga (sekitar 40 juta jiwa), bantuan sembako menjangkau 18,8 juta rumah tangga (75 juta jiwa), sementara BPS hanya mengakui 23,85 juta jiwa sebagai penduduk miskin.
Kontradiksi ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak percaya sepenuhnya pada data BPS. Mereka tahu bahwa jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan jauh lebih besar dari yang tercatat secara resmi. Namun, untuk kepentingan narasi politik, data BPS tetap dipertahankan sebagai "bukti keberhasilan" pemerintah.
Ketika Angka Menjadi Alat Politik
Penurunan kemiskinan sebesar 0,1 poin persentase dari 8,57% menjadi 8,47% yang diklaim pemerintah sebagai "prestasi" sebenarnya adalah penurunan yang tidak signifikan secara statistik. Dengan margin of error yang biasa terjadi dalam survei nasional, perbedaan 0,1% ini bisa jadi hanya fluktuasi statistik biasa, bukan penurunan riil.
Lebih problematik lagi, penurunan ini terjadi di tengah inflasi pangan yang tinggi, kenaikan harga BBM, dan berbagai tekanan ekonomi lainnya yang seharusnya membuat lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. Fakta bahwa angka kemiskinan justru "turun" di tengah kondisi ekonomi yang tidak kondusif menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas data tersebut.
Kemiskinan Indonesia adalah persoalan struktural. Oligarki ekonomi-politik menciptakan sistem di mana elite menguasai sumber daya vital, namun data BPS seolah-olah menyembunyikan realitas struktural ini dengan angka-angka yang "tampak baik."
Suara dari Lapangan: Ketika Statistik Bertabrakan dengan Realitas
Kritik terhadap data BPS tidak hanya datang dari akademisi dan peneliti, tetapi juga dari praktisi yang bekerja langsung dengan masyarakat miskin. Mereka melihat bagaimana keluarga-keluarga yang secara objektif membutuhkan bantuan tidak masuk dalam kategori "miskin" versi BPS.
Contoh konkret terjadi di Kampung Apung Jakarta Utara, di mana warga mengeluh tidak menerima bantuan selama bertahun-tahun meskipun kondisi ekonomi mereka jelas memerlukan dukungan. Ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan BPS gagal menangkap kelompok-kelompok rentan yang sebenarnya membutuhkan perhatian pemerintah.
CELIOS dalam berbagai laporannya menyebutkan bahwa banyak masyarakat rentan tidak terdata sebagai miskin di DTKS karena standar BPS yang terlalu rendah. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap program-program bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka.
Perbandingan Internasional: Indonesia Tertinggal dari Negara Serupa
Ketika negara-negara seperti Malaysia dan Filipina telah mengadopsi pendekatan multi-dimensi dalam mengukur kemiskinan---menggabungkan data pendapatan, pengeluaran, dan indikator kesejahteraan lainnya---Indonesia masih bertahan dengan metodologi sederhana yang hanya fokus pada pengeluaran.
Malaysia, misalnya, menggunakan Poverty Line Income (PLI) yang disesuaikan dengan biaya hidup riil di setiap negeri. Filipina mengadopsi Philippine Statistics Authority (PSA) method yang mempertimbangkan variasi regional dan pola konsumsi modern. Sementara Indonesia masih berpegang pada formula 1998 yang sudah tidak relevan.
Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia menaikkan garis kemiskinan ke US$3,65-$6,85 per hari untuk mencerminkan status sebagai negara berpendapatan menengah atas. Namun, rekomendasi ini sepertinya diabaikan karena akan "merusak" narasi keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.
Mengapa BPS Enggan Berubah?
Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah: mengapa BPS sebagai lembaga yang seharusnya independen dan profesional enggan memperbarui metodologi yang sudah terbukti usang?
Beberapa faktor dapat menjelaskan keengganan ini:
Tekanan Politik: Sebagai lembaga di bawah pemerintah, BPS tidak sepenuhnya independen dari kepentingan politik. Data kemiskinan yang rendah menguntungkan narasi keberhasilan pemerintah, terutama menjelang atau setelah pemilihan umum.
Keterbatasan Kapasitas: Memperbarui metodologi memerlukan riset mendalam, survei ulang, dan investasi besar dalam sistem data. BPS mungkin tidak memiliki kapasitas atau anggaran yang memadai untuk melakukan pembaruan komprehensif.
Resistensi Internal: Perubahan metodologi akan membuat data kemiskinan lama tidak dapat dibandingkan langsung dengan data baru. Ini akan "merusak" tren penurunan kemiskinan yang selama ini menjadi kebanggaan BPS dan pemerintah.
Kurangnya Tekanan Publik: Masyarakat umum tidak memahami detil teknis metodologi kemiskinan, sehingga kurang ada tekanan publik untuk melakukan reformasi.
Jalan Keluar: Reformasi Menyeluruh yang Tidak Bisa Ditunda
Untuk mengatasi krisis validitas data kemiskinan Indonesia, diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak bisa ditunda lagi:
1. Pembaruan Metodologi Komprehensif
BPS harus segera memperbarui metodologi CBN dengan:
- Menyesuaikan proporsi makanan dan non-makanan berdasarkan pola konsumsi terkini
- Memasukkan kebutuhan modern seperti internet, transportasi, dan makanan jadi
- Mengadopsi pendekatan multi-dimensi yang menggabungkan data pendapatan dan pengeluaran
2. Garis Kemiskinan Regional yang Realistis
Garis kemiskinan harus disesuaikan dengan disparitas biaya hidup antar daerah. Tidak masuk akal jika garis kemiskinan di Jakarta sama dengan di daerah rural Papua. Setiap provinsi atau bahkan kabupaten harus memiliki garis kemiskinan yang mencerminkan biaya hidup riil di wilayah tersebut.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Publik
BPS harus lebih transparan dalam metodologi dan proses pengambilan data. Publikasi reguler tentang cara pengukuran, survei yang dilakukan, dan keterbatasan data akan meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan kritik konstruktif dari akademisi dan praktisi.
4. Keterlibatan Stakeholder yang Lebih Luas
Proses reformasi metodologi harus melibatkan tidak hanya pemerintah dan akademisi, tetapi juga organisasi masyarakat sipil, praktisi lapangan, dan bahkan masyarakat yang menjadi subjek pengukuran kemiskinan.
5. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Independen
Perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi metodologi pengukuran kemiskinan secara berkala. Lembaga ini harus bebas dari intervensi politik dan memiliki mandat untuk melakukan kritik konstruktif terhadap data pemerintah.
Saatnya Mengakhiri Ilusi Statistik
Data kemiskinan BPS yang mengklaim hanya 8,47% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan adalah ilusi statistik yang berbahaya. Berbahaya karena menyembunyikan realitas struktural kemiskinan yang masih mengakar di Indonesia, dan berbahaya karena menjadi dasar kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Ketika 68,3% penduduk Indonesia hidup dengan kurang dari US$6,85 per hari menurut Bank Dunia, sementara BPS mengklaim hanya 8,47% yang miskin, ada yang salah dengan cara kita memahami kemiskinan. Dan yang salah bukan realitas lapangan, melainkan metodologi dan standar yang kita gunakan.
Reformasi metodologi kemiskinan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah dan BPS harus berani mengakui bahwa metodologi yang digunakan selama ini sudah tidak relevan dan berkomitmen untuk melakukan pembaruan menyeluruh. Hanya dengan data yang akurat dan metodologi yang valid, Indonesia dapat merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.
Rakyat Indonesia layak mendapatkan kebijakan yang didasarkan pada data yang benar, bukan pada ilusi statistik yang menguntungkan narasi politik semata. Saatnya mengakhiri permainan angka dan mulai serius mengatasi kemiskinan struktural yang masih membelenggu jutaan anak bangsa.
Artikel ini disusun berdasarkan analisis terhadap data BPS, laporan Bank Dunia, penelitian SMERU Research Institute, CELIOS, dan berbagai sumber kredibel lainnya. Kritik yang disampaikan bertujuan konstruktif untuk mendorong perbaikan sistem pengukuran kemiskinan Indonesia agar lebih akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI