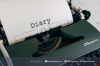Masa-masa paling suram ketika diterpa gangguan mental terjadi pada sepanjang tahun 2018. Waktu itu keadaan saya kacau. Sangat-sangat kacau. Saya diteror oleh gejala yang baru saya ketahui belakangan bernama halusinasi dan delusi (waham). Keduanya terus menghantui sepanjang tahun, membuat saya kehilangan realitas pada kehidupan yang saya jalani sehari-hari.
Saya kurang ingat kapan pertama kali gejala-gejala itu mulai muncul. Mungkin pertengahan tahun 2017, mungkin juga pada akhir tahun 2017. Namun, gejala-gejala itu mulai menganggu bagi saya pada awal tahun 2018. Awalnya saya diterpa oleh halusinasi auditori (suara). Suara yang saya dengar macam-macam: ada yang memaki, menghasut, dan bising bak ingar bingar keramaian. Perilaku saya sehari-hari jadi bergantung pada suara macam apa yang sedang saya dengar. Kala dilanda oleh suara yang memaki misal, saya akan mudah marah, kesal, atau bahkan mengamuk sampai membanting barang-barang. Lalu, saat saya dilanda oleh suara yang menghasut, saya akan tanpa pikir panjang melakukan apapun yang suara itu suruh. Salah satu yang paling sering: saya disuruh pergi dari rumah, diperingati kalau ada seseorang yang bakal datang mencelakai saya. Suara itu berkata: cepat pergi! Atau seseorang akan membunuhmu! Saya akan langsung pergi kala mendengar suara tersebut, tanpa persiapan, tanpa membawa benda-benda penting (seperti kartu identitas dll), dan dengan pakaian yang seadanya. Lalu, saat saya dilanda oleh suara yang seperti ingar bingar keramaian, saya bakal jadi nggak mudeng sama setiap perkataan orang lain. Diajak ngomong dalam keadaan itu, saya bakal kebanyakan hah-heh-hoh, persis seperti orang tua yang pendengarannya sudah ada di tahap prihatin. Selain itu, saya juga jadi sulit fokus, mudah lupa, dan sering insomnia gara-gara terus mendengar suara berisik tersebut.
Masih di tahun yang sama, selain halusinasi saya juga akhirnya mulai mengalami delusi. Delusi atau waham yang saya alami berupa merasa yakin diawasi, dibuntuti, atau bahkan diincar nyawanya oleh seseorang. Saya bakal merasa cemas, khawatir, gelisah, atau bahkan takut sejadi-jadinya kala mengalami hal tersebut. Gerak-gerik saya dalam keadaan itu juga kentara banget. Menurut tetangga yang pernah memperhatikan saya, dia pernah melihat saya berjalan dengan gelisah, gusar, dan terus menengok ke belakang seolah-olah ada orang lain yang mengikuti saya. Perasaan seperti ini juga pernah saya alami waktu di rumah, saat saya sedang mengerjakan sesuatu di laptop dan tiba-tiba merasa seseorang telah memata-matai saya melalui kamera laptop yang saya gunakan. Rasa takut yang teramat sangat membuat saya menutup laptop, menghentikan kegiatan, dan jadi nggak pernah mau menggunakan laptop itu sama sekali selama berhari-hari (atau kadang berminggu-minggu). Kadang, saya juga jadi curiga kepada orang-orang rumah, merasa kalau merekalah yang selama ini mengawasi dan mengintai saya. Kecurigaan itu membuat saya nggak betah di rumah dan memilih pergi dari sana untuk menenangkan diri. Tentu, di masa itu saya belum menyadari bahwa perasaan yang saya alami adalah delusi.
Namun yang paling ngeri dari semuanya adalah saat halusinasi visual menyerang. Jadi, selain mengalami halusinasi auditori, saya juga mengalami halusinasi visual (penglihatan). Memang, harus saya akui dibanding dengan halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan adalah halusinasi yang jarang sekali menerpa kehidupan saya sehari-hari. Namun, sekalinya muncul, beuh! Saya akan sangat kacau, nggak keruan, berantakan, luluh lantak, dan entah istilah apa lagi yang bisa saya pakai untuk menggambarkan kondisi ini. Salah satu yang paling mengerikan dan masih saya ingat adalah saat saya melihat wajah semua orang menyeramkan. Di mata saya, muka mereka sama: melotot, bergigi taring, dan terus menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Saya pernah lari terbirit-birit waktu mengalami ini saat sedang jalan pulang dari suatu tempat ke rumah. Dengan napas tersengal-sengal, sesampainya di depan rumah saya langsung membuka pintu dengan kasar, nggak peduli lagi menutupnya, dan kemudian mengurung diri di kamar. Ibu saya menghampiri waktu itu untuk bertanya kenapa saya terlihat ketakutan. Namun, saya nggak berani menjelaskan apa-apa, sebab, di mata saya wajah ibu juga menunjukan rupa yang sama. Itu menjadi keadaan terburuk yang pernah saya alami dari menderita gangguan mental. Menjadikan saya takut berhari-hari dan akhirnya selalu mengurung diri.
***
Karena gejala yang nggak mereda dan terus bertambah intensitasnya, ibu akhirnya membawa saya ke psikiater pada awal Januari 2019. Jantung saya berdebar-debar saat duduk di ruang tunggu poli psikiatri. Saya overthinking waktu itu, merasa kalau pertemuan saya dengan psikiater bakal berlangsung dengan nggak mengenakan. Ada teater di kepala saya bahwa psikiater yang saya temui bakal mencecar saya dengan macam-macam pertanyaan. Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa punya pikiran seperti itu. Semua terjadi begitu saja, tanpa saya ketahui sebabnya.
Namun, teater dalam kepala buyar ketika ternyata psikiater yang saya temui adalah orang yang humble. Ia tersenyum ramah, menyapa saya dan ibu saat saya masuk dengan jantung---yang masih---berdebar-debar. Nggak banyak yang saya ingat saat sesi konsul berlangsung selain ibu yang banyak mengeluh ini-itu tentang kondisi saya. Ia mengadu soal saya yang sering kelihatan cemas, takut, dan insomnia yang melanda setiap hari. Singkat cerita, dari konsultasi hari itu, saya didiagnosa pertama kali mengalami gangguan kecemasan (anxiety disorder).
Namun, pada pertengahan tahun diagnosa itu berubah menjadi skizofrenia paranoid. Psikiater akhirnya tahu kondisi saya yang sebenarnya, setelah semuanya terungkap pada suatu sesi konsul. Waktu itu saya disuruh untuk menuliskan apa yang saya cemaskan dan takutkan sehari-hari ke dalam buku catatan. Metode itu ditempuh gara-gara saya sulit berkomunikasi, karena sejak ibu absen mengantar saya ke psikiater (karena halangan pekerjaan), saya diharuskan datang dan menjelaskan apa-apa sendiri. Saat membaca buku catatan saya pada suatu hari, psikiater menyadari bahwa beberapa minggu belakangan ini saya sering menulis tentang suara-suara yang membuat saya ketakutan. Dia lalu jadi membuka lagi catatan saya di halaman-halaman sebelumnya. Karena terlalu sering keluhan soal suara itu muncul, psikiater akhirnya bertanya, "kamu tahu nggak itu suara siapa?"
Saya menggeleng.
Dia lalu bertanya lagi, "Suara itu terdengar di telinga kamu, atau cuma kayak suara hati aja?"
Saya menjawab, "Di telinga, Dok."
"Benar-benar jelas di telinga?"
Saya mengangguk.
Suasana mendadak hening. Mata psikiater kembali berlabuh ke buku catatan saya, membuka kembali halaman-halaman sebelumnya, lalu setelahnya berkata, "Minggu depan bisa nggak kamu datang sama ibu kamu? Cuma untuk hari itu aja."
Saya diam sebentar. Kemudian mengangguk untuk menyanggupi permintaannya. Ia lalu meresepkan saya obat. Nggak lama saya keluar dengan membawa resep tersebut, menebusnya ke apotek, dan membawa pulang obat yang saat itu entah kenapa beda dari obat-obat saya sebelumnya.
Pada minggu berikutnya, sesuai janji saya datang ke psikiater ditemani oleh ibu saya. Ia sampai harus izin kepada bosnya untuk menemani saya berkunjung ke rumah sakit hari itu. Di sanalah semuanya terungkap: saya mengalami gejala psikotik. Suara-suara yang saya dengar merupakan bagian dari halusinasi. Sementara rasa cemas dan takut yang mengganggu sehari-hari---yang tadinya diduga sebagai gejala kecemasan---ternyata adalah delusi. Di situlah pertama kali saya mendengar kata skizofrenia. Psikiater kemudian menjelaskan kepada saya dan ibu apa itu skizofrenia. Secara singkat ia adalah gangguan mental yang mempengaruhi penderitanya dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Masalah utama penderita skizofrenia terletak pada otaknya. Di mana penderita sulit membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan. Skizofrenia juga terbagi dalam beberapa golongan. Yang mana, dalam kasus saya, saya mengalami skizofrenia paranoid.
Terungkapnya hal itu membuat ibu saya baru tahu kalau saya sering mendengar suara-suara yang nggak nyata. Selama ini ia nggak tahu sama sekali karena saya yang minim sekali berbicara untuk cerita. Selain itu, saya juga nggak sadar bahwa suara-suara itu merupakan gejala dari suatu gangguan mental, sehingga nggak perlu rasanya untuk cerita ke siapapun, termasuk ke ibu saya. Ibu hanya bisa melihat gejala-gejala yang nampak pada diri saya, seperti kecemasan, ketakutan, dan insomnia. Sehingga, hanya itulah yang bisa ia sampaikan ke psikiater saat pertama kali saya konsul. Di mulai dari sejak itu, setelah semuanya terungkap, perjuangan saya yang sesungguhnya dalam menghadapi gangguan mental dimulai.
Minggu-minggu berikutnya sesi konsultasi selalu fokus ke bagaimana saya harus menghadapi halusinasi dan delusi. Di antara keduanya, yang paling sering diperbincangkan adalah halusinasi suara. Selain harus mengonsumsi obat untuk menekan gejalanya, psikiater juga meminta kepada ibu untuk mengalihkan pikiran saya dari suara-suara tersebut. Ia berpesan: jangan sampai saya tenggelam atau terhanyut oleh suara-suara itu. Saya juga diharuskan cerita ke ibu setiap kali mendengar suara-suara, selain untuk memberi sinyal ke ibu kalau saya butuh dialihkan, hal itu juga untuk mengonfirmasi apakah suara yang saya dengar nyata atau nggak. Ini menjadi fokus masalah yang terus dihadapi dan selalu dibicarakan setiap kali saya berkonsultasi. Hal itu dilakukan demi saya bisa mengatasi gejala dan terhindar dari tindakan-tindakan yang nggak berdasarkan realita.
***
Dan, sejak itu kemudian tahun-tahun berlalu. Banyak sudah yang saya lewati seputar menghadapi gangguan mental ini. Sejak pertama berobat, sampai saya menulis ini, waktu sudah berjalan selama kurang lebih enam tahun. Selama itu saya terus berjuang: rajin berobat dan terus mendengarkan apa-apa yang dikatakan psikiater. Pada masa stabil, saya mulai penasaran soal gangguan mental yang saya alami dan mulai bertanya banyak ke psikiater tentang hal-hal yang berkaitan dengan gangguan mental ini. Salah satu yang membuat saya penasaran adalah berapa lama saya harus menjalani ini, terapi ini. Psikiater lalu memberi tahu bahwa pemulihan skizofrenia adalah proses yang panjang. Konon lamanya tergantung dari tingkat keparahan masing-masing individu. Ia pernah bilang: semakin lama terdeteksi, semakin lama pula jangka waktu pengobatan yang dijalani. Hal itu membuat saya paham, bahwa saya harus ekstra sabar dalam menghadapi gangguan mental yang menyiksa ini.
Masalah utama saya di awal-awal menjalani terapi adalah soal obat. Adanya obat yang saya minum pagi hari, yang ternyata membuat saya lumayan mengantuk menjadi kegelisahan saya di awal-awal mengonsumsi obat tersebut. Memang, nggak sedahsyat obat malam yang membuat saya langsung tepar dan bermimpi indah di pulau kapuk. Namun, tetap saja saya merasa risi karena dengan begitu saya jadi kebanyakan tidur. Untungnya, efek itu hanya sementara saja. Cuma di awal-awal saja saya mengantuk saat meminum obat pagi dan seterusnya saya hanya mengantuk waktu meminum obat malam saja. Yang mana, obat malam yang membuat ngantuk itu memang diperlukan agar saya bisa tidur nyenyak dan punya waktu yang cukup untuk beristirahat. Psikiater pernah berpesan: kualitas tidur yang baik dapat menstabilkan dopamin. Yang mana, dalam kasus saya yang mengalami skizofrenia, ketidakstabilan zat dopamin itulah yang membuat saya mengalami gejala. Saya kini paham kenapa dulu kondisi saya bisa separah itu. Dopamin yang berlebih, dan insomnia yang parah, adalah kombinasi yang ekstrem untuk membuat segalanya memburuk.
Pada suatu sesi konsul saya pernah bertanya ke psikiater tentang kenapa saya bisa begini. Psikiater lalu menjelaskan kalau skizofrenia adalah gangguan mental yang multifaktor. Ia nggak disebabkan oleh satu hal, melainkan banyak. Ada tiga faktor yang disebutkan oleh psikiater waktu itu: genetik, biologis, dan lingkungan. Di antara ketiganya, saya merasa relate dengan faktor lingkungan berupa stres berat yang dulu pernah menimpa saya, yang kemungkinan membuat saya mengembangkan potensi skizofrenia. Jadi, di masa lalu saya pernah stres gara-gara mendapat tekanan di lingkungan kerja. Saya lalu memutuskan resign. Namun, alih-alih stres itu hilang, saya malah mendapat tekanan lagi dari orang-orang di lingkungan rumah. Keputusan saya untuk resign dicemooh. Dibilang bodoh, tolol, dan berbagai ujaran lain yang nggak seharusnya pantas untuk dilontarkan ke saya. Saya mengerti apa yang saya lakukan adalah kegagalan. Tapi, bukan dengan itu orang lain bebas menghardik saya dan merasa seolah-olah saya nggak bakal punya kesempatan lagi. Hidup terasa serba salah waktu itu: bertahan salah, resign pun juga salah. Dan, karena saya terus memendam semuanya sendiri, jadilah saya semakin terpuruk selama berhari-hari.
Namun, perlu saya tekankan lagi bahwa skizofrenia adalah gangguan mental yang multifaktor. Nggak selalu orang yang merasakan stres seperti saya bakal mengalami skizofrenia juga. Bisa jadi, pada kasus saya dua faktor lain selain faktor lingkungan juga sudah ada di diri saya sejak lama tanpa saya sadari dan ketahui. Dan, apapun penyebabnya sekarang, buat saya nggak lebih penting dari bagaimana menghadapinya.
Sepanjang belajar menghadapi skizofrenia, saya paham bahwa nggak ada kata sembuh bagi penyintasnya, melainkan pulih. Pulih dalam arti si penyintas bisa kembali normal dalam menjalani kehidupan, namun dengan bantuan obat-obatan. Saya akui memang berat di awal-awal ketika harus menelan fakta bahwa saya harus selalu meminum obat. Ada kalanya saya meratapi nasib, kehilangan semangat, dan jadi malas mengonsumsi obat secara rutin. Efeknya: ya, tentu saja saya jadi kambuh lagi. Psikiater agak kecewa ketika mengetahui saya minum obat bolong-bolong dan akhirnya kambuh. Namun, alih-alih memarahi, ia justru memberi saya edukasi. Ia beri tahu lagi betapa pentingnya minum obat bagi saya yang mengalami skizofrenia. Dia juga berpesan kepada saya untuk jangan memusuhi obat, dan mulailah menganggapnya seperti teman. Menurutnya, minum obat bagi yang membutuhkan harus dianggap sebagai rutinitas yang ringan, yang nggak perlu dijalani dengan malas-malasan atau bermuka masam. Psikiater lalu memberi saya contoh orang-orang di luar sana yang juga harus mengonsumsi obat demi keberlangsungan kehidupan. Bukan untuk membandingkan katanya, tetapi untuk membuat saya sadar bahwa saya bukanlah satu-satunya orang di dunia yang harus menjalani rutinitas tersebut. Saya cukup mengerti pesan psikiater. Secara nggak langsung ia ingin bilang kepada saya bahwa obat adalah alat bantu yang penting. Mungkin analoginya sama seperti orang bermata minus yang harus mengenakan kacamata---dan nggak masalah dengan itu---saya pun sepertinya harus punya persepsi yang sama.
Nasihat psikiater cukup mudah untuk dipahami dan diterima. Sejak itu, semangat saya dalam mengonsumsi obat muncul lagi. Saya kembali rajin mengonsumsinya dan nggak menganggapnya lagi sebagai beban yang harus diratapi berhari-hari. Lagi pula, kalau dipikir-pikir buat apa juga saya merasa beban minum obat yang prosesnya saja bisa berlangsung sangat cepat. Menyadari ini, saya rasa bukan rutinitasnya yang berat, tetapi pikiran saya yang ke mana-mana sama fakta harus selalu meminum obat. Saya merasa menjadi makhluk paling menyedihkan di muka Bumi yang harus menelan pil itu setiap hari. Pikiran semacam itulah yang membuat saya lupa dari tujuan utama: nggak mau lagi merasakan kambuh.
Dan, terbukti juga akhirnya, ketika saya kembali rajin mengonsumsi obat---dan nggak menganggapnya lagi sebagai beban---perlahan tapi pasti gejala-gejala itu mereda kembali. Psikiater cukup happy ketika mendengar saya semakin stabil dari waktu ke waktu. Ia berkata: jika keadaan saya terus seperti ini, maka target pengobatan saya untuk hanya meminum satu jenis obat setiap hari bisa dengan mudah tercapai dan terpenuhi. Saya cukup happy mendengar itu karena berarti jalan menuju pulih itu: ada.
***
Lalu masalah lainnya dalam menghadapi skizofrenia adalah stigmanya. Penderita skizofrenia---atau gangguan mental secara keseluruhan---sering kali dianggap atau dicap "orang gila". Bahkan, hanya ketika mendengar seseorang pergi ke psikiater, kebanyakan pasti bertanya dengan dahi mengernyit penuh heran, "lo gila, Bro?" Saya sendiri pernah mendapat stigma itu langsung dari seorang ibu-ibu sekitar rumah yang nggak sengaja bertemu saya waktu sedang mengantre di warung. Si ibu bertanya setelah memperhatikan saya dalam beberapa detik yang panjang.
"Kamu bukannya anaknya si anu yang katanya gila itu ya? Yang berobat ke psikiater?"
Saya menjawab datar, "Iya, Bu."
Si ibu bertanya lagi, "Kok kamu kelihatan normal-normal aja?"
Jujur, waktu itu saya agak kesal dengan ucapan si ibu. Bisa-bisanya dia blak-blakan menyebut saya "gila" hanya gara-gara dia dengar saya berobat ke psikiater. Kenapa juga dia harus heran melihat saya normal? Bukankah dia tahu saya berobat?
Saya kemudian menjawab, "Ya, kan saya berobat, Bu. Ikhtiar."
Si ibu diam. Ia hanya mengangguk pelan sampai tiba gilirannya untuk dilayani pemilik warung.
Pertanyaan si ibu menandakan ia kurang paham bahwa gangguan mental bisa dipulihkan dengan berobat ke medis. Kondisi saya waktu itu sudah jauh berbeda dari kondisi saya waktu tahun 2018 atau 2019 yang lalu. Saya sudah lebih baik dalam menilai realitas sehingga kehidupan yang saya jalani pun tampak normal di mata orang lain. Beberapa orang ada yang nggak percaya saya memiliki gangguan mental hanya gara-gara melihat waktu itu kondisi saya cukup stabil. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat memang nggak teredukasi soal isu kesehatan mental dengan baik. Mereka terus meyakini kepercayaan lama bahwa penderita gangguan mental adalah selalu ODGJ yang berkeliaran di jalan dengan pakaian lusuh dan nggak akan bisa sembuh.
Anggapan lain yang beredar di masyarakat adalah kebanyakan menganggap gangguan mental atau jiwa adalah sesuatu yang lain dari penyakit fisik. Mereka merasa bahwa gangguan jiwa adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang nggak terlihat, dan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan dunia medis atau kedokteran. Makanya, orang-orang jadi berpendapat bahwa gangguan jiwa adalah karena diguna-guna, kesurupan, dan berbagai pendapat lain yang nggak jauh dari logika mistika. Sehingga, gara-gara pendapat ini banyak orang memilih untuk membawa penderita gangguan mental atau jiwa ke "orang pintar", untuk kemudian dibacakan mantra atau bahkan disembur mukanya dengan air yang sudah terkontaminasi (oleh jigong si penyembur). Mereka rela menempuh cara-cara seperti itu, karena kurangnya pengetahuan soal isu kesehatan mental dan percaya begitu saja kepada si "orang pintar" yang mereka yakini sangat bisa menyembuhkan si penderita. Alasan mereka untuk percaya ke "orang pintar" juga kurang kuat. Bahkan mereka juga nggak tahu apa latar belakang si "orang pintar", mengapa dia bisa menyembuhkan seseorang.
Saya sendiri sudah beberapa kali mendapat stigma seperti itu. Bahkan salah satu pelakunya adalah dari saudara sendiri. Kebanyakan menilai bahwa saya diguna-guna, kerasukan jin, sehingga saran-saran yang mereka berikan pun adalah ke "orang pintar". Begitu kental stigma dan saran seperti itu di masyarakat membuat mereka jadi kurang paham bahwa gangguan mental juga berkaitan dengan fungsi organ tubuh dan kimia otak. Skizofrenia yang saya alami misal, masalahnya ada di otak. Berlebihnya zat dopamin membuat saya mengalami halusinasi dan delusi: mendengar, melihat, dan merasakan yang nggak nyata. Untuk itulah saya berobat. Untuk menyeimbangkan kembali zat tersebut agar saya bisa normal dalam menjalani kehidupan. Sampai sini, setelah mengalami, menghadapi, dan mengetahui, saya sepakat kalau penyakit mental sama seperti penyakit fisik: sama-sama perlu pertolongan medis.
Nggak hanya pada penyintasnya, stigma juga dilayangkan pada terapi obat gangguan mental. Karena kurangnya pemahaman soal isu kesehatan mental, terapi obat untuk gangguan mental sering kali dianggap bahaya dan menyebabkan ketergantungan (apa lagi yang berobatnya lama seperti saya). Stigma seperti ini jelas menghambat dan merugikan banyak orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat dari terapi tersebut. Selama saya mengonsumsi obat, saya nggak pernah merasa ketergantungan dengan obat yang saya minum. Bagi saya, terapi obat membuat saya lebih baik, membuat saya terhindar dari gejala-gejala yang dulu menghantui, dan membuat saya terbantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu berbeda dari definisi ketergantungan yang sering dilayangkan pada orang-orang yang menyalahgunakan obat. Saya mendapatkan obat secara legal, mereka mendapatkannya secara ilegal. Saya meminumnya sesuai dengan dosis yang ditentukan dokter, mereka meminumnya seenak udel. Saya merasakan manfaat positif dari obat tersebut, mereka mengincar efek negatif dari mengonsumsi obat tersebut. Mungkin dari pada menyebutnya ketergantungan, saya rasa lebih tepat menyebutnya sebagai kebutuhan. Sayangnya, kebiasaan banyak orang yang mudah percaya pada info yang nggak dicari tahu dulu kebenarannya, membuat stigma soal obat berbahaya laku keras dan bersemayam dalam benak banyak masyarakat.
Kini, setelah enam tahun berobat, bisa dibilang kondisi saya cukup baik. Dibandingkan dengan di masa lalu, saya sudah jarang mengalami halusinasi, delusi, atau bahkan insomnia yang dulu jadi makanan saya sehari-hari. Pernah, ada kalanya di suatu masa di hidup saya, saya meratap: kok, hidup gue jadi gini ya? Tapi, begitulah hidup: nggak ketebak. Ada kalanya kehidupan berjalan nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi, ya, harus diakui memang seperti itulah adanya. Kata orang realita itu kejam. Tapi bagi saya halusinasi dan delusilah yang justru lebih kejam. Pelan-pelan, halusinasi dan delusi menyingkirkan saya dari realita, membuat saya terlihat aneh dan membuat saya ketakutan pada hal-hal yang sebenarnya nggak nyata. Saya pernah sedih, kecewa, dan merasa menjadi manusia paling nggak berguna gara-gara meratapi ini. Tetapi, di tengah-tengah ratapan itu, saya justru menemukan arti hidup dari hal-hal kecil. Entah, ketika saya membantu driver ojek yang sulit menemukan alamat, membeli dagangan dari seorang ibu yang berjualan keliling (meski dengan jumlah yang nggak seberapa), atau membantu seorang nenek yang kebingungan untuk registrasi di rumah sakit untuk berobat ke poli yang dia tuju. Saya punya peran, pun begitu juga dengan semua orang. Dan kalau saya punya peran---meski peran itu kecil dan kurang berarti di mata orang lain---itu berarti saya masih berguna. Saya lalu sadar: pikiran yang membuat saya merasa nggak berguna adalah pikiran yang menipu. Saya bukan apa yang saya pikirkan, atau orang lain pikirkan. Saya adalah bagaimana saya berpikir. Saya percaya bahwa hidup adalah siklus untuk mengalami perasaan-perasaan yang pernah kita alami---atau orang lain pernah alami. Kalau saya pernah sedih, pasti saya akan bahagia lagi. Kalau saya pernah jatuh, pasti saya akan bangkit lagi. Dan, kalau saya pernah kambuh, pasti suatu hari saya akan pulih lagi. Menulis cerita ini mungkin nggak membuat saya pulih seratus persen, tetapi menyelesaikannya membuat saya paham apa itu rasanya lega.
***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI