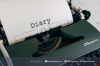Tahun 2015 tercatat sebagai salah satu momen paling kelam dalam sejarah ekologis Indonesia. Kala itu, asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membubung tinggi, menyelimuti Sumatra dan Kalimantan dengan selimut abu yang menyesakkan. Tak hanya langit yang gelap, tetapi juga harapan jutaan orang yang menggantung pada udara bersih, tanah subur, dan hidup yang sehat.
Asap itu tak mengenal batas negara. Ia merayap ke Malaysia, Singapura, bahkan Filipina. Lebih dari 500 ribu orang jatuh sakit, jutaan lainnya terdampak secara langsung---terutama anak-anak dan lansia. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, aktivitas lumpuh, dan rumah sakit penuh dengan pasien sesak napas.
Sebanyak 2,6 juta hektare lahan habis terbakar. Sebagian besar di antaranya adalah lahan gambut, harta karun karbon yang ketika terbakar, melepaskan emisi dalam skala global. Pada puncaknya, emisi harian dari karhutla Indonesia bahkan melampaui total emisi harian Amerika Serikat---negara industri terbesar di dunia.
"Waktu itu saya berada di Pekanbaru, berkunjung ke rumah teman SMA. Setiap pagi, langit warnanya abu-abu gelap. Kami semua pakai masker, tapi tetap saja sakit kepala dan batuk tak bisa dihindari," kenang Ari. Sumarto Taslim, warga Jakarta Timur.
Kebakaran yang bermula dari pembukaan lahan dengan cara dibakar---oleh korporasi maupun petani---berkembang menjadi bencana besar, diperparah oleh kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Pemerintah bergerak: membentuk satgas darurat, menggandeng dunia internasional, dan menindak sejumlah perusahaan pembakar lahan. Namun, langkah-langkah itu kerap dinilai lambat dan tak menyentuh akar masalah.
Dari tragedi ini lahir Badan Restorasi Gambut dan Mabgrive (BRGM)---sebuah upaya untuk menambal luka ekologis dan menata ulang tata kelola lahan. Tapi perjalanan memperbaiki ekosistem tak bisa instan. Butuh waktu panjang, komitmen nyata, dan keberanian politik yang tak mudah tergoyah.
Kini, satu dekade berlalu, ancaman karhutla belum sirna. Tahun 2025, Indonesia kembali bersiaga, sudah. mulai nampak di beberapa daerah di Riau.
Meskipun tren karhutla menurun secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, potensi bahaya tetap tinggi. Dua kali musim kemarau, suhu ekstrem yang terus meningkat, serta praktik pembakaran lahan yang belum benar-benar hilang, menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
"Jangan tunggu langit hitam dulu baru panik. Pencegahan harus dimulai dari regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi kepada petani serta korporasi," kata Ari. Sumarto Taslim.