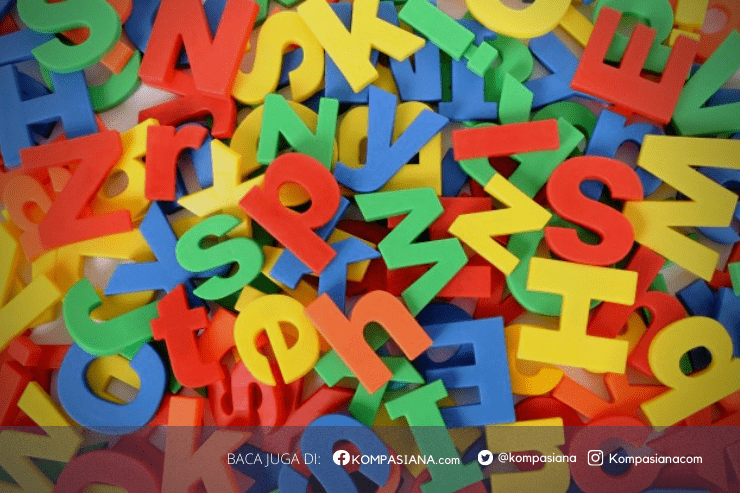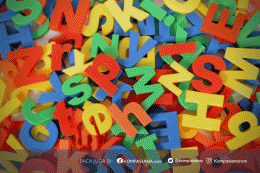Dalam logika ini, banyak keluarga di Aceh merasa lebih "modern" bila berbicara dengan anak-anak dalam bahasa Indonesia. Mereka percaya bahasa nasional menjanjikan masa depan, tetapi tanpa sadar merendahkan bahasa ibu sendiri. Perlahan, bahasa daerah kehilangan posisi tawar di pasar simbolik, hingga dipandang bukan sebagai aset, melainkan beban.
c. Perspektif Foucault: Kuasa dan Pengetahuan
Michel Foucault menegaskan bahwa hilangnya bahasa bukanlah proses alamiah, melainkan hasil dari operasi kuasa-pengetahuan. Institusi—sekolah, pemerintah, media—menentukan mana bahasa yang sah, mana yang bernilai, dan mana yang dipinggirkan.
Di Aceh, bahasa daerah kerap diposisikan sebagai tidak berguna atau kurang relevan dengan modernitas. Sekolah mengabaikannya dari kurikulum, pemerintah jarang memakainya dalam administrasi, sementara media lebih memilih bahasa nasional atau internasional. Dalam struktur kuasa semacam ini, bahasa lokal tidak diberi kesempatan hidup, melainkan secara perlahan didorong menuju invisibilitas.
Ketiga perspektif ini memperlihatkan bahwa bahasa jauh melampaui fungsi komunikatifnya. Ia adalah instrumen identitas, sumber daya sosial, sekaligus arena perebutan legitimasi. Kehilangannya bukan sekadar hilangnya kata, melainkan runtuhnya salah satu pilar kebudayaan. Dan bila pilar ini roboh, seluruh bangunan identitas masyarakat pun akan rapuh.
Realitas di Aceh: Antara Retorika dan Fakta
Aceh kerap digambarkan sebagai tanah yang teguh memegang jati diri. Identitas religius, sejarah perlawanan, hingga klaim sebagai Serambi Mekkah berulang kali digaungkan dalam pidato pejabat, promosi budaya, dan slogan resmi pemerintah. Namun, di balik retorika itu, wajah kebijakan bahasa di Aceh menunjukkan ketimpangan yang tajam.
Bahasa Aceh memang mendominasi ruang publik—dari percakapan sehari-hari di Banda Aceh hingga media lokal. Tetapi bahasa lain seperti Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Kluet, dan Tamiang hanya muncul sebagai pelengkap upacara, dekorasi seremoni, atau konten festival tahunan. Fungsinya dipersempit menjadi simbol tradisi, bukan alat ekspresi hidup. Akibatnya, komunitas linguistik non-dominan merasa bahasa mereka tidak benar-benar diakui dalam narasi kebudayaan Aceh kontemporer.
Kondisi ini semakin jelas terlihat di dunia pendidikan. Penelitian Mulyani et al. (2024) menunjukkan banyak guru sekolah dasar dan menengah memahami pentingnya bahasa daerah bagi penguatan daya nalar anak. Namun, kesadaran itu tidak pernah diikuti kebijakan struktural. Tidak ada pelatihan guru, tidak tersedia buku ajar, bahkan ruang dalam kurikulum pun absen. Bahasa daerah hanya tercatat secara formal dalam dokumen muatan lokal, tetapi tidak pernah benar-benar hidup di ruang kelas.
Situasi serupa tampak di ranah publik perkotaan. Studi lanskap bahasa di Peunayong (Sari et al., 2024) mencatat hanya 4% papan toko menggunakan bahasa Aceh, sementara mayoritas memakai bahasa Indonesia dan Inggris. Angka kecil ini bukan sekadar data, tetapi cermin dari pergeseran nilai. Bagi pelaku usaha, bahasa lokal dianggap tidak menjual, tidak modern, bahkan bisa membatasi pasar. Sebaliknya, bahasa nasional dan global dipandang sebagai lambang kemajuan.
Semua ini menunjukkan bahwa persoalan bahasa di Aceh bukan lagi soal pasar bebas atau pilihan praktis, melainkan persoalan legitimasi sosial dan politik. Bahasa daerah kehilangan wibawa dan nilai tawarnya, baik di mata institusi maupun masyarakat. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan anggapan bahwa bahasa ibu tidak relevan dengan masa depan. Inilah titik kritis: ketika bahasa tidak lagi dilihat sebagai modal hidup, ia hanya menunggu waktu untuk tergelincir menjadi artefak budaya—dihormati secara simbolik, tetapi ditinggalkan dalam praktik sehari-hari.
Pembelajaran Global: Bukti Revitalisasi Itu Mungkin
Situasi genting yang dialami bahasa daerah di Aceh tidak harus berakhir dengan kepunahan. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa bahasa yang nyaris hilang dapat kembali hidup ketika ada komitmen politik, dukungan institusi, dan keterlibatan komunitas. Berbagai contoh global menunjukkan bahwa revitalisasi bukan mimpi, melainkan hasil dari strategi yang tepat.