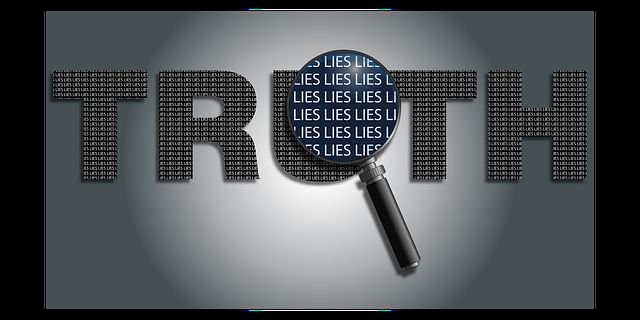Seringkali linimasa media sosial dihiasi dengan aneka #save ini atau #out itu. Bak jamur di musim hujan, atau mungkin lebih tepatnya saling adu slogan kerap dijumpai.
Motifnya bisa untuk mengajak semisal #saveKPK bisa juga bermakna menentang seperti yang dialami pelatih Timnas Garuda, usai kekalahan 0-3 dari Thailand. Beredar di media sosial #simonout!
Kukutip dari wikipedia.org. slogan adalah
motto atau frasa yang dipakai pada berbagai konteks (politik, agama atau komersial) sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Agar gampang diingat.
Kata slogan, berasal dari bahasa Gaelik yaitu sluagh-ghairm yang berarti "teriakan bertempur". Gegara baca ini, aku jadi ingat ujaran yang kerap dihadirkan saat pawai tujuhbelasan "Merdeka atau Mati!" atau "NKRI Harga Mati!".
Nah, masih menurut wikipedia, slogan itu bisa yang terlihat atau tertulis. Bisa juga berbentuk ucapan vulgar yang dipaparkan orator secara retoris. Karena tujuan hadirnya slogan adalah konsep retorika, upaya persuasif ide dan tujuan.
Satu contoh seperti saat pemilu, baik pilpres atau pileg kemarin. Rakyat nyaris kenyang dengan aneka retorika berbungkus slogan yang dilemparkan para Sloganers (orangnya, kubunyikan begitu), untuk kemudian pelan-pelan memuai di udara, atau malah menjadi biang yang menyulut kericuhan. Sehingga mulut, jari telunjuk plus jari jempol berlomba mencari tertuduh. Hiks...
.

Beberapa bacaan sejarah politik bangsa. Apalagi di era "Demokrasi Liberal" tahun 1950-an. Retorika politisi diukur berdasarkan ajuan bobot argumentasi saat di parlemen. Bukan dari wawancara yang menghasilkan polemik di masyarakat, atau paparan fakta-fakta pada sebuah talkshow! Eh, masa itu belum ada, ya? Haha..
Jadi, pertandingan argumen di parlemen lebih dominan pedagogis daripada demagogisnya. Sehingga produk yang dihasilkan tidak mengesankan sebagai transaksi elite partai, tapi pendidikan politik yang bermutu. Bukan pula berdasarkan banyaknya jumlah spanduk, banner atau apalah yang menghiasi pinggir-pinggir jalan.
Periode 1950-an itu, dianggap banyak pengamat politik Indonesia, sebagai satu masa ketika politik bekerja dalam kendali etika. Ada debat publik yang keras, bahkan berpolemik melalui surat kabar. Tetapi kehangatan sosial tetap terjaga.
Ada penghargaan terhadap kualitas kemanusiaan yang menjamin tidak terjadinya "pembunuhan karakter" akibat perselisihan politik.
Dalam kolomnya, Rocky Gerung (Tempo, 7 Agustus 2007) menyatakan. Politik pada saat ini, masih dilihat sebagai peralatan kekuasaan untuk jangka pendek. Bukan sebagai penerapan nilai-nilai demokrasi untuk peradaban jangka panjang. Ada yang sepakat? Kayaknya bakal debateble, ya?