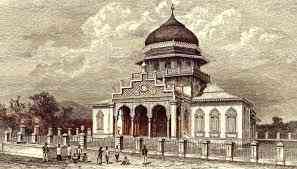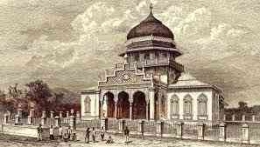Konteks Sejarah
Sebagai wilayah yang berakar kuat dalam tradisi Islam sejak beberapa abad yang lalu, Aceh memiliki silsilah yang panjang dan sejarah yang lebih jelas tentang penerapan hukum Islam dibandingkan dengan Muslim berpenduduk dominan lainnya di Nusantara. Dalam kasus hukum Islam dan adat di Aceh, banyak pemimpin
Aceh percaya bahwa keduanya saling melengkapi; bagian tak terpisahkan dari identitas budaya tunggal. Sebuah pepatah Aceh (hadih maja) yang sangat populer sering dikenang dalam berbagai acara formal (akademik) dan acara keagamaan informal:
"agama ngon adat han jeut cre, lagee zat ngon sifeut" (agama dan adat tidak dapat dipisahkan, keduanya seperti substansi). sesuatu dan atributnya). Sejumlah penulis Aceh berusaha mendamaikan kedua entitas
tersebut dan menyajikan contoh sintesis antara hukum adat dan hukum Islam dalam sistem sosial Aceh. Bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Kurdi, adat telah diislamkan dari waktu ke waktu melalui banyak cara sepanjang sejarah Aceh.
Sejak lama, pepatah populer tentang hubungan kompleks antara berbagai elemen dalam masyarakat Aceh masa lalu telah ditekankan oleh para pemimpin Aceh. Mengenai elit Aceh dalam sejarah pra-modern Aceh, setidaknya ada tiga kepemimpinan utama:
- Sultan di istananya di Kutaraja;
- Para uleebalang (bangsawan), yang merupakan penguasa yang memerintah sendiri dan menguasai sebagian besar perdagangan dan memungut pajak di otoritas masing-masing;
- Para ulama (pemuka agama/ulama), yang sebagian besar berbasis di dayah Islam (lembaga pembelajaran).
Sementara para ulama memimpin perjuangan melawan Belanda, para uleebalang ikut serta di pihak Belanda dalam pertempuran melawan para ulama.
(Re)integrasi Adat dan Agama
Upaya kuat untuk membawa (re)integrasi adat dan agama terjadi pada masa Orde Baru (1966-1998).Sebuah organisasi bernama Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) atau Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh didirikan pada tahun 1986. Di bawah kepemimpinan baru Badruzzaman Ismail pasca Orde Baru (1998-2002),
LAKA bertekad menjadi sarana penyatuan adat dan agama. Segera setelah runtuhnya rezim Orde Baru, berdasarkan UU 44/1999, Aceh diberikan otonomi khusus di tiga bidang: pendidikan, adat dan agama termasuk penguatan peran ulama dalam merumuskan kebijakan daerah.
Pada tahun 2002, LAKA berubah nama menjadi Majelis Adat Aceh (MAA) atau Majelis Adat Aceh. Tampaknya, Qanun baru ini dibuat untuk menyelaraskan hubungan antara MAA dengan lembaga adat yang baru lebih tinggi, yaitu wali nanggroe.
Meskipun kedudukannya khusus dan otonom dalam pemerintahan Aceh, lembaga MAA dan ketuanya (sesuai Pasal 9 dan 10 Qanun baru) kini berada di bawah arahan dan memiliki tanggung jawab untuk melapor kepada wali nanggroe. Alih-alih menghidupkan kembali institusi uleebalang yang menguasai dan memimpin formalitas adat, Qanun tampaknya telah menugaskan MAA sebagai penerus baru untuk menjalankan apa yang seharusnya diorganisir oleh uleebalang.
Memberdayakan Adat
Pemberdayaan Adat Menyusul berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, otonomi khusus Aceh atas agama dan juga adat diselesaikan. Pada tahun 2008, dua Qanun tentang adat disahkan; satu berurusan dengan pembinaan hidup dengan adat dan ritual adat (Qanun 9 tahun 2008)
dan yang lain berfokus pada lembaga adat (Qanun 10 tahun 2008). Qanun tersebut berusaha untuk memasukkan norma dan lembaga adat di Aceh untuk memainkan peran kunci dalam proses pemerintahan dan untuk memungkinkan pemangku kepentingan adat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan di Aceh pada umumnya dan dalam pelaksanaan hukum Islam pada khususnya.
Organisme Birokrasi
Organisme Birokrasi Dinamika sosial dan politik Aceh dalam dua dasawarsa terakhir mengungkapkan fakta menarik tentang bagaimana lembaga mediasi adat di Aceh akhirnya berubah menjadi lembaga adat itu sendiri. Menurut Qanun terkait adat, MAA diberi wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengatur delapan lembaga adat, yang sebagian besar berbasis dan beroperasi di tingkat desa.
Kedelapan lembaga itu antara lain: Tuha peut (Badan Permusyawaratan Desa dengan empat anggota), Tuha lapan (Badan Permusyawaratan Desa dengan delapan anggota), Keujruen blang (Sesepuh yang bertanggung jawab atas urusan persawahan), Panglima laot (Sesepuh yang peduli dengan masalah). perikanan dan bahari laut), Pawang glee (seorang tetua yang menjaga hutan dan lingkungan), Peutua seneubok (seorang tetua yang menjaga tanah dan pertanian), Haria peukan (seorang tetua yang mengelola pasar tradisional), dan Syahbanda (seorang tetua yang menguasai dermaga).
Selain kewenangan ini, MAA telah ditugaskan untuk bertanggung jawab untuk mempromosikan ritual adat dalam pernikahan serta proses rekonsiliasi; mendidik masyarakat tentang adat melalui sekolah, seminar dan lokakarya; penyebarluasan informasi adat melalui media cetak dan elektronik; dan menegakkan peradilan adat untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak dalam rangka pelaksanaan syariat Islam.
Dengan semua tugas tersebut, MAA melalui cabang-cabangnya baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan tidak hanya memfasilitasi revitalisasi adat dalam banyak hal, tetapi juga telah menstandarkan praktik adat seperti apa serta lembaga-lembaganya yang dapat diterima di Aceh.
Singkatnya, sebagai badan negara yang bertanggung jawab atas norma-norma adat dan lembaga-lembaganya, MAA telah berubah menjadi birokrasi hierarkis yang mengatur dan mengawasi semua hal yang berhubungan dengan adat di seluruh provinsi. Legislasi Qanun tentang adat, bagaimanapun, tidak serta merta diterjemahkan ke dalam penguatan MAA sebagai badan provinsi yang mengatur adat.
Mengingat kenyataan ini dan sejauh menyangkut posisi birokrasi DSI dan MAA, adalah sah untuk mengatakan bahwa adat memiliki peran yang kurang berpengaruh dibandingkan hukum Islam dalam kehidupan publik kontemporer Aceh. Meskipun posisi MAA vis a-vis DSI dirusak dalam sistem pemerintahan Aceh saat ini,
adat telah dibentuk kembali dan diubah menjadi bagian dari struktur negara. Akibatnya, seperti banyak lembaga formal negara lainnya, sangat mungkin bahwa sifat elastis adat akan beralih ke bentuk yang tidak fleksibel dan struktur yang kaku.
Kedaulatan Budaya
Kedaulatan Budaya Kewenangan MAA atas adat bahkan dipertanyakan mengingat fakta bahwa lembaga lain yang sangat dihormati secara politik, wali nanggroe, didirikan pada tahun 2013. Dianggap sebagai pelindung warisan Aceh baik di dalam maupun di luar provinsi, wali nanggroe telah menghilangkan peran dan status penting MAA.
MAA berada di bawah kekuasaan wali nanggroe dan hanya menjadi "majelis fungsional" di antara dewan-dewan lain yang ada dalam struktur tersebut. Pendirian lembaga wali nanggroe di Aceh mendapat kritik dari berbagai pihak. Kementerian mencantumkan 21 item yang termasuk dalam Qanun 8 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Wali Nanggroe yang harus diperjelas terutama dalam konteks kewenangannya yang tumpang tindih dengan kepemimpinan politik di tingkat provinsi.
Seorang anggota DPRD provinsi dari Partai Islam (PKS) mendesak pemerintah pusat untuk tidak mencurigai lembaga wali nanggroe, karena seperti banyak provinsi lain di Indonesia yang memiliki lembaga adat, wali nanggroe di Aceh juga merupakan lembaga yang terutama menyangkut adat. Masyarakat di Aceh masih mencari jalan terbaik untuk mempertemukan tugas dan fungsi masing-masing wali nanggroe dan MAA guna memperkuat posisi adat di Aceh.
Di sisi lain, MAA merupakan salah satu perangkat wali nanggroe dalam membina kehidupan adat di Aceh. Posisi ambivalen ini semakin parah karena otoritas wali nanggroe tidak secara aktif mengarahkan atau membimbing MAA ke arah mana harus berjalan. Lagi pula, lembaga wali nanggroe lebih suka menghadiri upacara yang hanya melibatkan pengunjung internasional atau investor asing yang masuk daripada berurusan dengan segala macam formalitas adat di tingkat lokal.
Hak atas Sumber Daya Alam
Hak atas Sumber Daya Alam Seperti yang terjadi di bagian lain Indonesia dan sebagai akibat dari reformasi hukum dan politik yang mengarah pada undang-undang desentralisasi dan otonomi khusus yang diberikan kepada sejumlah provinsi di Indonesia (khususnya Aceh), telah terjadi kebangkitan adat yang nyata.
Isu pengelolaan tanah khususnya yang menyangkut hak ulayat atau hak masyarakat menjadi topik kunci dan krusial dari berbagai perbedaan pendapat di antara berbagai pihak. Tuntutan warga desa akan hak untuk mengakses sumber daya alamnya sendiri mulai muncul setelah lama dibungkam pada masa Orde Baru (1966-1998).
Sebuah kasus di bawah ini menggambarkan bagaimana hak atas sumber daya alam telah digaungkan melalui peristiwa dan resolusi konflik di berbagai bagian Aceh. Kasus ini bermula ketika warga Desa Lhoknga di Kabupaten Aceh Besar menuntut untuk menggunakan norma adat tanah hak ulayat untuk mengklaim akses ke sumber daya alam desa.
Menurut adat Aceh, tanah semacam ini dikenal sebagai tanah mukim atau tanah kullah dan pemindahan hak atasnya tunduk pada kontrol masyarakat yang ketat.
Para pemimpin desa lokal Lhoknga memperdebatkan sebuah perusahaan semen internasional, Lafarge, (didirikan pada awal 1980-an) atas berbagai masalah termasuk pencemaran lingkungan dan hak-hak sosial ekonomi penduduk desa.
Mereka juga menuntut lebih banyak kompensasi termasuk membuat aturan yang memprioritaskan penduduk desa setempat dalam perencanaan perekrutan personel perusahaan dan membagi satu persen keuntungan tahunan perusahaan dengan penduduk desa.
Meskipun liputan berita tampaknya entah bagaimana mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, banyak yang curiga bahwa surat kabar lokal dan pemerintah provinsi berada di posisi yang sama dengan perusahaan.
Perselisihan itu akhirnya diselesaikan pada tahun 2009 ketika para pihak berhasil merundingkan kesepakatan tertulis bahwa sejumlah kompensasi harus dibayarkan setiap tahun kepada penduduk desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keberhasilan penyelesaian sengketa ini tak lepas dari bantuan seorang mediator informal, Anwar Ahmad, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Aceh Besar dan juga pernah menjadi staf kerja perusahaan tersebut.
Proses penyelesaian sengketa mungkin akan menemui jalan buntu jika Anwar Ahmad dalam berbagai peran resmi dan sosialnya tidak terlibat dalam membantu dan memfasilitasi semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama. Apakah penyelesaian sengketa ini akan tetap berkelanjutan sangat tergantung pada manfaat yang diterima oleh penduduk desa dari pembayaran kompensasi tahunan perusahaan.
Namun demikian, cara penyelesaian kasus ini sebagian besar melalui bantuan pemerintah kabupaten menegaskan fakta bahwa mekanisme adat tetap berada di bawah struktur formal negara, sehingga memperkuat klaim tentang status entitas adat yang relatif lemah dalam ruang publik kontemporer di Aceh.
Keadilan Adat
Sejauh menyangkut legitimasi peradilan adat atau penyelesaian hukum berbasis masyarakat, landasan sosial dan hukum yang kuat menopang keberadaannya di Aceh kontemporer. 10/2008 merupakan dasar yang paling mendasar dari pengakuan peradilan adat sebagai bagian dari sistem hukum formal di Aceh.46
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1) Qanun Aceh no.9/2008, peradilan adat ditegakkan oleh tiga lembaga lokal yaitu (1) gampong atau desa; 2) mukim atau satuan jumlah gampong; dan (3) panglima laot atau 'panglima laut' yang mengatur masalah maritim adat.
Dengan kata lain, meskipun para pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk memilih proses hukum sesuai keinginan mereka sendiri, sistem hukum Aceh lebih memilih penyelesaian sengketa secara adat. Selain itu, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 telah menjadi acuan resmi untuk menyelesaikan perselisihan keluarga Islam di pengadilan negara Islam di seluruh Indonesia49,
para pemimpin agama desa di Aceh masih mengandalkan pendapat hukum dari yurisprudensi tradisional Syafi`i serta hukum adat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum keluarga. Sebaliknya, hampir semua peraturan (qanun) Aceh mengatur bahwa ketika ada konflik antara adat dan hukum Islam, adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Perkara Khalwat
Tumpang tindihnya mekanisme hukum antara peradilan adat dan peradilan syariah dalam tindak pidana khalwat bersumber dari dua ketentuan yang saling bertentangan yang ditemukan dalam Qanun Jinaya no. Pasal 23 (1) Qanun ini menyatakan bahwa barang siapa yang terbukti melakukan tindak pidana khalwat, diancam dengan hukuman cambuk paling banyak sepuluh kali atau denda paling banyak seratus gram emas atau pidana penjara paling lama sepuluh bulan.
Meskipun demikian, Pasal 24 Qanun yang sama memberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk memeriksa suatu tindak pidana khalwat termasuk untuk menghukum pelakunya. Dikatakan "pelanggaran khalwat yang berada di bawah yurisdiksi peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Qanun (lain)
pedoman kehidupan adat dan/atau peraturan terkait lainnya tentang adat." Pertentangan kewenangan mengadili delik khalwat ini, bagaimanapun, dibantah oleh Azubaili dkk51 dengan alasan bahwa baik peradilan adat maupun peradilan syariah memiliki yurisdiksi masing-masing.
Qanun yang relevan tentang bagaimana peradilan adat berjalan dan menghukum pelanggar (khalwat) telah diundangkan sebelumnya, Sementara Pasal 13 (1)d Qanun ini mengatur bahwa pelanggaran khalwat berada di bawah yurisdiksi peradilan adat, Pasal 16 mengatur masing-masing hukuman yang dapat diterapkan kepada pelanggar khalwat termasuk:
"nasihat; sebuah peringatan; pernyataan permintaan maaf; kompensasi (sayam); tebusan (diyat); denda; restitusi; pengecualian oleh penduduk desa; penggusuran dari desa; penghapusan hak adat; dan bentuk hukuman lainnya menurut kebiasaan setempat." Kajian Yusrizal dan Amalia menegaskan bahwa para tetua desa di gampong
yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda mengadili dan menyelesaikan pelanggaran khalwat yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Apalagi sering terjadi kasus-kasus dimana putusan peradilan adat memaksa pasangan pelanggar khalwat untuk menikah putusan semacam ini tidak tercantum dalam Qanun tetapi sudah banyak dipraktikkan.
Semua ini mengisyaratkan bahwa di satu sisi pengadilan syariah akan menghukum pelanggar khalwat dengan jumlah cambukan tertentu, di sisi lain, peradilan adat yang dijalankan oleh tetua desa juga memeriksa pelanggaran khalwat di desanya masing-masing dengan menjatuhkan berbagai sanksi. selain cambuk)
kepada para pelanggarnya. Ditegaskan bahwa delik khalwat seringkali menjadi istilah yang begitu luas mencakup khalwat itu sendiri, ikhtilat bahkan zina (zina), dan ironisnya, banyak masyarakat di desa-desa Aceh yang tidak mau membedakannya ketika perbuatan semacam itu. pelanggaran terjadi, dan sebaliknya lebih suka semua jenis pelanggaran ini diselesaikan oleh tetua desa.
Barangkali, seperti yang dikemukakan oleh Mansur dkk, perlu dibuat klarifikasi dalam qanun dengan menetapkan sejauh mana pelanggaran khalwat merupakan bagian dari yurisdiksi peradilan adat dan jenis pelanggaran khalwat apa yang harus diselidiki oleh petugas. dari wilayatul hisbah yaitu
Pertama, peradilan adat telah menciptakan teka-teki di mana ia berusaha untuk menawarkan sanksi alternatif yang lebih fleksibel dan manusiawi terhadap hukum Islam, atau justru membuka jalan bagi hukuman adat yang diduga tidak benar dan keras yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya.
Meskipun para pemimpin desa telah diberi wewenang untuk menerapkan aturan-aturan ini di wilayah mereka, agak samar apakah mereka melakukannya secara mandiri dan independen dari pengadilan negara atau mekanisme tingkat desa semacam itu merupakan bagian instrumental dari administrasi hukum Islam Aceh pada umumnya.
Sementara norma dan lembaga adat secara hukum disahkan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat, pengakuan dan yurisdiksi mereka cukup terbatas karena fakta bahwa adat umumnya hanya berlaku untuk wilayah tertentu dan seringkali kurang memiliki kepastian hukum.
Sebaliknya, hukum Islam (lembaga dan peraturan) memiliki status yang lebih kuat dan jangkauan yang lebih luas di semua kabupaten di provinsi Aceh. Membuat adat adaptif terhadap perubahan dengan cara dibirokratisasi ternyata justru mengakibatkan terpinggirkannya adat itu sendiri.
Meskipun status resminya dalam peraturan Aceh saat ini, adat dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dari hukum Islam. Subordinasi adat terhadap hukum Islam di Aceh pasca-Orde Baru menjadi
lebih terlihat daripada klaim yang terus berlanjut tentang hubungan yang selaras antara adat dan hukum Islam di Aceh. Rupanya, sebuah adat otonom yang lepas dari penerapan syariat Islam bukanlah sesuatu yang diproyeksikan oleh banyak pemimpin Muslim di Aceh kontemporer.