Filsafat Hukum Episode 8: Positivisme Hukum
Bab I: Positivisme sebagai Arus Utama Filsafat Hukum
1.1. Apa itu Positivisme Hukum?
Positivisme hukum adalah salah satu aliran paling berpengaruh dalam filsafat hukum modern, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak ditentukan oleh kebaikan moral atau keadilan substansialnya, melainkan oleh sumber formal yang sah. Berbeda dengan teori hukum alam yang menautkan hukum dengan moralitas universal, positivisme berangkat dari asumsi metodologis bahwa hukum harus dipelajari sebagai sistem normatif yang otonom.
Tradisi ini berakar pada karya Jeremy Bentham dan John Austin di abad ke-19. Bentham menolak "metafisika hukum alam" dan menekankan kodifikasi hukum positif demi kepastian. Austin kemudian memformulasikan definisi hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat, didukung ancaman sanksi. Hukum, bagi Austin, adalah instrumen komando, bukan refleksi keadilan moral.
Pada abad ke-20, positivisme berkembang lebih kompleks. Hans Kelsen dengan Pure Theory of Law berusaha membangun ilmu hukum yang murni, bebas dari politik dan moralitas. Ia memperkenalkan konsep Grundnorm sebagai norma dasar yang menjadi fondasi validitas seluruh sistem hukum. H.L.A. Hart, filsuf hukum dari Oxford, melengkapi warisan ini dengan konsep "aturan pengakuan" (rule of recognition) yang menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat menentukan validitas hukum tanpa perlu merujuk pada nilai moral eksternal.
Positivisme hukum menekankan deskripsi, bukan preskripsi. Tujuannya adalah membedakan analisis hukum dari filsafat moral, politik, maupun teologi. Dengan cara itu, ia memungkinkan hukum dipahami secara ilmiah, konsisten, dan dapat diverifikasi. Kritik dari kalangan non-positivis sering menilai bahwa pemisahan ini terlalu kaku, tetapi kekuatan positivisme justru terletak pada kejelasan metodologisnya.
Secara historis, positivisme hukum tumbuh dalam konteks modernitas, ketika negara-bangsa membutuhkan kepastian hukum dan otoritas normatif yang terlembaga. Hingga kini, ia tetap menjadi paradigma dominan dalam fakultas hukum di seluruh dunia, terutama karena kegunaannya dalam praktik hukum sehari-hari.
1.2. Prinsip Inti: Pemisahan Hukum dan Moral (Separation Thesis)
Prinsip inti positivisme hukum adalah tesis pemisahan (separation thesis) antara hukum dan moralitas. Bagi para positivis, pertanyaan "apakah hukum berlaku?" berbeda dari "apakah hukum itu adil?". Validitas hukum ditentukan oleh kriteria formal dalam sistem hukum, bukan oleh isi moralnya.
Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah berdaulat yang ditaati, terlepas dari adil atau tidaknya. Kelsen mengembangkan argumen serupa dengan menyatakan bahwa ilmu hukum murni harus netral, tidak boleh bercampur dengan politik atau etika. Hart lebih moderat: ia mengakui bahwa moral sering memengaruhi isi hukum, tetapi menolak bahwa moralitas adalah syarat keberlakuan hukum.
Tesis ini berimplikasi praktis. Dalam dunia nyata, hakim, pengacara, dan birokrat sering dihadapkan pada aturan yang jelas tetapi tidak selalu adil. Dengan separation thesis, mereka dapat menjalankan hukum tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan perdebatan moral yang panjang. Namun, kritik menyebut bahwa hal ini berpotensi membiarkan hukum yang tidak adil tetap berfungsi, sebagaimana terjadi pada rezim totaliter abad ke-20.
Meski begitu, pemisahan hukum dan moralitas tetap menjadi pilar analisis hukum modern. Ia tidak serta merta menolak moralitas, tetapi berupaya menjaga otonomi ilmu hukum sebagai disiplin.
1.3. Positivisme vs Natural Law sebagai Perdebatan Klasik
Perdebatan antara positivisme dan hukum alam merupakan salah satu konflik filosofis tertua dalam sejarah hukum. Hukum alam, sejak Thomas Aquinas hingga Lon Fuller, menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip moral universal; hukum yang tidak adil pada dasarnya bukan hukum. Sebaliknya, positivisme menolak tautan niscaya tersebut.
Hart pernah berdebat dengan Fuller dalam Harvard Law Review (1958). Fuller menegaskan bahwa hukum totaliter, seperti di Nazi Jerman, gagal menjadi hukum karena mengabaikan prinsip moralitas internal hukum. Hart menanggapi bahwa hukum tersebut tetap "hukum", meskipun kejam, karena memenuhi kriteria validitas sistemiknya.
Kontras ini membentuk garis besar diskursus hukum modern: apakah hukum terutama bersifat normatif-moral atau formal-institusional.
1.4. Pengaruh Besar Positivisme di Abad 20
Positivisme hukum memberi pengaruh luar biasa pada perkembangan ilmu hukum abad ke-20:
- Pertama, ia memberikan dasar metodologis bagi kodifikasi hukum modern. Negara-negara pasca-Revolusi Industri, dengan birokrasi yang kompleks, memerlukan sistem hukum yang konsisten, dapat diprediksi, dan bebas dari debat moral tak berkesudahan.
- Kedua, positivisme memungkinkan hukum dipelajari secara ilmiah. Kelsen mendorong hukum dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, sementara Hart menjadikannya bagian dari filsafat analitik bahasa. Hal ini mengangkat status studi hukum sejajar dengan ilmu sosial dan filsafat analitik lainnya.
- Ketiga, pengaruh praktisnya tampak dalam pendidikan hukum. Fakultas hukum di Eropa, Amerika, hingga Asia banyak mengajarkan hukum dalam kerangka positivis: bagaimana mengenali aturan yang sah, cara kerjanya, dan bagaimana ia ditegakkan, ketimbang mencari dasar moral transendennya.
- Keempat, positivisme menjadi alat kritik terhadap hukum alam yang dianggap kabur, metafisik, dan rawan manipulasi ideologis. Dalam konteks politik, ia melayani kebutuhan negara modern untuk menegakkan hukum positif sebagai fondasi stabilitas sosial.
Namun, warisan ini tidak tanpa masalah. Kritik dari Mazhab Frankfurt, Critical Legal Studies, hingga teori feminis menunjukkan bahwa positivisme berisiko mengabaikan dimensi keadilan substantif. Meski demikian, kontribusinya dalam menata metodologi hukum tetap fundamental, menjadikan positivisme salah satu pilar utama filsafat hukum kontemporer.
Glosarium
Positivisme hukum: aliran filsafat hukum yang memisahkan validitas hukum dari moralitas.
Separation thesis: prinsip inti positivisme yang menyatakan hukum dan moralitas adalah domain analisis terpisah.
Grundnorm: norma dasar dalam teori Kelsen yang memberi validitas pada sistem hukum.
Rule of recognition: konsep Hart untuk menjelaskan kriteria validitas hukum dalam suatu masyarakat.
Natural law: teori hukum yang menautkan hukum dengan moralitas universal.
Daftar Pustaka
Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961.
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
Austin, John. The Province of Jurisprudence Determined. Cambridge: Cambridge University Press, 1832.
Fuller, Lon. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1964.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1789.
Rekomendasi Bacaan Pengayaan
1. Raz, Joseph. The Authority of Law. Oxford: Oxford University Press, 1979.
2. Coleman, Jules. The Practice of Principle. Oxford: Oxford University Press, 2001.
3. Shapiro, Scott. Legality. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
4. Finnis, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press, 1980.
5. Waldron, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: Oxford University Press, 1999.
*
Bab II: Positivisme Klasik
II.1. Konteks Sejarah dan Pemikiran: John Austin
John Austin adalah tokoh sentral dalam lahirnya positivisme hukum klasik di Inggris abad ke-19. Ia hidup pada masa transisi pasca-Revolusi Industri, ketika Inggris menghadapi perubahan sosial cepat, urbanisasi, dan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih teratur. Sebagai murid Jeremy Bentham, Austin terinspirasi oleh utilitarianisme tetapi berusaha membangun teori hukum yang lebih sistematis dan terpisah dari moralitas.
Karyanya yang paling berpengaruh, The Province of Jurisprudence Determined (1832), mendefinisikan hukum bukan sebagai refleksi moral, melainkan sebagai fenomena sosial yang dapat dipelajari secara ilmiah. Austin menekankan pemahaman hukum sebagai “perintah dari penguasa yang berdaulat”, didukung oleh sanksi. Dengan pendekatan ini, ia meletakkan dasar bagi positivisme hukum: analisis hukum berdasarkan sumber dan struktur formalnya, bukan pada nilai etis yang melandasinya.
II.2. Command Theory of Law: Hukum sebagai Perintah dari yang Berdaulat
Teori utama Austin, command theory of law, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya, yang keberlakuannya dijamin dengan ancaman sanksi. Tiga unsur utama menandai teori ini. Pertama, hukum selalu berasal dari otoritas tertinggi (sovereign), yaitu pihak yang ditaati secara konsisten oleh masyarakat, tetapi tidak tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Kedua, hukum berbentuk perintah (command), yaitu instruksi yang mewajibkan atau melarang tindakan tertentu. Ketiga, keberlakuan hukum dijamin dengan sanksi, sehingga kepatuhan masyarakat muncul karena ancaman hukuman, bukan kesadaran moral.
Dengan kerangka ini, Austin memisahkan hukum dari agama, moralitas, dan adat. Ia menolak gagasan bahwa hukum harus selaras dengan keadilan universal. Baginya, hukum berlaku karena berasal dari penguasa sah dan ditegakkan dengan kekuasaan koersif. Definisi ini memberikan kejelasan analitis dan menegaskan hukum sebagai produk politik dan otoritas negara.
II.3. Kritik Austin terhadap Hukum Alam
Austin menentang keras tradisi hukum alam yang, menurutnya, mencampurkan deskripsi hukum positif dengan klaim normatif moral. Ia berargumen bahwa teori hukum alam gagal membedakan antara “apa hukum itu” (is) dan “apa hukum seharusnya” (ought). Bagi Austin, kebingungan ini menghalangi hukum untuk dipelajari secara ilmiahMenurut Austin, hukum alam berbahaya karena memberi legitimasi pada pembangkangan hukum positif atas nama moralitas abstrak. Ia menilai hukum harus dipahami sebagai kenyataan sosial konkret, bukan ideal moral transenden. Baginya, yang penting adalah mendeskripsikan aturan yang benar-benar berlaku dalam suatu masyarakat, terlepas dari adil atau tidaknya.
Dengan memisahkan hukum dari moralitas, Austin berusaha melindungi studi hukum dari “metafisika” dan menegaskan posisinya sebagai disiplin empiris. Kritik ini menjadi salah satu fondasi pemikiran positivisme hukum, meskipun dikritik balik oleh para pendukung hukum alam modern seperti Lon Fuller dan John Finnis.
II.4. Kelebihan & Kelemahan Teori Austin
Teori Austin menawarkan sejumlah kelebihan sebagai berikut:
- Pertama, ia memberikan definisi hukum yang jelas dan operasional, membedakan antara hukum positif dengan moralitas atau adat. Hal ini memperkuat kepastian hukum, penting dalam masyarakat modern yang kompleks.
- Kedua, teorinya menekankan pentingnya kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Dengan menyoroti unsur sanksi, Austin menegaskan dimensi koersif hukum yang membedakannya dari norma sosial lainnya.
- Ketiga, command theory memberi kerangka awal bagi pengembangan positivisme hukum yang lebih matang oleh Kelsen dan Hart.
Namun, kelemahan teori Austin juga signifikan. Pertama, definisinya terlalu sempit: tidak semua hukum bersumber dari “perintah penguasa”. Banyak aturan hukum lahir dari kebiasaan atau praktik sosial, seperti common law di Inggris, yang sulit dijelaskan hanya sebagai perintah. Kedua, konsep kedaulatan absolut tidak sesuai dengan realitas politik modern yang mengenal pembagian kekuasaan, konstitusi, dan hukum internasional. Ketiga, Austin gagal menjelaskan hukum yang berlaku terhadap penguasa itu sendiri, padahal dalam negara konstitusional modern, penguasa juga tunduk pada hukum.
Selain itu, teori Austin mengabaikan aspek legitimasi dan keadilan. Dengan hanya menekankan asal-usul formal hukum, ia tidak mampu membedakan hukum yang sah dari hukum yang tiranik. Kritik ini semakin relevan setelah pengalaman rezim totaliter di abad ke-20. Dengan demikian, meskipun historis penting, teori Austin dianggap sebagai tahap awal positivisme hukum yang kemudian diperbaiki oleh generasi selanjutnya.
II.5. Bentham & Utilitarian Roots of Positivism
Jeremy Bentham (1748-1832), mentor intelektual Austin, merupakan tokoh penting dalam menyiapkan fondasi positivisme hukum. Bentham dikenal sebagai bapak utilitarianisme modern, dengan prinsip “the greatest happiness of the greatest number” sebagai dasar moralitas dan kebijakan publik.
Dalam hukum, Bentham mengkritik tradisi common law Inggris yang menurutnya penuh dengan fiksi, ketidakpastian, dan ketergantungan pada preseden. Ia menolak gagasan bahwa hukum dapat ditemukan dalam adat atau kebiasaan; bagi Bentham, hukum harus dikodifikasi oleh legislator dengan jelas dan sistematis. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah sarana meningkatkan kesejahteraan sosial.
Bentham juga menolak doktrin hukum alam, yang ia anggap sebagai “nonsense upon stilts” (omong kosong mengada-ada). Baginya, hak-hak hanya ada sejauh diberikan oleh hukum positif; hak alami tanpa dukungan hukum adalah ilusi. Pandangan ini kelak menginspirasi Austin untuk merumuskan hukum semata sebagai perintah penguasa.
Namun, berbeda dengan Austin yang fokus pada definisi formal hukum, Bentham tetap mempertahankan dimensi evaluatif melalui utilitarianisme. Ia menganggap legislasi harus dinilai berdasarkan kemampuannya memaksimalkan kebahagiaan sosial. Dalam arti ini, Bentham menggabungkan positivisme metodologis dengan orientasi moral-pragmatis.
Karya Bentham memberikan pengaruh besar pada tradisi hukum modern: dorongan kodifikasi, kejelasan aturan, dan sikap kritis terhadap fiksi hukum. Bersama Austin, ia menandai pergeseran besar dari hukum alam ke positivisme hukum modern.
II.6. Positivisme Awal vs Perkembangan Modern
Perbandingan antara positivisme klasik (Bentham, Austin) dan positivisme modern (Kelsen, Hart, Raz) menunjukkan transformasi penting dalam filsafat hukum.
- Sumber Hukum dan Kedaulatan; Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah penguasa berdaulat. Namun, dalam masyarakat modern dengan konstitusi, kedaulatan tidak lagi tunggal. Kelsen mengganti konsep “sovereign” dengan struktur hierarkis norma yang berpuncak pada Grundnorm. Hart kemudian memperkenalkan rule of recognition untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menentukan aturan hukum tanpa perlu figur penguasa absolut.
- Konsep Perintah dan Norma: Austin menekankan hukum sebagai perintah. Namun, banyak hukum modern tidak berbentuk perintah dengan sanksi (misalnya aturan kontrak, aturan yang memberi kewenangan administratif). Kelsen menekankan hukum sebagai sistem norma, bukan sekadar perintah. Hart mengkritik teori perintah karena tidak menjelaskan hukum yang memberi hak atau kewenangan, serta tidak menjelaskan hukum yang berlaku bagi penguasa itu sendiri.
- Hubungan dengan Moralitas: baik Austin maupun Bentham menolak hukum alam. Namun, Hart memperhalus sikap ini dengan mengakui adanya “minimum content of natural law”: hukum tetap membutuhkan aturan dasar untuk kelangsungan hidup masyarakat (seperti larangan kekerasan). Raz mengembangkan lebih lanjut, menekankan “otoritas hukum” sebagai alasan praktis untuk bertindak, yang tetap otonom dari moral, tetapi dapat berinteraksi dengannya.
- Tujuan Hukum: Bentham mengaitkan hukum dengan utilitarianisme: hukum baik jika meningkatkan kebahagiaan sosial. Austin lebih formalistik. Kelsen menekankan netralitas ilmiah, sementara Hart membuka ruang untuk dimensi sosial dan moral dalam analisis hukum. Dengan demikian, positivisme modern lebih fleksibel dalam menghadapi kompleksitas hukum kontemporer.
- Kritik dan Relevansi: Positivisme klasik dipuji karena kejelasan, tetapi dikritik karena simplistik. Positivisme modern memperbaiki kelemahan itu dengan konsep normatif yang lebih canggih. Meski dikritik oleh natural law, critical legal studies, feminisme, dan teori kritis lainnya, positivisme tetap dominan dalam pendidikan hukum karena kegunaannya yang praktis.
Dengan demikian, positivisme klasik adalah fondasi, sedangkan positivisme modern adalah elaborasi yang lebih kompleks. Evolusi ini menunjukkan kemampuan positivisme untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik, sosial, dan intelektual, tetap menjadi salah satu aliran utama filsafat hukum.
Glosarium
Command Theory: teori Austin yang menyatakan hukum sebagai perintah penguasa berdaulat disertai ancaman sanksi.
Sovereign: otoritas tertinggi yang ditaati masyarakat tanpa tunduk pada otoritas lain.
Utilitarianisme: prinsip moral Bentham bahwa tindakan terbaik adalah yang memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
Grundnorm: norma dasar dalam teori Kelsen yang memberi validitas sistem hukum.
Rule of Recognition: konsep Hart untuk menjelaskan kriteria validitas hukum dalam suatu masyarakat.
Daftar Pustaka
Austin, John. The Province of Jurisprudence Determined. Cambridge: Cambridge University Press, 1832.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1789.
Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961.
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
Raz, Joseph. The Authority of Law. Oxford: Oxford University Press, 1979.
Rekomendasi Bacaan Pengayaan
1. Cotterrell, Roger. The Politics of Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, 1989.
2. Shapiro, Scott. Legality. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
3. Lacey, Nicola. A Life of H.L.A. Hart. Oxford: Oxford University Press, 2004.
4. Finnis, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press, 1980.
5. Tamanaha, Brian. A General Jurisprudence of Law and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001.
*
Bab III: Hans Kelsen dan Pure Theory of Law
III.1. Konteks Intelektual Kelsen: Austria, Abad 20, Latar Belakang Neokantianisme
Hans Kelsen (1881-1973) lahir di Praha dan berkembang dalam tradisi intelektual Austria awal abad ke-20, sebuah periode penuh dinamika politik, sosial, dan filosofis. Kekaisaran Austro-Hungaria, tempat ia dibesarkan, menghadapi keruntuhan, konflik etnis, dan transformasi menuju negara-bangsa modern. Konteks ini memengaruhi cara Kelsen memahami hukum sebagai instrumen vital untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial.
Secara intelektual, Kelsen dipengaruhi oleh neokantianisme, khususnya mazhab Baden yang menekankan perbedaan antara ilmu alam (berbasis kausalitas) dan ilmu normatif (berbasis validitas). Dari filsafat Kant, ia menyerap ide tentang otonomi hukum sebagai sistem normatif yang tidak dapat direduksi ke fakta sosial atau moralitas.
Sebagai profesor hukum di Wina, Kelsen menjadi arsitek utama Konstitusi Austria 1920. Ia juga terlibat dalam lembaga internasional, termasuk Mahkamah Arbitrase Internasional. Dengan latar ini, Kelsen berupaya merumuskan teori hukum universal yang bebas dari ideologi politik, agama, atau kepentingan nasional. Teorinya, Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law), dimaksudkan sebagai jawaban ilmiah atas fragmentasi hukum dan politik pada zamannya.
III.2. Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law)
Kelsen memperkenalkan Pure Theory of Law sebagai usaha sistematis untuk memurnikan ilmu hukum dari campur tangan politik, etika, maupun sosiologi. Bagi Kelsen, ilmu hukum harus netral, otonom, dan fokus hanya pada “hukum sebagai hukum”. Ia menyebut pendekatannya “murni” karena menolak reduksi hukum ke dalam bentuk lain, seperti moralitas universal (hukum alam) atau fakta sosial (positivisme sosiologis).
Prinsip dasar teori ini adalah bahwa hukum merupakan sistem norma, bukan sekadar fakta atau perintah. Norma bersifat “sollen” (apa yang seharusnya) dan berbeda dengan kenyataan empiris (“sein”). Dengan demikian, ilmu hukum harus menganalisis struktur dan validitas norma, bukan isi moralnya.
Kelsen juga mengusulkan pemahaman hukum secara hierarkis. Setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada suatu norma dasar (Grundnorm) yang dipresuposisikan. Pendekatan ini menggabungkan ketelitian analitis dengan inspirasi neokantian: hukum sebagai konstruksi normatif yang otonom.
Teori ini memungkinkan analisis hukum yang universal. Misalnya, hukum pidana, perdata, maupun konstitusional dapat dipahami dalam kerangka sistem normatif yang sama. Selain itu, teori Kelsen memberi jalan bagi pemikiran hukum internasional sebagai sistem yang sah secara normatif, terlepas dari kedaulatan negara tertentu.
Dengan Pure Theory, Kelsen ingin membebaskan hukum dari “kontaminasi” ideologi. Menurutnya, hukum bukanlah soal keadilan absolut, melainkan soal validitas formal dalam sebuah sistem. Inilah yang membedakan Kelsen dari pendahulunya seperti Austin dan Bentham, sekaligus membuka jalan bagi teori hukum modern yang lebih abstrak dan normatif.
III.2.1. Pemisahan Hukum dari Politik, Moral, dan Sosiologi
Bagi Kelsen, hukum harus dipahami secara “murni”, artinya dilepaskan dari politik, moral, dan sosiologi. Politik hanya menjelaskan siapa yang membuat hukum, tetapi bukan hakikat hukum itu sendiri. Moralitas berhubungan dengan keadilan, tetapi keadilan adalah nilai relatif, bukan syarat validitas hukum. Sosiologi hukum berguna untuk menjelaskan perilaku masyarakat, tetapi tidak bisa menjelaskan keberlakuan normatif hukum.
Dengan pemisahan ini, Kelsen berusaha menjaga ilmu hukum sebagai disiplin otonom, bebas dari klaim ideologis. Misalnya, seorang hakim tidak boleh menilai undang-undang berdasarkan moralitas pribadi, melainkan berdasarkan kedudukannya dalam hierarki norma. Pemurnian ini menjadikan hukum dapat dipelajari secara ilmiah dan netral, sebuah cita-cita yang sejalan dengan semangat positivisme ilmiah abad ke-20.
III.2.2. Hukum sebagai Sistem Norma Hierarkis
Kelsen menolak pandangan Austin tentang hukum sebagai “perintah penguasa”. Baginya, hukum lebih tepat dipahami sebagai sistem norma yang tersusun hierarkis. Norma tingkat rendah memperoleh validitas dari norma tingkat lebih tinggi, membentuk struktur piramida.
Contohnya, sebuah peraturan menteri sah karena bersumber pada undang-undang. Undang-undang sah karena diturunkan dari konstitusi. Konstitusi sendiri sah karena berpangkal pada norma dasar (Grundnorm). Hierarki ini menciptakan keteraturan logis, sehingga hukum dapat dianalisis tanpa merujuk ke faktor eksternal.
Model hierarkis ini memungkinkan hukum dipahami sebagai sistem yang konsisten. Penyelesaian konflik norma pun dapat dilakukan dengan melihat posisi relatif dalam hierarki. Pemikiran ini sangat berpengaruh dalam pembentukan sistem hukum modern, khususnya di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut tradisi hukum tertulis.
III.2.3. Grundnorm (Norma Dasar)
Konsep paling terkenal dari Kelsen adalah Grundnorm. Ia mendefinisikannya sebagai norma dasar yang tidak diturunkan dari norma lain, melainkan dipresuposisikan agar seluruh sistem hukum memiliki validitas.
Misalnya, dalam sistem konstitusional, Grundnorm dapat dipahami sebagai “Konstitusi harus ditaati”. Konstitusi memperoleh validitas bukan karena norma lebih tinggi, tetapi karena masyarakat dan ilmuwan hukum mempresuposisikan norma dasar tersebut.
Kelsen menekankan bahwa Grundnorm bukanlah hukum positif dan bukan pula moral universal. Ia adalah konstruksi teoretis yang memungkinkan kita menjelaskan keberlakuan hukum positif. Tanpa Grundnorm, sistem hukum akan terputus dan kehilangan legitimasi formal.
Konsep ini sering dikritik sebagai “fiksi metafisik”, tetapi bagi Kelsen, ia adalah syarat logis agar hukum dapat dianalisis secara koheren. Dengan Grundnorm, kita bisa memahami bagaimana norma memperoleh validitas tanpa harus kembali ke penguasa absolut atau keadilan alamiah. Inilah sumbangan besar Kelsen terhadap teori hukum modern.
III.3. Hukum Internasional & Kelsen: Hukum Dunia sebagai Sistem Normatif
Kelsen bukan hanya teoretikus hukum nasional, tetapi juga salah satu arsitek intelektual hukum internasional. Ia berusaha membuktikan bahwa hukum internasional adalah sistem normatif yang sah, bukan sekadar perjanjian politik antarnegara.
- Pertama, ia menolak doktrin kedaulatan absolut. Menurut Kelsen, kedaulatan negara hanyalah konstruksi hukum, bukan fakta alamiah. Oleh karena itu, hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi, karena ia menetapkan norma dasar bagi negara. Dengan kata lain, validitas hukum nasional bergantung pada hukum internasional.
- Kedua, Kelsen melihat hukum internasional sebagai sistem hierarkis global. Norma-norma internasional (misalnya larangan perang agresif atau perlindungan hak asasi manusia) menjadi dasar sahnya aturan hukum nasional. Ini berarti hukum internasional bukan sekadar koordinasi, tetapi subordinasi normatif.
- Ketiga, Kelsen menekankan pentingnya lembaga internasional. Ia mendukung pembentukan Mahkamah Internasional dan bahkan membayangkan hukum dunia dengan otoritas global. Menurutnya, perdamaian dunia hanya bisa dicapai jika hukum internasional dipahami sebagai sistem hukum tertinggi, bukan sekadar kesepakatan politik.
Pemikiran ini sangat radikal di zamannya, ketika banyak negara masih menganggap hukum internasional sebagai “hukum lemah”. Namun, pasca Perang Dunia II dan lahirnya PBB, gagasan Kelsen menemukan relevansi. Prinsip supremasi hukum internasional, pengadilan internasional, dan perlindungan HAM global banyak terinspirasi oleh kerangka Kelsen.
Namun, teorinya juga menghadapi kritik. Banyak negara masih menolak subordinasi hukum nasional pada hukum internasional. Realitas politik menunjukkan bahwa kekuatan militer dan ekonomi sering lebih menentukan daripada norma hukum. Meski demikian, Kelsen tetap memberikan fondasi konseptual bagi hukum internasional modern, khususnya dalam lembaga seperti International Criminal Court (ICC).
III.4. Kritik terhadap Kelsen
III.4.1. Apakah Grundnorm itu Fiksi Metafisik?
Konsep Grundnorm sering dikritik sebagai fiksi metafisik yang justru bertentangan dengan ambisi Kelsen untuk membuat ilmu hukum “murni”. Para kritikus, seperti H.L.A. Hart, berargumen bahwa validitas hukum tidak membutuhkan norma dasar yang dipresuposisikan, tetapi cukup dijelaskan melalui praktik sosial pengakuan (rule of recognition). Dengan kata lain, Grundnorm dianggap abstraksi yang tidak perlu.
Bagi pendukung Kelsen, Grundnorm memang fiksi, tetapi fiksi yang berguna. Ia berfungsi sebagai postulat metodologis, bukan kenyataan empiris. Namun, kritik ini tetap melemahkan klaim “kemurnian” teori Kelsen.
III.4.2. Kesulitan Menjelaskan Dinamika Sosial Hukum
Kritik lain menyoroti ketidakmampuan teori Kelsen menjelaskan dinamika sosial. Dengan fokus pada validitas normatif, teori ini mengabaikan bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, termasuk faktor ekonomi, politik, dan budaya.
Misalnya, keberlakuan hukum sering dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, legitimasi politik, atau struktur kekuasaan. Semua ini sulit dijelaskan hanya dengan konsep normatif. Oleh karena itu, banyak sarjana menyebut teori Kelsen steril dan ahistoris.
III.5. Relevansi Kelsen Hari Ini: Hukum Konstitusi, ICC, Hukum Internasional
Meskipun dikritik, teori Kelsen tetap relevan dalam beberapa bidang hukum kontemporer.
- Hukum Konstitusi: pemikiran Kelsen tentang hierarki norma sangat berpengaruh dalam desain pengadilan konstitusi. Model Mahkamah Konstitusi Austria (1920), yang dirancang Kelsen, menjadi prototipe bagi banyak negara. Konsep supremasi konstitusi, judicial review, dan invaliditas norma yang bertentangan, semuanya berakar pada pemikiran Kelsen.
- Hukum Internasional: dalam era globalisasi, hukum internasional semakin penting. Gagasan Kelsen bahwa hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional menjadi relevan dalam kasus ICC, pengadilan HAM regional, maupun hukum perdagangan global. Meski tidak semua negara menerima supremasi ini, prinsip-prinsip dasar seperti jus cogens dan kewajiban erga omnes mendekati kerangka Kelsenian.
- ICC dan Pengadilan Global: Kelsen membayangkan pengadilan dunia untuk menjamin perdamaian. ICC, meski terbatas, mewujudkan sebagian visi ini. Pemikiran bahwa kejahatan seperti genosida dan kejahatan perang tunduk pada yurisdiksi global adalah realisasi praktis gagasan Kelsen tentang hukum internasional sebagai norma tertinggi.
- Relevansi Akademis: dalam pendidikan hukum, Pure Theory tetap menjadi rujukan penting untuk memahami sifat normatif hukum. Meskipun Hart, Dworkin, dan teori kritis menawarkan alternatif, Kelsen tetap dianggap tonggak utama positivisme normatif.
Dengan demikian, meskipun tidak sempurna, teori Kelsen masih membekali kita kerangka analisis yang berguna untuk menghadapi tantangan hukum konstitusi, internasional, dan globalisasi.
Glosarium
Pure Theory of Law: teori Kelsen yang memurnikan hukum dari politik, moral, dan sosiologi.
Grundnorm: norma dasar yang dipresuposisikan sebagai sumber validitas sistem hukum.
Norma Hierarkis: struktur hukum yang tersusun dari tingkat rendah ke tinggi.
Neokantianisme: aliran filsafat yang memengaruhi Kelsen, menekankan otonomi ilmu normatif.
ICC: International Criminal Court, pengadilan pidana internasional permanen.
Daftar Pustaka
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961.
Raz, Joseph. The Authority of Law. Oxford: Oxford University Press, 1979.
Stone, Julius. The Province and Function of Law. Sydney: Law Book Co., 1946.
Rekomendasi Bacaan Pengayaan
1. Paulson, Stanley. Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of Kelsen’s Reine Rechtslehre. Oxford: Clarendon, 1992.
2. Bix, Brian. Jurisprudence: Theory and Context. London: Sweet & Maxwell, 2012.
3. Loughlin, Martin. Foundations of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2010.
4. d’Aspremont, Jean. International Law as a Belief System. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
5. Pattaro, Enrico (ed.). A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Dordrecht: Springer, 2005
*.
Bab IV: H.L.A. Hart dan The Concept of Law
IV.1. Lahir, Pendidikan, dan Konteks: Oxford, Filsafat Analitik, Pasca-Perang Dunia II
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) merupakan salah satu filsuf hukum paling berpengaruh dalam abad ke-20. Ia lahir di Inggris dan menempuh pendidikan di New College, Oxford, dengan fokus pada Klasik dan Filsafat. Setelah itu, ia menjadi pengacara (barrister) sebelum bergabung dengan dinas intelijen Inggris (MI5) selama Perang Dunia II. Pengalaman ini memperdalam wawasannya tentang pentingnya aturan, ketaatan, serta legitimasi hukum dalam menjaga stabilitas sosial.
Setelah perang, Hart kembali ke Oxford dan mengabdikan diri di bidang filsafat hukum. Ia dipengaruhi oleh tradisi filsafat analitik, khususnya karya-karya Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin, dan filsuf bahasa biasa lainnya. Tradisi ini menekankan klarifikasi konsep melalui analisis bahasa dan praktik sosial, sebuah pendekatan yang sangat membedakan Hart dari pendahulunya seperti John Austin maupun Hans Kelsen.
Pada tahun 1952, Hart diangkat menjadi Professor of Jurisprudence di Oxford, menggantikan Arthur Goodhart. Ia kemudian menerbitkan karya monumentalnya, The Concept of Law (1961), yang dianggap sebagai tonggak utama positivisme hukum modern. Buku ini tidak hanya merevisi kelemahan teori perintah (command theory) John Austin, tetapi juga mengembangkan kerangka konseptual baru yang menjelaskan fungsi hukum dalam masyarakat dengan lebih realistis.
Konteks pasca-Perang Dunia II sangat memengaruhi Hart: dunia menghadapi trauma totalitarianisme, pengadilan Nuremberg, dan munculnya perdebatan baru tentang hukum dan moralitas. Dalam atmosfer intelektual ini, Hart menawarkan pendekatan analitis yang menekankan kejelasan, diferensiasi konseptual, dan perhatian pada praktik hukum yang nyata.
IV.2. The Concept of Law (1961)
IV.2.1. Arti The Concept of Law
The Concept of Law pertama kali diterbitkan oleh Clarendon Press, Oxford, pada tahun 1961. Buku ini segera menjadi karya klasik dalam filsafat hukum dan hingga kini masih digunakan secara luas di universitas-universitas top dunia. Hart menulisnya sebagai jawaban terhadap kebingungan konseptual dalam teori hukum modern, terutama kelemahan teori perintah John Austin serta abstraksi normatif Hans Kelsen.
Dalam buku ini, Hart menekankan bahwa hukum tidak bisa direduksi sekadar pada “perintah berdaulat” atau “sistem norma murni”. Sebaliknya, hukum harus dipahami melalui kombinasi aturan sosial yang kompleks, yang terdiri atas aturan kewajiban (primary rules) dan aturan tentang aturan (secondary rules). Melalui kerangka ini, Hart berhasil menjelaskan bagaimana hukum dapat berfungsi secara stabil dalam masyarakat, sekaligus bagaimana ia dapat berubah dan ditegakkan.
The Concept of Law juga memperkenalkan gagasan sentral seperti rule of recognition, sebuah mekanisme sosial yang menentukan apa yang diakui sebagai hukum yang sah. Dengan pendekatan analitis dan perhatian pada praktik sosial, Hart membangun fondasi bagi positivisme hukum modern.
IV.2.2. Kritik terhadap Austin (Kelemahan “Command Theory”)
Hart secara sistematis mengkritik John Austin dan teori hukumnya yang dikenal sebagai command theory. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, yang didukung oleh ancaman sanksi. Hart berpendapat bahwa teori ini gagal menangkap kompleksitas hukum modern.
Pertama, tidak semua hukum berbentuk perintah. Misalnya, hukum kontrak atau hukum pernikahan tidak bersifat memerintah, melainkan memberikan fasilitas bagi individu untuk menciptakan hak dan kewajiban baru. Jika hukum hanya dipahami sebagai perintah, maka sifat kreatif dan permisif hukum akan terabaikan.
Kedua, Austin menekankan bahwa hukum berasal dari penguasa berdaulat yang tidak tunduk pada aturan. Hart menunjukkan bahwa dalam sistem hukum modern, bahkan penguasa pun tunduk pada konstitusi. Konsep “kedaulatan” dalam teori Austin terlalu sederhana untuk menjelaskan struktur negara hukum kontemporer.
Ketiga, ancaman sanksi tidak cukup untuk menjelaskan kepatuhan hukum. Banyak orang menaati hukum bukan karena takut dihukum, tetapi karena menganggap hukum sebagai aturan sosial yang sah. Hukum bekerja melalui rasa legitimasi, bukan hanya rasa takut.
Dengan demikian, Hart menolak reduksi hukum ke dalam perintah berdaulat. Ia menggantinya dengan konsep hukum sebagai sistem aturan yang lebih luas, mencakup aturan kewajiban (primary rules) dan aturan sekunder (secondary rules). Kritik ini menandai pergeseran penting dalam positivisme hukum, dari model komando menuju model aturan.
IV.2.3. Primary Rules (Aturan Kewajiban) & Secondary Rules (Aturan tentang Aturan)
Kontribusi terbesar Hart dalam The Concept of Law adalah distingsinya antara primary rules dan secondary rules.
Primary rules adalah aturan yang mengatur kewajiban langsung bagi anggota masyarakat. Misalnya, larangan membunuh, kewajiban membayar pajak, atau kewajiban menjaga kontrak. Primary rules penting karena memberikan kerangka perilaku dasar yang memungkinkan kehidupan sosial berjalan tertib. Namun, sistem yang hanya berisi primary rules cenderung primitif dan tidak fleksibel: ia kesulitan menghadapi perubahan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa.
Untuk menjawab kelemahan ini, Hart memperkenalkan secondary rules, yaitu aturan yang mengatur bagaimana primary rules dibuat, diubah, atau ditegakkan. Secondary rules terdiri dari tiga jenis utama: rule of recognition, rule of change, dan rule of adjudication.
Dengan adanya secondary rules, sistem hukum dapat menjadi lebih kompleks dan stabil. Ia dapat menentukan apa yang sah sebagai hukum, bagaimana hukum baru diciptakan, dan bagaimana sengketa hukum diselesaikan.
Distingsi primary-secondary rules memungkinkan Hart menjelaskan perbedaan antara masyarakat primitif (yang hanya memiliki aturan kebiasaan) dan masyarakat modern (yang memiliki struktur hukum formal). Tanpa secondary rules, hukum akan kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial.
Kerangka ini menunjukkan kejeniusan Hart dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial yang bersifat institusional, bukan sekadar perintah atau norma abstrak.
IV.2.4. Rule of Recognition, Rule of Change, Rule of Adjudication
Dalam kerangka Hart, secondary rules terbagi ke dalam tiga kategori:
- Rule of Recognition: merupakan aturan fundamental yang menentukan apa yang dianggap sebagai hukum sah dalam suatu sistem. Misalnya, dalam sistem hukum modern, rule of recognition biasanya menunjuk pada konstitusi, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, dan putusan pengadilan. Ia adalah dasar legitimasi seluruh hukum positif.
- Rule of Change: adalah aturan yang memungkinkan hukum diperbarui atau diubah. Dengan adanya rule of change, hukum tidak statis, melainkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah prosedur legislatif yang memungkinkan parlemen membuat undang-undang baru atau mencabut yang lama.
- Rule of Adjudication: adalah aturan yang memberi kewenangan pada lembaga tertentu untuk menafsirkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Pengadilan berfungsi berdasarkan rule of adjudication, memastikan bahwa hukum ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten.
Ketiga jenis secondary rules ini membuat sistem hukum menjadi kompleks dan fungsional. Tanpa rule of recognition, hukum akan kehilangan dasar otoritasnya. Tanpa rule of change, hukum akan kaku dan tidak relevan. Tanpa rule of adjudication, hukum akan kehilangan daya operasional dalam praktik.
Hart menekankan bahwa kombinasi primary dan secondary rules adalah karakteristik utama hukum modern. Inilah yang membedakan sistem hukum modern dari masyarakat primitif yang hanya mengandalkan kebiasaan. Dengan analisis ini, Hart berhasil menyajikan kerangka konseptual yang menjelaskan sifat hukum secara lebih komprehensif daripada teori hukum sebelumnya.
IV.3. Hukum & Moral: Minimum Content of Natural Law
Salah satu aspek paling penting dari teori Hart adalah refleksinya tentang hubungan antara hukum dan moral. Sebagai seorang positivis hukum, Hart tetap mempertahankan tesis utama bahwa hukum dan moral adalah konsep yang berbeda secara analitis-artinya, keberlakuan suatu hukum tidak tergantung pada validitas moralnya. Namun, Hart tidak jatuh pada positivisme ekstrem yang sepenuhnya mengabaikan moral. Dalam The Concept of Law (1961), ia memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai “minimum content of natural law” atau “isi minimum hukum alam.”
IV.3.1. Pemisahan Hukum dan Moral: Separation Thesis
Hart membedakan dengan tegas antara law as it is (hukum sebagaimana adanya) dan law as it ought to be (hukum sebagaimana seharusnya). Ia mengkritik tradisi hukum alam yang beranggapan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Bagi Hart, hukum yang tidak adil tetaplah hukum, sejauh ia memenuhi kriteria validitas sistem hukum yang berlaku. Misalnya, undang-undang diskriminatif atau tirani tetap sah secara hukum, meskipun secara moral dipersoalkan.
Namun, Hart menolak pandangan absolut bahwa hukum sepenuhnya terlepas dari moralitas. Menurutnya, ada keterkaitan tak terelakkan antara hukum dan moral, terutama karena hukum harus berfungsi dalam masyarakat manusia yang memiliki kebutuhan tertentu.
IV.3.2. Minimum Content of Natural Law
Hart memperkenalkan ide “minimum content of natural law” sebagai jembatan antara positivisme dan realitas moral. Ia berpendapat bahwa ada kondisi faktual universal dalam kehidupan manusia yang memaksa hukum untuk memiliki isi moral minimum. Jika hukum sepenuhnya mengabaikan kondisi-kondisi ini, ia tidak akan berfungsi sebagai hukum.
Hart menyebut lima kondisi utama:
- Kerentanan manusia: manusia pada dasarnya rentan secara fisik. Karena itu, hukum harus melindungi mereka dari kekerasan, pembunuhan, dan ancaman fisik. Tanpa perlindungan ini, masyarakat tidak dapat bertahan.
- Kesamaan relatif: walaupun ada variasi kemampuan, manusia relatif setara dalam kekuatan fisik dan kecerdasan. Tidak ada kelompok yang bisa mendominasi sepenuhnya tanpa batas. Karena itu, hukum harus mengatur interaksi agar konflik tidak merusak kohesi sosial.
- Altruisme terbatas: manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, hukum harus membatasi egoisme individu dan mendorong aturan yang memungkinkan kerja sama.
- Keterbatasan sumber daya: dunia tidak menyediakan segala sesuatu dalam kelimpahan. Karena sumber daya terbatas, hukum harus mengatur distribusi dan kepemilikan agar kehidupan sosial tidak jatuh ke dalam anarki.
- Keterbatasan daya dan pengertian manusia: manusia tidak serba tahu dan serba bisa. Oleh karena itu, hukum harus menetapkan aturan yang jelas dan dapat dipahami agar orang dapat menyesuaikan perilaku mereka.
Kelima kondisi ini menunjukkan bahwa ada isi minimum moral dalam setiap sistem hukum, sekalipun sistem itu sangat berbeda secara budaya. Tanpa perlindungan dasar terhadap kehidupan, keadilan, dan kerja sama, hukum tidak mungkin bertahan. Dengan kata lain, meskipun Hart seorang positivis, ia mengakui dimensi “hukum alam” dalam arti empiris-pragmatis.
IV.3.3. Hart vs Natural Law Tradisi
Hart berbeda dari pemikir hukum alam klasik seperti Thomas Aquinas atau John Finnis. Bagi tradisi hukum alam, hukum yang tidak adil tidak memiliki kekuatan hukum sejati (lex iniusta non est lex). Hart menolak klaim ini. Menurutnya, hukum yang tidak adil tetap sah, tetapi mungkin kehilangan otoritas moral.
Namun, dengan “minimum content of natural law”, Hart menunjukkan bahwa ada titik temu antara positivisme dan hukum alam: keduanya sama-sama mengakui perlunya dimensi moral minimum agar hukum dapat berfungsi. Bedanya, bagi Hart, moralitas minimum itu bersumber dari fakta empiris tentang kondisi manusia, bukan dari prinsip metafisik atau teologis.
IV.3.4. Relevansi Kontemporer
Konsep ini sangat relevan dalam perdebatan modern. Misalnya, dalam isu hak asasi manusia, Hart memberikan argumen mengapa perlindungan minimum seperti hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan harus dijamin dalam setiap sistem hukum. Ia juga menjelaskan mengapa sistem hukum totaliter pada akhirnya tidak stabil: karena mengabaikan kebutuhan dasar manusia, hukum kehilangan legitimasi sosialnya.
Dalam konteks global, “minimum content of natural law” juga dapat diaplikasikan pada hukum humaniter internasional. Perlindungan terhadap warga sipil, larangan genosida, dan keharusan untuk memperlakukan manusia secara bermartabat dapat dilihat sebagai ekspresi dari isi minimum hukum alam menurut Hart.
IV.3.5. Kesimpulan
Dengan konsep “minimum content of natural law”, Hart berhasil menegaskan bahwa positivisme hukum tidak identik dengan nihilisme moral. Ia tetap memisahkan hukum dan moral secara analitis, tetapi mengakui bahwa hukum, agar berfungsi, harus mencerminkan kebutuhan dasar manusia. Inilah yang menjadikan Hart bukan hanya sebagai pewaris positivisme, tetapi juga sebagai jembatan antara tradisi hukum alam dan filsafat hukum modern.
*
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

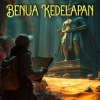
![[Novel] Musamus Tubuh Kecil Jiwa Besar, Episode 63-64](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/16/cover-novel-musamus-01-jpeg-tayang-68c956e1ed641509283d4682.jpeg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
![[publicspeaking] Dari Gagasan Ke Tonjok, Saat Pejabat Lebih Suka Tantangan Fisik daripada Logika](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/06/0293f24c-094a-47c4-9163-7dbfe3f74f22-68bc1999ed641579ee6f8832.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)



