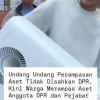Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional. Momen ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan perjuangan panjang para pekerja demi keadilan dan martabat di tempat kerja. Sejarah mencatat bahwa Hari Buruh lahir dari aksi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1886 di Haymarket, Chicago, Amerika Serikat, saat para buruh menuntut penerapan jam kerja delapan jam sehari. Aksi itu berujung pada kekerasan, korban jiwa, dan penindasan, namun juga menjadi titik tolak bangkitnya gerakan buruh global.
Kini, lebih dari satu abad kemudian, buruh tak lagi menghadapi cambuk dan pabrik berasap, tetapi berhadapan dengan ketidakpastian kerja, fleksibilitas semu, dan teknologi yang mengubah wajah pasar tenaga kerja secara radikal.
Ketika Laba Jangka Pendek Menjadi Segalanya
Pasca krisis ekonomi 1998, banyak perusahaan di Indonesia dan dunia mengadopsi paradigma bottom line, yakni mengejar keuntungan bersih jangka pendek sebagai tolak ukur utama keberhasilan. Dalam logika ini, efisiensi biaya menjadi mantra utama---dan sayangnya, manusia sering menjadi korban pertamanya.
Bekerja bukan lagi soal membangun karier, melainkan sekadar menjadi bagian dari sistem yang sewaktu-waktu bisa diputus. Pekerja tetap dipandang sebagai beban, sementara sistem outsourcing dan kerja kontrak jangka pendek dianggap lebih efisien dan fleksibel.
Muncullah idiom-idiom baru yang mencerminkan degradasi nilai kemanusiaan dalam dunia kerja:
- “Pecat pegawai anda begitu tidak dibutuhkan lagi, karena mereka selalu bisa disewa lagi nanti saat diperlukan.”
- “Biarkan satu pekerja anda pergi, karena masih ada seribu lamaran dengan gaji yang lebih rendah akan datang menggantikan.”
Ungkapan-ungkapan ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga mencerminkan perubahan budaya yang mengikis martabat pekerja. Manusia dikomodifikasi, direduksi menjadi alat produksi, bukan lagi subjek utama dari tujuan organisasi.
Konsekuensi Dehumanisasi di Tempat Kerja
Strategi efisiensi semu ini bisa jadi menguntungkan dalam jangka pendek, namun akan menjadi bumerang dalam jangka panjang. Perusahaan yang tidak membangun loyalitas, justru akan menghadapi biaya tinggi akibat employee turnover, kehilangan pengetahuan organisasi, penurunan moral kerja, dan retaknya budaya korporat.
Paradoksnya, upaya "menghemat" dengan mengabaikan manusia justru menimbulkan hidden cost yang jauh lebih besar: rendahnya produktivitas, lemahnya inovasi, dan rapuhnya organisasi menghadapi krisis.
Manusia Adalah Aset Strategis, Bukan Beban