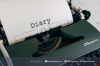Beberapa rumah di pinggir jalan kampung pun tetap dibangun dengan konsep rumah panggung, meskipun tidak begitu tinggi, karena kolong rumah berupa rawa atau lumpur basah (sering terendam air pasang), tempat hidup ketam dan ikan cempakul (tempakul- oxudercidae/ oxudercinae).
Dalam bahasa Inggris, cempakul dikenal sebagai mudskipper karena kebiasaannya melompat-lompat di lumpur saat air surut. Cempakul memiliki bentuk unik dan mampu hidup di dua alam (amfibi). Cempakul suka bersembunyi ke dalam lumpur dengan membuat semacam leng.
Ketam membuat sarang berbentuk gunungan tanah. Semakin banyak ketam di bawah rumah, semakin banyak pula gunungan tanah. Jika ketam tengah berkeliaran dan dikejutkan oleh kedatangan binatang lain maupun manusia, maka mereka segera berlari terbirit-birit masuk ke sarang melalui lubang di puncak "gunung".
Anak-anak sering menangkap ketam dengan menggunakan lidi yang ujungnya dibuat kolongan (lingkaran) dan di masukan ke kaki atau sapit ketam.
Memanfaatkan Air Tadah Hujan
Hidup di wilayah pasang surut, menyebabkan masyarakat Kuala Tungkal tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengandalkan air hujan untuk memasak, mencuci, dan mandi. Air hujan ditampung dalam drum dan ember berbagai ukuran.
Dulu kami memiliki empat drum berukuran besar dan beberapa drum berukuran sedang. Drum-drum itu dipesan dari pembuat drum, tersebar di beberapa tempat. Satu dua drum memiliki tutup, meminimalisir hidup dan berkembangnya jentik-jentik. Air di drum bertutup dimanfanfaatkan untuk minum dan memasak.
Jadi bukanlah hal yang aneh jika kebanyakan atap rumah di Kuala Tungkal pada tahun 1970-an dikelilingi talang demi bisa mengumpulkan air yang diarahkan ke drum. Saat itu belum ada PDAM Tirta Pangabuan (beroperasi dua puluh tahun kemudian, tahun 1990-an) dan tidak mungkin membuat sumur tanah.
Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan air bersih sering menjadi persoalan pelik. Meski berada dekat dengan laut, terdapat banyak sungai, masyarakat justru kesulitan memperoleh air agar dapat memenuhi keperluan sehari-hari.
Hal itu disebabkan kualitas air di kawasan pasang surut cenderung dipengaruhi kadar garam (asin), tingkat keasaman cukup tinggi, hingga pencemaran alami.
Wilayah pasang surut seringkali terjebak dalam sebuah paradoks. Air tampak melimpah ruah, tetapi tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Air sungai bercampur dengan air laut, rasanya cenderung asin atau payau. Sementara itu, air rawa berwarna hitam pekat, berbau, mengandung zat besi tinggi.
Dalam kondisi seperti itu, air hujan menjadi harta berharga, merupakan nadi utama dalam menopang aktivitas kehidupan dan keberlanjutan ekosistem.