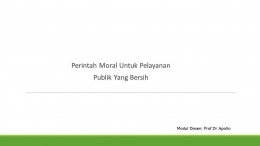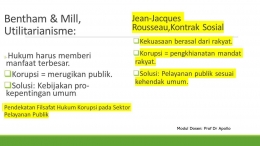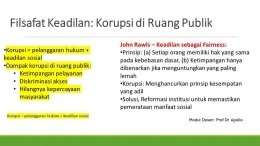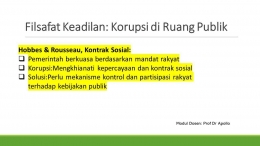Sementara dalam aspek aksiologi, pelayanan publik memiliki tujuan utama yaitu kebaikan bersama (bonum commune). Konsep ini berasal dari tradisi filsafat politik klasik, khususnya Aristoteles dan Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa kehidupan bernegara seharusnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan keuntungan kelompok tertentu. Oleh karena itu, ketika pelayanan publik tercemar oleh korupsi, maka tujuan tersebut menjadi terdistorsi, dan negara kehilangan arah moralnya.
Pelayanan Publik sebagai Praktik Moral
Pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi juga merupakan praktik moral yang menuntut pertanggungjawaban etis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dihadapkan pada dilema moral: apakah mengikuti prosedur yang bisa dimanipulasi demi kepentingan pribadi, atau mempertahankan integritas dengan risiko tekanan dari atasan atau sistem? Di sinilah pentingnya pendekatan etika dalam pelayanan publik.
Etika publik mengajarkan bahwa pelayanan publik yang sejati adalah tindakan yang menghormati nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Seorang pegawai publik bukan hanya pelaksana teknis kebijakan, melainkan juga agen moral yang bertugas menjaga integritas sistem dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Lebih jauh, pendekatan moral menempatkan pelayanan publik sebagai arena aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, pelayanan yang baik bukan hanya tentang memenuhi target kinerja, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan warga negara dengan adil dan manusiawi. Dalam konteks ini, praktik pelayanan publik adalah bentuk nyata dari moralitas publik.
Filsafat Demokrasi dan Hubungannya dengan Pelayanan Publik
Dalam filsafat politik demokrasi, pelayanan publik merupakan bentuk aktualisasi kehendak rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan yang sah dalam sistem demokrasi, dan pemerintah hanyalah pelaksana dari mandat tersebut. Oleh karena itu, pelayanan publik harus mencerminkan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan.
Pelayanan yang korup adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Ketika seorang pejabat publik melakukan korupsi, ia bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencederai amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini menimbulkan efek domino berupa menurunnya partisipasi warga dalam kehidupan politik, menguatnya sinisme publik terhadap institusi negara, dan tumbuhnya apatisme yang berujung pada melemahnya demokrasi itu sendiri.
Konsep ini dikuatkan oleh pemikiran Rousseau yang menyatakan bahwa kontrak sosial antara rakyat dan penguasa harus didasarkan pada kehendak umum (volont gnrale). Ketika kehendak umum itu dikhianati melalui tindakan korupsi, maka legitimasi kekuasaan menjadi gugur. Oleh karena itu, pelayanan publik yang bersih dan berintegritas bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga keharusan filosofis dalam sistem politik demokratis.
Dimensi Filsafat dalam Menilai Praktik Korupsi
Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana korupsi merusak tatanan pelayanan publik, kita perlu mengintegrasikan berbagai dimensi filsafat:
- Dimensi ontologis. Korupsi menyalahi hakikat keberadaan negara sebagai pelayan rakyat.
- Dimensi epistemologis. Korupsi menyimpangkan pemahaman kita tentang fungsi pelayanan publik---dari melayani menjadi menguasai.
- Dimensi aksiologis. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang seharusnya mendasari pelayanan, seperti keadilan, kesejahteraan bersama, dan kesetaraan.