Lapago adalah tanah honai, rumah bundar yang hangat. Honai bukan sekadar arsitektur, melainkan simbol kebersamaan, perlindungan, dan kekuatan keluarga. Di lembah Baliem, sejarah perang suku dulu bukan hanya soal konflik, tetapi mekanisme menjaga keseimbangan sosial.
Ha Anim di selatan Papua adalah rumah bagi orang Asmat dan Marind. Ukiran kayu Asmat mendunia, tetapi sedikit orang tahu bahwa setiap ukiran adalah roh leluhur yang diturunkan dalam bentuk kayu. Sagu adalah makanan utama, tetapi lebih dari itu, ia adalah simbol kehidupan: dari pohon sagu, orang bisa makan, minum, bahkan membangun rumah. Tujuh dunia ini menunjukkan bahwa Papua adalah universitas kehidupan. Setiap wilayah adalah guru, setiap tradisi adalah kitab, setiap ritual adalah ruang belajar.
Etnografi sebagai Jalan Masuk
Etnografi berasal dari bahasa Yunani: ethnos berarti bangsa atau suku, grapho berarti menulis. Tetapi dalam konteks Papua, etnografi bukan sekadar menulis. Ia adalah keberanian untuk masuk dalam kehidupan orang lain, mendengar cerita, dan menuliskannya dengan hati.
Seorang etnografer tidak cukup datang dengan kertas dan pena. Ia harus duduk bersama, makan bersama, bekerja bersama, bahkan menangis bersama. Etnografi adalah seni sekaligus metode: seni mendengar dengan empati, metode memahami dengan kedalaman. Papua sudah lama menjadi ladang etnografi. Koentjaraningrat menulis tentang orang Dani. Karl Heider mempelajari sistem perang dan film etnografi. Tetapi etnografi hari ini tidak bisa lagi berhenti pada "mendokumentasikan yang eksotis." Ia harus relevan dengan masyarakat. Ia harus menjadi cermin yang memampukan orang Papua melihat dirinya sendiri, bukan hanya cermin untuk orang luar.
Dr. George Mentansan dari Universitas Papua pernah berkata: "Menulis etnografi tidak selalu harus terikat pada sistematika akademis. Yang penting adalah keberanian menyelami kehidupan masyarakat, mendengar suara mereka, dan menuliskannya dengan jujur." Pernyataan ini penting, sebab etnografi Papua tidak hanya milik peneliti asing, tetapi juga milik mahasiswa, guru, bahkan orang kampung yang menulis kisahnya sendiri.
Tradisi di Tengah Globalisasi
Papua hari ini berada di persimpangan besar. Globalisasi datang membawa teknologi, internet, ekonomi digital, dan gaya hidup baru. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang: sekolah semakin banyak, informasi mudah diakses, ekonomi terbuka. Anak-anak Papua bisa belajar dengan laptop, berkomunikasi dengan saudara di luar negeri, dan membangun usaha online. Tetapi di sisi lain, globalisasi membawa ancaman. Bahasa daerah ditinggalkan, upacara adat dianggap kuno, tanah adat dipakai untuk proyek besar tanpa musyawarah. Hutan ditebang, sungai diracuni limbah, dan identitas perlahan hilang. Contoh nyata adalah soal tanah. Bagi orang Papua, tanah bukan sekadar benda ekonomi, tetapi tubuh kehidupan. Tanah adalah ibu. Tanah adalah roh leluhur. Tetapi hari ini, tanah sering dipandang hanya sebagai lahan investasi. Negara membangun jalan tanpa bertanya pada adat. Perusahaan membuka tambang tanpa menghormati hutan larangan. Globalisasi juga menyentuh kehidupan pemuda. Mereka hidup di dunia ganda: satu kaki dalam tradisi, satu kaki dalam dunia digital. Siang ikut pesta adat, malam mengunggah video di TikTok. Mereka bisa menari wor, tetapi juga bisa menari hip-hop. Mereka bisa duduk di honai, tetapi juga bisa bermain game online. Pertanyaannya: apakah globalisasi akan merusak tradisi, atau justru bisa memperkaya tradisi? Jawabannya ada di tangan pemuda.
Pemuda sebagai apa?
Pemuda Papua bukan sekadar pewaris pasif. Mereka adalah penulis bab baru kebudayaan. Dengan energi dan kreativitas, mereka bisa menafsirkan ulang tradisi agar tetap relevan. Seharusnya ada empat strategi penting, yakni Pertama, pendidikan berbasis adat. Sekolah formal sering melupakan pengetahuan lokal. Padahal, anak-anak bisa belajar matematika sekaligus cara menokok sagu, mengenali burung cenderawasih, atau membaca simbol rumah adat. Pengetahuan lokal adalah dasar identitas. Kedua, teknologi digital. Media sosial bisa dipakai untuk mendokumentasikan adat. Di Biak, ada komunitas muda yang membuat film dokumenter tentang tradisi keladi. Di Jayapura, ada gerakan membuat kamus digital bahasa daerah. Teknologi bisa menjadi jembatan, bukan ancaman. Ketiga, partisipasi pemuda dalam kelembagaan adat. Selama ini, lembaga adat diisi generasi tua. Jika jarak antar generasi terlalu lebar, regenerasi terputus. Pemuda harus diberi ruang agar kesinambungan budaya terjamin. Keempat, gerakan ekologis berbasis adat. Hutan larangan, sungai sakral, dan tanah keramat adalah warisan berharga. Nilai-nilai itu bisa menjadi inspirasi gerakan ekologis modern menghadapi krisis iklim global. Pemuda Papua bisa menjadi penghubung antara adat lokal dengan diskursus internasional. Dengan cara ini, pemuda bukan hanya pewaris budaya, tetapi juga influencer sosial, advokat, dan diplomat budaya. Mereka bisa menjembatani masyarakat adat dengan dunia luar, sekaligus menjaga akar identitas.
Negara dan Budaya

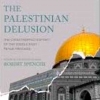
![[dpr] Gaji Tetap Mengalir, Tapi Hati Rakyat Sudah Pergi: Perlunya Etika dan Adab bagi Anggota Dewan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/02/file1b549156-2ec1-45a4-b331-a757f7fc9902-68b6499eed64152c5867fef4.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)




