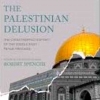Oleh :Yeremias Edowai
Papua adalah rumah besar yang penuh warna, sebuah bentangan tanah di ujung timur Indonesia tepatnya kawasan Melanesia yang dihiasi oleh gunung bersalju abadi, laut biru dengan ombak yang menggulung, hutan rimba yang lebat, serta rawa-rawa yang tenang. Tetapi keindahan itu bukan hanya milik alam, melainkan juga milik manusia yang menjadikannya ruang hidup. Papua adalah rumah budaya, tempat di mana manusia, alam, dan roh-roh leluhur saling bertemu dalam satu kesatuan.
Dalam peta antropologi, wilayah ini dikenal memiliki sembilan kawasan budaya, dua di antaranya berada di Papua Nugini, sehingga yang tersisa di Papua Indonesia ada tujuh. Angka tujuh itu bukan sekadar penanda geografis, melainkan simbol bagi kekayaan identitas. Ketujuh kawasan itu Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai, Meepago, Lapago, dan Ha Anim ibarat tujuh pintu yang jika kita masuk ke dalamnya, kita akan menemukan dunia yang berbeda-beda, namun tetap satu dalam nama Papua.Orang Papua percaya, budaya adalah napas kehidupan. Ia hadir dalam tarian, dalam ukiran, dalam suara tifa, dalam cara menokok sagu, dalam tradisi bakar batu, dalam nyanyian malam di bawah cahaya api unggun. Semua itu bukan sekadar hiasan, melainkan cara manusia menyatu dengan dunia yang lebih luas.Namun, sering kali wajah Papua dilihat dengan kacamata sempit. Negara Indonesia dan beberapa negara luar seperti Amerika Serikat lebih sering menyebut wilayah Papua sebagai daerah konflik atau wilayah kaya sumber daya yang mereka jadikan sebagai dapur. Perspektif semacam ini membuat budaya Papua seakan-akan terpinggirkan, seolah-olah hanya ornamen yang tidak penting. Padahal, Papua adalah gudang pengetahuan manusia yang bisa menjadi cermin bagi kita semua.Etnografi hadir untuk membuka jendela itu. Memahami Papua tanpa etnografi ibarat membaca buku hanya dari sampulnya: kita tahu judul, tapi tidak pernah mengerti isi.
Tujuh Dunia Budaya Papua
Penulis selami tujuh dunia budaya Papua satu per satu.
Mamta adalah rumah bagi orang Sentani dan Jayapura. Danau Sentani bukan sekadar air yang membentang, melainkan halaman hidup yang memberi makan, tempat manusia berenang bersama sejarah. Perahu lesung adalah lambang identitas, dan pesta danau bukan hanya atraksi wisata, melainkan doa panjang untuk keseimbangan alam.
Saireri, di Biak, Yapen, Waropen, adalah tanah bahari. Tarian wor bergema di pesisir, mengisahkan hubungan manusia dengan laut dan bintang-bintang. Tradisi mansorandak, penyambutan tamu, memperlihatkan betapa orang Saireri memuliakan kehidupan.
Domberai di Fakfak dan Kaimana dikenal dengan semboyan "satu tungku tiga batu." Falsafah itu sederhana, tetapi penuh makna: hidup bersama hanya bisa kokoh jika tiga batu agama, adat, dan pemerintah berdiri seimbang menopang periuk kehidupan.
Bomberai memiliki kearifan ekologis yang disebut sasi, yaitu aturan adat untuk melarang mengambil hasil laut atau hutan pada waktu tertentu. Dengan sasi, alam mendapat kesempatan untuk bernapas, dan manusia belajar sabar menunggu saat panen.
Meepago di pegunungan Paniai, Dogiyai, dan Deiyai menjadikan keladi sebagai pusat kehidupan. Bakar batu adalah pesta solidaritas: batu dibakar, daging babi dan umbi ditaruh di atasnya, lalu dimakan bersama. Filosofi "Dou, Gai, Ekowai" mengajarkan orang Mee untuk hidup jujur, baik hati, dan setia.
Lapago adalah tanah honai, rumah bundar yang hangat. Honai bukan sekadar arsitektur, melainkan simbol kebersamaan, perlindungan, dan kekuatan keluarga. Di lembah Baliem, sejarah perang suku dulu bukan hanya soal konflik, tetapi mekanisme menjaga keseimbangan sosial.
Ha Anim di selatan Papua adalah rumah bagi orang Asmat dan Marind. Ukiran kayu Asmat mendunia, tetapi sedikit orang tahu bahwa setiap ukiran adalah roh leluhur yang diturunkan dalam bentuk kayu. Sagu adalah makanan utama, tetapi lebih dari itu, ia adalah simbol kehidupan: dari pohon sagu, orang bisa makan, minum, bahkan membangun rumah. Tujuh dunia ini menunjukkan bahwa Papua adalah universitas kehidupan. Setiap wilayah adalah guru, setiap tradisi adalah kitab, setiap ritual adalah ruang belajar.
Etnografi sebagai Jalan Masuk
Etnografi berasal dari bahasa Yunani: ethnos berarti bangsa atau suku, grapho berarti menulis. Tetapi dalam konteks Papua, etnografi bukan sekadar menulis. Ia adalah keberanian untuk masuk dalam kehidupan orang lain, mendengar cerita, dan menuliskannya dengan hati.
Seorang etnografer tidak cukup datang dengan kertas dan pena. Ia harus duduk bersama, makan bersama, bekerja bersama, bahkan menangis bersama. Etnografi adalah seni sekaligus metode: seni mendengar dengan empati, metode memahami dengan kedalaman. Papua sudah lama menjadi ladang etnografi. Koentjaraningrat menulis tentang orang Dani. Karl Heider mempelajari sistem perang dan film etnografi. Tetapi etnografi hari ini tidak bisa lagi berhenti pada "mendokumentasikan yang eksotis." Ia harus relevan dengan masyarakat. Ia harus menjadi cermin yang memampukan orang Papua melihat dirinya sendiri, bukan hanya cermin untuk orang luar.
Dr. George Mentansan dari Universitas Papua pernah berkata: "Menulis etnografi tidak selalu harus terikat pada sistematika akademis. Yang penting adalah keberanian menyelami kehidupan masyarakat, mendengar suara mereka, dan menuliskannya dengan jujur." Pernyataan ini penting, sebab etnografi Papua tidak hanya milik peneliti asing, tetapi juga milik mahasiswa, guru, bahkan orang kampung yang menulis kisahnya sendiri.
Tradisi di Tengah Globalisasi
Papua hari ini berada di persimpangan besar. Globalisasi datang membawa teknologi, internet, ekonomi digital, dan gaya hidup baru. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang: sekolah semakin banyak, informasi mudah diakses, ekonomi terbuka. Anak-anak Papua bisa belajar dengan laptop, berkomunikasi dengan saudara di luar negeri, dan membangun usaha online. Tetapi di sisi lain, globalisasi membawa ancaman. Bahasa daerah ditinggalkan, upacara adat dianggap kuno, tanah adat dipakai untuk proyek besar tanpa musyawarah. Hutan ditebang, sungai diracuni limbah, dan identitas perlahan hilang. Contoh nyata adalah soal tanah. Bagi orang Papua, tanah bukan sekadar benda ekonomi, tetapi tubuh kehidupan. Tanah adalah ibu. Tanah adalah roh leluhur. Tetapi hari ini, tanah sering dipandang hanya sebagai lahan investasi. Negara membangun jalan tanpa bertanya pada adat. Perusahaan membuka tambang tanpa menghormati hutan larangan. Globalisasi juga menyentuh kehidupan pemuda. Mereka hidup di dunia ganda: satu kaki dalam tradisi, satu kaki dalam dunia digital. Siang ikut pesta adat, malam mengunggah video di TikTok. Mereka bisa menari wor, tetapi juga bisa menari hip-hop. Mereka bisa duduk di honai, tetapi juga bisa bermain game online. Pertanyaannya: apakah globalisasi akan merusak tradisi, atau justru bisa memperkaya tradisi? Jawabannya ada di tangan pemuda.
Pemuda sebagai apa?
Pemuda Papua bukan sekadar pewaris pasif. Mereka adalah penulis bab baru kebudayaan. Dengan energi dan kreativitas, mereka bisa menafsirkan ulang tradisi agar tetap relevan. Seharusnya ada empat strategi penting, yakni Pertama, pendidikan berbasis adat. Sekolah formal sering melupakan pengetahuan lokal. Padahal, anak-anak bisa belajar matematika sekaligus cara menokok sagu, mengenali burung cenderawasih, atau membaca simbol rumah adat. Pengetahuan lokal adalah dasar identitas. Kedua, teknologi digital. Media sosial bisa dipakai untuk mendokumentasikan adat. Di Biak, ada komunitas muda yang membuat film dokumenter tentang tradisi keladi. Di Jayapura, ada gerakan membuat kamus digital bahasa daerah. Teknologi bisa menjadi jembatan, bukan ancaman. Ketiga, partisipasi pemuda dalam kelembagaan adat. Selama ini, lembaga adat diisi generasi tua. Jika jarak antar generasi terlalu lebar, regenerasi terputus. Pemuda harus diberi ruang agar kesinambungan budaya terjamin. Keempat, gerakan ekologis berbasis adat. Hutan larangan, sungai sakral, dan tanah keramat adalah warisan berharga. Nilai-nilai itu bisa menjadi inspirasi gerakan ekologis modern menghadapi krisis iklim global. Pemuda Papua bisa menjadi penghubung antara adat lokal dengan diskursus internasional. Dengan cara ini, pemuda bukan hanya pewaris budaya, tetapi juga influencer sosial, advokat, dan diplomat budaya. Mereka bisa menjembatani masyarakat adat dengan dunia luar, sekaligus menjaga akar identitas.
Negara dan Budaya
Selama ini, negara cenderung memandang Papua dari kacamata sempit: keamanan dan ekonomi. Papua dilihat sebagai daerah konflik dan ladang sumber daya. Pandangan semacam ini sering mengabaikan dimensi budaya. Contohnya sederhana: pemerintah membangun jalan tanpa dialog adat. Bagi negara, itu infrastruktur. Bagi masyarakat, itu bisa berarti kehilangan tanah leluhur. Ritual disingkirkan demi efisiensi proyek, padahal yang hilang bukan hanya upacara, tetapi juga sistem pengetahuan yang menjaga ekologi. Etnografi bisa menjadi penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal menanamkan akar pada budaya. Masyarakat adat tidak boleh dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai sumber pengetahuan.
Menjaga Akar di Tengah Angin
Papua berada di titik penting. Jika globalisasi dijalani tanpa refleksi, identitas bisa hilang. Tetapi jika globalisasi dijalani dengan akar budaya, justru ia akan memperkuat jati diri. Etnografi adalah jembatan. Ia merekam keragaman, menjadi refleksi kritis, dan mengajarkan kita untuk tidak sekadar melihat Papua dari luar. Tradisi dan modernitas tidak harus dipertentangkan. Pemuda adalah kunci pertemuan itu. Dengan kreativitas, mereka bisa menjaga akar budaya sekaligus membuka jalan masa depan. Sebagaimana kata Dr. George Mentansan: menulis etnografi bukan monopoli akademisi, tetapi tugas siapa saja yang berani menyelami kehidupan masyarakat dan menuliskannya dengan jujur. Dalam dunia yang berubah cepat, suara masyarakat adat bukan objek penelitian, tetapi sumber kebijaksanaan. Papua tidak boleh hanya dilihat sebagai tanah kaya, tetapi harus dipahami sebagai tanah pengetahuan. Dan pada akhirnya, Papua adalah cermin: ia mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya soal membangun jalan atau menggali tambang, tetapi juga soal merawat akar, mendengar suara leluhur, dan menjaga hubungan manusia dengan alam.[*]
*Penulis adalah mahasiswa Universitas Cenderawasih, Jayapura
Sumber inspirasi: Dr. George Mentansan, Dosen Antropologi Universitas Papua (Unipa), Manokwari
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI