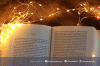Saat pandemi kita punya harapan untuk lebih banyak belajar dan mengasah kemampuan. Tapi, binge watching membuat semuanya sirna.
Menonton film merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk mengisi waktu luangnya. Ketika website dan aplikasi penyedia film berbasis streaming seperti Netflix muncul, lahirlah sebuah fenomena baru dalam industri film yang disebut sebagai binge watching. Istilah ini muncul ketika Netflix meluncurkan film series berjudul “House of Cards pada tahun 2013 silam. Tidak seperti siaran tv kabel, Netflix melakukan inovasi dengan merilis seluruh episode di satu waktu.
Istilah binge watching ternyata tidak hanya berlaku bagi para penikmat film di Netflix saja. Menurut pengertian Conlin, Billings dan Averset (2016), binge watching adalah keadaan dimana seseorang mengkonsumsi keseluruhan episode bahkan season dalam jumlah waktu yang kecil tapi ajeg. Ini berarti semua produk film ataupun tv series selain produk Netflix dapat masuk ke dalam kategori tersebut. Seperti halnya serial K-Drama, Anime, Bollywood atau produk hiburan lainnya.
Fenomena binge watching atau “menonton secara marathon” sampailah juga di Indonesia. Munculnya fenomena binge watching di Indonesia ataupun di seluruh dunia, salah satunya dipengaruhi oleh merebaknya pandemi Covid-19. Jumlah pelanggan Netflix di Indonesia yang pada kuartal ke-4 tahun 2019 sudah mencapai angka 8,8 juta, diprediksi masih akan terus bertambah lebih banyak lagi, seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 (Salsabilla, 2020).
Dari penjelasan di atas, muncul sebuah pertanyaan di benak penulis, sekaligus menjadi rumusan masalah diartikel ini. Apakah fenomena binge watching yang terjadi selama pandemi Covid-19 berkorelasi kuat dengan kapitalisme?
Pertanyaan ini muncul karena menurut penulis ada sebuah hubungan khusus, dari fenomen binge watching yang bisa dijelaskan dengan menggunakan dua konsep pemikiran kritis, yakni leisure time (watu senggang) dan komodifikasi konsumen.
Pengertian dan Konsep Leisure Time
Leisure menurut Adorno dalam Suseno (2013), berasal dari bahasa latin Lice-reis yang berarti liburan. Pengertian ini mengalami pergeseran makna saat memasuki abad ke-18, dan berganti menjadi waktu luang. Pergeseran ini didasarkan pada berubahnya keadaan sosial dan budaya, karena perkembangan kapitalisme modern. Sehingga semakin ke depan, leisure memiliki turunan makna yang berarti waktu luang yang dimiliki di luar jam kerja.
Adanya pergeseran makna dari leisure membuat sejumlah akademisi melakukan studi leisure pada akhir tahun 1970-an. Studi tersebut melahirkan sebuah konsep, bahwa leisure memiliki korelasi kuat pada konsep kapitalisme dan mengarah pada marjinalisasi perempuan. Menikmati waktu luang pada waktu itu dianggap menjadi hal terbatas bagi perempuan. Karena waktu luang adalah hak bagi laki-laki untuk bersantai setelah seharian bekerja, dan tidak berlaku bagi perempuan.
Kapitalisme akhirnya berdampak pada terciptanya dominasi di kelas sosial secara ekonomi dan budaya. Hal inilah yang kemudian mendorong beberapa kritikus politik dari The Frankfurt School seperti Theodor Adorno, hadir untuk membicarakan tentang dominasi kapitalis yang tercipta dari konsep leisure. Adorno menarik perhatian pada tiga cara signifikan, dimana kapitalisme lewat leisure time justru ingin merusak dan menurukan derajat kita sebagai manusia.
a). Leisure time becomes toxic: Ketika masyarakat menghabiskan waktu luang dengan tidak benar, waktu itu akan terbuang dengan percuma. Adorno mengemukakan bahwa masyarakat seharusnya lebih menggunakan waktu yang ada untuk memperluas dan mengembangkan diri. Seperti membaca buku, menulis, eksperimen dan lainnya. Sehingga, harapannya masyarakat bisa menjadi lebih baik dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
b). Capitalism doesn’t sell us the things we really need: Seperti yang diketahui, kadang ketika kita tertarik pada sesuatu yang kita sendiri tidak akan berpikir bahwa barang tersebut penting atau tidak, kita akan cenderung untuk membeli dan memilikinya. Hal ini lah yang membuat Adorno menyatakan bahwa kaum kapitalis menjual barang yang sebetulnya tidak diperlukan oleh masyarakat tapi dipaksa untuk membeli secara tidak langsung.
c). There are proto-fascists everywhere: Kapitalisme menurut Adorno pada hakikatnya adalah bentuk modern di era industri dan swasta. Adorno beranggapan bahwa kapitalisme sejatinya adalah kekuatan swasta yang membuat semua orang tunduk dan tak berdaya ketika mereka harus menyuarakan segala hak yang penting untuk kesejahteraan hidupnya. Mereka takut untuk bersuara karena mereka bisa saja dipecat atau di PHK, karena dianggap melawan supremasi kapitalis.

Pengertian dan Konsep Komodifikasi
Mosco dalam Mumpuni (2018) mengartikan komodifikasi sebagai proses mengubah nilai pada suatu produk yang sebelumnya hanya memiliki nilai guna menjadi nilai tukar, dimana produsen sudah merancang nilai kebutuhan produk ini melalui harga produk tersebut. Komunikasi menjadi salah satu ranah yang potensial sebagai tempat terjadinya proses komodifikasi. Ini di sebabkan karena komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh semua orang setiap hari.
Komunikasi merupakan komoditas yang besar pengaruhnya, tidak hanya dalam pesan yang disampaikan, tetapi juga dalam simbol yang digunakan.
Sebagai contoh, kita setiap hari dapat menemukan ada orang-orang yang suka membaca atau mungkin menyaksikan tayangan berita di televisi. Proses konsumsi ini bisa dikategorikan ke dalam proses komodifikasi. Menurut Mosco ada 3 bentuk komodifikasi dalam ekonomi politik komunikasi (2018):
a). komodifikasi konten, adanya transformasi pesan dari sekadar data menjadi sistem pemikiran penuh makna dalam bentuk produk yang dipasarkan.
b). komodifikasi audiens, audiens yang dijual kepada pengiklan. audiens adalah komoditas untuk mendapatkan iklan dan pemasukan
c). komodifikasi pekerja, keahlian dan jam kerja pekerja yang dijual.
Di sisi lain, Mosco juga berpendapat bahwa ada dua buah dimensi yang saling membuat keterhubungan antara komodifikasi dengan komunikasi, yaitu adanya pengaruh dari penggunaan teknologi tertentu, untuk memperlancar proses komunikasi. Dengan teknologi komunikasi proses komodifikasi dalam masyarakat secara keseluruhan dapat menembus berbagai batasan komunikasi. Ini tentu saja dapat mempengaruhi interaksi sosial masyarakat (Mosco, 2009).
Adorno dan Horkheimer (2002) dalam tulisannya The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception, mengkritisi, bahwa komodifikasi terjadi karena hasil dari masuknya teknologi di suatu industri budaya. Proses produksi benda budaya (musik dan film) pada zaman pra-industri diproduksi secara otonom/murni; tidak ada campur tangan industri dengan segala sistem pasar dalam proses produksinya; dan produk masih dibuat atas tujuan seni atau pendidikan.
Namun, industri saat ini telah mengambil alih proses produksi berbagai artefak kebudayaan. Kemudian membingkai ulang berbagai produk yang seolah telah menjadi kebutuhan massa, dan menjadi faktor penentu dalam proses produksinya. Sehingga, benda budaya yang sebelumnya dipenuhi dengan nilai-nilai tinggi, otentik (authenticity), dan kebenaran (truth), oleh industri budaya diproduksi secara massal menjadi komoditas yang penuh dengan perhitungan laba (profit).
Dalam konteks media massa saat ini, menurut Adorno (2002) media telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan industri budaya, yaitu budaya yang sudah mengalami komodifikasi, karena produk budaya yang dihasilkan, pertama, tidak otentik, dimana, kebudayaan yang diproduksi secara otonom/murni tidak lagi dihasilkan oleh rakyat atau masyarakat yang memilikinya. Akan tetapi ada campur tangan industri dengan segala sistem pasar dalam proses produksinya.
Benda budaya, yang dipenuhi dengan nilai-nilai tinggi, otentik dan kebenaran telah mengalami pergeseran makna, diproduksi secara massal berdasarkan selera pasar. Kedua, manipulatif, dimana kebudayaan yang diproduksi oleh industri budaya dengan tujuan agar dibeli di pasar, bukan lagi pada daya kreativitas sang kreator, sehingga telah menghasilkan kebudayaan semu/palsu. Ketiga, terstandarisasi, dimana, adanya bentuk penyeragaman dalam mekanisme industri budaya.

Analisis Binge-Watching
Binge watching adalah kegiatan yang menghabiskan banyak sekali waktu untuk menyelesaikannya. Bila dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Adorno soal leisure time, pelaku binge watching mempergunakan waktunya secara kurang tepat. Karena sebuah keadaan tertentu, penonton akhirnya ‘terpaksa’ melakukan binge watching dengan alasan yang variatif. Di sinilah Adorno menyampaikan kritiknya atas perilaku binge watching yang merugikan kita.
Ungkapan Adorno tentang “Leisure time become toxic”, selaras dengan fenomena binge watching yang membuat penontonnya menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan hal lain. Inilah yang menyebabkan kenapa Adorno begitu heran dengan perilaku masyarakat industri, yang sebetulnya bisa lebih baik dalam segi kemampuan, keahlian dan kualitas dirinya, jika mereka mau menggunakan waktu luang yang tersedia untuk mengembangkan diri.
Bila diperhatikan, secara tidak langsung binge watching berkorelasi dengan konsep komodifikasi. Sesuai dengan tujuannya, komodifikasi adalah cara umum yang dipakai oleh para pelaku industri, untuk dapat mendulang profit sebesar-besarnya. Dalam komodifikasi, ada bentuk pertukaran nilai yang dilakukan antara audiens (leisure time) dengan pelaku industri (konten film). Pertukaran ini secara tidak langsung juga ikut dipopulerkan oleh audiens lewat media sosial dan menjadi tren.
Jika penonton yang datang dan menonton secara binge semakin banyak, alhasil film yang ditonton akan menjadi tren dan kebiasan binge watching juga akan ikut menjadi tren. Hal ini tentu berdampak besar pada semakin banyaknya pundi-pundi kekayaan yang masuk ke pelaku industri. Inilah yang dinamakan oleh Adorno sebagai “Capitalism doesn’t sell us the things we really need”, atau mudahnya kita jatuh dan terjebak ke dalam kebutuhan semu.
Adorno dalam dalam DARI MAO KE MARCUSE Percikan Filsafat Marxis Pasca Lenin karya Franz Magnis Suseno (2013), berpendapat bahwa industri kapitalis sejatinya ingin benar-benar membuat kita melupakan apa yang benar-benar kita butuhkan. Adorno menejelaskan fenomena ini sebagai kebutuhan semu. Kita sebetulnya tidak butuh suatu barang. Tapi, iklan lewat narasi-narasinya membuat kita menjadi lebih tertarik untuk membelinya, dan siklus ini terus berulang.
Dititik inilah kita dapat menemukan fenomena lain dari komodifikasi, yakni komodifikasi konsumen. Netflix, sebagai penyedia layanan film streaming, pasti mengkategorikan penonton berdasarkan genre yang mereka suka. Hal ini tentu sangat memudahkan para pengiklan untuk menargetkan pasar. Semakin audiens sering menonton secara binge, alhasil filmnya jadi populer. Film yang populer otomatis akan mendapatkan lebih banyak iklan, karena lebih menguntungkan.
Inilah yang disebut oleh para pemikir kritis sebagai kapitalisme ganda. Ketika kita sudah mengkonsumsi serangkaian film secara binge dan mengorbankan leisure, kita sebetulnya sudah membuat mereka kaya. Namun, kehadiran para pengiklan di berbagai film populer membuat kita semakin tergoda untuk mencoba berbagai produk yang ditawarkan oleh pengiklan, meski kita tidak butuh. Inilah yang dinamakan kapitalisme ganda, turunan fenomena dari kebutuhan semu.
Akhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa binge watching berkorelasi kuat dengan kegiatan kapitalisme. Ketika kita mengorbankan waktu leisure yang berharga hanya untuk menonton film secara kontinu, sejatinya kita telah menurunkan derajat hidup kita satu persen setiap harinya. Ketika kita sudah larut, komodifikasi akan membuat kita semakin larut dalam kebutuhan semu. Jadi, nonton film itu boleh, asal jangan berlebihan. Karena investasi hidup kita masih panjangkan?
Daftar Pustaka:
Conlin, L., Billings, A. C., & Averset, L. (2016). Time-shifting vs. appointment viewing: the role of fear of missing out within TV consumption behaviors. Communication & Society, 29(4), 151–164. doi: 10.15581/003.29.4.151-164
Adorno, T & Horkheimer, M. (2002). The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception. Dalam The Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragment. Stanford: Stanford University Press
Mumpuni, P. (2018). Komodifikasi Kemiskinan pada Reality Show “Mikrofon Pelunas Hutang”. Majalah Ilmiah Inspiratif, 3(5).
Suseno-Magnis, F. 2013. DARI MAO KE MARCUSE Percikan Filsafat Marxis Pasca Lenin. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
Mosco, V. (2009). The Political Economy of Communication. SAGE Publication; London
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI