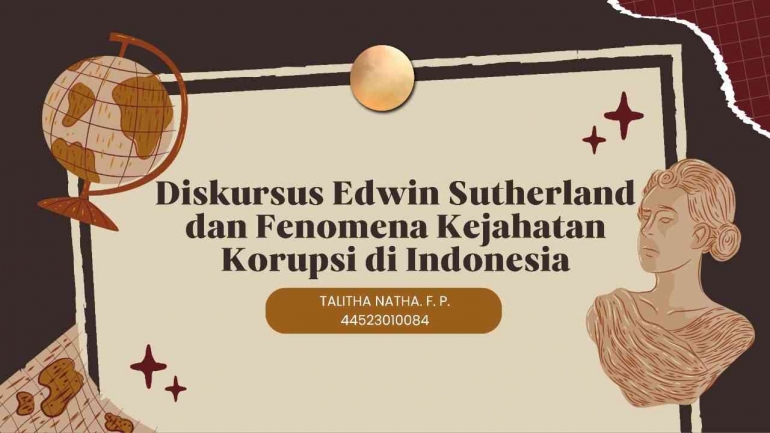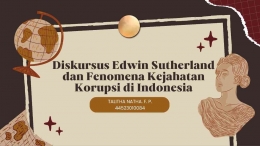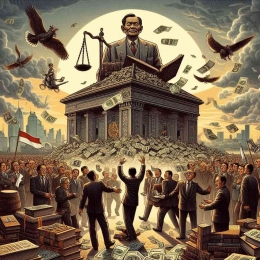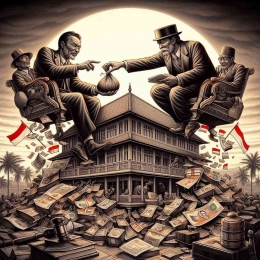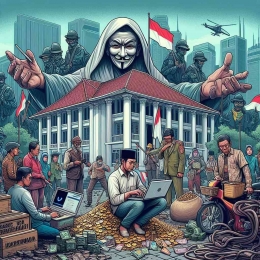Nama: Talitha Natha Fathinah Pulungan
NIM: 44523010084
Jurusan: Digital Komunikasi
Mata Kuliah: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ETIK UMB
Dosen Pengampu: Prof. Dr.Apollo, Ak., M.Si.
Universitas Mercu Buana
Pendahuluan
Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia sejak lama. Sejak era Orde Baru hingga reformasi, praktik korupsi terus berlangsung di hampir semua lini birokrasi dan pemerintahan. Bahkan di era reformasi dan keterbukaan informasi saat ini, kasus-kasus korupsi masih sering terungkap dan pelakunya sudah sangat sistematis dan terstruktur.
Menurut survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC), indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2021 berada pada peringkat 102 dari 180 negara. Angka korupsi Indonesia juga tak kunjung membaik dari tahun ke tahun. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada 2021 mencapai Rp17,8 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp14,5 triliun.
Tentu fenomena korupsi yang begitu masif dan sistematis ini perlu ditelaah dari berbagai sisi, baik sosiologis, politis, budaya, dan kriminologis. Salah satu teori penting dalam kriminologi yang relevan untuk memahami fenomena korupsi di Indonesia adalah teori Edwin H. Sutherland.
Edwin H. Sutherland adalah seorang kriminolog yang mengemukakan teori Asosiasi Diferensial. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku kriminal seseorang ditentukan dari proses belajar melalui interaksi dan asosiasi dengan orang lain yang memiliki norma-norma perilaku menyimpang atau kriminal. Apabila seseorang berinteraksi dan bergaul secara intensif dalam suatu kelompok yang memiliki dan mentransmisikan definisi-definisi yang menyimpang terhadap suatu tindakan, maka orang tersebut cenderung untuk meniru perilaku menyimpang atau kriminal dari kelompoknya. Sutherland merumuskan 9 proposisi dalam teori asosiasi diferensial ini:
- Perilaku kriminal dipelajari.
- Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
- Bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran kriminal itu berlangsung di dalam kelompok hubungan dekat.
- Bila terjadi perilaku kriminal maka hal itu dipelajari melalui dominasi aturan-aturan yang membenarkan pelanggaran hukum atas aturan-aturan yang melarangnya.
- Arah sikap difasilitasi atau didorong oleh definisi menyokong atau tidak menyokong pelanggaran hukum.
- Suatu kelompok menjadi kriminogenik bila frekuensi delinkuensinya lebih tinggi dibanding kelompok - kelompok lainnya yang sama dalam hal bagian dari elemen delinkuen dan nondelinkuen.
- Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal meliputi (a) teknik melakukan kejahatan dan (b) arah sikap, pembenaran, rasionalisasi, dan atitude.
- Kejahatan ekspresif timbul dari frustasi akibat kegagalan mencapai kesejahteraan dan prestise. Kejahatan instrumen adalah akibat dari kesempatan untuk keuntungan pribadi dan juga kebutuhan.
- Direktris utama pelanggaran hukum adalah kebutuhan dan kesempatan.
Konsep-konsep kunci dalam teori asosiasi diferensial adalah asosiasi diferensial itu sendiri dan definisi. Asosiasi diferensial merujuk pada pola pergaulan dan interaksi sosial yang cenderung berbeda di antara orang-orang yang terlibat dalam perilaku menyimpang dibanding orang-orang yang tidak terlibat perilaku menyimpang. Sedangkan definisi mencakup orientasi nilai, sikap dan pemikiran mengenai perilaku menyimpang atau kriminal, apakah hal tersebut dianggap benar atau salah.
Mengapa Penting untuk Memahami Fenomena Korupsi di Indonesia?
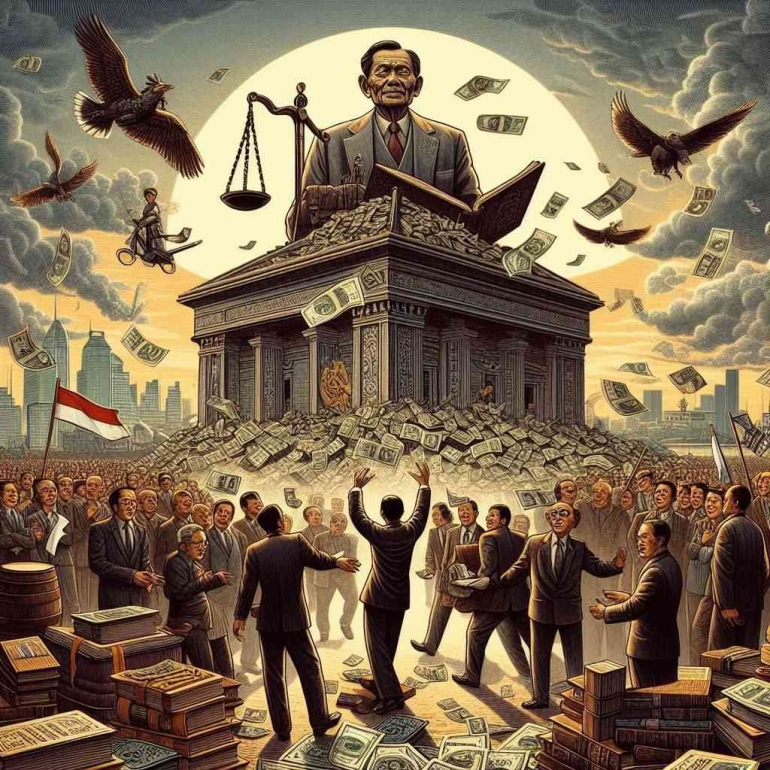
Teori asosiasi diferensial yang dicetuskan Edwin Sutherland pada awal tahun 1940-an adalah salah satu teori penting dalam kriminologi. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku kriminal seseorang dipelajari melalui interaksi dan asosiasi dengan orang lain yang memiliki norma, nilai, dan perilaku menyimpang.
Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan cenderung terlibat perilaku kriminal dan melanggar hukum apabila lebih banyak berinteraksi dalam lingkungan yang menganggap perilaku kriminal tersebut dapat diterima. Pola asosiasi diferensial antara perilaku kriminal dan konformis inilah yang menentukan kecenderungan seseorang terlibat tindak kriminal atau tidak.
Teori asosiasi diferensial relevan untuk menjelaskan perilaku koruptif yang marak terjadi di Indonesia saat ini. Praktik korupsi yang sistematis dan meluas di berbagai lini birokrasi dan jabatan publik mengindikasikan bahwa pelaku telah mempelajari perilaku koruptif ini dari lingkungan sosial dan pergaulan mereka.
Interaksi rutin dengan rekan-rekan yang juga korup serta budaya organisasi yang kondusif dan toleran terhadap kecurangan cenderung membuat perilaku koruptif ini seolah menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan demi keuntungan pribadi maupun golongan.
Korupsi di Indonesia memang sudah sistemik dan meluas hingga ke akar rumput. Berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Corruption Watch, praktik korupsi terjadi di hampir semua lembaga negara, serta di tingkat pemerintahan pusat hingga desa.
Nilai kerugian negara akibat korupsi juga sangat fantastis, mencapai Rp1.000-3.000 triliun per tahunnya menurut beberapa sumber. Jumlah yang sangat besar ini tentu berdampak buruk, mulai dari menghambat pembangunan, menurunkan kualitas hidup rakyat, hingga memperlebar kesenjangan sosial.
Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus digiatkan di Indonesia. Perlu adanya political will yang kuat dari pemerintah beserta jajarannya untuk memberantas korupsi secara masif dan konsisten, tanpa pandang bulu.
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pun wajib terus dilakukan untuk menghilangkan celah-celah yang rawan praktik korupsi. Sementara dari sisi hukum, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas dan maksimal kepada para koruptor juga penting, agar memberikan efek jera.
Di samping itu, edukasi dan kampanye antikorupsi sejak dini kepada generasi muda juga krusial. Ini dilakukan agar budaya intoleransi dan stigma negatif terhadap praktik korupsi bisa terinternalisasi secara masif di tengah masyarakat. Dengan demikian, tekad kolektif untuk memberantas korupsi akan semakin kuat.
Kesimpulannya, fenomena korupsi yang sudah sistemik dan masif di Indonesia ini harus segera ditangani dan diberantas. Pendekatan pencegahan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi antikorupsi sejak dini penting untuk terus digalakkan demi meminimalisir tingkat korupsi di Indonesia.
Konsep Teori Konsep Asosiasi Diferensial
Edwin Sutherland dalam teori asosiasi diferensialnya menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukan bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari proses pembelajaran dan asosiasi interaksi sosial dengan kelompok-kelompok tertentu di lingkungan individu. Pola interaksi sosial yang cenderung berbeda antara individu-individu yang melakukan kriminalitas dan individu yang patuh pada hukum inilah yang disebut asosiasi diferensial.
Melalui asosiasi diferensial dengan kelompok tertentu yang sering melakukan tindakan melanggar hukum, maka seseorang bisa belajar cara, teknik, serta dalih pembenaran yang merasionalkan tindakan kriminal tersebut. Intinya perilaku kriminal dipelajari melalui proses asosiasi dan interaksi intensif dengan kelompok kriminal.
Teori Asosiasi Diferensial dan Korupsi di Indonesia

Praktik korupsi yang begitu massif dan sistematis di hampir semua tingkatan birokrasi dan pemerintahan di Indonesia, mengindikasikan adanya asosiasi diferensial baik secara vertikal maupun horizontal di antara para pelakunya.
Tidak sulit untuk menemukan bahwa pejabat tinggi cenderung berinteraksi intensif dengan pejabat tinggi lainnya dan melakukan praktik korupsi bersama-sama. Demikian pula adanya transfer pengetahuan tentang cara melakukan korupsi dari generasi pejabat senior kepada juniornya. Mereka belajar teknik dan cara merasionalkan perilaku korupsi melalui asosiasi dan interaksi intensif ini.
Dalam teorinya, Sutherland merumuskan 9 proporsi yang menjelaskan mekanisme terbentuknya perilaku kriminal dan menyimpang melalui proses belajar difensial dalam asosiasi personal:
- Perilaku kriminal diperoleh melalui interaksi/komunikasi. Perilaku korup pejabat publik diperoleh dari proses interaksi dan komunikasi dengan rekan-rekan sesama pejabat maupun atasannya yang korup.
- Perilaku kriminal dipelajari dan diperkenalkan selama masa pergaulan personal. Korupsi yang dilakukan pejabat publik turut dipengaruhi dan dipelajari dari lingkungan kerja dan pergaulannya sehari-hari.
- Bagian penting proses pembelajaran terjadi dalam kelompok personal yang intensif. Interaksi dan asosiasi yang kuat dan intens dengan kelompok birokrat korup akan semakin memperkuat proses pembelajaran tersebut.
- Teknik melakukan kejahatan dipelajari melalui asosiasi difensial. Trik dan cara melakukan korupsi juga turut dipelajari pejabat publik dari lingkungannya.
- Arah motivasi ditentukan oleh definisi hukum yang negatif & positif. Sikap toleran terhadap suap dan KKN mendorong perilaku koruptif.
- Seseorang menjadi delikuensi tergantung pada frekuensi asosiasi diferensial melebihi asosiasi konformis. Semakin sering dan intensif bergaul dgn kelompok korupsi, maka makin tinggi kemungkinan meniru perilaku tersebut.
- Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. Semakin sering, lama, prioritas dan intensitasnya, maka perilaku korupsi makin mungkin diperoleh individu tersebut.
- Proses terjadinya perilaku kriminal melalui asosiasi diferensial adalah mirip dengan proses belajar konformitas. Keduanya diperoleh melalui interaksi dan asosiasi social.
- Walaupun sebab musabab awal perilaku kriminal dapat disebabkan kondisi patologis/biologis, namun perilaku kriminal itu sendiri dipelajari. Meski terkait motif ekonomi, perilaku korupsinya sendiri harus dipelajari dari lingkungan.
Mengacu 9 proporsi Sutherland di atas, jelas terlihat bahwa faktor lingkungan dan asosiasi dengan kelompok korup memiliki andil besar terhadap pembentukan perilaku koruptif pejabat publik di Indonesia. Oleh karena itu komitmen reformasi birokrasi dan sistem yang kondusif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) menjadi keniscayaan untuk memutus rantai praktik korupsi yang sudah sistemik dan meluas di Indonesia saat ini.
Contoh Kasus Korupsi di Indonesia
Salah satu kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi e-KTP senilai Rp2,3 triliun oleh mantan dirut PT Pegadaian, Irman Zahiruddin dan rekan-rekannya di Kemendagri pada 2012-2013. Dalam kasus ini, Irman melakukan korupsi anggaran lewat pengadaan proyek e-KTP.
Berdasarkan teori asosiasi diferensial, terjadinya perilaku koruptif Irman dipengaruhi oleh lingkungan di tempatnya bekerja. Praktik suap dan korupsi pengadaan barang sudah lazim terjadi di lingkungan Kemendagri dan Pegadaian tempatnya bernaung. Interaksi dan asosiasi Irman dengan rekan-rekan seprofesi yang korup inilah yang turut membentuk pemikiran dan mempengaruhi perilakunya.
Berdasarkan teori asosiasi diferensial, terjadinya perilaku koruptif Irman dipengaruhi oleh lingkungan di tempatnya bekerja. Praktik suap dan korupsi pengadaan barang sudah lazim terjadi di lingkungan Kemendagri dan Pegadaian tempatnya bernaung. Interaksi dan asosiasi Irman dengan rekan-rekan seprofesi yang korup inilah yang turut membentuk pemikiran dan mempengaruhi perilakunya.
Sebagaimana konsep teori Sutherland, pengaruh lingkungan kerja yang korup akan sangat kuat apabila seseorang memiliki intensitas interaksi dan kedekatan yang tinggi dengan kelompok koruptor tersebut. Intensitas dekat Irman dengan jaringan suap Kemendagri diduga turut memperkuat perilaku koruptifnya dalam kasus pengadaan e-KTP senilai triliunan ini.
Contoh ini memperlihatkan bahwa, sebagaimana perspektif teori asosiasi diferensial, perilaku kriminal termasuk korupsi dipengaruhi dan dipelajari dari lingkungan sosial pelaku. Lingkungan kerja kondusif KKN yang tercipta di Kemendagri dan Pegadaian mendorong Irman yang awalnya bersih menjadi koruptor ulung.
Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari reformasi lingkungan kerja dan birokrasi yang kondusif korupsi serta pendidikan budaya etis sejak dini. Hal ini akan meminimalkan terbentuknya perilaku koruptif akibat lingkungan dan interaksi sosial yang salah.

Perspektif Teori Lain
Selain Sutherland, perspektif lain untuk menganalisis penyebab korupsi di Indonesia dikemukakan Cesare Beccaria dalam teori Rasionalisme. Menurut Beccaria, manusia dimotivasi oleh kemauan untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan kesenangan. Oleh karena itu, korupsi dilakukan pelakunya semata demi keuntungan pribadi karena kesempatan untuk itu tersedia. Dengan kata lain korupsi yang begitu menggoda tanpa hukuman dan sanksi yang berarti akan mendorong siapapun untuk korupsi demi keuntungan pribadi.
Sementara Robert Merton dalam Teori Anomie mengatakan korupsi sebagai bentuk penyimpangan yang disebabkan karena ada kesenjangan antara kemampuan/alat yang dimiliki individu untuk mencapai tujuan (kesejahteraan) yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Karena terbatasnya akses pada cara-cara legal/formal untuk meraih kesuksesan sosial, maka individu didorong untuk melakukan tindakan penyimpangan seperi korupsi.
Nilai dan Moralitas Jawa
Merujuk pada sistem simbolik dan nilai-nilai tradisional dari budaya Jawa sebagaimana digambarkan dalam Serat Centhini, Suluk, maupun teks-teks tradisional lainnya, sungguh tidak terdapat pembenaran bagi perbuatan tercela seperti korupsi. Bahkan ada istilah Jawa, Sundul Unti Therek Kang Temon-Temon, yang merujuk pada sindiran untuk kaum elit politik atau pejabat yang senang melakukan penyimpangan.
Kutipan dari Serat Wedhatama misalnya:
"Lamun ing tyas anglakoni lepat, jumbuhing karsa miwah luhuring budi... Wruha ing lathi, rineka lena suci..."
Jelas bahwa nilai-nilai moral budi luhur sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa, sejalan dengan nilai moral agama-agama. Tindakan korup adalah bentuk pelanggaran nilai tersebut.
Konsep "Memayu Hayuning Bawono"
Memayu hayuning bawono adalah salah satu konsep filsafat Jawa yang artinya "memperindah keindahan dunia". Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan alam semesta. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memayu hayuning bawono yakni memperindah dunia dengan berperilaku baik, bijaksana, dan selaras dengan alam.
Menurut antropolog Clifford Geertz, orang Jawa meyakini bahwa dunia beserta segala isinya diciptakan dalam keadaan tertata rapi, proporsional, dan penuh keteraturan. Ketika manusia berperilaku serakah atau tamak, maka keseimbangan itu terganggu. Oleh sebab itu manusia harus selalu berupaya menjaga keselarasan dengan alam.
Sementara menurut Koentjaraningrat, paham keseimbangan alam dan "memayu hayuning bawono" bagi orang Jawa berakar dari pandangan hidup agraris mereka. Petani sangat bergantung pada keselarasan alam dan lingkungannya agar panen dapat berhasil. Jika terjadi bencana alam atau perilaku manusia yang mengganggu keseimbangan, hasil panen akan gagal.
Konsep ini relevan diterapkan dalam upaya pencegahan perilaku korupsi yang sudah sangat merusak tatanan sosial dan pembangunan di Indonesia. Praktik korupsi yang merajalela dapat dianalogikan seperti perilaku serakah dan tamak yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan negara.
Oleh karena itu, pemahaman akan konsep "memayu hayuning bawono" dan keseimbangan alam perlu ditanamkan sejak dini agar terbentuk kesadaran kolektif bahwa perilaku korupsi itu destruktif dan mengganggu keharmonisan tatanan sosial. Sama halnya seperti bencana alam atau wabah penyakit yang mengancam panen dan kehidupan petani.
Strategi penerapannya antara lain dengan menggencarkan pendidikan dan sosialisasi filosofi Jawa sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Penanaman nilai-nilai luhur ketimuran ini diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang lebih beretika dan antikorupsi.
Selain itu, konsep memayu hayuning bawono juga dapat diimplementasikan lewat system birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan asas keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat. Dengan begitu praktik KKN dan korupsi diharapkan bisa diminimalisir demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Implementasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Jawa dalam Strategi Antikorupsi
Nilai-nilai luhur budaya Jawa seperti rukun, gotong royong dan keselarasan sejak lama diajarkan lewat tradisi tutur dan petuah bijak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai inilah yang kemudian melahirkan konsep "memayu hayuning bawono" (memperindah dunia), yang intinya adalah bahwa manusia memiliki kewajiban untuk berperilaku baik agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Konsep serupa juga tertuang dalam idiom Jawa populer seperti "rukun agawe santosa, crah agawe bubrah" (kerukunan menciptakan kedamaian, perpecahan menciptakan kehancuran). Idiom ini secara tegas mengajarkan bahwa perilaku serakah, tamak dan saling menjatuhkan hanya akan merusak tatanan masyarakat.
Prinsip rukun dan gotong royong inilah yang kini mulai pudar dimakan zaman, seiring merebaknya perilaku koruptif di berbagai lini. Praktik KKN yang merajalela bak virus tanpa obat ini telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan melemahkan kemajemukan bangsa Indonesia yang dikenal ramah, santun dan penuh toleransi.
Oleh sebab itu, pendidikan budaya Jawa perlu dihidupkan kembali dan ditanamkan secara masif kepada generasi milenial dan Gen Z Indonesia agar perilaku antikorupsi dapat mengakar kuat. Strategi implementasinya adalah dengan memasukkan muatan pengenalan filosofi dan nilai-nilai luhur Jawa ke dalam kurikulum formal pendidikan di Indonesia, mulai dari SD hingga jenjang pendidikan tinggi.
Misalnya melalui mata pelajaran kewarganegaraan, muatan lokal bahasa Jawa, sosiologi, antropologi, hingga filsafat. Dengan mengenalkan nilai "memayu hayuning bawono" dan prinsip rukun sejak bangku sekolah, diharapkan terbentuk karakter generasi penerus bangsa yang paham bahwa korupsi itu perbuatan terkutuk yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain edukasi formal di sekolah, perlu ada usaha serupa dari para orang tua dan tokoh masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi macapatan dan petuah bijak para leluhur yang mengandung pesan moral. Misalnya teknik ngudarasa (bercerita) dan petuah "Aja Dumeh" yang sering dilakukan orang Jawa zaman dahulu untuk menyampaikan nasihat moral secara intergenerasi dalam lingkungan keluarga.

Singkatnya, pendekatan gabungan melalui penguatan pendidikan nilai budaya dan kearifan lokal serta penegakan hukum yang tegas tanpa toleransi merupakan kunci dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya dengan cara inilah praktik KKN yang sudah sistemik dapat mulai diberantas dan ditumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, modern dan makmur sesuai cita-cita pendiri bangsa.
Kesimpulan
Teori yang dicetuskan oleh Edwin Sutherland adalah teori belajar sosial yang menjelaskan bahwa perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena kejahatan korupsi di Indonesia, yang merupakan salah satu masalah besar yang merugikan negara dan masyarakat.
Fenomena kejahatan korupsi di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, antara lain:
(1) terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta;
(2) melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang, baik politik, birokrasi, bisnis, maupun masyarakat sipil;
(3) menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya;
(4) sulit untuk diberantas, karena adanya faktor sistem, budaya, dan mentalitas yang mendukung korupsi.
Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
(1) kesempatan, yaitu adanya celah dan kelemahan dalam sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum;
(2) keserakahan, yaitu adanya motif untuk memperoleh keuntungan, kekuasaan, status, dan pencitraan secara tidak sah;
(3) kebutuhan, yaitu adanya tekanan ekonomi, sosial, atau politik yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi;
(4) pengungkapan, yaitu adanya resiko dan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi jika tertangkap atau dilaporkan.

Warisan budaya dan kearifan lokal Indonesia seperti konsep Jawa "memayu hayuning bawana" dan "rukun agawe santosa" sesungguhnya sudah sejak lama mengajarkan prinsip keseimbangan dan antikorupsi. Sayangnya nilai-nilai luhur ini mulai memudar dimakan zaman, seiring merebaknya perilaku koruptif di tubuh birokrasi publik tanah air. Oleh sebab itu, penguatan kembali pendidikan budaya etis dan moral sejak dini dipandang perlu untuk membangun kembali karakter bangsa yang antikorupsi dan mencegah penyebaran perilaku koruptif lebih luas lagi ke generasi penerus bangsa.
Di samping penguatan pendidikan nilai budaya dan moralitas, instrumentasi hukum yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu juga mutlak diperlukan untuk memberantas praktik korupsi yang sudah sistemik dan meluas di negeri ini.
Komitmen nyata dan political will dari pemerintah dan pemimpin negara juga urgent diperlukan untuk mewujudkan tatanan birokrasi dan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Tanpa ada kemauan politik yang kuat dan konsisten untuk memberantas korupsi, maka perilaku koruptif akan sangat sulit diberantas mengingat sudah mengkristal dan membudaya.
Serta partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga aktivis antikorupsi diperlukan. Melalui aksi kolektif dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai moralitas ketimuran yang tinggi, praktik korupsi yang sudah sistemik dan massif tersebut dapat mulai ditangani dan diberantas.
Untuk mengatasi fenomena kejahatan korupsi di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif, koordinatif, dan konsisten dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, media, maupun masyarakat. Upaya tersebut meliputi:
(1) penguatan sistem hukum, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan, lembaga, dan aparatur yang berwenang dalam pemberantasan korupsi;
(2) perubahan budaya, yaitu menumbuhkan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
(3) pembinaan mentalitas, yaitu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang cenderung menerima, mendukung, atau melakukan korupsi;
(4) pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi, mengkritisi, dan melaporkan praktik-praktik korupsi.
Daftar Pustaka
Simanjuntak, B. A. (2021). Application of Edwin Sutherland differential association theory on
perpetrators of corruption in Indonesia. JCHJS, 6(2), 104-112.
Sutherland, E.H., Cressey, D.R. & Luckenbill, D.F. (1992). Principles of criminology.General Hall.
Wardani, P. I. (2013). Diskursus budaya Jawa dalam pembangunan karakter bangsa. Jurnal Ilmiah
CIVIS, 3(1), 1554-1565.
Adityo, R. K. (2021). Pola komunikasi antarkultur masyarakat Jawa. Channel Jurnal Komunikasi, 9(2),
43-52.
Aziz, A. (2019). Implementing Javanese Values Based on Local Wisdom to Prevent Corruption Behavior of
Government Apparatus. Jurnal Bawana, 12(1), 53-62.
Koentjaraningrat. (1990). Javanese Culture. Singapore: Oxford University Press
Lubis, M., & Scott, J. (1988). Javanese Culture and The Meanings of Locality: Some Recent Writing on
Indonesia. Asian Studies Review, 12(1), 49--59.
Pratikno. (2018). Membangun Kapasitas Antikorupsi dengan Pendekatan Nilai-Nilai Budaya dan
Kearifan Lokal di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 10(1), 13--24.
Saputra, W. (2019). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Kearifan Lokal Jawa: Telaah Atas Pemikiran
Nurcholish Madjid. Aksara, 29(2), 221-232