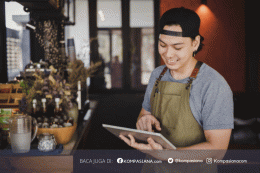UMK Naik, Tapi PHK Meningkat: Industri Kita Sakit?
Ironi ekonomi sedang terjadi.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik di berbagai daerah. Pemerintah daerah menepati janji: memperjuangkan upah layak bagi buruh. Namun, hampir bersamaan, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) justru ikut melonjak. Di sektor tekstil, sepatu, hingga elektronik ringan, pabrik-pabrik mengurangi tenaga kerja atau bahkan tutup total.
Pertanyaannya bukan hanya mengapa ini terjadi. Yang lebih penting: apa makna dari gejala ini bagi masa depan industri kita? Apakah kita sedang menyaksikan gejala sakit kronis dari industri nasional?
Sebagai ekonom industri yang sudah mengamati dinamika struktural sejak dekade 1980-an, saya melihat ini bukan sekadar kebetulan siklikal. Kita sedang menghadapi persoalan mendalam yang menuntut evaluasi ulang terhadap cara kita merancang hubungan antara buruh, pengusaha, dan negara.
Kenaikan UMK: Tujuan Mulia, Efek Samping Nyata
Tak ada yang salah dengan kenaikan upah minimum. Dalam banyak hal, ini adalah instrumen penting untuk menjamin daya beli, mengurangi kesenjangan, dan melindungi kelompok rentan. Namun, kenaikan UMK yang tidak diiringi peningkatan produktivitas akan membebani sektor industri padat karya secara langsung.
Sebagai ilustrasi, pada tahun 2025, UMK di sejumlah kawasan industri utama naik antara 7 hingga 11 persen. Namun dalam periode yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur hanya naik sekitar 2,5 persen, berdasarkan data Kementerian Perindustrian.
Artinya, beban biaya tenaga kerja naik lebih cepat daripada nilai tambah yang dihasilkan.
Efek Domino bagi Industri Padat Karya
Sektor yang paling terpukul tentu saja adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan mainan. Industri ini memang banyak menyerap tenaga kerja, tetapi margin keuntungannya sangat tipis dan sangat tergantung pada volume produksi besar dengan efisiensi tinggi.
Kenaikan UMK membuat struktur biaya menjadi lebih berat. Ketika perusahaan tak bisa menyesuaikan harga jual---karena pasar global tak bisa dipaksa mengikuti biaya dalam negeri---maka opsi yang tersisa adalah mengurangi pekerja, memotong shift, atau relokasi.
Hal inilah yang terjadi di Karawang, Majalengka, dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), lebih dari 47.000 pekerja terdampak PHK hanya dalam dua kuartal pertama tahun 2025.
Relokasi dan Deindustrialisasi Sunyi
Situasi ini mendorong gelombang relokasi diam-diam. Beberapa perusahaan tekstil dan alas kaki mulai memindahkan produksinya ke Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh---negara yang menawarkan upah lebih murah, insentif fiskal lebih kompetitif, dan regulasi yang relatif lebih stabil.
Fenomena ini bukan hanya soal kehilangan investasi, tapi juga gejala deindustrialisasi sunyi---di mana pabrik-pabrik pergi tanpa banyak pemberitaan, dan Indonesia semakin bergantung pada sektor informal, jasa rendah produktivitas, dan ekspor bahan mentah.
Pertanyaan Besar: Apakah Model Industri Kita Masih Relevan?
Dalam perspektif ekonomi industri, kita perlu jujur bertanya:
Apakah struktur industri kita saat ini masih cocok dengan tantangan zaman?
Kita masih terlalu bergantung pada industri padat karya berorientasi ekspor yang sangat sensitif terhadap fluktuasi upah dan nilai tukar. Padahal, ekonomi global kini bergerak ke arah industri berbasis inovasi, efisiensi energi, dan nilai tambah tinggi.
Sayangnya, investasi pada riset dan pengembangan masih minim. Pendidikan vokasi belum nyambung dengan kebutuhan industri baru. Dan insentif pemerintah masih cenderung menyamaratakan, tanpa membedakan sektor yang produktif dan yang stagnan.
Solusi: Keseimbangan Baru antara Upah dan Produktivitas
Bukan berarti UMK tak boleh naik. Tapi kenaikan upah harus sejalan dengan strategi peningkatan produktivitas dan efisiensi industri. Pemerintah harus mengarahkan investasi pada sektor dengan potensi naik kelas, bukan hanya mempertahankan sektor lama yang sudah kewalahan.
Selain itu, kita butuh reformasi sistem hubungan industrial:
- Upah berbasis kompetensi dan produktivitas
- Insentif bagi perusahaan yang menaikkan upah sekaligus menciptakan lapangan kerja
- Dana pelatihan dan reskilling bagi sektor yang terdampak disrupsi teknologi dan globalisasi
Penutup: Sakit atau Sedang Berkembang?
UMK naik, PHK meningkat. Ini bukan sekadar kontradiksi statistik. Ini gejala dari ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi kita. Jika tidak dikelola dengan cermat, kita bukan hanya kehilangan pabrik, tapi juga kehilangan arah pembangunan industri yang berkelanjutan.
Industri yang sehat bukan yang bertahan karena subsidi atau proteksi, tapi yang mampu tumbuh karena produktivitas dan inovasi.
Sudah saatnya kita bertanya:
Industri kita sakit... atau sedang menunggu resep baru untuk sembuh?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI