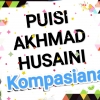Oleh: Imam Sahroni Darmawan, S.T
(Penulis, pegiat Desa, dan pemerhati politik hukum Indonesia)
“Di negeri ini, hukum bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal siapa yang punya kuasa, akses, dan uang.”
Ungkapan ini bukan hiperbola. Di tengah jargon negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), Indonesia justru menghadirkan paradoks: hukum melimpah ruah, namun keadilan sulit diraih. Rakyat kebingungan oleh tumpukan aturan yang tumpang tindih, sementara elite politik justru memanfaatkannya untuk mengkonsolidasikan kuasa.
Hukum Menumpuk, Kepastian Menguap
Menurut catatan BPHN (2023), Indonesia memiliki lebih dari 45.000 produk hukum aktif, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, hingga regulasi sektoral. Meski angka tersebut tidak dipublikasikan sebagai data resmi final, banyak pakar sepakat bahwa Indonesia mengalami regulatory hypertrophy, yaitu kelebihan aturan tanpa koordinasi yang efektif antar-lembaga dan level pemerintahan.
Laporan Bank Dunia (2023) menyebut bahwa Indonesia mengalami “overregulation with weak enforcement mechanisms,” yang memperbesar ketidakpastian hukum, memperumit dunia usaha, dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
Ketika Legislasi Dijadikan Arena Politik Kekuasaan
Masalah hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada kuantitas, tetapi juga pada proses lahirnya hukum. Revisi UU KPK (2019), yang memperlemah lembaga antirasuah, disahkan cepat tanpa proses deliberatif dan mengabaikan penolakan publik. Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, sebuah langkah yang langsung memuluskan pencalonan putra presiden.
Empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, termasuk Prof. Saldi Isra, yang menyebut putusan ini sebagai bentuk “penyelundupan Norma konstitusi.” Ketua MK saat itu, Anwar Usman, ipar Presiden, kemudian dijatuhi sanksi etik berat dan dicopot dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan MK pada 7 November 2023.
Meski demikian, putusan MK itu tetap berlaku karena bersifat final dan mengikat.
Ini adalah contoh telanjang dari judicial capture, ketika lembaga yudisial tidak lagi independen, tetapi menjadi perpanjangan kekuasaan.
Warga Kecil dan Jerat Pasal Karet
Ilustrasi dampak hukum tidak adil dapat ditemukan dalam kasus warga Desa Wadas, Purworejo (2022–2023). Puluhan warga ditangkap secara represif karena menolak tambang batu andesit untuk proyek bendungan Bener. Mereka hanya mempertahankan tanah dan ruang hidupnya, namun negara merespons dengan pasal-pasal pidana dan tindakan represif.
Kasus serupa terjadi di Rempang, Kepulauan Riau, ketika warga menolak penggusuran paksa untuk pembangunan kawasan Rempang Eco-City. Data dari berbagai lembaga advokasi seperti YLBHI dan Walhi menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan terus meningkat.
Menurut estimasi laporan YLBHI (2023), terdapat lebih dari 170 kasus kriminalisasi terhadap petani, aktivis, jurnalis, dan masyarakat adat. Modusnya berulang: penggunaan pasal-pasal karet seperti UU ITE, UU Minerba, hingga pasal perusakan dalam KUHP.
Indonesia dalam Rule of Law Index
Laporan World Justice Project Rule of Law Index 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 142 negara, dengan skor keseluruhan 0,53. Skor ini stagnan sejak 2015, dan tergolong rendah dalam indikator:
- Absence of Corruption: 0,42
- Civil Justice: 0,44
- Judicial Constraints on Government Powers: 0,46
Artinya, Indonesia lemah dalam hal pemberantasan korupsi, independensi lembaga hukum, dan akses masyarakat terhadap keadilan.
Jalan Keluar: Bukan Tambah Aturan, Tapi Tambah Keberanian
Reformasi hukum harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar merapikan tumpukan aturan. Beberapa langkah transformatif yang layak dipertimbangkan:
1. Regulatory Guillotine
Model Korea Selatan dan Georgia: merevisi dan menghapus ribuan regulasi usang dengan membentuk regulatory review unit independen yang terlibat bersama akademisi dan masyarakat sipil.
2. Legislasi Terbuka untuk Rakyat
Terapkan platform legislative feedback daring, di mana RUU yang akan dibahas wajib dibuka untuk komentar publik minimal 30 hari. Negara-negara seperti Finlandia dan Kanada sudah melakukannya dengan sukses.
3. Reformasi Mahkamah Konstitusi
Batasi masa jabatan hakim MK, larang afiliasi politik langsung, dan gunakan seleksi terbuka berbasis meritokrasi akademik.
4. Legal Tech untuk Rakyat
Bangun layanan hukum berbasis AI dan bahasa lokal, seperti chatbot hukum gratis untuk masyarakat desa agar mereka tahu hak-haknya dan bisa mengakses bantuan hukum dasar. India telah memulainya sejak 2022.
Hukum Harus Melindungi, Bukan Menindas
Indonesia tidak kekurangan aturan, yang kita kekurangan adalah keberanian moral untuk menegakkan hukum secara adil. Jika hukum hanya berfungsi untuk melindungi elite dan menindas rakyat kecil, maka “negara hukum” tinggal slogan kosong.
Keadilan yang tidak merata bukanlah keadilan. Dan hukum yang tidak membela yang lemah, hanyalah alat kekuasaan.
Catatan:
Tulisan ini berdasarkan data hingga pertengahan 2024. Semua informasi dapat ditelusuri melalui dokumen resmi BPHN, putusan Mahkamah Konstitusi, World Justice Project, laporan YLBHI, dan arsip media nasional.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI