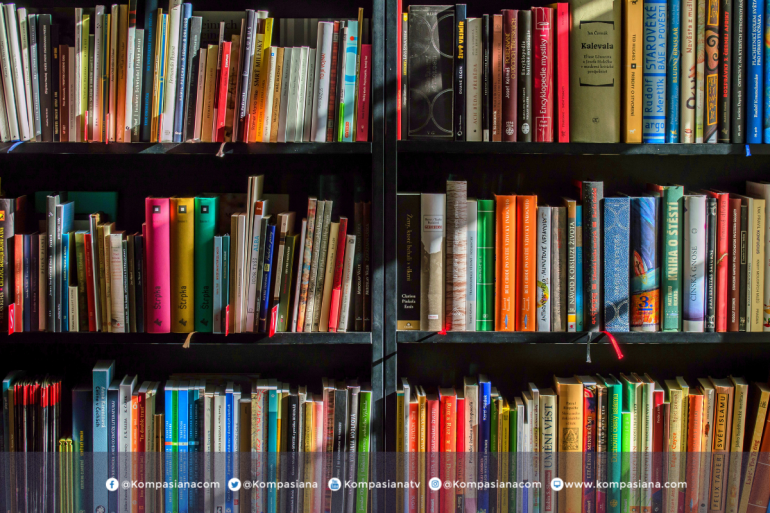Di era digital saat ini, kita hidup di tengah arus informasi yang deras, cepat, dan sering kali membingungkan. Timeline media sosial menjadi ruang di mana setiap orang bisa berbicara, berkomentar, bahkan menghakimi. Fenomena seperti cancel culture, fear of missing out (FOMO), doomscrolling, hingga kelelahan digital sudah menjadi bagian dari keseharian banyak anak muda, termasuk mahasiswa seperti saya.
Dalam situasi ini, muncul satu pertanyaan sederhana namun penting: bagaimana cara kita tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa arus emosi di tengah kebisingan digital?
Jawabannya, bagi saya, temen-temen bisa ditemukan melalui buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring --- sebuah karya populer yang memperkenalkan kembali ajaran Stoikisme, atau dalam bahasa sederhananya: filsafat hidup tenang dan rasional.
Stoikisme: Filsafat yang Kembali Relevan
Stoikisme lahir di Yunani sekitar abad ke-3 SM dan dikembangkan oleh tokoh seperti Zeno, Seneca, dan Marcus Aurelius. Tapi menariknya, filosofi kuno ini justru sangat relevan di zaman modern --- terutama dalam menghadapi tekanan hidup, overthinking, dan kegelisahan sosial akibat teknologi.
Henry Manampiring dalam bukunya menulis:
"Stoisisme mengajarkan bahwa kita hanya perlu memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan tidak perlu cemas berlebihan terhadap hal-hal di luar kendali kita."
(Manampiring, 2018, hlm. 25)
Kalimat itu sederhana, tapi menjadi semacam wake-up call bagi saya pribadi. Karena dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial, kita justru sering memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan: komentar orang lain, jumlah likes, citra digital, atau gosip viral yang bahkan tak ada hubungannya dengan diri kita.
Fenomena "Kelelahan Digital" dan Krisis Emosi Kolektif
Fenomena yang paling terasa di kalangan mahasiswa hari ini adalah digital fatigue atau kelelahan digital. Aktivitas akademik dan sosial kini nyaris sepenuhnya bergantung pada layar --- Zoom, WhatsApp, Instagram, TikTok, hingga forum kampus daring.
Kita berpindah dari satu tab ke tab lain tanpa sadar bahwa otak sedang bekerja keras untuk menanggapi begitu banyak stimulus sekaligus. Akibatnya, emosi cepat naik, konsentrasi menurun, dan rasa cemas meningkat.
Data dari We Are Social (2024) menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di depan layar, dan lebih dari separuhnya merasa "lelah secara mental" akibat paparan media sosial berlebihan.
Dalam konteks ini, Stoikisme bisa menjadi obat kesadaran --- semacam "vitamin mental" yang menolong kita untuk mengambil jarak dari hiruk-pikuk digital.
Mengendalikan Apa yang Bisa Dikuasai
Salah satu prinsip dasar Stoikisme adalah Dikotomi Kendali (The Dichotomy of Control). Henry Manampiring mengutip ajaran Epictetus:
"Sebagian hal berada dalam kendali kita, sebagian lagi tidak. Jika kita fokus pada hal yang berada di luar kendali, kita akan menjadi budak kehidupan."
(Manampiring, 2018, hlm. 42)
Jika diterjemahkan ke kehidupan digital, maknanya sangat dalam:
Kita tidak bisa mengontrol opini publik, tidak bisa mencegah semua orang menilai kita, atau mengatur algoritma media sosial. Tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap semua itu.
Misalnya, ketika seseorang mengomentari unggahan kita dengan nada sinis, kita bisa:
membalas dengan tenang,
mengabaikan,
atau sekadar tersenyum lalu lanjut hidup.
Reaksi yang kita pilih itulah yang menentukan kualitas batin kita --- bukan situasi eksternalnya.
Stoikisme tidak mengajarkan untuk "menyerah", melainkan untuk bijak memilih pertempuran batin: mana yang pantas diperjuangkan, dan mana yang lebih baik dilepaskan.
Fenomena Overthinking dan Validasi Digital
Sebagai mahasiswa komunikasi, saya banyak mengamati bagaimana media sosial membentuk budaya validasi. Kita hidup di zaman ketika "aku ada karena aku dilihat". Banyak teman sebaya yang merasa nilainya ditentukan oleh seberapa sering mereka muncul di Instagram atau seberapa menarik tampilan feed-nya.
Hal ini menciptakan pola pikir external validation --- ketergantungan pada pengakuan dari luar diri.
Padahal, seperti kata Marcus Aurelius yang dikutip Manampiring:
"Ketenangan datang ketika kita berhenti berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan orang lain, dan mulai memperhatikan apa yang seharusnya kita lakukan sendiri."
(Manampiring, 2018, hlm. 77)
Stoikisme mengajarkan self-validation --- kemampuan untuk menilai diri berdasarkan nilai dan prinsip pribadi, bukan berdasarkan jumlah pengikut atau komentar.
Fenomena anxiety dan burnout di media sosial bisa dikurangi jika kita belajar, seperti para Stoik, untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada hal yang tidak pasti.
Ketika Komentar Menjadi Luka: Belajar Emosi dari Stoik
Henry Manampiring mengingatkan bahwa Stoikisme bukan tentang menekan emosi, tapi mengelola emosi agar tidak memperbudak akal.
"Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan opini kita tentang peristiwa itu."
--- Epictetus, dikutip dalam Filosofi Teras (Manampiring, 2018, hlm. 84)
Artinya, komentar buruk di internet tidak akan melukai kita jika kita tidak memberi makna negatif padanya. Luka itu datang bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari cara kita menafsirkannya.
Di sinilah relevansi besar Stoikisme di era media sosial:
Ketika ruang digital menjadi tempat pertarungan opini dan emosi, kemampuan untuk "mengambil jeda" sebelum bereaksi menjadi bentuk kebijaksanaan baru.
Sebagai mahasiswa komunikasi, saya belajar bahwa komunikasi sejati tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tapi juga tentang mengatur respon terhadap pesan yang datang. Ini sejalan dengan prinsip Stoik bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri kita.
"Meng-ghosting" Masalah
Dalam buku Filosofi Teras, Henry juga menulis bahwa ketenangan batin tidak datang dari menghindari masalah, melainkan dari sikap terhadap masalah.
Sering kali, ketika menghadapi tekanan akademik, tugas bertumpuk, atau konflik sosial, kita justru memperpanjang penderitaan dengan pikiran yang berputar-putar: "Kenapa aku gagal?", "Kenapa dosen tidak suka aku?", "Kenapa mereka lebih sukses?"
Padahal, seperti dijelaskan dalam Filosofi Teras, kebahagiaan sejati justru datang dari kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, dan berfokus memperbaiki hal-hal yang bisa diusahakan.
"Kebahagiaan sejati bukan karena keadaan baik, tapi karena sikap yang baik terhadap keadaan."
(Manampiring, 2018, hlm. 106)
Fenomena Cancel Culture dan Stoikisme
Fenomena cancel culture di media sosial menunjukkan bagaimana opini publik bisa berubah menjadi amarah massal. Sekali seseorang melakukan kesalahan, netizen seolah berlomba menghukum tanpa ampun.
Dalam perspektif Stoikisme, ini memperlihatkan bagaimana emosi kolektif yang tak terkendali bisa merusak kebijaksanaan sosial.
Marcus Aurelius pernah menulis:
"Jika seseorang berbuat salah, itu karena ia tidak tahu lebih baik. Maafkan dan bantu ia belajar."
(Manampiring, 2018, hlm. 89)
Pesan ini relevan sekali. Alih-alih ikut terbawa arus menghujat, kita bisa memilih sikap tenang, reflektif, dan empatik. Komunikasi publik yang sehat tidak dibangun dari reaksi emosional, tetapi dari kesadaran bahwa manusia bisa belajar dari kesalahan.
Mahasiswa dan Tantangan Eksistensi
Sebagai mahasiswa, kita berada di tahap hidup yang penuh perubahan: mencari jati diri, masa depan, dan makna. Tekanan akademik, ekonomi, dan sosial sering kali memunculkan krisis eksistensi --- apakah aku cukup? apakah aku di jalur yang benar?
Stoikisme memberikan perspektif menenangkan:
"Jangan berharap hidup menjadi lebih mudah; berharaplah agar kamu menjadi lebih kuat."
(Manampiring, 2018, hlm. 93)
Filosofi ini menegaskan bahwa penderitaan tidak harus dihindari, tapi bisa dijadikan latihan mental untuk memperkuat karakter.
Dalam konteks komunikasi, hal ini mirip dengan kemampuan self-presentation dan resilience --- dua keterampilan penting di era digital yang penuh tekanan sosial. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter sejati diuji bukan ketika segalanya lancar, tapi ketika kita tetap tenang saat badai datang.
Relevansi untuk Komunikasi Digital
Menariknya, prinsip Stoikisme bisa diterapkan dalam teori komunikasi modern, terutama dalam pengelolaan pesan dan noise (gangguan komunikasi).
Dalam media sosial, noise bukan hanya sinyal yang buruk, tapi juga opini yang salah, emosi yang meluap, atau distorsi makna. Seorang Stoik akan memilih untuk:
memilah informasi yang perlu direspons,
tidak tergesa-gesa beropini,
dan menjaga tone komunikasi tetap rasional dan empatik.
Sikap ini sangat penting di tengah budaya komunikasi yang cepat dan impulsif.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI