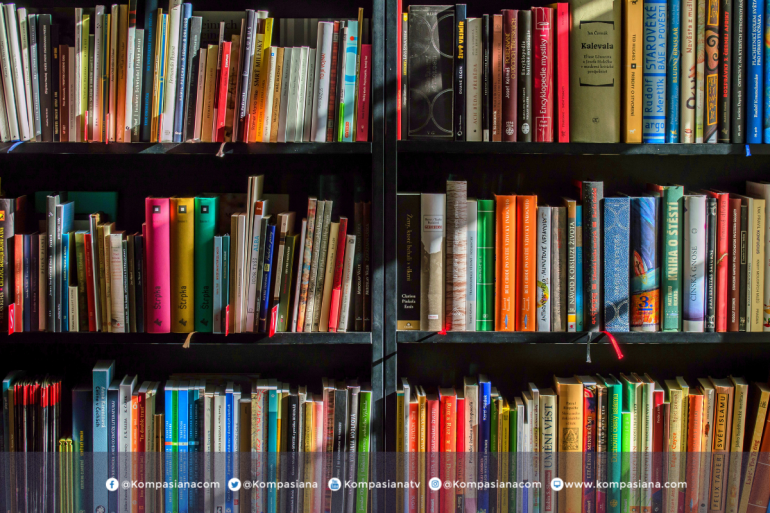Artinya, komentar buruk di internet tidak akan melukai kita jika kita tidak memberi makna negatif padanya. Luka itu datang bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari cara kita menafsirkannya.
Di sinilah relevansi besar Stoikisme di era media sosial:
Ketika ruang digital menjadi tempat pertarungan opini dan emosi, kemampuan untuk "mengambil jeda" sebelum bereaksi menjadi bentuk kebijaksanaan baru.
Sebagai mahasiswa komunikasi, saya belajar bahwa komunikasi sejati tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tapi juga tentang mengatur respon terhadap pesan yang datang. Ini sejalan dengan prinsip Stoik bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri kita.
"Meng-ghosting" Masalah
Dalam buku Filosofi Teras, Henry juga menulis bahwa ketenangan batin tidak datang dari menghindari masalah, melainkan dari sikap terhadap masalah.
Sering kali, ketika menghadapi tekanan akademik, tugas bertumpuk, atau konflik sosial, kita justru memperpanjang penderitaan dengan pikiran yang berputar-putar: "Kenapa aku gagal?", "Kenapa dosen tidak suka aku?", "Kenapa mereka lebih sukses?"
Padahal, seperti dijelaskan dalam Filosofi Teras, kebahagiaan sejati justru datang dari kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, dan berfokus memperbaiki hal-hal yang bisa diusahakan.
"Kebahagiaan sejati bukan karena keadaan baik, tapi karena sikap yang baik terhadap keadaan."
(Manampiring, 2018, hlm. 106)
Fenomena Cancel Culture dan Stoikisme
Fenomena cancel culture di media sosial menunjukkan bagaimana opini publik bisa berubah menjadi amarah massal. Sekali seseorang melakukan kesalahan, netizen seolah berlomba menghukum tanpa ampun.
Dalam perspektif Stoikisme, ini memperlihatkan bagaimana emosi kolektif yang tak terkendali bisa merusak kebijaksanaan sosial.