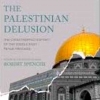Mungkin kita tidak asing dengan kalimat berikut “Kakak, kamu harus mengalah dengan adik ya. Kakak ‘kan sudah besar, adiknya masih kecil” atau “Kakak, kamu harus bisa bantu Papa dan Mama untuk mengajari adikmu ya.” Kedua kalimat tersebut terdengar sederhana. Namun, bagi banyak anak perempuan tertua, itu adalah mantera yang secara akumulatif membentuk watak, juga beban hidup mereka. Sebuah fenomena yang mungkin belum sepenuhnya didiagnosa secara medis, tapi hal tesebut membekas dalam jejak psikologis seumur hidup bagi mereka anak perempuan tertua dalam relasi bersaudara sebuah keluarga.
Di banyak rumah tangga, sosok anak pertama sering dianggap sebagai simbol kebanggaan orang tua. Jika anak pertama itu perempuan, maka statusnya menjadi lapisan yang lebih kompleks: ia diharapkan kuat seperti ayah, penyayang seperti ibu, dan sekaligus menjadi teladan bagi semua adik. Harapan itu datang tanpa jeda. Bahkan sejak kecil, ia jarang ditanya, “Apakah kamu siap menjadi Kakak?”
Dalam praktiknya, banyak anak perempuan sulung menjadi “tulang punggung emosional” keluarga. Ia dituntut memahami konflik orang tua tanpa pernah dijelaskan. Ia disuruh menjaga adik tanpa tahu cara mengasuh. Ia diajarkan sabar, tapi jarang diberi ruang marah. Perlahan, Ia dibentuk menjadi figur penjaga stabilitas, tanpa pernah benar-benar mendapat jaminan stabilitas untuk dirinya sendiri.
Fenomena ini sering dikenal sebagai eldest daughter syndrome. Walau tidak diklasifikasikan sebagai gangguan mental dalam DSM-5, gejalanya tercermin dalam berbagai penelitian psikologi keluarga. Salah satu konsep paling relevan adalah parentifikasi, yakni ketika anak harus menjalankan peran orang tua dalam hubungan keluarga. Dalam konteks budaya Asia, beban ini seringkali lebih berat ditanggung oleh anak perempuan tertua karena peran gender yang dilekatkan sejak dini.
Situasi ini diperkuat oleh ekspektasi masyarakat yang cenderung mengidealkan anak sulung sebagai anak “yang paling tahu diri”. Ketika berhasil, keberhasilannya dianggap “sudah seharusnya”. Namun, ketika gagal, ia jadi sorotan. Anak pertama perempuan jarang diberi ruang untuk takut, ragu, atau salah arah—karena keluarga dan lingkungan terlalu sering melihatnya sebagai figur yang sudah dewasa, bahkan ketika usianya masih belasan.
Hal ini pun dapat berdampak pada pembentukan identitas dan pola relasi sosial di usia dewasa. Banyak perempuan yang dibesarkan sebagai anak tertua yang mungkin kita kenal mengalami kesulitan meminta tolong, karena terbiasa memberi dan melayani. Beberapa menjadi pribadi perfeksionis yang tidak pernah puas dengan diri sendiri. Yang lain memendam rasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain, meski itu mengorbankan kebahagiaannya sendiri.
Di ruang keluarga, sosok anak perempuan tertua seringkali diandalkan. Di ruang sosial, Ia dikagumi. Tapi, di ruang batinnya, Ia pun dapat merasa sangat sepi. Siapa yang menguatkan saat Ia runtuh? Siapa yang mendengarkan ketika Ia tidak ingin menjadi kuat? Menjadi anak perempuan tertua adalah perjalanan sunyi. Di balik pencapaian dan kedewasaannya, ada sisi yang sering tidak dilihat: seseorang yang mungkin sedang menunggu dipeluk, bukan dipuji. Yang ingin dimengerti, bukan hanya diminta mengerti.
Tidak sedikit juga anak perempuan pertama sudah diberikan tanggung jawab mengasuh adiknya bahkan sebelum sang Kakak bisa menyisir rambutnya dengan rapi ataupun mengikat tali sepatunya sendiri. Kedua orang tua mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memperhatikan adiknya. Maka, Sang Kakak harus bisa ‘mengisi’ peran tersebut. Ia menjadi miniatur orang tuanya sebelum waktunya. Sang Kakak belajar memandikan adiknya, menenangkan adiknya saat adiknya menangis, dan berusaha mengalah saat adiknya memaksakan kehendak sang adik saat bermain bersama. Semua ini dilakukannya bukan karena peran yang dipilih oleh sang Kakak, melainkan diturunkan secara kultural melalui generasi. Dalam situasi ini, sang Kakak pun menerapkan parentifikasi. Hooper (2007) menjelaskan bahwa parentifikasi ini, jika berlebihan, dapat menimbulkan gangguan fungsi emosi dan identitas diri pada usia dewasa. Jurkovic (1997) juga mencatat bahwa anak-anak yang mengalami parentifikasi kronis cenderung memendam rasa bersalah, takut gagal, dan kehilangan kepercayaan terhadap kebutuhan pribadi.
Namun, peran sebagai “pengganti orang tua” ini bukan hanya memengaruhi cara mereka bersikap dan bertindak di rumah, melainkan juga membentuk cara berpikir dan merasa mereka dalam jangka panjang. Anak perempuan tertua perlahan belajar bahwa eksistensinya dihargai karena kemampuan mengurus, mengalah, dan menyesuaikan dirinya—bukan karena siapa dirinya sebenarnya. Dari sinilah tekanan psikologis mulai tumbuh, bukan sebagai ledakan besar, tetapi sebagai retakan-retakan halus yang lama-lama menggerogoti harga diri.
Tidak sedikit anak perempuan tertua merasa harus menjadi figur sempurna: berprestasi di sekolah, sabar di rumah, kuat di luar, dan lembut di dalam. Ketika adiknya gagal, Sang Kakak pun dibebani pertanyaan kenapa adiknya tidak dijaga. Ketika keluarganya goyah, Ia pun diminta menjadi “lem perekat”. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Paulhus et al. (1999) menunjukkan bahwa anak sulung, terutama perempuan, cenderung mengalami tingkat perfectionisme, kecemasan, dan tekanan sosial yang lebih tinggi dibanding saudara kandung lainnya. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi sosial untuk menjadi teladan dan simbol kehormatan keluarga. Hal senada juga dipertegas oleh Frank Sulloway dalam bukunya Born to Rebel (1996) yang menyebutkan bahwa anak pertama biasanya lebih konservatif, patuh pada otoritas, dan sering kali menjadi “penjaga warisan nilai keluarga”. Namun, pada anak perempuan, fungsi ini sering disandingkan dengan tekanan emosiaonal untuk tetap tampil lembut dan penyayang, menciptakan ketegangan psikologis yang tidak kecil.
Jarang dipertanyakan kepada anak perempuan tertua “Apakah kamu bahagia, Kak?” Anak perempuan tertua sejatinya adalah tempat semua orang bertumpu. Ketika adik-adiknya stres, ia menjadi tempat curhat. Ketika orang tua kesulitan dalam relasi keduanya maupun dalam mengawasi adiknya, Ia pun dipanggil. Tapi, ketika Ia sendiri lelah, jarang ada ruang aman baginya untuk beristirahat atau bahkan menangis.