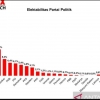Satu minggu yang lalu, halaman media massa dihiasi oleh pemberitaan tentang protes dan pemecatan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir. Pemecatan diawali dari aksi protes yang dilakukan oleh seratusan tenaga medis dengan tuntutan untuk memperbaiki taraf hidup dan kondisi kerja mereka. Pemerintah daerah kemudian menjawab demonstrasi ini dengan pemecatan. Terlepas dari kebenaran maksud protes yang dilakukan oleh seratusan tenaga kerja itu, saya memandang pemecatan dari pemerintah daerah merupakan contoh menarik dari tren kegagalan demonstrasi di Indonesia. Dengan demikian, sangat menarik untuk menelusuri akar permasalahan kegagalan demonstrasi sepanjang sejarah kita menggunakan pendekatan humaniora.
Tahun 2019, terjadi pula gelombang demonstrasi besar-besaran mahasiswa dari sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Tuntutan yang pada saat itu dibawa adalah pembatalan dan pengkajian kembali berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai sarat kepentingan-kepentingan tertentu –seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan lainnya.
Demonstrasi tersebut juga tidak dapat dinilai berhasil karena tuntutan yang pernah dibawa mahasiswa kemudian tidak sepenuhnya dipertimbangkan. Sepanjang jalan sejarah, kita juga melihat demonstrasi-demonstrasi lain yang pada akhirnya serupa dengan suatu pergelaran jalanan yang tidak pernah sampai ke dalam kaukus atau rapat administrator negara. Lalu, apa yang menjadi sebab kegagalan demonstrasi dalam sejarah kita?
Saya menduga sedikitnya ada dua jawaban yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, manusia Indonesia memahami demonstrasi sebagai sebuah ritus atau ritual dalam demokrasi. Kedua, adanya satu aspek pola pemikiran kapitalis yang telah merasuk ke dalam alam pikiran kita. Keduanya bukan merupakan satu-satunya bentuk faktor, melainkan dua komponen faktor yang dapat jadi bersilang ruwet dengan faktor yang lain.
Sekalipun Indonesia tidak pernah secara eksplisit mengadopsi paham konfusianisme, pemahaman mengenai pemikiran ini akan sangat berguna untuk menjelaskan faktor pertama. Konfusius dalam analek-analeknya beberapa kali mengungkapkan tentang pentingnya ritus atau ritual dalam bernegara. Ciri yang menonjol dari ritus yang dimaksudkan olehnya adalah adanya peran dan fungsi dari setiap orang.
Dalam suatu ritual pernikahan misalnya, terdapat seorang pria akan berperan sebagai mempelai yang berfungsi menerima mempelai perempuan dari keluarganya. Demikian pula, semua orang dalam sebuah ritual memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemain musik, penyaji makanan, petugas petasan, dan lainnya.
Mereka juga kemudian memiliki fungsi masing-masing untuk memetik gitar, meletakkan piring, dan lainnya. Negara berjalan dengan suatu skema yang sama. Raja berperan sebagai raja dan berfungsi mengatur jalannya negeri, menteri sebagai menteri dan lain sebagainya.
Setelah melihat pemaparan ini, tampak bahwa ritus atau ritual dalam penataan kenegaraan sebenarnya merupakan konsep yang tidak khas pada konfusianisme semata. Ciri tersebut merupakan ciri umum dari birokrasi yang efisien dan seharusnya dijalankan di suatu administrasi negara. Salah satu contoh sistem birokrasi yang menjalankan ‘ritus’ semacam ini adalah birokrasi kolonial Hindia Belanda di bawah naungan Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
Kini, kita harus beralih pada praktik protes atau demonstrasi di dalam sistem ‘ritus’ yang saya jelaskan di atas. Konfusius mengeksplisitkan bahwa protes merupakan suatu aksi yang dilakukan dengan menghentikan peran dan fungsi secara sengaja. Umumnya, hal ini dilakukan oleh sarjana-sarjana atau kelompok terpelajar konfusian yang pergi ke istana kerajaan dari ‘universitas’ mereka –meninggalkan kelas mereka, menghentikan fungsi mereka untuk belajar, dan menyuarakan protes di depan dewan raja.
Namun, syarat dilakukannya protes adalah adanya disfungsi peran dari suatu anggota administrasi. Dengan demikian, protes misalnya dilakukan kepada raja yang tidak menjalankan peran dan fungsi sebagai raja, ayah yang tidak menjalankan peran dan fungsi sebagai ayah, dan disfungsi yang lain.
Raja, ayah, atasan di perusahaan, senior, dan peran-peran lain yang terlihat superior di mata paham konfusianisme sesungguhnya tidak sepenuhnya superior. Mereka menjadi superior bila mereka menjalankan peran dan fungsi dengan baik dan menjunjung nilai konfusianisme dengan baik (kebaikan, kejujuran, dan lainnya).
Aksi protes dengan pola seperti ini sesunguhnya tidak endemik di Cina atau negeri-negeri konfusianis. Jawa Mataraman misalnya, juga memiliki aksi protes serupa yang disebut pepe (tapa pepe) atau menjemur diri. Skema yang ditunjukkan oleh aksi pepe sangat mirip sifatnya dengan protes sarjana konfusianis di Cina dan Semenanjung Korea.
Apa hubungan pola ini dengan demonstrasi yang ada di Indonesia? Saya bukan merupakan sarjana demokrasi sehingga tidak dapat menyatakan apakah praktik yang akan saya jelaskan di bawah dibenarkan di dalam demokrasi. Namun, kita dapat melihat bahwa administrator negara dan masyarakat pada umumnya menganggap aksi protes dan demonstrasi sebagai ritual atau ritus rutin dari demokrasi. Anggapan ini adalah esensi dari kegagalan aksi-aksi tersebut.
Berlainan dengan praktik demokrasi kita masa kini, konfusianisme dan pola birokrasi tradisional Jawa tidak menganggap bahwa aksi protes adalah sebuah ritus atau ritual. Aksi protes adalah bentuk mogoknya ritus. Dengan demikian, ketika aksi protes mengemuka, semua mata akan tertuju pada aksi protes tersebut dan mempertimbangkannya dengan serius karena semua orang ingin kembali kepada rutinitas ‘ritual’ kenegaraan.
Namun demikian, Indonesia masa kini tidak menganggap aksi protes sebagai sebuah anomali, tetapi justru sebagai sebuah rutinitas. Pada akhirnya, daya tekan aksi protes akan luntur menjadi suatu rutinitas belaka. Kita dapat melihat kecenderungan untuk memandang protes sebagai suatu ‘hal biasa’ atau ‘hal rutin’ pada pernyataan administrator-administrator negara.
Misalnya, Menteri Hukum dan HAM Mahfud M. D. yang sempat berkomentar bahwa protes terhadap penegakan hukum selalu terjadi sepanjang sejarah kita. Terdapat indikasi bahwa protes tersebut merupakan ‘hal biasa yang rutin’. Untuk faktor pertama ini, kita mungkin harus berefleksi kepada kenyataan tata kenegaraan konfusianis, Hindia Belanda, atau Jawa Mataraman.
Faktor kedua yang melemahkan daya tekan aksi protes adalah adanya pemikiran kapitalisme yang menganggap manusia sebagai tenaga kerja dan tenaga kerja sebagai komoditas. Bagaimana ini dapat berkaitan dengan aksi protes? Pertama-tama, pemikiran bahwa tenaga kerja merupakan komoditas telah meninggalkan nasib tenaga kerja pada mekanisme pasar.
Hal ini menyebabkan manusia satu dan manusia lain dalam peran dan fungsinya dapat digantikan (replaceable). Pemikiran ini pada akhirnya menjelma tidak hanya khas pada kasus tenaga kerja, tetapi pada semua individu. Kita mungkin harus bercermin pada pernyataan Bupati Ogan Ilir yang mengungkapkan bahwa ia dapat ‘mengganti’ semua tenaga medis yang protes dan dipecat.
Pada kasus protes mahasiswa, administrator negara mungkin akan berpikir bahwa generasi akan berganti dan protes akan mereda –karena mahasiswa juga pada akhirnya menjadi secara alamiah dapat tergantikan (replacable) oleh generasi-generasi yang baru. Pemikiran kapitalis ini menaruh sedikit sekali simpati pada kekhasan manusia.
Dengan skema itu, tindakan lanjutan dari sebuah aksi protes adalah penggantian, bukan lagi restrukturisasi, ruang dialog, atau perbaikan internal. Semua orang dipandang akan dapat digantikan. Bila kita memandang dari sisi sebaliknya, keadaan ‘harus dapat digantikan’ ini memang sangat perlu untuk menjaga kesehatan sistem ekonomi dan politik –atau dalam skala kecil kesehatan sistem ekonomi bisnis misalnya.
Kita tentu akan kerepotan bila terdapat satu tenaga kerja di dalam perusahaan kita yang memiliki suatu keahlian yang sangat khas dan tidak dapat digantikan. Namun demikian, keunikan dan kekhususan merupakan ciri khas manusia. Dengan demikian, kita terjebak untuk mempertahankan kesehatan sistem tersebut –yang dengan tidak langsung juga menyingkirkan kesehatan kemanusiaan kita.
Terdapat banyak masalah yang sudah dan akan timbul dari adanya pemikiran kapitalistik tentang manusia sebagai komoditas. Salah satu yang paling prominen adalah lemahnya daya tekan aksi protes. Tidak hanya demonstrasi di jalan, aksi protes kecil pada atasan kerja kita dalam skema kapitalistik ini juga pada akhirnya menyebabkan kita tidak memiliki kuasa.
Ketiadaan kuasa ini tidak dapat diatasi dengan cepat semata-mata melalui gagasan Foucault untuk memberikan akses pengetahuan agar tercipta relasi kuasa yang lebih sehat. Orang-orang yang secara hierarkis lebih inferior terancam keamanan kerjanya di dalam suatu perusahaan –bila sistem merasa mereka tidak kondusif, mereka dapat kapan saja digantikan oleh tenaga kerja baru dari pasar komoditas.
Penindasan kemudian ada sebagai konsekuensi dari sistem. Lebih lagi, Indonesia sedang memasuki suatu masa yang disebut surplus atau bonus demografi. Membeludaknya jumlah angkatan kerja tersebut terjadi bersamaan dengan krisis terbesar pertama pada abad ke-21 –pandemi virus COVID-19. Pasar komoditas tenaga kerja akan semakin kompetitif dan keamanan kerja akan terus mengalami ujian.
Dengan demikian, untuk menjaga kesehatan kemanusiaan, kita perlu memikirkan ulang tatanan administrasi, birokrasi, kenegaraan, dan sistem ekonomi kita dengan mempertimbangkan atau melibatkan ilmu-ilmu humaniora. Melakukan penataan ulang sistem tidak secara drastis harus mengubah sistem demokrasi atau kapitalisme, tetapi justru memolesnya dengan sentuhan yang lebih humanis.
Perkembangan manusia hingga titik ini telah menunjukkan suatu upaya dehumanisasi yang sangat hebat. Pada masa ini, peradaban kita memiliki kepentingan untuk menengok ke sejarah, lebih daripada masa-masa yang lain.
Daftar Sumber
Brown, Ian. 1997. Economic Change in Southeast Asia c. 1830—1980. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Confucius. 2013. Complete Works of Confucius. London: Minerva.
Duyvendak, J. J. L. 1947. Wegen en Gestalten der Chineesche Geschiedenis. Amsterdam: Elsevier.
Preger, W. 1944. Dutch Administration in the Netherlands Indies. Melbourne: F. W. Cheshire.
Spence, Jonathan D. 1991. The Search for Modern China. London: W. W. Norton & Company.
Vlekke, Bernard H. M. 2016. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG.
Yokohawa, Nobuharu; Ghosh, Jayati; dan Rowthorn, Bob. 2013. Industrialization of China and India: Their Impacts on the World Economy. London: Routledge.
Penulis
Christopher Reinhart adalah peneliti bidang sejarah kuno dan sejarah kolonial wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Sejak tahun 2019, menjadi asisten peneliti Prof. Gregor Benton pada School of History, Archaeology, and Religion, Cardiff University. Sejak tahun 2020, menjadi asisten peneliti Prof. Peter Carey. Dapat dihubungi melalui surel: a.ch.reinhart@gmail.com