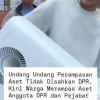"Tuhan tidak lelah mengampuni; kitalah yang lelah meminta maaf."-Paus Fransiskus, Misericordiae Vultus (2015).
Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia yang lahir dari rahim Amerika Selatan, menghembuskan napas terakhirnya pada pagi 21 April 2025, meninggalkan jejak spiritual yang dalam di tengah konflik kemanusiaan global.
Kematiannya pada pukul 07.35 waktu Roma bukan hanya akhir dari kepemimpinan seorang tokoh religius, tetapi juga penutup babak perlawanan terhadap ketidakadilan--khususnya dalam konflik Israel-Palestina yang telah menelan puluhan ribu nyawa.
Sebagai paus pertama dari Dunia Ketiga, Fransiskus tidak hanya mereformasi wajah Vatikan, tetapi juga menjadi suara bagi kaum miskin, migran, dan lingkungan hidup--sebuah komitmen yang menggetarkan kekuasaan sekaligus menginspirasi gerakan keadilan global.
Ia meninggal di Vatikan, dikelilingi oleh doa umat dari berbagai penjuru dunia, termasuk mereka yang tertindas dan tercerabut dari hak-haknya--seperti rakyat Palestina, yang selama ini ia bela dengan suara kenabiannya.
Spiritualitas Kerendahan Hati dan Perlawanan terhadap Ketimpangan
Lahir sebagai Jorge Mario Bergoglio (17 Desember 1936), ia memilih jalan pelayanan sebagai Jesuit sebelum terpilih sebagai Paus pertama dari Ordo tersebut pada 2013.
Kepemimpinannya ditandai dengan kesederhanaan, keberpihakan pada kaum marginal, dan keberanian menyuarakan kritik terhadap kekuasaan yang lalim.
Paus Fransiskus mengabdikan hidupnya pada prinsip "Gereja yang miskin untuk orang miskin", sebuah paradigma yang mengacu pada Teologi Pembebasan (Gutierrez, 1971) dan tradisi Ignatian.
Dalam konteks Indonesia, pemikirannya selaras dengan kritik struktural terhadap neoliberalisme, seperti yang dielaborasi oleh Arief Budiman (1995) dalam Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Fransiskus mengecam "ekonomi yang membunuh" (Evangelii Gaudium, 2013), seruan yang relevan dengan ketimpangan Indonesia, di mana 1% populasi menguasai 47% kekayaan (OXFAM, 2024).
Advokasi Lingkungan: Laudato Si' dan Ekoteologi Nusantara
Ensiklik Laudato Si' (2015) menjadi magnum opus-nya, menggabungkan ekologi, keadilan sosial, dan iman.
Dokumen ini menginspirasi gerakan lingkungan di Indonesia, seperti aksi Walhi menentang deforestasi.
Teori Ecotheology (John B. Cobb, 2007) dan konsep "ekofeminisme" (Vandana Shiva) terasa dalam gagasannya bahwa "kerusakan lingkungan adalah dosa modern".
Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Siti Syamsiyatun (2022) dalam Jurnal Studi Agama-Agama tentang relasi agama dan konservasi alam di Indonesia.
Suara Melawan Penjajahan: Kritik terhadap Israel
Pada November 2024, Paus Fransiskus mengecam "kesombongan penjajah" Israel di Palestina, menyebut agresi Tel Aviv di Gaza sebagai "genosida".
Pernyataan ini menjadi puncak dari serangkaian kecamannya sejak 2023, termasuk seruan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang porak-poranda. Dalam pidatonya, ia menegaskan:
"Kota Suci [Yerusalem] harus menjadi tempat pertemuan, bukan pertikaian--tempat di mana Kristen, Yahudi, dan Muslim merasa dihormati".
Kritiknya tidak hanya bersifat moral tetapi juga politis. Ia menolak penggunaan kekuatan "tidak bermoral" Israel di Lebanon dan Gaza, sekaligus menyoroti kemunafikan negara-negara yang menjual senjata sambil berkoar tentang perdamaian.
Pemimpin spiritual Gereja Katolik yang ke-266 ini bukan hanya seorang imam, tetapi seorang negarawan moral, pemikir publik, dan simbol global perjuangan kemanusiaan yang tak gentar menyuarakan keadilan, bahkan ketika harus menantang kekuatan-kekuatan duniawi yang dianggap tak tersentuh.
Dalam dekade terakhir hidupnya, Paus Fransiskus menjelma sebagai suara moral dunia yang tidak takut menyentuh luka geopolitik.
Salah satu sikap paling kontroversial--namun penuh integritas--adalah penolakannya terhadap pendudukan Israel atas Palestina.
Ia secara terbuka mengecam tindakan militer yang merampas nyawa anak-anak Gaza, pemblokadean ekonomi, serta kolonisasi Tepi Barat yang sistematis.
Dalam salah satu homilinya, ia mengutip Kitab Yesaya: "Bangsa yang tidak mencintai keadilan akan binasa oleh pedangnya sendiri."
Pernyataan itu menohok para elite dunia yang bungkam atau berpihak demi kepentingan politik semata.
Paus Fransiskus tidak sekadar berbicara. Ia secara simbolik mencium tanah Palestina saat berkunjung ke Betlehem pada 2014, menolak dikawal oleh tentara Israel saat menyeberangi Tembok Pemisah, dan membuka jalur diplomatik Vatikan untuk mengakui kedaulatan Negara Palestina.
Tindakannya menggemakan teori aksi komunikatif dari Jurgen Habermas, bahwa kekuasaan sejati lahir bukan dari dominasi koersif, tetapi dari rasionalitas komunikatif yang memuliakan martabat manusia.
Analisis Teoretik: Moralitas Kantian dan Akar Konflik
Dalam perspektif teori moral Immanuel Kant, tindakan Israel di Gaza dianggap melampaui batas kewajiban moral--terutama ketika serangan membabi-buta mengorbankan warga sipil.
Kant menekankan bahwa moralitas harus didasarkan pada kewajiban universal, bukan hasil akhir.
Paus Fransiskus, melalui kecamannya, sejalan dengan prinsip ini: menolak pembenaran kekerasan meski atas nama "pertahanan diri".
Analisis akar konflik oleh peneliti Indonesia menunjukkan bahwa klaim historis-religius dan campur tangan politik internasional memperkeruh situasi.
Paus Fransiskus memahami kompleksitas ini, sehingga kritiknya tidak hanya ditujukan pada Israel, tetapi juga pada komunitas global yang abai terhadap penderitaan Palestina.
Sikap Paus Fransiskus terhadap konflik Israel-Palestina bisa dianalisis melalui pendekatan etika profetik, sebagaimana dikembangkan oleh Kuntowijoyo dalam ranah ilmu sosial transformatif.
Ia tidak sekadar menjadi pemimpin agama, tetapi juga "nabi zaman kini" yang menyuarakan nilai keadilan transenden dalam kerangka tindakan konkret.
Konsep ini selaras dengan gagasan "politik berbasis nurani" yang banyak dibahas dalam jurnal-jurnal keislaman dan humaniora Indonesia, seperti Jurnal Pemikiran Islam dan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
Dalam ranah hubungan internasional, Paus Fransiskus juga mempraktikkan pendekatan moral diplomacy yang menantang struktur realpolitik.
Ia memperlihatkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, aktor non-negara seperti Gereja Katolik dapat memainkan peran normatif signifikan melalui diplomasi nilai.
Hal ini sesuai dengan kerangka teori konstruktivisme, yang menekankan pentingnya identitas, norma, dan nilai dalam membentuk dinamika internasional (Wendt, 1999).
Warisan yang Tak Padam
Kematian Paus Fransiskus meninggalkan vacuum spiritual dalam perjuangan melawan ketidakadilan.
Seperti nyala lilin di tengah kegelapan, suaranya tentang perdamaian di Tanah Suci tetap bergema--mengingatkan dunia bahwa kemanusiaan harus melampaui sekat-sekat politik. Dalam kata-katanya sendiri:
"Perang selalu merupakan kekalahan bagi semua orang. Hanya perdamaian yang membebaskan. Perdamaian tidak akan datang dari senjata, tetapi dari keberanian mencintai tanpa syarat."

Referensi:
- Budiman, A. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- CNBC Indonesia. (2025). Breaking News: Paus Fransiskus Meninggal Dunia dalam Usia 88 Tahun.
- Antara News. (2024). Paus Fransiskus Kecam "Kesombongan Penjajah" Israel di Palestina.
- CNN Indonesia. (2024). Posisi Paus Fransiskus Soal Konflik Israel-Palestina.
- Gutierrez, G. (1971). A Theology of Liberation. Maryknoll: Orbis Books.
- Habermas, Jrgen. (1984). The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.
- Journal for Islamic Studies. (2024). Melihat Perang Israel-Palestina Dalam Sudut Pandang Teori Moral Immanuel Kant.
- Repository UIN Jakarta. (2024). Analisis Akar Konflik Palestina-Israel.
- Syamsuddin, Din. (2007). "Etika Profetik dan Transformasi Sosial." Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 10, No. 1.
- Kuntowijoyo. (2005). Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan.
- Neliti. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel-Palestina dalam Media Indonesia.
- Deutsche Welle. (2025). Paus Fransiskus Meninggal Dunia.
- Viva.co.id. (2024). Paus Fransiskus Sampaikan Kecaman Lebih Keras Lagi Sebut "Arogansi Penjajah" Israel.
- Wahid, Abdurrahman. (1994). "Agama sebagai Kritik Sosial." Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. V, No. 3.
- Wendt, Alexander. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI