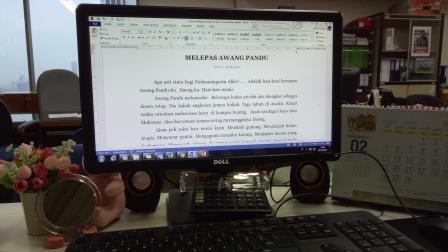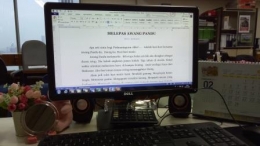Apa arti cinta bagi Padmaningrum Alila?….. Adalah hari-hari bersama Awang Pandu-ku. Daeng-ku. Hari-hari manis.
Awang Pandu melamarku. Beberapa bulan setelah aku diangkat sebagai dosen tetap. Dia kakak angkatan jaman kuliah. Tiga tahun di atasku. Kenal waktu orientasi mahasiswa baru di kampus kuning. Anak saudagar kaya dari Makassar. Aku dan teman-teman sering memanggilnya Daeng.
Alam jadi saksi hari manis kami. Mendaki gunung. Menjelajah hutan tropis. Menyusur pantai. Mengagumi terumbu karang. Menjejaki muara yang berlumpur. Mengayuh jukung di sungai yang tampak tenang tapi banyak buayanya. Mengamati burung di surga Kepulauan Seribu.
Daeng-ku selalu ada di sampingku. Waktu aku terpeleset saat mendaki. Saat berteriak terkejut melihat ular di hutan. Saat kesakitan akibat tertusuk bulu babi. Saat terkagum mengintip banteng-banteng dari balik pepohonan. Saat jukung terbalik dan aku gelagapan di tengah sungai.
Lucu, waktu ingat peristiwa jukung terbalik. Takut tiba-tiba ada buaya yang akan segera melahapku hidup-hidup. Berteriak aku ketika sesosok tegap menangkapku dari belakang. Aku kira buaya. Ternyata Awang Pandu. Aku dibantunya berenang segera ke tepi sungai Cigenter, Ujung Kulon. Itulah pertama kali aku bersentuhan dengannya. Semester satu. Kulit bersentuh kulit. Berdegup di dalam dada. Kata nya ini jatuh cinta? Entah, mungkin ya.
Awang Pandu selalu ada di mana ada aku. Setelah lulus dia melanjutkan studi Pascasarjana di kampus yang sama. Kami bertemu dan bertemu lagi. Saling merekatkan taut hati. Bahkan, setelah aku lulus dan bekerja sebagai staf pengajar di kampus lain, Awang Pandu tetap memujaku. Membuatku besar kepala.
Laki-laki tegap berkulit gelap itu berwajah kebapakan. Kataku. Garis wajahnya tegas. Jika tak kenal, sepintas orang akan menyangkanya sombong. Dan galak. Serta dingin. Padahal dia lembut dan sopan. Juga humoris.
Selain kegiatan jelajah alam, aku juga bergumul dengan pers kampus. Majalah dinding, majalah kampus, bulletin kampus, tak pernah meluputkan tulisanku. Kata Awang Pandu, aku jurnalis kampus yang manis. Dengan kacamata minus lima yang sering merosot dari hidungku yang tidak bangir? Ah laki-laki. Mau saja aku dibodohi turunan Adam.
Aku mengambil kekhususan Mikrobiologi yang memaksa seseorang banyak berkutat dengan mikroorganisme di laboratorium. Dituntut bekerja steril, cepat, dan tekun. Alasannya? Aku tertantang oleh ilmu itu. Yang kurasa sulit, jauh melebihi semua cabang ilmu Biologi yang lain. Selama ini, belum ada mahasiswa yang bisa lulus cum laude dari Mikro setelah Irmansyah, kakak angkatan yang lulus sekitar pertengahan era 80.
Aku tertantang untuk mencatat sejarah baru di kampus ini. Perempuan, lulus cum laude dari Mikro. Itu tujuanku. Tercapai. Lalu, tanpa kesulitan berarti, aku lulus seleksi penerimaan dosen di sebuah universitas swasta. Awang Pandu mencubit hidungku waktu itu sambil memanggil manja, ”Bu Dosen, Bu Dosen…” Membuat wajahku berubah-ubah warna. Semu merah di pipi.
---------------------------------
Aku tidak tahu apakah aku sungguh-sungguh mencintai Awang Pandu. Entahlah. Sampai dia melamarku aku masih tidak tahu. Tepatnya mungkin belum mau tahu. Aku masih sibuk dengan mimpi-mimpi. Seperti kupu-kupu, agaknya aku belum puas mengepak sayap.
Waktu melewati jalurnya. Mendaki tebing hari. Demi hari. Pekan. Bulan dan tahun. Ada yang berubah padaku. Tapi tidak pada Awang Pandu.
“Sepertinya ini sudah saatnya, Alila. Sekolahku sudah selesai. Pekerjaan tetap sudah ada. Kamu juga sudah bekerja tetap. Kira-kira, kapan ya aku bisa ketemu orang tuamu?…..” tanya Awang Pandu waktu aku menghadiri wisuda pascasarjananya. Saat itu aku sudah bekerja sebagai dosen tetap Mikrobiologi di FK . Sebuah universitas swasta tertua di Jakarta. Sementara dia mengabdi di almamater tercinta.
“Mau apa?” tanyaku. Pertanyaan bodoh.
“Melamar.”
“Melamar siapa?”
“Padmaningrum Alila dong.”
“Kenapa terburu-buru?”
“Menurutmu terburu-buru?”
“Hmmmm” gumamku menyisakan tanya bagi Daeng-ku.
----------------
Aku sedang dalam proses seleksi di sebuah koran nasional. Melamar jadi wartawan. Dengan niat penuh. Meski pekerjaan tetap sebagai dosen kujalani. Aku kepingin jadi wartawan. Kepingin sekali. Kurasa aku akan menyesal seumur hidup jika hanya melewatkan hidupku di kampus dan laboratorium. Terlalu banyak rasanya sesuatu di luar sana yang ingin kujelang. Egois, barangkali. Benarkah?……
Aku diam-diam. Karena Bunda pasti tidak setuju. Diam-diam aku juga ragu Awang Pandu akan tetap pada niatnya melamarku, seandainya aku tetap nekat jadi wartawan.
Dalam tiap kesempatan, Awang Pandu kembali menanyakan perihal pernikahan. “Apa yang membuatmu ragu, Alila? Bilang saja.”
Aku diam.
“Daeng, aku kan tidak cantik. Tidak kaya. Kenapa aku?”
“Ada pertanyaan lain yang lebih serius gak sih. Masa seperti itu ditanyakan,” ujarnya. Awang Pandu memandangiku. Berusaha mencari senyumku. Sekarang, dia sudah berani menggenggam jemariku lebih lama. Duduk dekat-dekat. Merangkul bahu. Uh, dulu mana berani.
“Aku bertanya serius.”
“Aku menjawab apa adanya.”
“Bohong.”
“Terserah.”
“Daeng….”
“Ya Alila yang manis.” Tuh, tangannya sudah pindah menelusuri pinggangku. Laki-laki……
“Aku mau berhenti.”
“Berhenti apa?”
“Berhenti jadi dosen. Aku lulus seleksi jadi wartawan di harian nasional. Bulan depan aku pendidikan wartawan ke Yogya. ”
------------------
Awang Pandu memintaku untuk berpikir ulang tentang pindah kerja jadi wartawan. Berkali-kali. Jawabanku tetap sama.
“Kamu yakin?”
“Yakin sekali.”
“Secepat itu kamu berubah pikiran.”
“Ini kesempatanku, Daeng. Belum tentu datang lain waktu. “
“Alila, lupa dengan cita-cita kita? Melanjutkan S2 setelah anak kedua. S3 sama-sama ? “
“Daeng keberatan?”
“Aku tidak berhak keberatan atas apapun. Pikir ulanglah Alila.”
“Tidak. Aku sudah mantap. “
“Bapak dan Bunda?”
“Bapak dan Bunda melarang. Tapi aku sudah memutuskan. Aku mau jadi wartawan. Aku terus.”
“Meskipun Bapak dan Bunda melarang?.”
Aku mengangguk cepat. Tak ada ragu. Dia menghela nafas sangat panjang.
“Jika kedua orang tuamu pun tidak bisa menghentikan langkahmu, apalagi aku. Berapa lama aku harus menunggumu?”
“Entah.”
“Alila?”
“Aku tidak tahu. Apakah Daeng merasa harus menungguku?“
“Kamu ingin aku menunggumu sampai kapan?”
Aku tak bisa menjawab. Tidak tahu jawabannya. Apakah aku menginginkan Daeng? Dia menginginkanku. Serius. Apakah aku juga begitu?
Jika aku menerima lamaran Daeng, sekarang, atau besok, aku harus siap menjadi istri yang melayaninya. Mengurus makannya, kebutuhannya, ada di rumah sepulang dia bekerja. Sebagai wartawan, bisakah?
Mungkin aku akan sering pulang larut malam, meliput di malam hari bahkan subuh. Mungkin aku tidak ada di rumah ketika dia pulang kerja selepas Ashar. Mungkin aku tak bisa bersamanya di hari libur. Dia butuh diurus. Tapi tak mengekangku di rumah. Mungkin, akupun lantas sudah terlalu lelah untuk bercinta dengannya ketika sampai di tempat tidur.
“Jika tak ada yang membuatku harus menunggu,………” Awang Pandu terhenti.
“Berlalulah….” Itu kuucapkan sangat perlahan.
Awang Pandu menatapku. Aku menunduk. Menangis. Untuk terakhir kali, Daeng-ku menggenggam jemariku. Lama sekali.
Setelah itu tak pernah ada lagi mimpi-mimpi tentang pernikahan kami. Rekening bank bersama atas namaku- yang sebetulnya berisi uangku dan uangnya, yang kami sisihkan dari penghasilan kami masing-masing setiap bulan untuk persiapan mencicil DP kredit rumah, menjadi saksi terakhir mimpi pernikahan.
Aku mentransfer kembali dana milik Awang Pandu ke rekeningnya. Meskipun dia tak pernah menyinggung sedikitpun tentang rekening bersama itu. Aku melakukannya untuk memberinya sebuah tanda kepastian. Bahwa dia tak terikat untuk menungguku. Bahwa sebaiknya dia segera mencari penggantiku. Mengharapkanku hanya akan seperti memelihara duri dalam hatinya.
Kalau saja aku memintanya menunggu. Dia akan menunggu. Rasanya ya. Tapi adilkah? Sungguhkah aku menginginkan penantian Awang Pandu-ku? Aku memilih pergi saja.
Aku ingin datang dan pergi
Menjelang dan berlalu
Melangkah dan berhenti
Pada alurku
Pada saatku
Pada waktuku
Pada giliranku
Seperti gelap yang datang menjemput malam
Seperti harum yang lepas pergi ketika kuntum bunga mekar
Aku ingin mencintai dan dicintai
Sewajarnya
Seperti nelayan mencintai lautan
Dan hutan tropis dicintai para penjelajah
Aku ingin membentang
Seperti lengkung pelangi
Dan warna warni adalah seri diriku
Kini, mampukah kupungut serak keping hatiku
Satu persatu?
Puisi itu kutulis dalam kereta sepanjang perjalanan Jakarta-Yogya. Air mataku meleleh. Pertengkaran dengan Bunda dan Bapak yang melarangku jadi wartawan. Perpisahan dengan Awang Pandu. Ah… runtuhkah dunia? Tidak. Aku mengucapkan selamat datang pada pemberontakan. Salahkah aku jika punya keinginan? ………….
Berbulan-bulan kemudian, ketika aku sudah disibukkan dengan aktivitasku sebagai wartawan, tak kusempatkan mengingat-ngingat lagi Daeng-ku.
-----------------
Dua tahun berlalu. Kabar dari lelaki itu datang suatu pagi di bulan Februari. Awang Pandu-ku. Memintaku merestui pernikahannya. Dengan Astrianti. Rekan satu angkatanku. Mantan aktivis Senat Mahasiswa. Punya usaha pertanian organik sendiri. Aku mengucap syukur alhamdulillah. Dialah yang tepat untuk Daeng. Rasanya ya. Naluri perempuanku mengatakan begitu.
Aku menghadiri akad nikah mereka. Betul-betul kusempatkan hadir pagi-pagi di masjid sekalipun semalam pulang larut dengan lelah yang sangat. Satu jam. Kemudian aku harus segera pergi liputan.
Di samping rumah Tuhan itu, waktu aku hendak berlalu, Awang Pandu menghampiri. Sendiri. Tanpa Astrianti. Rupanya dia sembunyi-sembunyi.
“Alila….”
“Ya?”
“Terima kasih sudah datang.”
“Tentu, Daeng. “
“Adakah seseorang?’
“Apa?”
“Setelah aku.”
Aku mengernyitkan dahi.
“Oh” jawabku singkat.
“Ada?”
Aku menggeleng. Tidak ada, Daeng. Aku belum berpikir tentang siapa penggantimu. Awang Pandu diam sebentar.
“Alila, sampai kapan?”
“Tidak tahu.”
“Jangan terlalu lama. Jika ada lelaki baik yang mencintaimu, terimalah dia. Cinta dapat menunggu. Kecuali jika kamu tidak mengharapkan untuk ditunggu. Jika seseorang tak diinginkan untuk menunggu, maka dia akan…. ” Awang Pandu menghentikan kalimatnya.
“Berlalu,” kataku melengkapi kalimatnya.
“Berlalu dengan pedih, ” kata Awang Pandu.
“Hmm.” Aku menjawab dengan gumam. Dalam benak kami ada kenangan yang sama. Di gunung, di pantai, di laut, di sungai, di kampus, di lab, di rekening bank.
Angin pagi sejuk di sekeliling masjid. Untuk pertama kalinya, keningku dikecup suami orang. Di samping rumah Tuhan. Nafas Awang Pandu meniup sebagian wajahku. Secepat angin aku berbalik. Berlari. Meninggalkan Daeng-ku yang masih berdiri. Daeng-ku? Tidak. Bukan lagi. Sekarang.
Apa arti cinta bagi Padmaningrum Alila?……….
---------------------------- selesai -----------------------------------