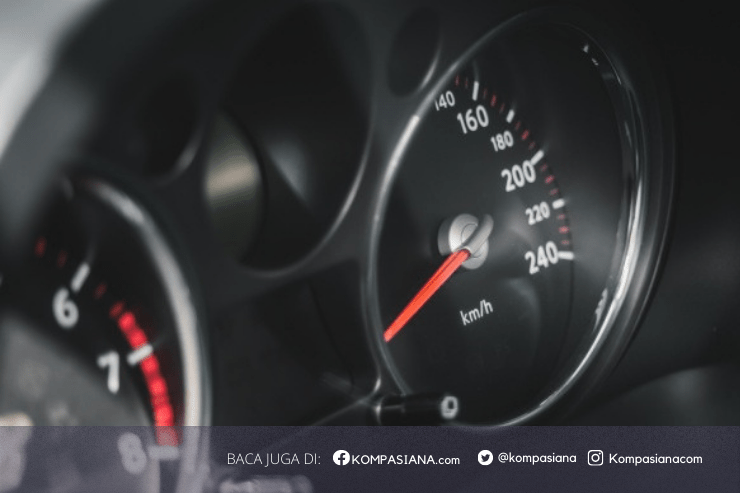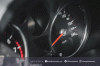Indonesia menaruh ambisi besar untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global. Pemerintah menggulirkan berbagai inisiatif, mulai dari target Net Zero Emission (NZE) 2060, pengembangan industri kendaraan listrik (EV), hingga mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Di atas kertas, langkah-langkah ini terlihat menjanjikan. Indonesia bahkan mendapat sorotan dunia karena posisinya yang strategis dalam rantai pasok energi masa depan, terutama berkat kekayaan sumber daya nikel. Namun, ketika melihat ke lapangan, perjalanan Indonesia menuju masa depan hijau tampak berjalan setengah hati, penuh paradoks dan kontradiksi. Antara keinginan untuk mengurangi emisi dan kenyataan bahwa industri hijau masih disokong oleh energi kotor, Indonesia seperti tengah berdiri di persimpangan jalan.
Mobil Listrik: Solusi atau Masalah Baru?
Dalam narasi resmi, mobil listrik disebut sebagai salah satu pilar utama untuk mengurangi emisi karbon nasional. Berbagai insentif digelontorkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, dari subsidi pembelian, insentif pajak, hingga program nasional pengembangan ekosistem EV. Pabrik-pabrik baterai dan kendaraan listrik mulai bermunculan, terutama di kawasan industri seperti Morowali dan Halmahera. Namun, ada ironi besar yang luput dari perbincangan: produksi kendaraan listrik dan baterainya di Indonesia saat ini masih bergantung pada rantai pasok yang beremisi tinggi. Sebagian besar smelter nikel yang menyuplai bahan baku baterai mobil listrik menggunakan listrik dari pembangkit batu bara. Ini menciptakan situasi di mana mobil listrik yang seharusnya menjadi simbol energi bersih, justru menimbulkan emisi besar dari proses produksinya. Dengan kata lain, mobil listrik Indonesia masih 'bernapaskan' energi kotor.
Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Nikel
Tidak hanya emisi karbon yang menjadi persoalan. Ledakan permintaan nikel untuk kebutuhan baterai juga memicu kerusakan ekologis yang masif. Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Halmahera, ekspansi tambang nikel menggerus hutan-hutan tropis yang sebelumnya menjadi benteng keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon. Sungai-sungai tercemar limbah tailing, habitat satwa endemik terancam, dan komunitas adat kehilangan tanah ulayat mereka. Proses ekstraksi dan pengolahan nikel yang intensif energi ini memperparah beban lingkungan yang seharusnya dikurangi lewat transisi energi. Ironisnya, dalam mengejar ambisi hijau global, Indonesia justru mengorbankan kekayaan ekologis lokalnya. Jika dibiarkan, alih-alih memperbaiki hubungan manusia dengan alam, transisi ini justru memperdalam ketidakadilan ekologis.
Ketergantungan Energi Fosil di Tengah Janji Energi Bersih
Keterbelakangan dalam infrastruktur energi bersih memperparah situasi. Untuk mendukung industri nikel dan kendaraan listrik, Indonesia justru masih membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru berbahan bakar batu bara. Alih-alih mempercepat dekarbonisasi, proyek-proyek ini memperpanjang umur energi fosil di Indonesia. Hal ini berlawanan dengan komitmen global untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara sebagai penyumbang emisi terbesar. Apalagi, kebijakan-kebijakan strategis seperti pengenaan pajak karbon justru ditunda, memperlihatkan bahwa politik energi Indonesia masih sangat berhati-hati --- bahkan cenderung berpihak pada energi konvensional. Dalam konteks ini, mobil listrik yang diimpikan menjadi bagian dari solusi perubahan iklim, justru lahir dari sistem energi yang memperparah perubahan iklim itu sendiri.
Meskipun perjalanan transisi energi Indonesia penuh tantangan, beberapa inisiatif positif patut dicatat. PLTS Terapung Cirata yang mulai beroperasi di Jawa Barat menjadi salah satu proyek energi bersih terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan negara-negara G7 membuka peluang untuk mempercepat penghentian PLTU dan memperluas bauran energi terbarukan. Pemerintah juga mulai merancang roadmap ekosistem EV nasional untuk mengintegrasikan produksi, penggunaan, dan daur ulang kendaraan listrik secara lebih holistik. Namun, tanpa reformasi struktural yang kuat dan konsisten, inisiatif-inisiatif ini berisiko hanya menjadi pencitraan sesaat yang tidak menyentuh akar masalah.
Masa depan transisi energi Indonesia kini bertumpu pada arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini adalah momentum penting untuk membalikkan arah --- dari transisi energi setengah hati menuju transformasi energi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah baru perlu berani mengambil langkah nyata: menghentikan pembangunan PLTU baru, mewajibkan smelter menggunakan energi terbarukan, memperketat standar tambang hijau, dan mengembangkan sistem EV yang benar-benar rendah emisi dari hulu ke hilir. Tanpa langkah-langkah radikal ini, Indonesia berisiko hanya menjadi "pabrik baterai dunia" yang berkontribusi besar terhadap polusi, alih-alih menjadi teladan pembangunan hijau.
Transisi energi adalah peluang langka --- tetapi juga penuh jebakan. Jika dikelola dengan visi jangka panjang dan keberanian politik, Indonesia bisa menjadi negara berkembang pertama yang sukses melakukan lompatan besar ke ekonomi hijau. Namun, jika transisi ini dijalankan dengan setengah hati, Indonesia hanya akan mengganti sumber krisis: dari polusi karbon kendaraan berbahan bakar minyak, menjadi polusi tambang dan emisi smelter nikel. Masa depan hijau tidak akan datang dengan sendirinya; ia harus diperjuangkan, dengan komitmen penuh, keberanian bertindak, dan keberpihakan pada keadilan ekologis.
Seperti kata pepatah, "Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak-cucu kita." Saat ini, Indonesia tengah menulis babak baru dalam sejarahnya --- apakah itu babak kemenangan, atau babak penyesalan, hanya waktu yang akan menjawab.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI