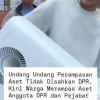Di bawah langit Kalimantan Barat yang biru dan lembab, asap tipis sering membubung di penghujung musim kemarau. Bagi sebagian orang kota, asap itu tanda bahaya. Bagi masyarakat adat Dayak, itulah tanda kehidupan baru akan dimulai---masa berladang.
Namun, kebiasaan turun-temurun ini kini berada di ujung tanduk. Menteri Kehutanan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan Perda yang membolehkan pembakaran lahan maksimal dua hektar akan dicabut.
Alasannya? Demi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Kebijakan ini terdengar tegas, tetapi di telinga para peladang tradisional, ia bagai palu godam yang menghantam kepala. Mereka merasa kembali disudutkan, seolah-olah semua api berasal dari korek api mereka. Pertanyaannya: benarkah peladang tradisional penyebab utama bencana asap?
---
Tradisi yang Bukan Asal Bakar
Bagi masyarakat adat Kalbar, membakar lahan bukanlah tindakan sembrono. Ini adalah ritual agraris yang diatur oleh kearifan lokal. Mereka tahu kapan waktu terbaik: bukan di puncak kemarau, melainkan di penghujung musim kemarau, saat hujan segera turun dan api tidak akan merajalela. Mereka membuat sekat bakar, memilih lahan mineral yang tidak mudah menyebarkan api, dan membakar melawan arah angin agar api terkendali.
"Kalau api merembet ke ladang tetangga, kami yang rugi. Ada sanksi adat yang berat," kata Yansen, seorang peladang di Kapuas Hulu. Dalam hukum adat, membakar lahan orang lain bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penghinaan terhadap kehormatan keluarga.
---
Mitos dan Fakta Asap
Ironisnya, kebakaran hebat yang menutup langit Kalimantan dengan kabut asap jarang berasal dari ladang dua hektar milik petani. Data KLHK menunjukkan, 90% titik panas berada di lahan gambut, yang mayoritas dibuka untuk perkebunan besar, terutama kelapa sawit. Lahan gambut, jika terbakar, menyala di bawah tanah dan sulit dipadamkan, menghasilkan asap berbulan-bulan.
Peladang tradisional menghindari gambut karena tanahnya tidak cocok untuk padi ladang dan rawan banjir. Mereka tidak punya modal untuk membuka lahan ribuan hektar, apalagi untuk menjual hasilnya ke pasar internasional.
Namun, ketika asap menyelimuti kota, jari telunjuk publik justru mengarah ke mereka---mereka yang hanya membakar lahan seluas lapangan sepak bola untuk memberi makan keluarga.
---
Kebijakan Pukul Rata dan Risiko Kriminalisasi
Larangan total membakar lahan tanpa membedakan pelaku dan skala justru menciptakan kriminalisasi. Kita pernah melihatnya di awal 2000-an, saat ratusan peladang ditangkap karena "membakar lahan", padahal yang mereka lakukan adalah tradisi yang diakui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi pengecualian bagi pembukaan lahan skala kecil berbasis kearifan lokal.
Tahun 2019, yang disebut sebagai "tahun terkelam bagi peladang tradisional" di Kalimantan Tengah, tercatat 35 peladang ditangkap hanya di provinsi itu. Selama satu dekade terakhir, ratusan peladang di berbagai daerah Kalimantan mengalami hal serupa.
Data mencatat bahwa dari 161 kasus karhutla perorangan, 121 orang ditetapkan tersangka, sementara dari 20 kasus korporasi, hanya dua perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka.
Di Sintang, Kalbar, kasus serupa bahkan memicu aksi massa dan gerakan #PeladangBukanPenjahat, sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma dan ketidakadilan.
Alternatif yang diusulkan pemerintah, seperti penggunaan alat berat atau metode tanpa bakar, terdengar modern tetapi jauh dari realitas desa. Biayanya mahal, hasilnya tidak selalu memuaskan, dan petani tetap harus membeli pupuk kimia---sesuatu yang justru dihindari dalam sistem perladangan tradisional yang memanfaatkan abu sebagai pupuk organik alami.
---
Akar Masalah: Gambut dan Perkebunan Besar
Kebijakan mencabut Perda ini berpotensi menutupi akar masalah sebenarnya: lemahnya pencegahan di lahan gambut dan minimnya penegakan hukum terhadap perusahaan besar yang membuka lahan dengan cara bakar. Dalam banyak kasus, investigasi hanya menyentuh pekerja lapangan, sementara pemilik perusahaan tetap duduk manis di kantor ber-AC.
Dana pencegahan karhutla pun sering terpakai hanya saat bencana sudah terjadi. Padahal, pencegahan memerlukan patroli rutin, penyediaan sekat kanal di gambut, dan pendidikan masyarakat.
Seperti kata pepatah Dayak, "Api yang kecil bisa jadi sahabat, api yang besar jadi bencana." Peladang tahu cara menjaga api kecil, sementara korporasi sering menciptakan api besar yang melahap segalanya.
---
Jalan Tengah yang Rasional
Solusi bukanlah larangan total, melainkan regulasi cerdas yang membedakan antara pembakaran terkendali oleh peladang tradisional dan pembakaran masif oleh korporasi. Pemerintah bisa membuat skema perizinan komunitas, pengawasan bersama, dan dukungan peralatan sederhana untuk pengendalian api.
Kearifan lokal bukan musuh pembangunan, tetapi aset yang bisa menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Dengan menggandeng masyarakat adat, negara tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga melindungi budaya yang telah menopang kehidupan di pedalaman selama ratusan tahun.
---
Seperti kata filsuf Tiongkok, Lao Tzu, "Pemerintah terbaik adalah yang sedikit mengatur, tetapi memastikan semua hidup dalam keseimbangan." Keseimbangan itu yang kini dipertaruhkan di Kalbar.
Jika pemerintah tergesa-gesa mencabut Perda tanpa mendengar suara peladang, kita bukan hanya kehilangan alat produksi pangan tradisional, tetapi juga menutup lembar sejarah panjang pertanian di bumi Borneo---sementara asap dari lahan gambut dan perkebunan besar tetap saja membumbung.***MG
---
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI