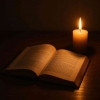Ketika kontroversi seputar kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak "nakal" ke barak militer belum juga reda, publik dikejutkan oleh pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut bahwa pendekatan tersebut tidak melanggar HAM---bahkan layak untuk diperluas secara nasional.
Pernyataan ini sontak menyulut perdebatan publik. Bagaimana bisa seorang menteri yang memegang amanah untuk menjaga prinsip-prinsip hak asasi justru mendukung pendekatan militeristik yang diterapkan pada anak-anak? Tidakkah ini mencerminkan kekeliruan memahami esensi perlindungan anak dan batas-batas wewenang seorang pejabat negara?
Pendekatan Militeristik dalam Pendidikan: Mengapa Bermasalah?
Di mata sebagian masyarakat, tindakan Dedi Mulyadi dianggap tegas dan solutif. Namun dalam perspektif pendidikan dan hak anak, pendekatan semacam itu menyimpan banyak persoalan serius.
Pendidikan militer berakar dari prinsip hierarki, ketaatan mutlak, dan penyeragaman perilaku. Disiplin di dalamnya dibentuk melalui tekanan, hukuman fisik dan mental, serta sistem komando yang tidak memberi ruang pada ekspresi personal. Sebaliknya, pendidikan anak berlandaskan pada prinsip tumbuh-kembang, partisipasi, penghargaan atas keunikan individu, dan pendekatan psikologis yang lembut namun tegas.
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pendekatan militer dalam pembinaan anak rawan menimbulkan trauma psikologis, merusak kepercayaan diri, dan menciptakan ketakutan alih-alih kesadaran moral. UNICEF dalam laporannya menyatakan bahwa pendekatan koersif dalam mendisiplinkan anak justru memperparah perilaku menyimpang dalam jangka panjang.
Menteri HAM vs Komnas HAM: Dua Suara dari Negara
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai bahwa "program Dedi tidak melanggar HAM dan perlu direplikasi ke daerah lain" memunculkan pertanyaan serius: apakah pendekatan keras ini benar-benar sesuai dengan prinsip hak anak?
Komnas HAM berpandangan sebaliknya. Melalui Wakil Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, lembaga ini menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai bahwa mengirim anak-anak ke barak militer merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam pernyataannya, Anis menegaskan bahwa "pendidikan semacam ini dapat mencederai martabat anak, mempermalukan mereka secara publik, dan justru menjauhkan anak dari sistem pendidikan yang ramah dan inklusif."
Komnas HAM juga menekankan bahwa "tidak ada dasar hukum yang membenarkan penanganan anak dalam situasi kenakalan sosial dengan cara yang mengarah pada militerisasi atau intimidasi." Selain tidak proporsional, pendekatan seperti ini dianggap berpotensi melanggar Konvensi PBB tentang Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 1990.
Konflik pandangan antara dua institusi ini memperlihatkan kegamangan negara dalam menegakkan prinsip perlindungan anak yang konsisten. Jika lembaga pengawas HAM dan Menteri HAM sendiri bertolak belakang, publik berhak bertanya: di mana arah moral dan konstitusional kebijakan negara?
Wewenang Menteri HAM: Bukan Pembuat Kebijakan Pendidikan
Perlu ditegaskan bahwa Menteri HAM bukan pembuat kebijakan pendidikan, apalagi kebijakan hukum dan ketertiban di daerah. Wewenang Menteri HAM adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh siapapun---pemerintah pusat maupun daerah---tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Mendorong replikasi pendekatan militer terhadap anak-anak bukan hanya di luar kapasitasnya sebagai menteri, tetapi juga dapat menimbulkan preseden buruk, seolah negara melegitimasi pendekatan keras yang tidak berbasis pedagogis dan ilmiah.
Jika pun Menteri HAM ingin terlibat dalam kebijakan pendidikan anak, maka seharusnya ia bersuara dalam memperkuat sistem rehabilitasi sosial, pendidikan karakter berbasis komunitas, dan intervensi psikologis yang menghargai martabat anak.
Alternatif: Pendidikan yang Humanis dan Rehabilitatif
Ketimbang barak militer, mengapa tidak mengembangkan pusat-pusat rehabilitasi berbasis sekolah yang menekankan keterlibatan keluarga, konseling, dan terapi psikososial?
Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan pendekatan restorative justice yang mulai diadopsi oleh Polri dan Kejaksaan dalam kasus anak, telah menunjukkan keberhasilan dalam membina anak tanpa kekerasan dan tanpa menjauhkan mereka dari lingkungan sosial.
Studi dari American Psychological Association menyebut bahwa anak-anak yang ditangani dengan pendekatan restoratif dan penuh empati lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi perilaku negatif dan lebih cepat pulih dari trauma sosial.
Menjaga Anak, Menjaga Masa Depan Bangsa
Anak-anak yang bersalah bukan untuk dihukum dengan keras, melainkan untuk dibimbing dengan cerdas. Mereka bukan bahan percobaan kebijakan populis, melainkan generasi yang harus disiapkan dengan kasih dan logika.
Dalam konteks ini, pendekatan militeristik justru memperlihatkan kemunduran cara berpikir negara terhadap pendidikan dan pembangunan manusia. Sementara dunia tengah berlomba mencetak generasi kritis dan berdaya pikir bebas, kita malah ingin membentuk generasi patuh tanpa suara.
Dan ketika Menteri HAM, yang seharusnya menjadi pagar terakhir pelindung hak-hak paling dasar warga negara, justru mendorong pendekatan semacam ini, maka itu pertanda kita perlu membunyikan alarm darurat demokrasi---dan mulai bertanya: siapa sebenarnya yang melindungi anak-anak Indonesia?***MG
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI